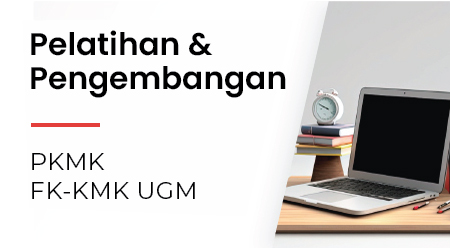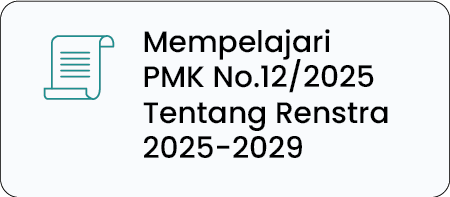Forum Nasional (Fornas) XV Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) tahun 2025 diselenggarakan oleh JKKI bekerja sama dengan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK-KMK Universitas Gadjah Mada. Forum ini mengangkat tema besar “Implementasi Kebijakan Transformasi Sektor Kesehatan dalam Undang-Undang Kesehatan 2023: Kebijakan Membangun Sistem Kesehatan.” Reportase ini mendokumentasikan jalannya sesi kedua pada hari pertama dengan subtema “Kebijakan Pelayanan Primer.”

Sesi ini dimoderatori oleh Mentari Widiastuti, MPH, Apt, yang membuka diskusi dengan menyoroti persistensi beban penyakit menular dan peningkatan beban penyakit tidak menular (PTM) di Indonesia. Kondisi tersebut mendorong lahirnya Integrasi Layanan Primer (ILP) sebagai bagian dari transformasi pelayanan primer sejak tahun 2022. Transformasi ini bertujuan mewujudkan layanan primer yang terintegrasi, komprehensif, dan berbasis siklus hidup.
Mentari juga menjelaskan bahwa implementasi ILP didukung oleh Konsorsium Primary Health Care (PHC) yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan bersama lembaga ThinkWell. Konsorsium ini menjadi wadah kolaborasi antara universitas, termasuk UGM, lembaga non-pemerintah, dan mitra lainnya untuk memperkuat layanan kesehatan primer serta memastikan pemerataan implementasi ILP di seluruh wilayah Indonesia.
Peran Perguruan Tinggi dalam Penguatan dan Keberlanjutan Implementasi ILP
 Dalam paparannya, Dr. Trihono menekankan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan ILP melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam bidang pendidikan, universitas dapat membuka peminatan pelayanan kesehatan primer serta memanfaatkan laboratorium lapangan untuk mendampingi pengelolaan layanan primer.
Dalam paparannya, Dr. Trihono menekankan bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan ILP melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam bidang pendidikan, universitas dapat membuka peminatan pelayanan kesehatan primer serta memanfaatkan laboratorium lapangan untuk mendampingi pengelolaan layanan primer.
Di bidang penelitian, kampus berperan dalam mengembangkan riset yang relevan dengan kebutuhan lapangan, seperti transformasi kelembagaan, sistem klaster layanan, hingga digitalisasi pemantauan wilayah. Hasil penelitian diharapkan menjadi dasar pengambilan kebijakan berbasis bukti dan inovasi layanan.
ILP sendiri merupakan respon atas lemahnya sistem kesehatan selama pandemi COVID-19. Hingga Oktober 2025, tercatat 8.188 puskesmas (79,7%) telah menerapkan ILP. Melalui pengabdian masyarakat, universitas berkontribusi dalam pendampingan puskesmas, pelatihan kader, dan peningkatan kapasitas tenaga kesehatan agar implementasi ILP berjalan lebih merata dan berkelanjutan.
Pembahas 1: Perkembangan dan Arah Keberlanjutan ILP dalam Kerangka Transformasi Pelayanan Kesehatan Primer
 Bahasan pertama dibawakan oleh Windy Oktavina, SKM, M.Kes dari Kementerian Kesehatan yang hadir secara daring. Windy menegaskan bahwa ILP merupakan pilar utama dalam transformasi pelayanan kesehatan primer di Indonesia. Fokus utamanya adalah memperkuat struktur layanan melalui empat inisiatif strategis; penguatan jejaring dan struktur, standardisasi layanan, edukasi kesehatan, serta digitalisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 19 Tahun 2024, pengembangan ILP dilakukan dengan sistem klaster yang mencakup lima area utama, meliputi pelaksana klaster manajemen, Klaster Kesehatan Ibu dan Anak, Klaster Kesehatan Dewasa dan Lansia, Klaster Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan dan Pelaksana Lintas klister. Dengan ILP, layanan berbasis komunitas, satuan pendidikan, tempat kerja, rujukan berjenjang, serta kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat terwujud. Windy menegaskan bahwa tujuan utama ILP adalah memastikan layanan kesehatan yang berkesinambungan bagi seluruh siklus hidup, mulai dari bayi, remaja, usia produktif, hingga lansia.
Bahasan pertama dibawakan oleh Windy Oktavina, SKM, M.Kes dari Kementerian Kesehatan yang hadir secara daring. Windy menegaskan bahwa ILP merupakan pilar utama dalam transformasi pelayanan kesehatan primer di Indonesia. Fokus utamanya adalah memperkuat struktur layanan melalui empat inisiatif strategis; penguatan jejaring dan struktur, standardisasi layanan, edukasi kesehatan, serta digitalisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 19 Tahun 2024, pengembangan ILP dilakukan dengan sistem klaster yang mencakup lima area utama, meliputi pelaksana klaster manajemen, Klaster Kesehatan Ibu dan Anak, Klaster Kesehatan Dewasa dan Lansia, Klaster Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan dan Pelaksana Lintas klister. Dengan ILP, layanan berbasis komunitas, satuan pendidikan, tempat kerja, rujukan berjenjang, serta kolaborasi lintas sektor diharapkan dapat terwujud. Windy menegaskan bahwa tujuan utama ILP adalah memastikan layanan kesehatan yang berkesinambungan bagi seluruh siklus hidup, mulai dari bayi, remaja, usia produktif, hingga lansia.
Sesi ini menekankan bahwa ILP menjadi kunci transformasi pelayanan kesehatan di Indonesia. Pendekatan berbasis siklus hidup mendorong layanan yang komprehensif dan berkelanjutan dilakukan dengan penguatan skrining kesehatan dan faktor risiko sebagai upaya pencegahan penyakit. Puskesmas sebagai penanggung jawab wilayah, diperkuat dan didukung oleh jejaring pustu, posyandu, dan kader kesehatan di tingkat komunitas. Pemerintah daerah dan berbagai mitra lintas sektor memiliki peran penting dalam memastikan keberlanjutan ILP Kolaborasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat menjadi kunci agar transformasi pelayanan kesehatan primer dapat berjalan efektif dan berdaya guna.
Pembahas 2: Meninjau ILP dari Perspektif Teori Organisasi: Kunci Keberlanjutan dan Transformasi Pelayanan Kesehatan Primer
 Prof. Dr. dr. Mubasysyir Hasanbasri, M.A meninjau ILP melalui lensa teori organisasi, dengan menekankan pentingnya sistem yang adaptif dan kolaboratif agar transformasi kesehatan primer dapat berkelanjutan. Beliau mempertanyakan: apakah ILP sudah benar-benar menyejahterakan masyarakat atau masih berfokus pada penyembuhan individu semata? Menurutnya, pendekatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) harus terintegrasi tanpa sekat, karena kesehatan tidak cukup diintervensi di fasilitas layanan; rumah dan komunitas harus menjadi lingkungan sehat. Beliau memberikan contoh kasus TB di komunitas seharusnya menjadi tanggung jawab sosial bersama, di mana kepala desa dapat menetapkan aturan pencegahan penularan sebagaimana diterapkan pada masa pandemi.
Prof. Dr. dr. Mubasysyir Hasanbasri, M.A meninjau ILP melalui lensa teori organisasi, dengan menekankan pentingnya sistem yang adaptif dan kolaboratif agar transformasi kesehatan primer dapat berkelanjutan. Beliau mempertanyakan: apakah ILP sudah benar-benar menyejahterakan masyarakat atau masih berfokus pada penyembuhan individu semata? Menurutnya, pendekatan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) harus terintegrasi tanpa sekat, karena kesehatan tidak cukup diintervensi di fasilitas layanan; rumah dan komunitas harus menjadi lingkungan sehat. Beliau memberikan contoh kasus TB di komunitas seharusnya menjadi tanggung jawab sosial bersama, di mana kepala desa dapat menetapkan aturan pencegahan penularan sebagaimana diterapkan pada masa pandemi.
Prof. Mubasysyir menekankan bahwa tujuan ILP adalah menjaga populasi agar tetap sehat melalui sistem yang kolaboratif dan terintegrasi dengan melibatkan komunitas sehingga bisa menjamin pasien yang membutuhkan pengobatan rutin tidak “drop out” dari rantai pelayanan hingga sembuh. Ia juga mengingatkan bahwa kemitraan lintas sektor, termasuk peran desa, dinas sosial, dan lembaga Pendidikan merupakan kunci keberlanjutan ILP. Dari perspektif Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM), keberhasilan ILP tercermin dari kemampuan sistem dalam menghilangkan sekat antara layanan dan masyarakat, serta memastikan pemerataan akses bagi semua kelompok. Pelayanan kesehatan diberikan kepada sasaran yang tepat dan berkeadilan, sehingga mampu mewujudkan “desa sehat” sebagai unit terkecil dari sistem kesehatan nasional.
Sesi Diskusi

Diskusi berlangsung interaktif dengan dua pertanyaan utama. Penanya pertama, Cornelis, mengangkat isu ketersediaan dua tenaga kesehatan per desa, mengingat keterbatasan fiskal daerah dan ketimpangan kapasitas antarwilayah. Ia juga menyinggung dilema prioritas antara UKM dan UKP di tengah pertumbuhan penduduk yang pesat. Menanggapi hal ini, Windy menjelaskan bahwa kebijakan dua nakes per desa dilakukan melalui skema P3K dengan mempertimbangkan kondisi infrastruktur, apakah terdapat polindes maupun pustu dan apakah masih berfungsi atau perlu perbaikan. Skrining dilakukan berbasis keluarga, bukan massal, dengan pendekatan kunjungan rumah untuk deteksi dini dan tindak lanjut pengobatan. Dr. Trihono menambahkan bahwa penerapan satu pustu di setiap desa perlu mempertimbangkan konteks lokal. Model ini efektif di wilayah dengan jumlah penduduk besar, namun di daerah perkotaan atau desa berpenduduk kecil, pelayanan dapat dioptimalkan melalui posyandu dan dokter keluarga. Pendekatan fleksibel ini diharapkan menjaga efisiensi tanpa mengurangi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar.
Pertanyaan kedua dari Luxi menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia mengusulkan adanya Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan yang menyatukan isu sosial, pendidikan, dan lingkungan. Prof. Mubasysyir menanggapi bahwa penyelesaian masalah kesehatan harus dimulai dari hulu, dengan riset pohon penyakit guna mengidentifikasi akar penyebab. Misalnya, stunting yang disebabkan oleh sanitasi buruk memerlukan intervensi lintas sektor. Dr. Trihono menambahkan contoh dari puskesmas di Kalimantan yang berhasil memperbaiki kesehatan lingkungan dengan mengubah area pinggiran sungai yang tadinya dipenuhi jamban yang tidak sehat menjadi tempat wisata. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan multisektor dapat menciptakan perubahan berkelanjutan, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi masyarakat.
Penutup
Sesi ini menegaskan bahwa keberhasilan ILP sebagai strategi transformasi layanan kesehatan primer tidak dapat dicapai hanya melalui kebijakan teknis, tetapi memerlukan kolaborasi lintas sektor dan dukungan perguruan tinggi. Pemahaman teoritis, riset terapan, serta pengabdian masyarakat menjadi pondasi penting dalam memastikan ILP berkelanjutan. Dengan keterlibatan semua pihak baik pemerintah, akademisi, dan Masyarakat maka transformasi menuju sistem kesehatan yang kuat, adil, dan berorientasi pada siklus hidup akan menjadi nyata.
Reporter: Leyna C (PKMK UGM)