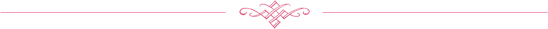Pada Sabtu (2/3/2019), S2 IKM FK – KMK menyelenggarakan seminar nasional terkait DBD di Auditorium Lantai 8, Gedung Pascasarjana Tahir, FK – KMK UGM. Seminar Nasional Demam Berdarah Dengue (DBD) dalam Perspektif Sistem Kesehatan bertujuan untuk membahas mengenai situasi terakhir DBD di Indonesia, peran lintas profesi dalam pencegahan dna penanganan DBD dan strategi penanganan DBD dan penyakit menular lainnya dalam perspektif sistem kesehatan. Seminar ini terbagi menjadi tiga sesi utama sesuai dengan tujuannya. Pada sesi pertama, lebih banyak dibahas mengenai gambaran dan situasi DBD di Indonesia serta beberapa program yang telah dilakukan terkait kasus DBD.
dr. Citra Indriyani, MPH mengawali pemaparan pertama dengan menjelaskan bahwa 75% beban dengue dunia ada di Asia Pasifik. Insidensinya secara tahunan selalu meningkat dari waktu ke waktu (sejak 1968- 2017) dan memiliki korelasi terhadap perubahan iklim. Jika perubahan iklim semakin tidak terkendali, maka beban dengue yang ada akan semakin meningkat. Hal ini ditandai dengan jumlah dengue meningkat ketika La Nina (1988,1996, 1998) terjadi sementara akan menurun pada saat El Nino (1987,1991,1994,1997). Namun demikian, angka fatalitas DBD menurun sejak 1968 – 2017 dengan tersedianya tatalaksana efektif. Sejak 2008, angka fatalitas DBD di Indonesia telah mencapai <1%.
DBD menyerang berbagai kelompok usia di Indonesia. Sejak 1993 – 2013, trend insidensi DBD pada kelompok usia > 15 tahun paling banyak meningkat, sementara untuk usia 5 – 14 tahun terjadi penurunan. Di Yogyakarta, diketahui bahwa 68% anak usia 1 – 10 tahun pernah terinfeksi dengue, dengan proporsi infeksi dengue yang meningkat seiring dengan peningkatan usia. Jumlah prevalensi infeksi multitipik pada kelompok 1 -18 tahun mencapai 50% lebih. Penyebaran kasus DBD sangat beragam dan ada di sekitar kita dengan kejadian kasus naik atau turunnya tergantung pada karateristik dari daerah tersebut.
Berdasarkan kategori WHO (2011), Indonesia termasuk pada hiperendemis DF/DBD. Hal tersebut mengacu pada empat kriteria yang dimiliki oleh Indonesia, yakni : masih merupakan masalah kesehatan utama, penyebab kematian dan hospitalisasi anak, adanya 4 serotipe yang bersirkulasi dan penyebaran hingga ke area pedesaan (rural area). Surveilans dengue di Indonesia terdiri dari surveilans pasif dan surveilans berbasis rumah sakit melalui KDRS (kewaspadaan dini rumah sakit). Di masa asimptomatik, jumlah virus dengue berada pada jumlah yang paling banyak pada tubuh seseorang dan periode ini sangat berperan dari terjadinya transmisi dengue.
Dr. dr. Ida Safitri, Sp.A(K) melanjutkan pemaparan mengenai tatalaksana klinis terbaru DBD. Terdapat dua guideline yang menjadi referensi tatalaksana DBD, yakni WHO 2011 dan WHO 2009. Saat ini Indonesia mengacu pada tatalaksana menurut WHO 2011 sebagai referensi bagi negara Asia Tenggara yang diterbitkan oleh WHO SEARO. Berdasarkan guideline tersebut, terdapat tiga klasifikasi yakni dengue fever, dengue haemorraghic fever dan expanded dengue syndrome. Untuk kriteria expanded dengue syndrome belum terwadahi oleh kode pembiayaan BPJS yang terbaru di fasilitas pelayanan kesehatan.
Warning signs merupakan tanda klinis dari seseorang yang patut menjadi perhatian utama. Sebelum terjadi perubahan parameter laboratorium, tubuh sudah menunjukkan tanda dari warning signs. Pada saat pasien sudah menunjukkan tanda warning signs, maka ia harus segera diobservasi. Adapun tanda dan gejala warning signs diantaranya ditandai dengan muntah berulang, letargi, perdarahan, tidak ada perbaikan klinis saat suhu reda, tidak bisa makan dan minum, keadaan pucat dengan ekstrimitas dingin dan diuresisi yang menurun hingga 4 – 6 jam. Perlu diketahui bahwa kegawatan pada dengue bukan pada penurunan trombosit melainkan pada kondisi terjadinya kebocoran plasma. Selanjutnya dilakukan penatalaksanaan sesuai penegakkan kondisinya : sindrom syok dengue terkompensasi dan sindrom syok dengue dekompensasi.
Terkait dengan penatalaksanaan DBD di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), penegakkan diagnosa sesuai dengan kompensasi BPJS dilakukan berdasarkan pada hasil pemeriksaan kadar trombosit. Seharusnya, untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, perlu melihat kembali pada tanda klinis dari pasien. Kasus – kasus Dengeu Shock Syndrome (DSS) dengan penyulit di PPK III juga masih memberikan beban biaya yang cukup besar dan melebihi paket biaya yang disediakan oleh BPJS berdasarkan pada data biaya perawatan DFH/DSS RSUP Dr. Sardjito Januari – Februari 2019. Oleh sebab itu, perlu dikaji kembali mengenai penegakkan diagnosis dan jumlah pembiayaan yang tepat bagi kasus dengue di PPK. Di samping itu, perlu juga dilakukan uji deteksi antigen serologi sebagai konfirmasi diagnostik (mengingat banyak penyakit dengan demam yang bergejala mirip dengan infeksi dengue) serta perhatian pada pengenalan tanda bahaya dan tatalaksana awal kegawatan terkait kasus dengue yang akan berpengaruh pada hasil outcome.
Pada paparan yang ketiga, dr. Lutfan Lazuardi, M.Kes., PhD menerangkan lebih banyak mengenai penggunaan sistem informasi kesehatan untuk melakukan prediksi terjadinya wabah DBD. Menurutnya, sistem deteksi saat ini masih tergolong terlambat dalam hal pelaporan mengenai kasus DBD. Seringkali kejadian atau outbreaks sudah terlanjur terjadi tanpa ada prediksi sebelumnya. Sistem prediksi menjadi penting sebagai sistem kewaspadaan dini/deteksi dini dan informasi untuk melakukan respon. Prediksi dapat dilakukan dengan memanfaatkan data yang aksesibel dan mudah didapatkan, mendekati real time dan free-access/gratis.
Kenaikan suhu permukaan laut sebesar 1,5 derajat Celcius berpengaruh besar pada terjadinya perubahan iklim yang bermanifestasi pada angka kejadian DBD.
Berdasarkan kajian ini, kasus DBD dapat diprediksi dengan data cuaca. Demikian halnya hasil yang ditemukan dari sebuah riset terbaru yang dilakukan di Indonesia dengan memanfaatkan salah satu akses data gratis melalui data google trends. Berdasarkan penelitian ini, diketahui bahwa data google trends memiliki pola deret waktu linier dan secara statistik berkorelasi dengan laporan demam berdarah yang resmi dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan. Pemanfaatan penggunaan google trends lebih lanjut dapat menjadi potensi sebagai salah satu pengawasan penyakit di Indonesia dengan perlunya mengidentifikasi perilaku pencarian informasi bagi penggunanya. Di samping itu, analisis data juga merupakan kunci dari kajian model prediksi pada kesehatan yang data analisisnya dapat digunakan dari berbagai sumber mumpuni, terutama di era big data system saat ini.
Dr. Retna Siwi Padmawati melengkapi paparan mengenai pencegahan melalui perilaku dan lingkungan. Beberapa hal yang telah dilakukan oleh masyarakat saat ini antara lain : pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M dan gerakan 1 rumah 1 jumantik; kegiatan promosi kesehatan melalui jumantik sekolah dan pramuka; pokjanal DBD dan penemuan dini kasus dan pengobatannya. Namun sejauh mana efektivitas dan sustainability dari pelaksanaan program tersebut masih menjadi pekerjaan rumah kita bersama. Salah satu studi yang dilakukan di Kuba (wilayah non – endemis DBD) menunjukkan bahwa dukungan pemerintah, ketersediaan link antara masyarakat, struktur program dan pemerintah serta adanya mobilisasi masyarakat menjadi faktor penting. Pendekatan yang selama ini dilakukan melalui COMBI (community for behavioural impact) dan pemberdayaan masyarakat perlu untuk dipertahankan. Sementara itu, pendekatan lain melalui participatory action research juga dibutuhkan dengan tidak hanya terbatas pada penelitian yang dilakukan tetapi juga mendapatkan intervensi yang memberikan dampak perubahan perilaku positif bagi pencegahan kasus. Beberapa hal yang menjadi tindak lanjut ke depannya antara lain penguatan advokasi, penguatan mobilisasi sosial dan tentu saja komunikasi dan koordinasi secara lintas sektor.
Paparan akhir diberikan oleh dr. Riris Andono Ahmad, Ph.D melalui kajian riset pengendalian dengue dengan teknologi Wolbachia. Tantangan kasus DBD di Indonesia masih menjadi masalah sebab angka kasus yang masih meningkat fluktuatif, uatamanya saat musim penghujan tiba. Vector nyamuk Aedes Aegepty cenderung dekat dengan perilaku manusia, dengan karakteristik tidak berbunyi, tidak sakit jika menggigit, tidak suka bau wangi dan suka menggigit di bagian bawah tubuh. Tantangan pengendalian dengue saat ini adalah masih belum tersedianya vaksin yang 100% efektif, belum tersedianya obat untuk dengue, 70& kasus bersifat asimptomatis, dan belum kuatnya sistem surveilans.
Melalui Eliminate Dengue Project (EDP), dikembangkan pemanfaatan bakteri alami Wolbachia yang memiliki kapasitas menekan pengembangan virus dengue. Wolbachia berfungsi sebagai vaksin pada tubuh nyamuk yang disebarluaskan sendiri dengan cara berkawin dengan nyamuk lain dan melahirkan nyamuk dengan Wolbachia didalam tubuhnya. Dengan adanya Wolbachia didalam tubuh nyamuk, maka virus dengue tidak memiliki kesempatan untuk berkembang dan berakibat pada nyamuk aedes aegypti yang tidak bisa mendistribusikan virus dengue sebagai penyebab dari kejadian DBD.
Penggunaan nyamuk dengan Wolbachia dilakukan di Yogyakarta, terutama di Sleman dan Bantul. Penelitian ini dilakukan dalam 4 fase yang terdiri dari fase persiapan dan kelayakan penialian keamanan, fase penyebaran skala terbatas nyamuk aedes aegypti dengan Wolbachia, fase penyebaran skala luas nyamuk Aedes Aegypti dengan Wolbachia dan fase penguatan adopsi dan implementasi kebijakan. Saat ini, riset yang sedang dilakukan berada pada fase ketiga untuk penyebaran skala luas. Hasil sementara yang didapatkan menunjukkan terjadi penurunan kasus DBD di wilayah sasaran penyebaran.
(Reporter: Kurnia Widyastuti/ PKMK)
{jcomments on}