Pendahuluan
Di Indonesia, 1,2 juta penyandang disabilitas memiliki akses ke JKN-PBI, dan sekitar 20.404 orang menerima alat bantu sejak 2015 hingga 2017 (TNP2K & Pemerintah Australia, 2019). Namun, jaminan kesehatan yang telah dimiliki oleh orang dengan disabilitas tersebut dinilai belum optimal dalam menyediakan manfaat pelayanan kesehatannya. Disisi lain, pelayanan kesehatan yang tersedia dinilai masih sulit untuk diakses oleh orang disabilitas karena fasilitas kesehatan belum inklusif. Saat ini, jaminan kesehatan telah menyediakan manfaat untuk disabilitas berupa alat bantu kesehatan seperti alat bantu dengar, protesa alat gerak, korset tulang belakang serta collar neck dan kruk sesuai dengan standar yang telah⁷ ditetapkan dalam Permenkes 28/2014. Namun, memastikan pencapaian UHC di Indonesia telah inklusif untuk kelompok rentan-marginal utamanya orang dengan disabilitas, tidak cukup hanya dengan melihat jumlah alat bantu yang telah diberikan. Hal ini karena kebutuhan kesehatan disabilitas tidak hanya berkaitan dengan alat bantu, tetapi mereka juga perlu untuk mendapat pelayanan kesehatan mendasar lainnya.
Untuk itu, PKMK FK-KMK UGM dengan dukungan INKLUSI melakukan survei di Bali, DI Yogyakarta dan NTT pada September – Desember 2023 untuk mengukur manfaat pelayanan kesehatan pada penyandang disabilitas yang telah didapatkan. Saat ini, terdapat 2666 data yang telah kami kumpulkan dan analisis. Dari data tersebut, kami mengetahui jumlah penyandang disabilitas yang memiliki jaminan kesehatan nasional (JKN), yang memiliki alat bantu kesehatan dan kualitasnya, dan yang mengakses pelayanan kesehatan dan kualitasnya. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif sehingga pada Januari – Februari kami melakukan FGD dengan pemangku kepentingan. Dari hasil FGD tersebut didapatkan bahwa masing-masing pemangku kepentingan telah berperan untuk menyediakan kebutuhan kesehatan penyandang disabilitas. Namun, hasil FGD kami menemukan masih adanya tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam menyediakan pelayanan kesehatan inklusif untuk penyandang disabilitas. Selain itu, berdasarkan pengalaman dari penyandang disabilitas, terdapat tantangan yang mereka hadapi ketika mengakses pelayanan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan RS. Tantangan yang paling banyak dihadapi adalah sarana prasarana dan tenaga kesehatan yang tidak inklusif untuk penyandang disabilitas. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pertimbangan bagi pengambil keputusan untuk menyusun kebijakan kesehatan yang inklusif. Kemudian, Mitra INKLUSI dan organisasi penyandang disabilitas lainnya dapat memanfaatkan untuk proses advokasi kebijakan tingkat nasional dan daerah.
Tujuan
- Memaparkan hasil penelitian mengenai implementasi pelayanan kesehatan bagi penyandang disabilitas fisik, disabilitas sensorik, dan disabilitas ganda
- Mendiskusikan tantangan dan peluang dalam perbaikan layanan kesehatan bagi penyandang disabilitas fisik, disabilitas sensorik, dan disabilitas ganda
- Menyampaikan rekomendasi kebijakan untuk peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan yang inklusif bagi penyandang disabilitas fisik, disabilitas sensorik, dan disabilitas ganda
Waktu
Hari, tanggal : Rabu, 30 Oktober 2024
Pukul : 12.00 – 16.00 WIB
Tempat : Ruang Auditorium Lt. 1, Gedung Pascasarjana Tahir Sayap Utara, FK-KMK UGM
Poster
- Penggunaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Penyandang Disabilitas Fisik dan Sensorik
- Kondisi Pelayanan Kesehatan yang Diakses dan Dimanfaatkan Penyandang Disabilitas di IndonesiaDiakses dan Dimanfaatkan Penyandang Disabilitas di Indonesia
- Mengenal Kebutuhan Terapi Bagi Penyandang DisabilitasPenyandang Disabilitas
- Situasi dan Tantangan Penyediaan Alat bantu dan Alat Bantu Kesehatan untuk Penyandang Disabilitas Fisik dan SensorikPenyediaan Alat bantu dan Alat Bantu Kesehatan untuk Penyandang Disabilitas Fisik dan Sensorik
| Waktu | Kegiatan | |
| 12.00 – 13.00 WIB | Registrasi Peserta dan Makan Siang Bersama | |
|
13.00 – 13.10 WIB |
Sambutan
|
|
| 13.10 – 13.15 WIB |
Pembukaan: Dr. Dra. Retna Siwi Padmawati, M.A – Ketua Tim Penelitian |
|
| 13.15 – 14.20 WIB |
Presentasi Hasil Penelitian
|
|
| 14.20 – 15.20 WIB |
Pembahasan dalam bentuk Talk Show
|
|
| 15.20 – 15.45 WIB | Diskusi: tanya dan jawab – Shita Listya Dewi – Peneliti | |
| 15.45 -16.00 WIB |
Penutupan – Dr. Dra. Retna Siwi Padmawati, M.A – Ketua Tim Penelitian |
|
PKMK-Yogya. Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada (PKMK FK-KMK UGM) bekerja sama dengan INKLUSI menyelenggarakan Diseminasi Hybrid yang bertajuk “Analisis Imlementasi Pelayanan Kesehatan untuk Penyandang Disabilitas (Fisik dan Sensorik) dalam Mencapai Universal Health Coverage (UHC)” pada Rabu (30/10/2024). Kegiatan penelitian ini didukung oleh Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia melalui progam INKLUSI Kemitraan Autralia-Indonesia Menuju Masyarakat Inklusif.

Acara dibuka dengan sambutan yang disampaikan oleh Dr. dr. Andreasta Meliala, M.Kes, MAS selaku Ketua PKMK mengenai tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas agar dapat menerima pelayanan kesehatan, baik di layanan kesehatan primer maupun rujukan. Melalui UHC, diharapkan tidak ada perbedaan dalam mengakses layanan kesehatan termasuk untuk para penyandang disabilitas. Selain itu, pelayanan kesehatan harus inklusif dan tidak membedakan seperti slogan “No one left behind”.
Sambutan kedua disampaikan oleh Irene Widjaya selaku Head of Partnership and Policy INKLUSI. Irene menyampaikan pentingnya program ini agar dapat meningkatkan kualitas hidup kawan-kawan penyandang disabilitas. Riset ini diharapkan dapat memberikan informasi berbasis data kepada pemangku kepentingan terkait implementasi layanan kesehatan penyandang disabilitas.
Dr. Dra. Retna Siwi Padmawari, M.A selaku Ketua Tim Penelitian memaparkan bahwa penelitan telah dilakukan sejak bulan 2023 hingga September 2024 di Yogyakarta, Bali, dan di Nusa Tenggara Timur (NTT). Penelitian ini telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan khusunya mitra INKLUSI yaitu SIGAB dan YAKKUM, pemerintah pusat meliputi Kementerian Kesehatan, BAPPENAS, Kemenko PMK, Kementrian Sosial dan Komisi Nasional Disabilitas. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan pemerintah daerah setempat seperti Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan BAPPEDA. Penelitian ini merupakan Langkah awal untuk menganalisis tantangan pelayanan Kesehatan yang dihadapi penyandang disabilitas. Penelitian ini juga diharapkan dapat membantu proses advokasi kebijakan serta dapat menjadi data/evidence untuk menyusun kebijakan.

Kegiatan pemaparan hasil penelitian dimoderatori oleh Shita Listya Dewi, MM., MPP., selaku peneliti PKMK FK-KMK UGM dan wakil direktur PKMK FK-KMK UGM. Terdapat 4 peneliti yang memaparkan hasil penelitian.
Tri Muhartini, MPA memaparkan hasil penelitian yang menemukan bahwa kebijakan kesehatan untuk penyandang disabilitas di level telah tersedia. Namun, masih belum dapat diimplementasikan secara optimal karena terbatasnya kebijakan operasional. Sementara itu, di level daerah, kebijakan kesehatan untuk penyandang disabilitas masih berpusat pada Peraturan Daerah tentang penyandang disabilitas yang hanya mengatur hak-hak kesehatan secara prinsip. Kondisi ini dapat terjadi karena terbatasnya data untuk merumuskan kebijakan, keterbatasan pemahaman tentang disabilitas, dan urusan disabilitas masih terpusat di Dinas Sosial (untuk level daerah). Kondisi ini membuat penyandang disabilitas mengalami keterbatasan akses ke fasilitas pelayanan kesehatan. Di sisi lain, fasilitas pelayanan kesehatan yang telah diakses belum memiliki sarana prasarana inklusif untuk penyandang disabilitas. Kondisi ini semakin diperburuk dengan SDM (sumber daya manusia) kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang belum dapat berkomunikasi sensitif dengan disabilitas.
Relmbus Fanda, MPH menyampaikan jika sebagian besar responden disabilitas fisik dan sensorik dari penelitian yakni 89% telah memiliki JKN, sedangkan yang belum memiliki JKN sebanyak 11,25% (300 disabilitas). Alasan belum memiliki JKN salah satunyakarena sistem pendaftaran belum dimengerti dan tidak mampu membayar premi. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah berupaya untuk memastikan penyandang disabilitas tercakup dalam JKN. Namun, penyanadang disabilitas yang memiliki JKN, hanya 25% memanfaatkannya. Terbatasnya pemanfaatan itu karena layanan JKN belum mencakup kebutuhan, tidak jelasnya layanan dan kepastian keaktifan peserta. Dari hasil analisis regresi, ditemukan salah satu faktor yang mempengaruhi penyandang disabilitas memanfaatkan JKN.
Ardina Nugrahaeni, MPH memaparkan hasil survei terkait kepemilikan alat bantu kesehatan, menunjukkan bahwa 66,35% penyandang disabilitas tidak memiliki alat bantu. Alasan utama meliputi tidak merasa membutuhkan, keterbatasan biaya, dan kurangnya informasi. Tantangan dalam penyediaan alat bantu melibatkan keterbatasan produksi dalam negeri, anggaran daerah, serta keterbatasan cakupan jenis dan tarif alat bantu di BPJS Kesehatan.
Muhamad Faozi Kurniawan, SE, MPH menyampaikan akses terhadap layanan terapi, seperti terapi fisik, wicara, dan okupasi, untuk penyandang disabilitas. Hasil menunjukkan bahwa 75% responden tidak mengakses layanan terapi, dengan alasan terbesar adalah tidak membutuhkan. Tantangan yang dihadapi termasuk kurangnya layanan terapi di Puskesmas dan keterbatasan durasi terapi yang didanai JKN.
Secara keseluruhan, temuan ini menunjukkan bahwa kebijakan kesehatan yang mengatur kebutuhan layanan kesehatan disabilitas saat ini sudah tersedia namun dalam pelaksanaan masih belum optimal. Selain itu, diperlukan pedoman untuk fasilitas pelayanan kesehatan inklusif, menyediakan pelayanan khusus seperti deteksi dini risiko disabilitas, informasi dan akses alat bantu kesehatan, materi dan metode komunikasi. Dari sisi pembiayaan kesehatan untuk penyandang disabilitas perlu adanya penguatan JKN dengan skema khusus untuk penyandang disabilitas.
Terdapat 5 pembahas yang memberikan komentar terhadap hasil penelitian yaitu:
drg. Vensya Sitohang, M.Epid., PhD selaku Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lansia, Ditjem Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan sedang menyusun Peraturan Menteri yang merupakan turunan dari UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023, yang mencakup substansi tentang kesehatan penyandang disabilitas. Rancangan ini mengedepankan kebutuhan SDM di Puskesmas, termasuk psikolog klinis dan fisioterapis sebagai tenaga prioritas. Tantangan terbesar dalam penyusunan kebijakan ini adalah kurangnya data tentang jumlah, jenis disabilitas, dan kebutuhan terapi spesifik. Kemenkes juga sedang mengembangkan kurikulum layanan kesehatan inklusif, dengan dua rancangan peraturan yang mengakomodasi penyandang disabilitas.
Sedy Fajar Muhamad selaku Analis Kebijakan Penjaminan Manfaat Rujukan BPJS Kesehatan menyebut bahwa tantangan utama dalam layanan untuk penyandang disabilitas meliputi akses, sarana prasarana, dan SDM, khususnya terkait jarak geografis dan transportasi. Saat ini, BPJS belum mencakup biaya transportasi, sehingga skema JKN belum mampu memenuhi kebutuhan perjalanan ke fasilitas kesehatan.
drg. Lien Andriany, M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan NTT menyampaikan bahwa di NTT, masalah akses, sarana, dan SDM masih menjadi kendala dalam layanan disabilitas. NTT sedang mengembangkan layanan telemedicine dan telekonsultasi untuk meningkatkan akses di daerah terpencil dan mendorong integrasi layanan primer yang lebih inklusif.
Iftita Rakhma Ikrima, MTPn selaku Perencana Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan BAPPENAS menyoroti pentingnya penguatan sistem dan integrasi regulasi untuk memastikan layanan kesehatan inklusif bagi penyandang disabilitas. Selain akses, kualitas layanan juga harus setara dan ramah bagi mereka. Partisipasi masyarakat juga penting untuk mendukung layanan kesehatan yang inklusif.
Muh Syamsudin, S.E. selaku Wakil Direktur SIGAB menekankan pentingnya pendampingan bagi penyandang disabilitas dalam mengakses layanan kesehatan. Banyak penyandang disabilitas yang menahan sakit karena kurangnya rasa percaya diri atau takut ditolak. Pendampingan tidak hanya bersifat psikologis tetapi juga terkait dengan akses layanan kesehatan yang setara.
Sigit Triyono, A.Md. Kep selaku Kasi Tim Medis Pusat Rehabilitasi YAKKUM menjelaskan bahwa rehabilitasi bagi penyandang disabilitas bertujuan memenuhi hak kesehatan mereka, dengan kolaborasi dari pemerintah daerah, seperti Dinkes dan Dinas Sosial. Hambatan utama dalam rehabilitasi adalah stigma masyarakat yang masih tinggi.
Acara ini ditutup oleh Dr. Dra. Retna Siwi padmawati, M.A yang menyampaikan harapan dari diseminasi ini agar dapat dikembangkan sebagai kebijakan bagi penyandang disabilitas.

Reporter:
Irma Noor Budianti (Divisi Public Health, PKMK FK-KMK UGM)



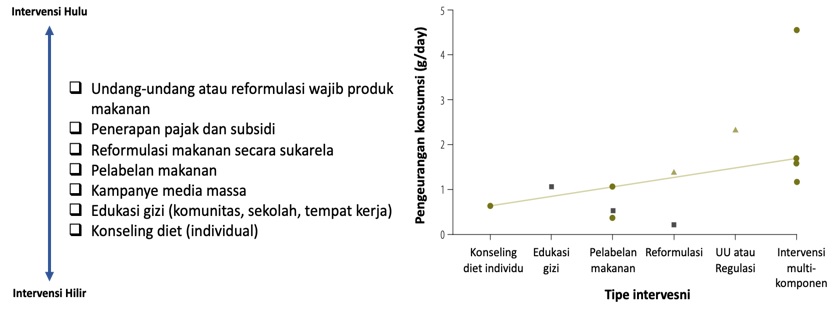

 Bencana nasional non alam yang disebabkan oleh Corona virus Disease (COVID-19) berdampak terhadap ekonomi, sosial dan kesehatan masyarakat secara luas. Pemerintah telah menetapkan bencana non alam ini sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
Bencana nasional non alam yang disebabkan oleh Corona virus Disease (COVID-19) berdampak terhadap ekonomi, sosial dan kesehatan masyarakat secara luas. Pemerintah telah menetapkan bencana non alam ini sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
 Pandemi COVID-19 telah menjadi tantangan pada sistem kesehatan dan dalam banyak kasus, melebihi kapasitas rumah sakit dan unit perawatan intensif (ICU). Para profesional kesehatan di fasilitas rujukan COVID-19 bekerja berjam – jam dengan mengenakan alat pelindung diri (APD) yang merepotkan dan tidak nyaman. Petugas kesehatan terus memberikan perawatan untuk pasien meskipun kelelahan, berisiko infeksi pribadi, ketakutan menularkan ke anggota keluarga, kecemasan terhadap penyakit atau kematian teman dan kolega, dan kehilangan banyak pasien.
Pandemi COVID-19 telah menjadi tantangan pada sistem kesehatan dan dalam banyak kasus, melebihi kapasitas rumah sakit dan unit perawatan intensif (ICU). Para profesional kesehatan di fasilitas rujukan COVID-19 bekerja berjam – jam dengan mengenakan alat pelindung diri (APD) yang merepotkan dan tidak nyaman. Petugas kesehatan terus memberikan perawatan untuk pasien meskipun kelelahan, berisiko infeksi pribadi, ketakutan menularkan ke anggota keluarga, kecemasan terhadap penyakit atau kematian teman dan kolega, dan kehilangan banyak pasien.
 Stunting banyak terjadi di negara miskin dan berkembang, salah satunya Indonesia. Stunting bukan hanya masalah badan yang pendek, melainkan juga masalah gizi buruk pada anak – anak yang dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Di Indonesia masyarakat masih menganggap stunting merupakan keturunan, padahal hasil penelitian menunjukkan genetik berkontribusi sebesar 15% (Absori et al, 2022). Sementara menurut Brinkman et al dalam Absori et al (2022), faktor – faktor yang mempengaruhi stunting adalah infeksi berulang, hormon pertumbuhan, nutrisi, asap rokok, dan polusi.
Stunting banyak terjadi di negara miskin dan berkembang, salah satunya Indonesia. Stunting bukan hanya masalah badan yang pendek, melainkan juga masalah gizi buruk pada anak – anak yang dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia. Di Indonesia masyarakat masih menganggap stunting merupakan keturunan, padahal hasil penelitian menunjukkan genetik berkontribusi sebesar 15% (Absori et al, 2022). Sementara menurut Brinkman et al dalam Absori et al (2022), faktor – faktor yang mempengaruhi stunting adalah infeksi berulang, hormon pertumbuhan, nutrisi, asap rokok, dan polusi.
