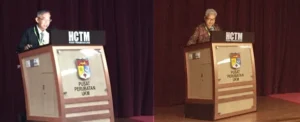Laksono Trisnantoro, Guru Besar Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
KOMPAS, 21 Agustus 2015
Tahun 2015, atau 70 tahun setelah Indonesia merdeka, status kesehatan masyarakat ternyata masih belum menggembirakan. Meskipun Pemerintah Indonesia-dalam hal ini Kementerian Kesehatan-telah berusaha keras, angka kematian ibu dan bayi masih tinggi, bahkan di daerah-daerah perkotaan yang mempunyai fasilitas dan tenaga kesehatan cukup.
Masyarakat yang mengidap tuberkulosis (TB) masih bertambah. Pengidap HIV/AIDS juga terus meningkat. Lebih memprihatinkan lagi, kondisi ini seiring dengan meningkatnya jumlah penyakit tidak menular, seperti diabetes, kanker, serta jantung. Anak-anak dan ibu hamil dengan gizi buruk, juga yang terlalu gemuk, masih banyak ditemui. Pengendalian pemakaian tembakau masih belum berjalan baik. Seolah semua usaha jalan di tempat.
Sebenarnya ada pelbagai kemajuan yang patut diapresiasi. Di sisi perlindungan untuk kesehatan masyarakat, misalnya, sudah ada Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Jaminan Kesehatan Daerah. Jumlah rumah sakit, tenaga kesehatan, dan dokter juga meningkat meskipun belum merata. Daerah-daerah dengan kondisi geografis sulit, seperti Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Barat, memang masih jauh tertinggal.
Sebaliknya, masyarakat yang mampu memilih masih belum puas dengan mutu pelayanan kesehatan. Masih banyak pasien Indonesia yang berobat ke negara lain. Sementara akses masyarakat miskin di sejumlah daerah sulit masih menjadi masalah besar. Sesungguhnya apa yang kurang dalam sistem kesehatan di negara yang sudah merdeka 70 tahun ini?
Negara kesejahteraan
Ketika Indonesia merdeka tahun 1945, para pendiri bangsa telah menulis di UUD 1945 yang menyatakan Indonesia sebagai negara kesejahteraan. Fakir miskin ditanggung negara, termasuk urusan kesehatan. Akan tetapi, yang diwariskan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda dan Jepang bukanlah sistem kesehatan yang bertujuan melindungi masyarakat dari sakit, khususnya mereka yang miskin.
Pada masa penjajahan, sistem kesehatan dibangun terutama untuk kepentingan penjajah melindungi aparat pemerintah serta karyawan perusahaan besar dari risiko sakit. Akibatnya, setelah Indonesia merdeka, amanah UUD 1945 tidak mudah dijalankan, terutama dalam pembiayaan sektor kesehatan.
Dalam pelayanan kesehatan untuk perorangan, setelah kemerdekaan, RS-RS milik gereja kehilangan sumber dana bantuan kemanusiaan dari Eropa. Maka, RS-RS keagamaan harus mencari dana dari pasien karena pemerintah tidak mempunyai dana cukup untuk pelayanan kesehatan. Masyarakatlah yang harus membayar, termasuk yang miskin. Masyarakat miskin hanya bisa mendapatkan pelayanan kesehatan gratis jika mampu membuktikan diri sebagai orang miskin, tidak mampu untuk mendapat pelayanan gratis. Terjadilah mekanisme pasar di pelayanan kesehatan.
Sistem pasar terus berlangsung sampai Orde Baru. RS swasta diperbolehkan menjadi lembaga berbentuk PT (mencari untung). Berbagai perkembangan ini membentuk sifat sektor pelayanan kesehatan perorangan yang semakin dipengaruhi oleh hukum pasar yang celakanya tidak ada pengawasan.
Muncul efek samping di situasi ini, misalnya adanya semacam kartel yang membatasi jumlah spesialis. Akibatnya, jumlah dokter spesialis dan subspesialis menjadi sangat kurang.
Desentralisasi
Tahun 1999, setelah krisis moneter dan reformasi politik di Indonesia, sektor kesehatan Indonesia juga mengalami desentralisasi. Sayangnya, hal ini dilakukan secara setengah hati. Kondisi ini bisa dilihat dari bertambahnya APBN pemerintah pusat selama 10 tahun terakhir, dengan pembiayaan kesehatan dilakukan oleh pusat kembali (resentralisasi).
Daerah-daerah, termasuk yang mampu, tidak memberikan anggaran cukup untuk sektor kesehatan. Dalam kasus program penurunan kematian ibu dan bayi, dana program masih bergantung pada APBN. Kegiatan-kegiatan kesehatan masyarakat menjadi identik dengan program Kementerian Kesehatan ataupun dinas kesehatan di daerah. Pemerintah merencanakan, melakukan, dan menilai sendiri kegiatan-kegiatan seperti imunisasi, pemberantasan nyamuk, sampai promosi kesehatan. Akibatnya, tidak ada sistem monitoring dan pengendalian secara independen. Peran masyarakat dan LSM masih terbatas dalam program kesehatan masyarakat. Dampak lanjutannya, pemerintah pusat kesulitan dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang seharusnya dilakukan pemerintah kabupaten dan provinsi.
Pada tahun 1999, reformasi politik menetapkan pemerintah sebagai sumber dana masyarakat miskin melalui program Social Safety-Net, yang diteruskan dengan Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin (Askeskin), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan saat ini JKN. Kebijakan ini mengakhiri periode mekanisme pasar yang sangat kuat.
Meski demikian, kebijakan pembiayaan untuk pelayanan perorangan ini tidak dapat mengangkat status kesehatan masyarakat. Selama 10 tahun terakhir, berbagai indikator kesehatan masyarakat, seperti angka kematian ibu dan bayi, demikian juga dengan penderita TB, masih belum dapat dikendalikan. Di sejumlah kota besar, jumlah kematian ibu meningkat seiring dengan peningkatan anggaran untuk jaminan kesehatan.
Transparansi data kurang
Kebijakan JKN dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) sebagai pengelola merupakan hal yang bertujuan baik. Akan tetapi, saat ini, hal itu sulit dinilai karena transparansi data belum baik.
Data penggunaan sarana kesehatan primer dan rujukan langsung dikirim ke kantor pusat BPJS tanpa ada analisis di daerah. Akibatnya, pemerintah kabupaten/kota/provinsi tidak dapat membuat perencanaan kesehatan dengan baik, khususnya untuk pencegahan penyakit.
Pelaksanaan kebijakan desentralisasi menjadi semakin tidak jelas di sektor kesehatan. Di JKN diduga terjadi salah sasaran dalam pemberian subsidi. Dana penerima bantuan iuran (PBI) masih sisa di sejumlah daerah, khususnya di kawasan yang berakses buruk. Dana ini kemudian dipergunakan untuk mendanai peserta BPJS di tempat lain yang merugi.
Di sisi lain, program kesehatan masyarakat ternyata juga belum baik dijalankan. Kegiatan-kegiatan kesehatan masyarakat identik dengan program Kementerian Kesehatan ataupun dinas kesehatan di daerah.
Pemerintah merencanakan, melakukan, dan menilai sendiri kegiatan-kegiatan seperti imunisasi, pemberantasan nyamuk, sampai promosi kesehatan. Akibatnya, tidak ada sistem monitoring dan pengendalian independen. Peran masyarakat dan LSM masih terbatas dalam program kesehatan masyarakat.
Kementerian-kementerian terkait kesehatan, seperti Kementerian Pekerjaan Umum atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tidak terkoordinasi selama bertahun-tahun. Kementerian Kesehatan dan dinas kesehatan terbatas menjadi pelaku pelayanan dengan dana pemerintah.
Fungsi pengawasan lembaga pelayanan pemerintah dan swasta serta penyusun kebijakan terabaikan. Dalam konteks kematian ibu, apabila sistem kontrol mutu pelayanan rujukan ibu dan mutu pelayanan rumah sakit dilakukan dengan baik, penurunan angka kematian ibu dapat dipercepat.
Apa yang perlu dilakukan
Sebagai refleksi 70 tahun perkembangan sistem kesehatan, ada beberapa hal kunci untuk dilakukan.
Pertama, kebijakan pembiayaan JKN perlu ditingkatkan lewat transparansi, efisiensi, dan pemerataan. Jangan sampai subsidi bagi masyarakat miskin (PBI) salah sasaran dan terjadi inefisiensi.
Kedua, diperlukan kerja sama pemerintah dan swasta. Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan masyarakat, perlu kerja sama antara Kementerian Kesehatan atau dinas kesehatan dan swasta melalui sistem kontrak.
Ketiga, perlu koordinasi lebih erat antara Kementerian Kesehatan dan kementerian lain atau dinas kesehatan dan dinas terkait kesehatan di daerah dalam konteks desentralisasi.
Keempat, perlu reorientasi pendidikan tenaga kesehatan. Dengan skema LSM dan swasta sebagai kontraktor, lulusan fakultas kesehatan masyarakat tidak harus menjadi PNS. Pola-pola kartel dalam pendidikan spesialis dan subspesialis harus dihilangkan.
Kelima, promosi kesehatan perlu ditingkatkan agar masyarakat sadar bahwa kesehatan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan juga masyarakat.
{jcomments on}
 Layanan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan kini dilakukan lebih terstruktur, melalui sistem yang disebut PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan).
Layanan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan kini dilakukan lebih terstruktur, melalui sistem yang disebut PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan).