 Bencana nasional non alam yang disebabkan oleh Corona virus Disease (COVID-19) berdampak terhadap ekonomi, sosial dan kesehatan masyarakat secara luas. Pemerintah telah menetapkan bencana non alam ini sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
Bencana nasional non alam yang disebabkan oleh Corona virus Disease (COVID-19) berdampak terhadap ekonomi, sosial dan kesehatan masyarakat secara luas. Pemerintah telah menetapkan bencana non alam ini sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
Pandemi COVID-19 mengakibatkan terganggunya ketersediaan dari pelayanan kesehatan dasar, terutama pelayanan kesehatan untuk ibu, anak dan bayi baru lahir. Di Amerika, beberapa rumah sakit membuat kebijakan untuk mengubah bangsal bersalin menjadi bangsal perawatan untuk pasien COVID-19, membatasi pendamping persalinan di kamar bersalin dan menawarkan induksi persalinan agar ibu yang akan bersalin secepat mungkin meninggalkan rumah sakit. Sedangkan di negara miskin dan berkembang, bahkan sebelum ada pandemi COVID-19 akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang berkualitas sangat jarang bahkan tidak tersedia atau tidak dapat dijangkau oleh jutaan wanita. Adanya pandemi COVID-19 memperburuk keadaan ini dan kemungkinan berdampak pada morbiditas dan mortalitas ibu dan anak (Stein, Ward, & Cantelmo, 2020).
Berdasarkan perkiraan para ahli dengan mempertimbangkan dampak epidemi Ebola (2014-2016) terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak, akan ada 4 negara miskin dan berkembang yang akan mengalami dampak tidak langsung dari pandemi COVID-19 ini. Keempat negara tersebut yaitu India, Indonesia, Nigeria dan Pakistan. Diperkirakan akan terjadi penambahan 31.980 kematian ibu, 395.440 kematian bayi baru lahir, dan 338.760 bayi lahir mati sehingga total 766.180 kematian tambahan di empat negara ini atau setara dengan peningkatan kematian sebesar 31% apabila terjadi penurunan pelayanan kesehatan saat pandemi. Hal ini akan menjadi kenyataan apabila tidak ada tindakan segera yang dapat membantu mencegah dampak tidak langsung pandemi COVID-19 pada pelayanan kesehatan ibu dan anak (Penn-Kekana, 2020).
Untuk mencegah dampak tidak langsung pandemi COVID-19, diperlukan suatu upaya inovatif untuk mengetahui bagaimana pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap program KIA dan KB melalui kegiatan elektronik monitoring dan evaluasi (e-monev) yang dilakukan di 120 kab/kota lokus penurunan AKI dan AKB. Kegiatan ini melibatkan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kebijakan dan Manajemen (PKMK) Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FK – KMK) UGM yang bekerja sama dengan 13 perguruan tinggi mitra untuk mendampingi 120 Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam mengumpulkan data, melakukan analisis, dan menyusun dokumen.
Sistem e-Monev ini berbasis web yang menggunakan data rutin Komdat untuk monitoring yang dilakukan Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Dinas Kesehatan kabupaten/kota. Kegiatan ini menghasilkan tiga bentuk dokumen meliputi dokumen analisis dampak, analisis kebijakan, dan policy brief berupa rekomendasi dan harapan untuk berbagai pihak. Terdapat 8 indikator pelayanan KIA dalam Komdat yang digunakan untuk monitoring yaitu kunjungan pertama ibu hamil (K1), kunjungan keempat ibu hamil (K4), persalinan di fasilitas kesehatan, kunjungan Neonatal (KN) Lengkap, pemantauan tumbuh kembang balita (SDIDTK), pelayanan imunisasi dasar lengkap, kematian ibu dan program KB. Data Komdat yang digunakan telah diverifikasi oleh Direktorat Kesehatan Keluarga, Ditjen Kesmas Kemenkes RI. Data yang telah diverifikasi dikelola dan disajikan dalam bentuk Dashboard yang disajikan di web. Data di web dianalisis oleh Dinas Kesehatan didampingi pendamping universitas, dan disajikan dalam bentuk analisis dampak.
Berdasarkan analisis di level nasional ada berbagai hasil menarik yang didapatkan, cakupan K4 merupakan indikator paling terdampak pandemi COVID-19 sedangkan program KB adalah indikator yang paling sedikit terdampak pandemi. Pandemi berdampak juga pada Posyandu yang tutup dan pembatasan jam pelayanan di fasilitas kesehatan yang berakibat pelayanan KIA dan KB tidak dapat terlaksana dengan optimal. Sebagian besar dinas kesehatan kabupaten/ kota memanfaatkan media sosial untuk memberikan edukasi dan memastikan pelayanan kesehatan tetap dapat diberikan.
Hal lain yang menyebabkan cakupan indikator mengalami penurunan adalah karena keengganan masyarakat untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan. Kekhawatiran akan tertular virus COVID-19 membuat ibu hamil menunda untuk memeriksakan kesehatannya. Selain itu, kekhawatiran tenaga kesehatan akan tertular dari pasien juga memberikan dampak terhadap pelaksanaan pelayanan KIA dan KB. Beberapa dinas kesehatan kabupaten/ kota juga menginformasikan adanya stigma negatif di masyarakat yang beredar terkait pandemi ini telah berdampak pada menurunnya jumlah masyarakat yang berkunjung ke fasilitas kesehatan dan ketidakjujuran pasien dapat meningkatkan peluang tenaga kesehatan tertular sehingga pelayanan tidak dapat diberikan secara optimal. Berbagai kebijakan telah diberlakukan untuk menangani pandemi ini, akan tetapi dinas kesehatan masih membutuhkan dukungan dari berbagai lintas sektor untuk memulihkan pelayanan.
Hasil dari kegiatan ini telah dipublikasikan dalam Bulletin of the World Health Organization,
selengkapnya https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8795852/
Referensi
Penulis ringkasan: Monita Destiwi
Tim Peneliti : Laksono Trisnantoro, Insan Rekso Adiwibowo, Monita Destiwi, Rokhana Diyah Rusdiati


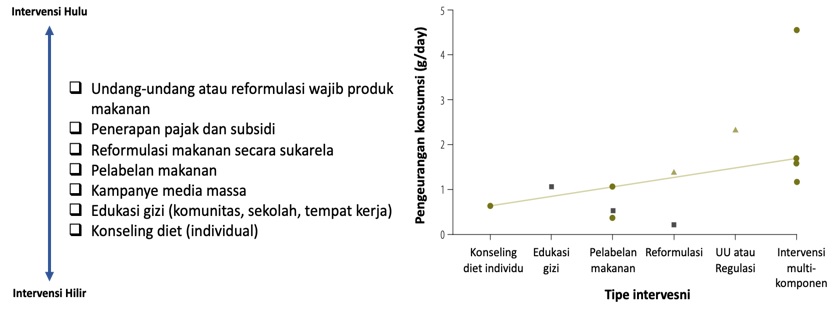

 Bencana nasional non alam yang disebabkan oleh Corona virus Disease (COVID-19) berdampak terhadap ekonomi, sosial dan kesehatan masyarakat secara luas. Pemerintah telah menetapkan bencana non alam ini sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.
Bencana nasional non alam yang disebabkan oleh Corona virus Disease (COVID-19) berdampak terhadap ekonomi, sosial dan kesehatan masyarakat secara luas. Pemerintah telah menetapkan bencana non alam ini sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.