Pada 9 November 2017, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) bekerjasama dengan GP. Farmasi Indonesia dan International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG) menyelenggarakan forum dialog Akses untuk Obat yang Berkualitas dan Terjangkau dalam Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional di Indonesia dengan tema “Ending the Vicious Cycle”. Acara ini diselenggarakan di Gedung Pakarti Centre, Jakarta Pusat.
Acara dibuka oleh Direktur Eksekutif CSIS, Philips J. Vermonte. Philips menyampakan bahwa isu kesehatan di Indonesia sudah menjadi salah satu isu yang sangat penting di CSIS. Forum ini dapat dijadikan sebagai wadah mengumpulkan para ahli, pembuat kebijakan, dan stakeholder sehingga dapat memulai melakukan riset dan mendiskusikan tentang isu kesehatan. Pihaknya juga menyampaikan bahwa isu kesehatan mengenai JKN sangat kompleks. Isu JKN bukan hanya terbatas pada kepesertaan saja, melainkan juga harus dikaitkan dengan koordinasi, kooperasi, investasi, dalam hal pengetahuan, waktu, instansi, dan lainnya.

Sesi 1 : Perspektif Global dan Regional
 Sesi 1 menghadirkan tiga pembicara, yaitu Prof. Hans Hogerzeil dari University of Groningen, Netherlands dan Dr. Suwit Wibulpolprasert serta Ms. Woranan Witthayapipopsakul dari International Health Policy Program, Ministry of Health, Thailand. Moderator sesi ini adalah Prof. Dr. Tikki Pangestu dari Lee Kuan Yew School of Public Policy.
Sesi 1 menghadirkan tiga pembicara, yaitu Prof. Hans Hogerzeil dari University of Groningen, Netherlands dan Dr. Suwit Wibulpolprasert serta Ms. Woranan Witthayapipopsakul dari International Health Policy Program, Ministry of Health, Thailand. Moderator sesi ini adalah Prof. Dr. Tikki Pangestu dari Lee Kuan Yew School of Public Policy.
Prof. Hans Hogerzeil memaparkan perspektif global terhadap akses obat untuk JKN. Dalam paparannya, Hans menyampaikan bahwa suatu obat menjadi sangat esensial ketika obat tersebut sangat mahal tetapi banyak dibutuhkan. Konsep obat esensial adalah jangkauan terbatas pada obat-obatan esensial yang dipilih, yang mengarah pada layanan kesehatan yang lebih baik, manajemen obat yang lebih baik, dan biaya yang lebih murah. Definisi obat esensial yaitu obat yang memenuhi prioritas kebutuhan layanan kesehatan di masyarakat.
Dalam hal akses terhadap obat-obatan esensial yang ada, Hans menekankan bahwa pengobatan kronis seumur hidup dengan obat-obatan esensial murah untuk NCDs menyebabkan tingginya pengeluaran di bidang kesehatan, kebangkrutan, dan kematian. Hans juga menyampaikan bahwa kurangnya pemerataan obat-obatan esensial yang tersedia hanya bisa dikoreksi oleh pemerintah melalui asuransi kesehatan sosial dengan subsidi untuk masyarakat miskin. Perlu disadari pula bahwa pengaruh globalisasi dan kurangnya kontrol peraturan di negara berpenghasilan menengah ke bawah menyebabkan banyaknya obat yang tidak memenuhi standar di pasaran, sehingga perlu fokus pada penegakan hukum terhadap beberapa badan peraturan yang dipalsukan.
 Materi selanjutnya dipaparkan oleh Dr. Suwit Wibulpolprasert dan Woranan Witthayapipopsakul mengenai pengalaman Thailand dalam memastikan akses terhadap obat-obatan yang terjangkau dan berkualitas untuk UHC/JKN.
Materi selanjutnya dipaparkan oleh Dr. Suwit Wibulpolprasert dan Woranan Witthayapipopsakul mengenai pengalaman Thailand dalam memastikan akses terhadap obat-obatan yang terjangkau dan berkualitas untuk UHC/JKN.
Sistem JKN di Thailand mulai dibangun sejak 1975. Hingga sekarang, kebijakan obat nasional diperbarui setiap 5 tahun sekali. Setiap kebijakaan obat nasional yang dibuat akan ditranslasikan ke dalam daftar nasional obat-obatan esensial (National List of Essential Medicines – NLEM). NLEM adalah manfaat farmasi dasar yang menjadi hak warga Thailand untuk skema asuransi kesehatan utama JKN. Beberapa kriteria dalam seleksi NLEM antara lain kebutuhan kesehatan, efektivitas biaya, dampak anggaran, kelayakan pengiriman, dan pemerataan. Obat-obatan herbal dan obat-obatan dengan harga yang sangat mahal pun masuk ke dalam NLEM.
Thailand menggunakan harga standar sebagai harga referensi untuk pengadaan publik, mencakup obat-obatan modern, tradisional, maupun herbal. Penetapan harga standar bertujuan untuk memastikan harga yang wajar di bawah persaingan pasar.
Terkait dengan sistem pengadaan pemerintah, fasilitas umum harus mendapatkan obat-obatan penting yang diproduksi oleh organisasi farmasi pemerintah. Pengadaan dilakukan secara terpusat, melalui proses seleksi, spesifikasi, perkiraan permintaan, negosiasi harga, pengadaan dan distribusi.
Pelajaran yang bisa diambil dari sistem JKN yang diterapkan di Thailand adalah JKN meningkatkan daya negosiasi publik melalui harga referensi standar pembelian monopsonistik, pengendalian anggaran akhir yang efisien memotivasi rumah sakit untuk menggunakan obat generik yang dapat menghemat biaya dan manfaat industri local, sistem pengadaan dan tawar-menawar secara kolektif dapat menjamin akses yang terjangkau terhadap obat-obatan berkualitas, dan beberapa mekanisme ada untuk memperkuat industri lokal bersamaan dengan memastikan akses terhadap obat-obatan esensial.
Sesi 2 : Tantangan yang Dihadapi Indonesia dan Pilihan Kebijakan
 Sesi 2 menghadirkan tiga orang pembicara, yaitu Prof. Dr. Tikki Pangestu mewakili Prof. Djisman Simandjuntak dari Universita Prasetya Mulya dan Syarifah Liza Munira dari Universitas Indonesia; Ir. Ferry Soetikno, M. Sc., MBA. dari Gabungan Perusahaan (GP) Farmasi Indonesia; dan Mr. Jorge Wagner, Ketua International Pharmaceutical Manufacturer Group (IPMG). Moderator sesi ini adalah Johannes Setijono, Ketua Dewan Penasehat GP Farmasi Indonesia.
Sesi 2 menghadirkan tiga orang pembicara, yaitu Prof. Dr. Tikki Pangestu mewakili Prof. Djisman Simandjuntak dari Universita Prasetya Mulya dan Syarifah Liza Munira dari Universitas Indonesia; Ir. Ferry Soetikno, M. Sc., MBA. dari Gabungan Perusahaan (GP) Farmasi Indonesia; dan Mr. Jorge Wagner, Ketua International Pharmaceutical Manufacturer Group (IPMG). Moderator sesi ini adalah Johannes Setijono, Ketua Dewan Penasehat GP Farmasi Indonesia.
Prof. Dr. Tikki Pangestu mengawali sesi ini dengan membahas akses terhadap obat-obatan yang terjangkau dan berkualitas di Indonesia. Status kesehatan di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini juga diiringi dengan kenaikan Indeks Kualitas Akses dan Kesehatan setiap tahunnya. Namun peningkatan indeks kualitas akses dan kesehatan masih cukup rendah bila dibandingkan dengan negara-negara sekitar seperti Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam.
Pesan kunci terhadap akses obat-obatan yang terjangkau dan berkualitas antara lain : secara keseluruhan kemajuan tersebut sudah terlihat namun tantangan masih tetap ada; Indonesia cukup mahir dalam menghadapi penyebab penyakit tertentu (misalnya kanker rahim) tapi masih lemah di sisi lain ( misal TB); dari segi pembiayaan, pembayaran out of pocket masih cukup tinggi; harga obat-obatan masih cukup tinggi antara obat generik dan obat bermerk; dan isu seputar tantangan menyeimbangkan harga dan kualitas.
Beberapa tantangan dalam menyeimbangkan harga dan kualitas antara lain : penekanan yang berlebihan terhadap pengurangan harga dapat membahayakan kualitas dan keamanan dan menyebabkan komplikasi medis, mengurangi keefektifan, perawatan di rumah sakit yang lebih lama dan waktu pemulihan yang lama untuk pasien; diperlukan koordinasi yang lebih baik antara pemangku kepentingan termasuk produsen, LSM, konsumen, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, LKPP, dan BPOM; dan kelangsungan hidup dan keberlanjutan industri farmasi nasional ikut dipertaruhkan jika keseimbangan harga dan kualitas tidak dipecahkan secara kolegial, adil, dan transparan.
 Ir. Ferry Soetikno, M. SC., MBA memaparkan keberlanjutan Industri Farmasi di Indonesia dalam mendukung JKN. Isu utama yang selalu terjadi dalam fenomena pelaksanaan program JKN adalah persediaan obat. Untuk itu, keberlanjutan industri farmasi menjadi sangat penting. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam keberlanjutan industri adalah peningkatan kapasitas internal sebagai komitmen dalam mendukung JKN. Selain itu, seleksi produk juga menjadi sangat penting. Hal ini berkaitan pula dengan rencana kerja operasional untuk mengidentifikasi kebutuhan yang harus dipenuhi setiap tahunnya. Pola pemesanan pun perlu diperhatikan untuk dapat mengetahui status persediaan obat saat ini, terlebih jika ada pemesanan skala besar untuk menghindari stock out. Hal lain yang juga menjadi sangat penting adalah risiko pasokan dan erosi harga. Dalam empat tahun terakhir penawaran berdasarkan harga menghasilkan penurunan harga hingga mencapai 40%.
Ir. Ferry Soetikno, M. SC., MBA memaparkan keberlanjutan Industri Farmasi di Indonesia dalam mendukung JKN. Isu utama yang selalu terjadi dalam fenomena pelaksanaan program JKN adalah persediaan obat. Untuk itu, keberlanjutan industri farmasi menjadi sangat penting. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam keberlanjutan industri adalah peningkatan kapasitas internal sebagai komitmen dalam mendukung JKN. Selain itu, seleksi produk juga menjadi sangat penting. Hal ini berkaitan pula dengan rencana kerja operasional untuk mengidentifikasi kebutuhan yang harus dipenuhi setiap tahunnya. Pola pemesanan pun perlu diperhatikan untuk dapat mengetahui status persediaan obat saat ini, terlebih jika ada pemesanan skala besar untuk menghindari stock out. Hal lain yang juga menjadi sangat penting adalah risiko pasokan dan erosi harga. Dalam empat tahun terakhir penawaran berdasarkan harga menghasilkan penurunan harga hingga mencapai 40%.
Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mendukung program JKN dan keberlangsungan industri farmasi adalah persaingan sehat, sistem penghargaan dan hukuman yang adil dan jelas, memprioritaskan produk buatan lokal, menggerakkan tindakan promotif dan preventif, sistem tender tidak hanya berdasarkan pada harga namun juga pada prestasi, dan meningkatkan investasi untuk melaksanakan rencana kerja industri farmasi Indonesia dan melakukan penelitian, serta memasukkan produk penelitian sendiri ke dalam e-catalogue.
 Mr. Jorge Wagner dari IPMG memberikan paparan mengenai tantangan dan peluang kemajuan terhadap program JKN. Kemajuan program JKN telah terlihat dalam prosesnya meskipun ada tantangan awal dalam pelaksanaan JKN. Penyempurnaan yang dilakukan terus-menerus ini akan menjamin ketersediaan obat generik berkualitas dan produk inovatif, diiringi dengan peningkatan proses perencanaan, proses seleksi obat / akses awal obat-obatan inovatif, proses lelang dan negosiasi, implementasi e-katalog lebih lanjut, serta mendorong penggunaan yang tepat melalui pedoman pengobatan standar.
Mr. Jorge Wagner dari IPMG memberikan paparan mengenai tantangan dan peluang kemajuan terhadap program JKN. Kemajuan program JKN telah terlihat dalam prosesnya meskipun ada tantangan awal dalam pelaksanaan JKN. Penyempurnaan yang dilakukan terus-menerus ini akan menjamin ketersediaan obat generik berkualitas dan produk inovatif, diiringi dengan peningkatan proses perencanaan, proses seleksi obat / akses awal obat-obatan inovatif, proses lelang dan negosiasi, implementasi e-katalog lebih lanjut, serta mendorong penggunaan yang tepat melalui pedoman pengobatan standar.
Perbaikan jangka panjang terhadap program JKN sangat diperlukan. IPMG berkomitmen dalam mencari solusi transformatif yang memerlukan pengaturan prioritas, dialog dan kerjasama antar pemangku kepentingan, termasuk kemitraan antara sektor swasta dan publik. Selain itu, pendekatan inovatif, termasuk co-payment, mengelola kesepakatan pembagian masuk dan risiko, dengan proses berbasis bukti untuk pengambilan keputusan harus dipertimbangkan. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam perbaikan jangka panjang adalah meningkatkan akses terhadap obat-obatan inovatif, kemungkinan transfer teknologi dan investasi pengembangan klinis.
Sesi 3 : Lanskap dan Situasi Indonesia : Perspektif Pembuat Kebijakan
 Sesi 3 menghadirkan tiga orang pembicara, yaitu Dra. Togi Hutadjulu, Apt., MHA., Direktur Pengawasan Produk Terapeutik dan Narkotika serta Zat Psikotropika dan Adiktif BPOM; Prof. Dr. dr. Fachmi Idris M.Kes., Direktur Utama BPJS Kesehatan; dan Dra. Maura Linda Sitanggang, Ph. D., Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan. Moderator sesi 3 adalah Dr. Becky Prastuti Soewondo, SE., MPH. daro Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia.
Sesi 3 menghadirkan tiga orang pembicara, yaitu Dra. Togi Hutadjulu, Apt., MHA., Direktur Pengawasan Produk Terapeutik dan Narkotika serta Zat Psikotropika dan Adiktif BPOM; Prof. Dr. dr. Fachmi Idris M.Kes., Direktur Utama BPJS Kesehatan; dan Dra. Maura Linda Sitanggang, Ph. D., Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan. Moderator sesi 3 adalah Dr. Becky Prastuti Soewondo, SE., MPH. daro Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia.
Dra. Togi Hutadjulu, Apt., MHA. menyampaikan bahwa Badan POM berperan dalam mengawasi jaminan keamanan dan mutu obat di Indonesia. Komponen pengawasan obat disesuaikan dengan standar WHO Global Benchmark Tool, yaitu menggunakan sistem pre market dan post market.
Ada beberapa tantangan terkait kesinambungan jaminan mutu obat. Penetapan pemenang tender berdasarkan harga obat yang termurah diduga berimplikasi pada trade-off terhadap jaminan mutu obat akibat pelaksanaan bisnis yang tidak profesional, khususnya dalam kepatuhan penerapan ketentuan regulatori sesuai saat diberikan ijin edar. Tantangan lainnya adalah terjadinya peningkatan toll manufacturing kerjasama antar perusahaan domestik dan MNC. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, BPOM perlu lebih peka dan akomodatif dengan mengawal regulator lebih intensif sesuai ketentuan yang berlaku.
Langkah strategis yang perlu dilakukan terhadap jaminan mutu obat pada era sistem JKN ini antara lain peningkatan pelaksanaan kawalan jaminan mutu secara komprehensif baik dari aspek khasiat, keamanan, maupun mutu; penyempurnaan dan penyusunan regulasi yang diperlukan; peningkatan efektivitas dan efisiensi tersedianya obat dengan menerapkan standar dan persyaratan nasional dan internasional; peningkatan pemenuhan standar dan persyaratan jaminan mutu, peningkatan kerjasama lintas sektor dan jejaring kerja, serta pemberdayaan lintas sektor dan masyarakat dalam pelaksanaan Risk Communication.
 Prof. Dr. dr. Fachmi Idris M.Kes. memaparkan tentang perspektif pembuat kebijakan dari sisi BPJS Kesehatan. Pada 2016, peserta Jaminan Kesehatan Nasional mencapai 171.9 juta peserta. Pemerintah telah mencanangkan peserta JKN pada 2019 bisa mencapai 100% populasi Indonesia. Di lain pihak, ada beberapa masalah yang sering dikeluhkan oleh peserta JKN antara lain biaya, display kamar, sistem antrian, dan ketersediaan obat. Masalah ini menjadi fokus penyelesaian pada 2017.
Prof. Dr. dr. Fachmi Idris M.Kes. memaparkan tentang perspektif pembuat kebijakan dari sisi BPJS Kesehatan. Pada 2016, peserta Jaminan Kesehatan Nasional mencapai 171.9 juta peserta. Pemerintah telah mencanangkan peserta JKN pada 2019 bisa mencapai 100% populasi Indonesia. Di lain pihak, ada beberapa masalah yang sering dikeluhkan oleh peserta JKN antara lain biaya, display kamar, sistem antrian, dan ketersediaan obat. Masalah ini menjadi fokus penyelesaian pada 2017.
BPJS Kesehatan sendiri tidak memiliki kewenangan dalam mekanisme pengadaan dan penanganan kekosongan obat, tetapi menjadi kontak pertama penyampaian keluhan, sehingga perlu adanya kerja sama dengan instansi lain seperti Kemenkes, BPOM, LKPP, Industri Farmasi, dan organisasi profesi dalam menangani kasus ketersediaan obat supaya lebih cepat.
Usulan perbaikan yang perlu dilakukan untuk mendukung program JKN antara lain: penetapan formulatorium nasional bersamaan dengan penetapan harga, adanya masa transisi pemberlakuan kebijakan obat untuk sosialisasi dan perbaikan sistem, adanya regulasi yang mewajibkan semua fasilitas kesehatan untuk memberikan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) karena saat ini komitmen penyediaan RKO hanya ada di kontrak antara BPJS Kesehatan dengan faskes, pemberian akses e-purchasing bagi faskes swasta dan apotek, dan harga obat berlaku secara nasional. Selain itu, fasilitas kesehatan perlu diberikan kewenangan untuk mengadakan obat lain selain yang tercantum dalam e-catalogue sebagai substitusi jika terjadi kekosongan obat dan BPJS Kesehatan akan membayar sesuai dengan harga e-catalogue.
 Dra. Maura Linda Sitanggang, Ph. D. memaparkan kebijakan tata kelola obat JKN. Langkah-langkah yang dilakukan terdiri dari Formulatorium nasional, Rencana Kebutuhan Obat, dan Pengadaan obat.
Dra. Maura Linda Sitanggang, Ph. D. memaparkan kebijakan tata kelola obat JKN. Langkah-langkah yang dilakukan terdiri dari Formulatorium nasional, Rencana Kebutuhan Obat, dan Pengadaan obat.
Tantangan yang ada dalam tata kelola obat JKN adalah RKO tidak akurat, obat yang akan diadakan tidak tayang dalam e-katalog, kewajiban satker/faskes dalam hal pembayaran belum diselesaikan, pembelian yang mendadak dan tidak terencana, akses e-purchasing bagi fakses swasta, dan persyaratan administrasi dari satker/faskes tidak lengkap. Solusi dari tantangan ini antara lain meningkatkan kepatuhan menyerahkan RKO dan kearutannya. Pada 2019 akan diatur kewajiban menyerahkan RKO yang dikaitkan dengan sanksi. Pengadaan obat dapat dilakukan dengan cara lain jika tidak ada dalam e-katalog. Selain itu, kewajiban satker/faskes dalam hal pembayaran kepada distributor harus segera diselesaikan supaya pemesanan berikutnya dapat dilayani.
Pada akhir sesi, Dra. Maura menekankan bahwa ketersediaan obat tergantung pada perencanaan kebutuhan, perencanaan pengadaan, proses pengadaaan, dan proses pendistribusian. Pengaturan terkait kewajiban menyerahkan RKO dan sanksinya akan mulai diterapkan pada 2019. Sedangkan akses e-purchasing bagi faskes swasta, sesuai rekomendasi KPK, akan diberikan pada 2018. Di samping itu, penerapan komitmen industri farmasi sebagai penyedia katalog obat harus dievaluasi terus menerus, termasuk evaluasi kesiapan industri farmasi sebagai penyedia obat.
Sesi 4 : Diskusi
Sesi Diskusi dipimpin oleh Dr. Nafsiah Mboi dan adalah Prof. Dr. Tikki Pangestu. Topik diskusi fokus pada tiga aspek, yaitu akses masyarakat terhadap JKN dengan kualitas dan efektifitas yang layak, keberlanjutan dari JKN dan farmasi, serta kerjasama antara pemerintah dengan sektor swasta.

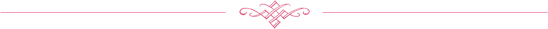



 oleh Dr. Melania Hidayat (Nasional Program Officer, UNFPA Indonesia). Indonesia termasuk negara dengan pencapaian KB yang cukup dramatis. Hanya dalam kurun waktu 25 tahun kita dapat menurunkan TFA lebih dari separuh, meningkatkan CPR 3 kali lipat, serta mengubah norma atau mindset “banyak anak banyak rejeki” saat ini menjadi “dua anak cukup”. Sejalan dengan perubahan politik dan sistem pemerintah, program KB ikut terdampak, termasuk struktur dan implementasi program. Desentralisasi KB terlihat terhambat, sehingga pada awal 2000 program KB di tingkat kabupaten tidak diperhatikan, hal ini ditinjau dari RPJMD segi kesehatan yang tidak mencantumkan program KB di dalamnya. Pendekatan KB saat ini harus diubah menjadi paradigma yang bahwa KB dilaksanakan untuk memenuhi hak warga negara. Jika dibandingkan ketika sebelum program JKN mulai diterapkan, sejak tahun 2000 semua indikator KB mengalami stagnasi bahkan menurun. Beberapa hal yang mungkin menjadi penyebabnya adalah desentralisasi, atau karena Indonesia mengalami S curve dimana pada titik tertentu banyak indikator mengalami penurunan. Sedangkan pada era setelah JKN tepatnya pada 2016-2017 demand satisfied meningkat. Isu stockout atau ketersediaan alat kontrasepsi pada 2015-2016, stockout-nya meningkat. Saat ini dengan penerapan JKN, beban pemerintah untuk menyiapkan alat kontrasepsi bagi warga berlipat hingga 3 kali.
oleh Dr. Melania Hidayat (Nasional Program Officer, UNFPA Indonesia). Indonesia termasuk negara dengan pencapaian KB yang cukup dramatis. Hanya dalam kurun waktu 25 tahun kita dapat menurunkan TFA lebih dari separuh, meningkatkan CPR 3 kali lipat, serta mengubah norma atau mindset “banyak anak banyak rejeki” saat ini menjadi “dua anak cukup”. Sejalan dengan perubahan politik dan sistem pemerintah, program KB ikut terdampak, termasuk struktur dan implementasi program. Desentralisasi KB terlihat terhambat, sehingga pada awal 2000 program KB di tingkat kabupaten tidak diperhatikan, hal ini ditinjau dari RPJMD segi kesehatan yang tidak mencantumkan program KB di dalamnya. Pendekatan KB saat ini harus diubah menjadi paradigma yang bahwa KB dilaksanakan untuk memenuhi hak warga negara. Jika dibandingkan ketika sebelum program JKN mulai diterapkan, sejak tahun 2000 semua indikator KB mengalami stagnasi bahkan menurun. Beberapa hal yang mungkin menjadi penyebabnya adalah desentralisasi, atau karena Indonesia mengalami S curve dimana pada titik tertentu banyak indikator mengalami penurunan. Sedangkan pada era setelah JKN tepatnya pada 2016-2017 demand satisfied meningkat. Isu stockout atau ketersediaan alat kontrasepsi pada 2015-2016, stockout-nya meningkat. Saat ini dengan penerapan JKN, beban pemerintah untuk menyiapkan alat kontrasepsi bagi warga berlipat hingga 3 kali. oleh Woro Srihastuti Sulistyaningrum, ST, MIDS (Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olah Raga – Kementrian PPN / Bappenas). Integrasi perencanaan KB (right-based family planning) dilatarbelakangi oleh melemahnya kinerja program KB maupun angka kematian ibu yang tinggi. Dasarnya adalah hak asasi manusia untuk mendapatkan pelayanan, keadilan dalam akses, KB terintegrasi dalam sistem kesehatan, berbasis bukti, maupun sensitif gender. Strategi yang perlu dilakukan untuk right-based family planning diantaranya meningkatkan kualitas pelayanan terutama dari sisi suplai, meningkatkan penggunaan metode KB berkesinambungan, meningkatkan tata kelola pelayanan KB, dan aplikasi serta inovasi terkait riset. Terkait hal ini rencana pembiayaan implementasi untuk 2017 – 2019 sebesar Rp. 8.923 milyar. Selain itu diperlukan tahapan kegiatan agar right-based family planning ini dapat terwujud, dimana dimulai pada 2016 – 2017 sebagai tahun persiapan, 2018 sebagai tahun implementasi, 2019 sebagai tahun monitoring dan evaluasi, 2019 sebagai dokumentasi best practice, dan 2020 merupakan exit strategy dengan adanya penetapan prioritas.
oleh Woro Srihastuti Sulistyaningrum, ST, MIDS (Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olah Raga – Kementrian PPN / Bappenas). Integrasi perencanaan KB (right-based family planning) dilatarbelakangi oleh melemahnya kinerja program KB maupun angka kematian ibu yang tinggi. Dasarnya adalah hak asasi manusia untuk mendapatkan pelayanan, keadilan dalam akses, KB terintegrasi dalam sistem kesehatan, berbasis bukti, maupun sensitif gender. Strategi yang perlu dilakukan untuk right-based family planning diantaranya meningkatkan kualitas pelayanan terutama dari sisi suplai, meningkatkan penggunaan metode KB berkesinambungan, meningkatkan tata kelola pelayanan KB, dan aplikasi serta inovasi terkait riset. Terkait hal ini rencana pembiayaan implementasi untuk 2017 – 2019 sebesar Rp. 8.923 milyar. Selain itu diperlukan tahapan kegiatan agar right-based family planning ini dapat terwujud, dimana dimulai pada 2016 – 2017 sebagai tahun persiapan, 2018 sebagai tahun implementasi, 2019 sebagai tahun monitoring dan evaluasi, 2019 sebagai dokumentasi best practice, dan 2020 merupakan exit strategy dengan adanya penetapan prioritas.



