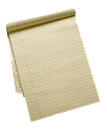Pada tanggal 10-11 Desember 2012, telah berlangsung pertemuan konsorsium fakultas bidang kesehatan untuk kesehatan ibu & anak serta gizi (KIA-Gizi). Kegiatan ini dihadiri oleh Dekan FK & FKM dari beberapa universitas terkemuka (UGM, Universitas Airlangga, Universitas Diponegoro, Universitas Indonesia, Universitas Hasanuddin, Universitas Padjajaran, dan lain-lain), Kementerian Kesehatan-Direktorat Bina Gizi-KIA, dan beberapa perwakilan dinas kesehatan provinsi di Indonesia. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari forum konsorsium yang telah diadakan sebelumnya. Agenda utama pertemuan adalah pembahasan dan finalisasi AD-ART konsorsium KIA-Gizi. Konsorsium tersebut diharapkan menjadi perwujudan peran serta perguruan tinggi dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak, serta terutama menurunkan angka kematian ibu dan anak. Konsorsium ini diharapkan dapat terbentuk tidak hanya berdasarkan ikatan moral, namun juga berbadan hukum, agar dapat menjalankan kegiatan dengan tepat membantu Kementerian Kesehatan mengatasi masalah KIA. Di tingkat provinsi atau daerah, konsorsium ini diharapkan dapat mengembangkan & memperkokoh hubungan perguruan tinggi dengan pemerintah daerah.

Agenda hari pertama konsorsium yaitu pembahasan dan finalisasi AD-ART. Perumusan final AD-ART menjadi diskusi yang hangat, muncul banyak masukan yang membangun dari Dekan FK & FKM, dinas kesehatan dan kementerian kesehatan. Perumusan visi dan misi konsorsium didiskusikan bersama sehingga masing-masing pihak memahami harapan satu sama lain. Kementerian kesehatan memberikan informasi bahwa sudah disediakan anggaran sebesar Rp. 1 Miliar untuk membiayai kegiatan konsorsium KIA-Gizi, sehingga diharapkan seluruh kegiatan yang dipandang potensial dapat dilaksanakan dengan baik. Pembahasan AD-ART juga tidak terlepas dari Tri Dharma Perguruan Tinggi yang menjadi acuan bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia dalam merencanakan kegiatan. Kegiatan konsorsium ini dilaksanakan dengan sepengetahuan Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi (Dikti) yang menjadi induk bagi seluruh perguruan tinggi seluruh Indonesia.
Agenda hari kedua konsorsium mengenai pembahasan peran perguruan tinggi dalam memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah pusat maupun daerah berdasarkan hasil penelitian dan rencana tindak lanjut kegiatan konsorsium. Dr. Kirana dari Direktorat Bina Kesehatan Anak memberikan pengantar mengenai harapan Kementerian Kesehatan terkait peran perguruan tinggi dalam meningkatkan derajat kesehatan ibu dan anak. Kirana juga memaparkan gambaran data hasil SDKI terbaru yang menunjukkan perubahan trend angka kematian anak menurut usia (namun data tersebut belum dapat dipublikasikan secara resmi). Beberapa daerah mengalami penurunan angka kematian bayi & balita, namun beberapa daerah lain justru mengalami peningkatan. Kementerian Kesehatan juga menekankan bahwa perguruan tinggi dapat berperan dalam mengakselerasi pencapaian MDGs terkait KIA.
Agenda hari kedua selanjutnya adalah pemaparan 3 policy briefs oleh Prof. Laksono Trisnantoro, salah satunya yaitu penggunaan angka kematian absolut untuk menentukan program KIA di daerah. Ketiga policy briefs tersebut kemudian dibahas oleh tiga orang narasumber, yaitu Prof. Dr. dr. Kuntaman MS, Sp.MK(K) dari Universitas Airlangga, Prof. Dr. dr. H. Alimin Maidin, MPH dari Universitas Hasanuddin, dan dr. Anung Sugihantono, M.Kes dari Dinkes Provinsi Jawa Tengah. Pembahasan berlangsung hangat dengan adanya diskusi beberapa pertanyaan dari peserta konsorsium, antara lain mengenai pengalaman dinas kesehatan dalam menggunakan angka kematian absolut untuk merencanakan program/ intervensi KIA. Selain itu, dipaparkan pula beberapa isu terkait hubungan dengan stakeholder lainnya dalam menyusun policy brief dan mengenai peran riil perguruan tinggi dalam melakukan penelitian hingga dapat menghasilkan policy brief yang berkualitas dan tepat sasaran.
Setelah membahas policy brief, agenda kegiatan hari kedua adalah diskusi mengenai konsultan manajemen KIA di Indonesia. Selama ini kita sudah sering mendengar banyak konsultan di bidang lain seperti konsultan pajak, konsultan hukum, konsultan teknik untuk pembangunan proyek tertentu, namun kita belum pernah mendengar mengenai konsultan manajemen KIA. Banyak program KIA yang belum berjalan efektif karena masih kurangnya kualitas manajemen program, mulai dari perencanaan-pelaksanaan-monitoring-hingga evaluasi. Seringkali program KIA sudah direncanakan dan dilaksanakan dengan baik, namun karena aspek monitoringnya masih lemah, sehingga program tersebut menurun kualitas pelaksanaannya. Belum adanya lembaga independen yang bertugas melakukan monitoring dan evaluasi program KIA juga menjadi masalah yang perlu dibahas lebih lanjut.
Pembahasan mengenai konsultan manajemen KIA juga melibatkan diskusi yang menggigit di antara peserta, beberapa peserta setuju dengan konsep konsultan manajemen KIA, namun masih bertanya-tanya mengenai bagaimana cara mencetak tenaga konsultan manajemen KIA tersebut, siapa yang dapat mencetak dan bagaimana prospek kelangsungan konsultan manajemen KIA tersebut. Beberapa peserta juga membahas mengenai pengalaman selama menjadi konsultan independen untuk beberapa lembaga di bawah PBB. Isu yang menjadi pembahasan hangat adalah mengenai kejelasan kualifikasi pendidikan, kejelasan wewenang dan peraturan, sehingga ada kejelasan kapan seseorang dapat disebut sebagai konsultan manajemen KIA. Jika konsultan manajemen KIA sudah bekerja nantinya, maka diperlukan cost effectiveness analysis untuk menilai apakah konsultan memang dapat meningkatkan efektivitas pelayanan KIA-gizi.
Agenda kegiatan setelah manajemen KIA adalah pembahasan rencana tindak lanjut. Diskusi rencana tindak lanjut dilakukan di dalam tiga kelompok kecil, yaitu kelompok Dekan FK & FKM, kelompok Kemenkes dan Dinas Kesehatan Provinsi dan kelompok manajemen KIA (penelitian). Masing-masing kelompok memberikan rencana kegiatan yang diharapkan dapat membantu pemerintah meningkatkan kesehatan ibu & anak. Berikut adalah hasil diskusi masing-masing kelompok:
- Kel. Dekan FK-FKM (perguruan tinggi)
- Akan disusun pokja KIA-Gizi
- Pokja KIA didukung penerbitan SK rektor, dengan unsur: FK (obsgyn, anak, IKMKP), FKM (AKK, Prodi Gizi Kesehatan, Kesehatan reproduksi)
- Penyusunan program kerja untuk menurunkan AKI-AKA
- Internal : pemantapan pokja, Tri Dharma perguruan tinggi salah satu fokusnya adalah KIA-Gizi
- Eksternal : audiensi, advokasi ke pemerintah daerah, rencana aksi dan implementasi
- Kel. Manajemen KIA :
- Penelitian perbaikan instrumen mutu pencatatan dan pelaporan data KIA berbasis IT
- Peningkatan kemampuan soft skill bidan desa untuk mengurangi risiko keterlambatan dalam pelayanan emergensi di tingkat desa
- Peningkatan kemampuan petugas rekam medik dalam mengaudit dan memperbaiki kualitas data KIA
- Penguatan sistem pelayanan KIA di Puskesmas
- Peningkatan kemampuan bidan dan dokter umum dalam kasus penanganan kasus beresiko
- Pengembangan rumah tunggu bagi ibu hamil resiko tinggi
- Monitoring dan evaluasi program KIA-gizi
- Peningkatan sistem surveilans respon KIA-gizi berbasis di masyarakat
- Peningkatan pemahaman masyarakat dalam penanggulangan stunting
- Peningkatan dan pemahaman masyarakat dalam penanggulangan obesitas
- Rujukan
- Kematian pada ibu nifas
- Proposal penelitian yang disusun oleh multi-center
- Perbaikan sistem rujukan
- Respon terhadap kasus kematian ibu selama masa nifas
- Identifikasi sumber dana potensial : PNBP BOPTN, Dikti, Balitbangkes, Unicef, AusAID, USAID, GTZ, WHO, WFP, Balitbangkes dinkes provinsi
- Kel. Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi
- Perlunya identifikasi pos anggaran di tahun 2013 dan tiga tahun berikutnya yang dapat dipergunakan untuk kegiatan oleh Konsorsium. Direktorat Bina Kesehatan Anak menyediakan dana Rp. 1 Milyar untuk kegiatan konsorsium. Lima ratus juta rupiah akan dialokasikan untuk pertemuan rutin konsorsium, dan 500 juta rupiah untuk digunakan untuk memfasilitasi kegiatan konsorsium di empat kabupaten dan empat provinsi (akan ditentukan kemudian). Informasi sementara, dana dekon akan disediakan untuk tujuh provinsi untuk memfasilitasi kegiatan konsorsium (jumlah akan ditentukan kemudian).
- Identifikasi kegiatan yang dilakukan oleh Dinkes dan Kemenkes yang dapat melibatkan konsorsium:
- Manajemen Asfiksia dan BBLR (FK-Spesialis Anak)
- Pelatihan PONED (FK-Obsgyn)
- Supervisi PONED bersama SpOG dan SpA ke Puskesmas PONED
- AMP (Audit Maternal Perinatal)
- Pentoloka (program khusus provinsi Jawa Timur): pertemuan tahunan ilmiah untuk kesehatan ibu dan anak serta PENAKIB (Forum Penurunan AKI-AKB)
- Pelatihan SDIDTK
- Kelas ibu hamil
- Pelatihan konseling menyusui
- Pelatihan Konseling MP-ASI
- Pelatihan tim asuhan gizi buruk untuk RS dan Puskesmas dengan perawatan
- MTBS, MTBM (Manajemen Terpadu Balita Sakit), Manajemen Terpadu Bayi Muda
- Pelatihan PMTCT (Prevention HIV Mother to Child Transmission) bagi puskesmas
- Pelatihan peningkatan kemampuan dokter umum puskesmas perawatan.
- Orientasi Neonatal Essensial untuk akademi kebidanan dan akademi keperawatan
- TOT kelas ibu balita, TOT SDIDTK, Orientasi MTBS untuk dokter umum
 Beberapa usulan peserta terkait hasil diskusi antara lain:
Beberapa usulan peserta terkait hasil diskusi antara lain:
- Perlu diadakan diskusi lebih lanjut antara Kemenkes dengan PT, mengenai sebenarnya apa yang menjadi kebutuhan Kemenkes saat ini, sehingga PT bisa membantu sesuai kebutuhan.
- Penganggaran untuk penelitian didasarkan pada road map yang telah disusun fakultas, dana penelitian universitas tidak bisa dibagi rata, melainkan berdasarkan skala prioritas universitas.
- Konsorsium KIA-Gizi dapat melaksanakan kegiatan baru atau melakukan scalling-up beberapa program yang dirasa sebenarnya bisa berjalan tapi ternyata sulit berjalan cakupan program masih rendah.