Rabu, 10 Oktober 2018
{tab title=”Sesi 1″ class=”orange” align=”justify”}
Placing Community health systems at the heart of service delivery
Pembicara :
- Kumanan Rasanathan, Health Systems Global Board, Cambodia
- Soumya Swaminthan, World Health Organization, Switzerland
- Amuda Baba Dieu-Merci, Panafrican Institute of Community Health, Democratic Republic of Congo
- Ariel Frisancho, Catholic Medical Mission Board, Peru
- Manmeet Kaur, City Health Works, USA
- Stefan Swartling Peterson, UNICEF, USA
- Helen Schneider, University of the Western Cape, South Africa
 Pokok-pokok bahasan/paparan/diskusi:
Pokok-pokok bahasan/paparan/diskusi:
Placing Community health systems at the heart of service delivery
 Laporan Kegiatan
Laporan Kegiatan
Kumanan Rasanathan, Health Systems Global Board, Cambodia, membuka plenary dengan menampilkan video tentang “we are free”. Video tersebut menunjukkan bahwa terdapat keterbatasan dari penderita HIV yang ingin mengakses layanan kesehatan, karena masalah akses, Deklarasi Alma Atta menekankan pada kepentingan layanan kesehatan yang dekat ke kehidupan dan partisipasi masyarakat. Diperkirakan dalam 40 tahun mendatang sistem kesehatan akan berjuang dengan perubahan penyediaan layanan disebabkan oleh demografi, epidemiologi, budaya dan transformasi teknologi termasuk urbanisasi. Namun, upaya penguatan sistem kesehatan sering mengabaikan peran komunitas/masyarakat. Para narasumber mempertimbangkan bagaimana kebutuhan sistem kesehatan harus sejalan dengan komunitas yang heterogen baik untuk manusia dan lingkungannya, serta pengalaman masyarakat tersebut.

Soumya Swaminthan, World Health Organization, Switzerland, memberikan keynote speech yang memaparkan tentang fasilitas kesehatan primer tidak hanya bagaimana ketersediaan gedung, dan obat, namun bagaimana melibatkan masyarakat untuk diberdayakan sehingga dapat berpartisapasi dalam masalah kesehatannya. Penelitian diharapkan dapat memberikan dampak tidak hanya kepada berapa banyak jumlah publikasi, namun lebih penting adalah bagaimana penelitian kita dapat berdampak langsung politik dan sistem kesehatan yang berguna kepada masyarakat. WHO menekankan dan mendorong pelaksnaan penelitian yang berlangsung interdisiplin sehingga luarannya dapat mencakup berbagai cakupan. WHO mendukung peningkatan penelitian dengan peningkatan kapasitas tim multi displin sehingga memiliki tools yang lebih sesuai dengan konteks penelitian tersebut.
Selanjutnya, plenary dilangsungkan dalam diskusi. Community Health Worker (CHW) dapat menyuarakan tentang masalah sebenarnya yang sedang dihadapi oleh masyarakat. CHW memberikan diharapkan dapat memberikan ruang untuk menghargai setiap ide – ide berdasarkan fakta yang berguna dalam pengambilan kebijakan kesehatan. Di sisi lain, banyak negara memiliki konflik kepentingan dan rapuh terhadap masalah politik dan keamanan. Leaving nobody behind masih terasa jauh, karena pelayanan kesehatan primer di pedesaan Bahakan masih berjuang dalam kekurangan tenaga kesehatan dan kualitas layanan yang diterima. CHW merupakan kunci dalam meningkatkan layanan kesehatan yang berbasis pada masyakarat, sehingga suara masyarakat dapat didengar. Lebih jauh, CHW dapat menjadi pedoman dalam memperbaiki berbagai keterbasan sistem kesehatan. CHW memerlukan dan dapat mendorong performans lintas sektor dalam memepercepat SDGs, sehingga yang masih menjadi persoalan adalah bagaimana kita membawa CHW sebagai social connector. CHW dapat memberikan gambaran konteks/gambaran sehingga dapat menyatukan masyarakat kedalam sistem kesehatan.
 Refleksi untuk Indonesia:
Refleksi untuk Indonesia:
Indonesia telah memiliki banyak CHW diantara kader JKN, Kader STBM dan kader lainnya yang telah diorganisasi oleh puskesmas. Namun, kader – kader tersebut masih bekerja untuk sektor kesehatan dan pemerintah perlu melibatkan mereka dalam kolaborasi lintas sektor. Pengambilan keputusan secara terpisah memperlambat penyelesaian masalah kesehatan dan juga pembangunan kesehatan.
Reporter : Relmbuss Biljers Fanda
{tab title=”Sesi 2″ class=”blue”}
Memberikan Perlindungan Finansial Kepada Mereka yang Masih Tertinggal
 Pokok-pokok bahasan / paparan / diskusi:
Pokok-pokok bahasan / paparan / diskusi:
Sesi presentasi oral ini terdiri dari beberapa pembicara. Masing – masing partisispan menceritakan hasil penelitian di negara mereka masing-masing dalam waktu 10 menit.

Pembicara pertama, Edmund Kaniki, menceritakan bagaimana sistem asuransi yang ada di Ghana masih menyisakan masalah, yaitu masih banyaknya masyarakat yang berhak atas perlindungan ternyata tidak memiliki kartu, atau tidak menyadari bahwa mereka berhak atas perlindungan tersebut.

Pembicara kedua, Quynh Lee, menceritakan bagaimana sistem asuransi di Vietnam bertransformasi dari sistem multi pool ke sistem single pool, namun mereka menghadapi tantangan untuk mencakup seluruh target populasi. Prioritas mereka pada saat ini adalah meningkatkan cakupan layanan yang ditanggung.
Pembicara ketiga, Sherhin Mahmoud, menceritakan bagaimana di Bangladesh terdapat pembiayaan microhealth, dimana tersedia perlindungan untuk inpatient dan out patient dengan premi sangat rendah. Satu kartu berlaku untuk satu keluarga, maksimum 6 orang. Terlihat bahwa kartu ini sangat laris di antara keluarga yang memiliki riwayat penyakit kronis, namun tidak berhubungan dengan tingkat sosioekonomi mereka. Ini menunjukkan bahwa disain layanan dan paket manfaat yang bersifat demand driven sangat diminati.
Pembicara keempat, Manase Mishra, menceritakan isu keseteraan dalam program UHC di India. Penelitian ini melihat inequity within household, across households dan distribusi spasialnya diantara masyarakat di kuintil IV (terendah). Terlihat bahwa ada penggunaan kartu asuransi untuk rawat inap lebih tinggi untuk mereka yang memiliki anggota keluarga yang difabel, namun tidak ada perbedaan antara peserta dari berbagai agama maupun kasta. Penggunaan kartu juga lebih tinggi di wilayah perkotaan.

Pembicara keenam, Dahai Yue, menceritakan bagaimana perluasan cakupan Medicaid di AS pun mengalami inequity, karena masih meninggalkan mereka yang berasal dari kelompok masyarakat dengan latar belakang etnik tertentu. Akses untuk kelompok dengan latar belakang non Kaukasian harus diupayakan secara khusus apabila AS bermaksud untuk memperluas kepesertaan masyarakat non Kaukasian dan lebih penting lagi untuk mengurangi inequity dalam akses dan status kesehatan.
 Refleksi untuk Indonesia:
Refleksi untuk Indonesia:
Cakupan kesehatan semesta merupakan aspirasi negara sejak 2014 dan pemerintah bertekad untuk mencapainya melalui Jaminan Kesehatan Nasional. Beberapa permasalahan yang disoroti oleh para pembicara di berbagai negara ini menunjukkan bahwa permasalahan mencapai cakupan kesehatan semesta dihadapi oleh semua negara.
Pelajaran pertama dari para peneliti ini adalah bahwa ada banyak penelitian yang menyoroti pentingnya perlindungan yang adil dan relevan dengan kebutuhan tersedia untuk semua. Penelitian semacam ini harus didorong untuk mengidentifikasi beberapa permasalahan di lapangan dan menawarkan solusi yang praktis dan strategis. Penelitian tersebut perlu sejak awal melibatkan stakeholder utama, yaitu badan penyedia perlindungan, BPJS, untuk memastikan bahwa hasil penelitian tersebut langsung di ketahui oleh BPJS untuk memberi masukan perbaikan kebijakan operasional BPJS dalam penyediaan perlindungan. Kesulitan adopsi rekomendasi hasil penelitian menjadi kebijakan seringkali bersumber pada posisi penelitian yang berada di “luar” sistem dan pihak stakeholder tidak dilibatkan sejak awal dalam proses pendefinisian masalah dan tujuan penelitian.
Pelajaran kedua adalah bahwa JKN memilki potensi untuk mengurangi inequity di Indonesia. Namun, inequity sistemik yang tidak segera diatasi akan berarti bahwa risiko inequity selalu terjadi, di berbagai tingkat, dan antar berbagai wilayah ataupun kelompok masyarakat. Terlebih lagi jika sumber inequity tersebut berasal dari faktor yang inheren di dalam sistemnya.
Pengalaman di negara – negara ini menunjukkan bahwa kita pun perlu memberikan perhatian khusus bagi kelompok masyarakat rentan tertentu, entah karena lokasi geografis mereka, riwayat kesehatan mereka, atau hal-hal terkait latar belakang mereka, untuk memastikan bahwa mereka memahami hak perlindungan yang mereka miliki dan bagaimana akses terhadap layanan yang mereka butuhkan bisa tersedia sesuai kebutuhan. Hal ini mungkin memerlukan kebijakan khusus, atau bahkan desain ulang dari caranya layanan diberikan dan dimana layanan tersebut tersedia.
Salah satu contoh pembelajaran bagaimana framework untuk cakupan kesehatan semesta diupayakan untuk kelompok masyarakat dengan kebutuhan khusus tersedia di bahan bacaan berikut:
Leave no one behind Strengthening health systems for UHC and the SDGs in Africa
Reporter : Shita Dewi
{tab title=”Sesi 3″ class=”red”}
Menggali Potensi Sektor Swasta dalam Penyediaan Layanan dan Pembiayaan
 Pokok-pokok bahasan / paparan / diskusi
Pokok-pokok bahasan / paparan / diskusi
Sesi ini berisi presentasi oral dari berbagai hasil penelitian dari seluruh dunia. Sesi ini mengidentifikasi berbagai kontribusi sektor swasta baik for profit maupun nirlaba terhadap sistem kesehatan. Kontribusi ini tidak terbatas pada ketersediaan layanan, tetapi juga pembiayaan, platform digital dan berbagai model kemitraan.

Pembicara pertama, Priya Balasubramanam, menyajikan tiga model yang dilakukan di India. Pertama, jaringan layanan “dokter keluarga” yang didirikan dalam bentuk franchise. Tenaga (klinisi atau pun non klinisi) yang bekerja di sini memiliki ‘saham’ di dalam franchise ini. Mereka didanai oleh swasta dan sedikit donasi. Sasarannya yaitu populasi perkotaan.
Inovasi lain adalah ‘contracting out’ yang dilakukan oleh pemerintah untuk penyediaan layanan primer ke 1. 200 puskesmas yang dimiliki oleh yayasan, semuanya berada di wilayan pedesaan atau sangat terpencil. Pembiayaannya 50% berasal dari swasta, dan 50% lagi dari pemerintah. Mereka biasanya dikepalai oleh dokter yang telah tua, pensiun, dan ingin tinggal di pedesaan. Model lain adalah layanan rawat jalan yang disediakan oleh digital platform yang didirikan oleh seorang anak muda yang memulai bisnis startup telemedicine. Kekuatan sektor swasta dalam hal ini adalah karena mereka mampu menyediakan layanan yang terintegrasi dan mudah diakses, sesuatu yang gagal dipenuhi oleh sektor pemerintah.
Pembaca yang tertarik dapat melihat bagaimana franchise dokter keluarga di India pada tautan ini:
http://www.thefamilydoctor.co.in/
Pembicara kedua, Sarah Dominis berbicara mengenai perspektif total market, yaitu melihat potensi tenaga penyedia kesehatan di sektor swasta yang sangat beragam, bukan hanya tenaga klinisi. Di India, terdapat beberapa potensi tenaga kesehatan non pemerintah yang digali, yaitu task sharing, short term contract, tenaga kesehatan berbasis komunitas.

Pembicara berikutnya, Shaikh Hasan, menyajikan pemetaan terhadap layanan yang tersedia di kota – kota kecil di Bangladesh. Shaikh menemukan bahwa layanan di kota – kota kecil ternyata didominasi oleh penyedia swasta yang ukurannya kecil yang biasanya terkonsentrasi di dekat sebuah RS publik yang besar di daerah tersebut, biasanya berbentuk toko obat dan praktek swasta, sehingga mengakibatkan gap dalam layanan. Namun, praktek dokter swasta memainkan peran penting dalam penyediaan layanan kepada masyarakat setelah jam kerja RS publik berakhir (setelah jam 5 sore). Jadi penting untuk menggali potensi mereka lebih jauh untuk menyediakan layanan yang berkualitas.

Pembicara berikutnya, Maureen Lewis, menyajikan inovasi sektor swasta di Brasil yang berdampak pada semakin besarnya peran mereka dalam pembiayaan dan memperkuat posisi mereka di pasar. Di Brasil terdapat 12 penyedia asuransi swasta yang besar dan memiliki cakupan kepersertaan yang cukup besar. Bahkan 2 diantaranya memiliki peningkatan kepesertaan lebih dari 30%, dan yang lebih menarik mereka adalah asuransi yang berbasis HMO. Inovasi yang dilakukan oleh dua perusahaan asuransi ini yaitu menawarkan perlindungan yang lebih dalam untuk layanan di level primer untuk kelompok lansia. Inovasi yang lain adalah perusahaan asuransi ini memantau kualitas secara lebih aktif dengan menggunakan rekam medis elektronik, sehingga bisa menekan biaya, dan memastikan bahwa dokter yang tergabung di dalam HMO itu harus mencapai standar tertentu untuk tetap dapat menerima pembayaran.
Pembaca yang tertarik dapat membaca lebih lanjut mengenai pertumbuhan sektor swasta di Brasil di artikel berikut ini
download document
Pembicara berikutnya, Katelyn Long, menyajikan tentang potensi dari rumah sakit berbasis keagamaan di India, khususnya jaringan RS Kristen dan Katolik. Hal ini dimungkinkan ketika pemerintah secara progresif membuat berbagai kebijakan strategic purchasing dari penyedia layanan swasta. Khususnya ini sangat penting bagi India karena mayoritas RS Kristen dan Katolik ini tersedia di daerah pedesaan dan daerah terpencil. Kepastian pembiayaan pemerintah melalui strategic purchasing ini memungkinkan RS Kristen dan Katolik di daerah – daerah tersebut tetap dapat menyediakan layanan.
Pembicara terakhir, Rashid Zaman, menyajikan situasi di Somalia dimana mayoritas tenaga pemerintah juga bekerja di sektor swasta, dan pendapatan mereka jauh lebih besar di sektor swasta dibandingkan di sektor pemerintah.
 Refleksi untuk Indonesia:
Refleksi untuk Indonesia:
Sektor swasta memainkan peran penting dalam sistem kesehatan di Indonesia. Namun kemitraan dengan mereka biasanya terbatas. Pemerintah biasanya “hanya” melihat potensi dari kontribusi kegiatan corporate social responsibility dan belum mengoptimalkan potensi lain secara lebih strategis. Hal ini terkadang dibatasi oleh tidak tersedianya regulasi atau panduan yang mengatur kemitraan yang lebih strategis. Bahkan adanya panduan dan aturan mengenai kemitraan pemerintah dengan badan usaha belum dapat dimanfaatkan secara maksimal karena tantangan – tantangan teknis di lapangan.
Berbagai pengalaman yang disajikan di sesi ini semoga dapat menginspirasi kita untuk melihat kemitraan secara lebih luas dan lebih strategis. Model – model kemitraan ini seringkali bukan inovasi tetapi sebenarnya mengambil sumbernya dari model – model lain yang sudah ada di dunia bisnis. Pemerintah perlu lebih fleksibel dalam bermitra dengan sektor swasta, misalnya dengan membuat kontrak jangka pendek untuk SDM non pemerintah dengan paket fringe benefit yang menarik, dan terbuka terhadap pola penyediaan layanan faskes swasta yang mungkin berbeda dengan yang biasanya tersedia (atau model layanan yang familar bagi pemerintah), dan pemerintah lebih fokus pada ‘membeli kualitas’.
Reporter : Shita Dewi
{tab title=”Sesi 4″ class=”grey”}
Memahami Sisi Politik dari Kebijakan: Proses dan Kekuasaan
 Pokok-pokok bahasan / paparan / diskusi
Pokok-pokok bahasan / paparan / diskusi
Augustina Kaduah menyoroti kontestasi dan negosiasi yang terlibat dalam penetapan Panduan Layanan Standar dan Daftar Obat Esensial di Ghana. Proses penetapan PLS dan DOE melibatkan Kementrian Kesehatan dan komite obat nasional, asuransi, akademia, dan organisasi profesional. Augustina memetakan pihak mana yang mengkontestasi dan menegosiasi usulan untuk hal-hal yang diatur di dalam PLS dan DOE tersebut, karena terjadi begitu banyak tensi dari berbagai organisasi profesi mengenai hal ini. Bahkan, terdapat pihak yang belum dilibatkan di dalam proses ini, karena posisinya dianggap kurang strategis, yaitu asisten dokter. Namun, setelah adanya pertemuan khusus dengan mereka, terdapat beberapa perubahan mengenai wewenang asisten dokter yang diatur di dalam PLS tersebut. Hal ini khususnya perlu diakomodasi karena di banyak wilayah terpencil di Ghana tidak terdapat dokter, hanya tersedia asisten dokter.

Chinyere Okeke membahas bagaimana karekteristik aktor kebijakan serta konteks mempengaruhi proses agenda setting, formulasi dan implementasi kebijakan untuk program layanan KIA di Nigeria. Layanan KIA gratis tersedia di NIgeria pada 2009 – 2015 dengan didanai oleh adanya debt relief demi pencapaian MDG, tetapi setelah 2015 program tersebut berakhir. Chinyere menggunakan framework yang digunakan oleh Grindle dan Thomas (1991) untuk memetakan karakteristik aktor kebijakan yang mencoba merevitalisasi program tersebut.

Pembaca yang berminat untuk mempelajari berbagai framework proses kebijakan termasuk Grindle dan Thomas dapat mengunduhnya di sini:
download document
Sophie Witter mendalami studi kasus dari 8 negara berpenghasilan menengah dan rendah dan menyajikan beberapa kesimpulannya. Pertanyaan yang Sophie ajukan adalah bagaimana para pengambil kebijakan mencari dan mengakses bukti yang mereka butuhkan untuk membuat kebijakan tertentu, serta apa yang mereka anggap cukup adekuat untuk disebut sebagai “bukti”.

Observasi Sophie menyimpulkan bahwa reformasi atau perubahan kebijakan biasanya bersumber pada salah satu dari model ini:
- Adopsi inisiasi asing
- Masukan dan ide dari badan internasional
- Kemitraan dengan badan internasional (co-production)
- Disusun sendiri berdasarkan ide dari beberapa contoh regional
- Disusun sendiri berdasarkan ide dari beberapa contoh dari domestik
Beberapa mekanisme yang dipakai untuk proses pembelajaran adalah:
- Kunjungan ke negara lain
- Hubungan pribadi dengan badan internasional
- Pertemuan internasional
- Technical assistance
- Kelompok kerja domestik
- Jaringan profesi regional
- Jaringan pelatihan regional
- Konsultan domestik yang berpengaruh
- Masyarakat praktisi
- Laporan
- Pilot/uji coba
Namun yang paling penting reformasi kebijakan tersebut biasanya diadaptasi dengan konteks lokal. Oleh karena itu, pembuat kebijakan selalu membutuhkan “bukti” untuk menjustifikasinya. Namun “bukti” biasanya hanya digunakan apabila tersedia dalam format yang mudah dipahami dan tepat waktu.
Pembaca yang berminat dapat melihat ke tautan berikut ini untuk menyimak ebih lanjut mengenai hasil penelitian ini:
https://www.opml.co.uk/projects/learning-action-health-systems
 Refleksi untuk Indonesia:
Refleksi untuk Indonesia:
Perubahan kebijakan merupakan suatu hal yang sering kali diharapkan sebagai solusi untuk mengatasi beberapa permasalahan dalam sektor kesehatan. Namun, seringkali kita berada di luar sistem pengambilan kebijakan sehingga tidak menyadari kompleksnya politik di balik penetapan dan perubahan kebijakan. Politik dapat terjadi bukan hanya antar lembaga pemerintah, tetapi juga diantara pihak non pemerintah. Oleh karena itu, kita harus sangat memahami isu kebijakan yang kita perjuangkan untuk memastikan bahwa kita memetakan semua kepentingan yang terlibat dan melibatkan seluruh stakeholder. Mengelola kepentingan dan kekuasaan yang masing – masing stakeholder merupakan kunci dari mendapat dukungan atas perubahan yang kita usulkan.
Selain itu, pembuat kebijakan di Indonesia juga telah semakin terbuka terhadap masukan dan bukti – bukti yang mendukung argumentasi terhadap suatu perubahan kebijakan. Artinya, peneliti harus meningkatkan kapasitas, bukan hanya kapasitas dalam menyediakan ‘bukti’ yang meyakinkan dan dikumpulkan dan dianalisis dengan cara yang robust, tetapi lebih penting lagi adalah kapasitas untuk menyajikan bukti tersebut dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami oleh pengambil kebijakan.
Kita diingatkan pula, bahwa masyarakat pun memiliki ‘kekuasaan’. Kekuatan demand sebenarnya dalam banyak hal membentuk bagaimana kebijakan perlu disusun. Tugas peneliti untuk bersikap membela kepentingan dari end user dan stakeholder utama sektor kesehatan, yaitu kepentingan masyarakat.
Reporter : Shita Dewi
{tab title=”Sesi 5″ class=”green”}
Attracting, retaining and sustaining the health workforce
Pembicara :
- Prudence Ditlopo, Center for Health Policy, Unida;laversity of the Witwatersrand, South Africa
- Borwornsom Leerapan, Mahidol University, Thailand
- Mary Nyikuri, Strathmore University, Kenya
- Kuimeng Song, Shandong Academy of Medical
 Pokok-pokok bahasan / paparan / diskusi
Pokok-pokok bahasan / paparan / diskusi
- The resilient nurse – what motivates professional nurses to stay in their jobs and in underserved areas? Findings from a longitudinal study in South Africa.
- Strategic planning of human resources for health to address the challenges of Thailand’s Universal Health Coverage under the epidemiological transition: a system dynamics approach.
- “I train and mentor, they take them”: nurses’ perspectives on quality of inpatient care for sick newborns across sectors in Nairobi, Kenya.
- Attracting health workers to rural community health organizations in Shandong Province, China: insights from a discrete choice experiment
 Laporan Kegiatan
Laporan Kegiatan
Afrika Selatan memiliki tantangan dalam merekrut dan mempertahankan perawat di daerah pedesaan dan kurang terlayani. Tantangan tersebut diterjemahkan lebih rinci seperti kekurangan staf, kelebihan beban kerja dan lingkungan kerja yang kurang menguntungkan. Penelitian menunjukkan masih terdapat kebutuhan yang signifikan terhadap sejumlah tenaga kesehatan di daerah yang kurang menguntungkan/ terlayani. Jumlah perawat yang terbatas dalam jumlah di wilayah tersebut diragukan, karena alasan bertahan adalah amal dan komitmen untuk berbuat baik.

Thailand telah mencapai universal health coverage dan berfokus dalam isu epidemiological transition dan aging population. Dalam 20 tahun mendatang, Thailand mencoba untuk mencapai kuantitas dan kualitas tenaga kerja yang cukup, dengan mengoptimalkan layanan tenaga kesehatan terhadap masyarakat, meminimalkan angka kebutuhan tenaga kesehatan yang tidak terpenuhi, memaksimalkan status kesehatan dan kualitas hidup dari masyarakat, dan meminimalkan angka pembelanjaan kesehatan. Sistem kesehatan perlu memperhatikan konsep dan instrumen untuk menangani masalah kompleksitas sistem.
Kenya memiliki layanan rawat inap untuk Kesehatan Ibu dan Anak yang fokus kepada bayi lahir dengan ukuran lebih kecil dan sakit, dan meluas tidak hanya sektor pemerintahan, namun juga kepada layanan keagamaan, dan swasta. Penelitian ini menjelaskan faktor – faktor yang mempengaruhi persepsi perawat tentang mutu layanan. Kemampuan perawat dalam layanan rawat inap tersebut dipengaruhi oleh proses penerimaan dan masa persiapan kerja, dukungan – dukungan yang diterima melalui orientasi dan pembelajaran secara terus kontinyu, penghargaan terhadap pengalaman mereka.
Cina memiliki masalah kekurangan jumlah dan rendahnya kompentensi dari tenaga kesehatan masyarakat “Community health organization (CHOs)” di pedesaan. Reformasi sistem kesehatan menekankan pada penguatan fasilitas kesehatan dasar. Community health organization (CHOs) harus dapat mengambil tanggung jawab dalam layanan kesehatan dasar, sehingga perlu dipastikan bahwa sistem kesehatan di China dapat menarik CHOs yang berkualitas. Alternatif kebijakan harus diatur berdasarkan kebutuhan dasar dari CHOs seperti gaji yang memadai dan keuntungan yang didapat, dan pengembangan karir yang lebih baik.

 Refleksi untuk Indonesia:
Refleksi untuk Indonesia:
Indonesia memiliki masalah keterbatasan tenaga kesehatan di daerah pedesaan. Kekurangan tenaga tersebut menimbulkan masalah dalam beratnya beban kerja yang dapat menurunkan motivasi kerja. Peran pemangku kepentingan dalam menarik tenaga kesehatan di pedesaan memiliki kontribusi yang cukup besar. Sistem kesehatan yang direncanakan mulai dari perekrutan sampai pada kesejahteraan berkontribusi terhadap ketersediaan tenaga kesehatan.
Reporter : Relmbuss Biljers Fanda
{tab title=”Sesi 6″ class=”blue”}
Institutions for accountability and trust
Pembicara :
- Jean-Paul Dossou, Centre de Recherche en Reproduction Humaine et en Démographie, Cotonou, Benin and Institute of Tropical Medicine Antwerp, Belgium
- André Janse van Rensburg, Stellenbosch University,South Africa
- Napaphat Satchanawakul, King’s College London, UK
- Sara Van Belle, Institute of Tropical Medicine, Antwerp, Belgium
 Pokok-pokok bahasan / paparan / diskusi:
Pokok-pokok bahasan / paparan / diskusi:
- Trust me if you can! Realist insights on how mistrust undermines effective public-private engagement and strategies to address it in West Africa
- The significance of power dynamics in shaping government and private sector mental health care engagement in constrained resource settings: lessons from South Africa
- Policy feedback effects of Thailand’s Universal Health Coverage towards the role and power of private hospitals in the health system
- Public accountability of INGOs working in sexual and reproductive health in Ghana: a realist inquiry
 Laporan Kegiatan
Laporan Kegiatan
Sektor swasta memiliki pengalaman yang kurang baik dalam bekerjasama dengan pemerintah terkait birokrasi, prosedur pembayaran yang panjang dan ketidakpastian. Sektor swasta menerima biaya kesehatan dari pasien lebih dari 30 Euro. Sistem kesehatan perlu inovasi terhadap pengurangan risiko dari sektor swata sehingga tidak terjadi kerugian dalam sumber daya dan khususnya perlu mengatur prosedur administrasi yang sederhana, terpercaya dan transparan. Lebih lanjut, sistem kesehatan juga perlu menciptakan komitmen yang akuntabel sehingga kepercayaan sektor swasta dapat meningkat.

Masalah kesehatan di Afrika Selatan memiliki kaitan dengan konsep kekuasaan sendiri baik dalam sumber daya maupun apa yang telah dilakukan melalui kekuatan dalam kesehatan jiwa tersebut. Temuan dalam studi ini menunjukkan bawa adanya pembingkaian dari layanan sosial yang diberikan, lebih fokus kepada masalah pendonoran, posisi dari NGO pendukung, dan ketidakjelasan dari makna kondisi kejiwaan itu sendiri. Masalah tersebut dijelaskan lebih lanjut pada isu hierarki pada struktur, kewenangan pemerintah dan swasta, ketersediaan tenaga profesional, perbedaan ideologi, framing, dan kompetensi.
Studi ini bertujuan untuk menguji skema UHC di Thailand pada 2002 yang telah mendapatkan umpan balik berupa peran, kekuatan, dan akuntabilitas dari rumah sakit swasta. Sistem UHC di Thailand terbagi atas tiga kelompok yaitu kelompok pegawai negeri, kelompok pekerja dan kelompok lainnya. Dampak positif dari UHC terhadap rumah sakit swasta adalah mengurangi “out-of-pocket”, menjadi pilihan untuk warga kota yang dapat mengakses layanan, mengurangi beban rumah sakit pemerintah, tidak adanya kesalahan dalam kompensasi, platform dalam pengembangan Public Private Partnership dan akreditasi dalam layanan gawat darurat dalam skema UHC. Namun dampak lain yang juga mengikuti adalah peran dari RS swasta sangat kecil, menjadi RS terlalu khusus untuk kelompok masyarakat tertentu, kekuatan dan suara RS swasta menjadi tidak masuk akal jika diwakilkan oleh asosiasi rumah sakit swasta.
International Non Government Organizations (INGO) meningkat secara jumlah pada 1990-an dan perlu diperhatikan pengawasan terkait akuntabilitas finansial dari NGO itu sendiri. Akuntabilas tersebut bisa berdasarkan pemetaan terkait kategori INGO berdasarkan layanan yang diberikan, komunitas mana yang terlayani, siapa yang menjadi ahli dalam INGO tersebut. Temuan tentang “accountability chain” di tingkat kabupaten menjelaskan komunitas yang terlayani mencakup cara – cara bagaimana melibatkan komunitas dan lokal NGO dari permulaan, transparansi dana donor. Kategori layanan yang diberikan NGO menjelaskan terdapat beberapa bentuk umpan balik dan bagaimana mekanismenya, baik melalui telpon, penangung jawab dan untuk beberapa kasus perlu adanya MoU. Data menunjukkan lemah akuntabiltas yang bersifat horizontal kepada pemerintah lokal.
 Refleksi untuk Indonesia:
Refleksi untuk Indonesia:
Sistem kesehatan di Indonesia memiliki kesamaan dalam hal aktor dan sistem kesehatan tersebut yaitu pemerintah baik pusat maupun daerah, fasilitas kesehatan baik umum maupun khusus (kejiwaan), NGO internasional dan sebagainya. Data yang dipaparkan dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan bagaimana aktor tersebut memandang sistem kesehatan tersebut shingga kerja sama lintas sektor dapat terjalin dengan baik. Isu akuntabiltas terkait sektor lain perlu diatur lebih lanjut sehingga sistem kesehatan di Indonesia dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
Reporter : Relmbuss Biljers Fanda
{/tabs}
Link Terkait:
{jcomments on}















 Buku Analisis Kebijakan Kesehatan (WHO, 2018) terbaru diluncurkan pagi ini. Buku ini merupakan pengembangan dari buku sebelumnya, Health Policy and System Analysis: A Methodological Reader (WHO, 2012). Lucy Gilson, sang penulis utama dan editor, menyampaikan bahwa terbitnya buku baru ini penting untuk lebih menempatkan kebijakan kesehatan pada posisi yang penting. Analisis kebijakan kesehatan merupakan bagian yang memiliki interface dengan perubahan kebijakan dan pengembangan sistem kesehatan. Pemahaman atas proses dan implementasi kebijakan memiliki potensi yang besar untuk memberi daya dorong untuk perubahan kebijakan kesehatan dan perbaikan dalam sistem kesehatan.
Buku Analisis Kebijakan Kesehatan (WHO, 2018) terbaru diluncurkan pagi ini. Buku ini merupakan pengembangan dari buku sebelumnya, Health Policy and System Analysis: A Methodological Reader (WHO, 2012). Lucy Gilson, sang penulis utama dan editor, menyampaikan bahwa terbitnya buku baru ini penting untuk lebih menempatkan kebijakan kesehatan pada posisi yang penting. Analisis kebijakan kesehatan merupakan bagian yang memiliki interface dengan perubahan kebijakan dan pengembangan sistem kesehatan. Pemahaman atas proses dan implementasi kebijakan memiliki potensi yang besar untuk memberi daya dorong untuk perubahan kebijakan kesehatan dan perbaikan dalam sistem kesehatan. Buku ini terdiri dari empat bagian. Bagian pertama semacam Overview terhadap topik Analisis Kebijakan Kesehatan, yang mencakup konsep dasar, arti pentingnya serta konteks politik ekonomi yang terkait di dalamnya.
Buku ini terdiri dari empat bagian. Bagian pertama semacam Overview terhadap topik Analisis Kebijakan Kesehatan, yang mencakup konsep dasar, arti pentingnya serta konteks politik ekonomi yang terkait di dalamnya.






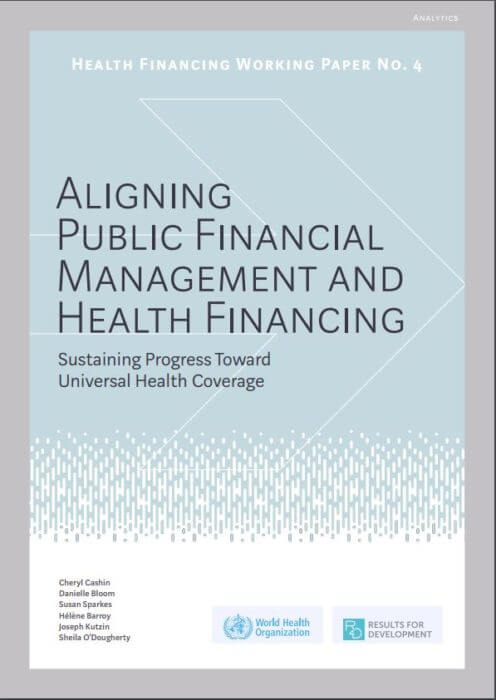 Public financial management (PFM) for health diharapkan dapat menghubungkan pembiayaan untuk tenaga kesehatan dan prioritas kesehatan (efisiensi alokasi pembiayaan). PFM juga dapat mempertimbangkan penekanan pengeluaran yang terlalu kecil untuk operasional. Lebih jauh, PFM diharapkan dapat meningkatkan kinerja pengelolaan dana UHC (efektif dan penggunaan yang setara dengan sumber daya). Masalah PFM yang umum dihadapi adalah kekurangan penguasaan prosedur dari kementerian kesehatan, menyalahgunakan prosedur negosiasi dengan dalih urgensi, ketidaksesuaian antara prosedur dan pengelolaan keuangan, dan prosedur dan peraturan yang kompleks dan kaku. Selengkapnya:
Public financial management (PFM) for health diharapkan dapat menghubungkan pembiayaan untuk tenaga kesehatan dan prioritas kesehatan (efisiensi alokasi pembiayaan). PFM juga dapat mempertimbangkan penekanan pengeluaran yang terlalu kecil untuk operasional. Lebih jauh, PFM diharapkan dapat meningkatkan kinerja pengelolaan dana UHC (efektif dan penggunaan yang setara dengan sumber daya). Masalah PFM yang umum dihadapi adalah kekurangan penguasaan prosedur dari kementerian kesehatan, menyalahgunakan prosedur negosiasi dengan dalih urgensi, ketidaksesuaian antara prosedur dan pengelolaan keuangan, dan prosedur dan peraturan yang kompleks dan kaku. Selengkapnya:

















 Sesi ini merupakan sesi yang termasuk dalam kelompok “membangun ketrampilan”. Pada sesi semacam ini, peserta diperkenalkan pada beberapa konsep baru dalam metodologi tertentu dan diajak berdiskusi dengan menggunakan beberapa contoh nyata dari penerapan metodologi tersebut dalam suatu intervensi atau program. Pertama, dipaparkan beberapa metodologi dalam penelitian dan bagaimana aplikasi atau contohnya dalam beberapa penelitian yang sejenis dan banyak dikutip dalam penelitian kesehatan atau penelitian kebijakan kesehatan.
Sesi ini merupakan sesi yang termasuk dalam kelompok “membangun ketrampilan”. Pada sesi semacam ini, peserta diperkenalkan pada beberapa konsep baru dalam metodologi tertentu dan diajak berdiskusi dengan menggunakan beberapa contoh nyata dari penerapan metodologi tersebut dalam suatu intervensi atau program. Pertama, dipaparkan beberapa metodologi dalam penelitian dan bagaimana aplikasi atau contohnya dalam beberapa penelitian yang sejenis dan banyak dikutip dalam penelitian kesehatan atau penelitian kebijakan kesehatan.

 Suatu layanan kesehatan dengan kualitas yang rendah mencerminkan tingginya angka mortality jika dibandingkan dengan jumlah yang tidak mendapatkan layanan kesehatan. Suatu sistem kesehatan dengan kualitas yang baik dinilai berharga dan terpercaya untuk semua orang sehingga dapat merespon perubahan kebutuhan suatu populasi. Universal Health Coverage dan Sustainable Developmnet Goals memiliki misi untuk meningkatkan ketersediaan pada bukti yang relevan dan sensitif terhadap penguatan kebijakan dan sisrem secara global. Pengambil keputusan menuntut sebuah review yang bertujuan untuk meng-cover isu tentang: efektivitas dari suatu kebijakan dan intervensi sistem kesehatan. Seting yang bagaimana dan seperti apa intervensi tersebut berkerja, persepsi dan pandangan stakeholders tentang tantangan sistem kesehatan dan pilihan kebijakan. Evidence synthesis for health policy and systems merupakan komponen yang fundamental dari pendekatan informatif berbasis bukti terhadap pengambilan keputusan.
Suatu layanan kesehatan dengan kualitas yang rendah mencerminkan tingginya angka mortality jika dibandingkan dengan jumlah yang tidak mendapatkan layanan kesehatan. Suatu sistem kesehatan dengan kualitas yang baik dinilai berharga dan terpercaya untuk semua orang sehingga dapat merespon perubahan kebutuhan suatu populasi. Universal Health Coverage dan Sustainable Developmnet Goals memiliki misi untuk meningkatkan ketersediaan pada bukti yang relevan dan sensitif terhadap penguatan kebijakan dan sisrem secara global. Pengambil keputusan menuntut sebuah review yang bertujuan untuk meng-cover isu tentang: efektivitas dari suatu kebijakan dan intervensi sistem kesehatan. Seting yang bagaimana dan seperti apa intervensi tersebut berkerja, persepsi dan pandangan stakeholders tentang tantangan sistem kesehatan dan pilihan kebijakan. Evidence synthesis for health policy and systems merupakan komponen yang fundamental dari pendekatan informatif berbasis bukti terhadap pengambilan keputusan.
 Sesi ini diawali dengan paparan Professor Anthony Culyer dari University of York yang saat ini menjabat sebagai Ketua International Decision Support Initiative (IDSI). Pada intinya disebutkan bahwa dalam situasi saat ini untuk sektor kesehatan, Cost-Effectiveness Analysis (CEA) bukan satu – satunya solusi. Terdapat ideologi tentang kesehatan yang berguna bagi semua. Apa value dan impact yang harus memiliki bukti. Hal ini bukan sebuah kegiatan politis namun teknis. Di Inggris dikembangkan oleh NICE dan didukung oleh pemerintah dan kelompok oposisi.
Sesi ini diawali dengan paparan Professor Anthony Culyer dari University of York yang saat ini menjabat sebagai Ketua International Decision Support Initiative (IDSI). Pada intinya disebutkan bahwa dalam situasi saat ini untuk sektor kesehatan, Cost-Effectiveness Analysis (CEA) bukan satu – satunya solusi. Terdapat ideologi tentang kesehatan yang berguna bagi semua. Apa value dan impact yang harus memiliki bukti. Hal ini bukan sebuah kegiatan politis namun teknis. Di Inggris dikembangkan oleh NICE dan didukung oleh pemerintah dan kelompok oposisi. Prof Calypso dari Imperial College Inggris membahas lebih banyak mengenai rationing plan. Tergantung pada situasi di berbagai negara. Perlu independensi negara yang mengembangkan perencanaan pelayanan kesehatan yang masuk ke UHC atau yang tidak. Menentukan Benefit Package dan obat apa yang harus masuk. Untuk itu capacity development penting sekali dalam kegiatan ini. Namun konteks yang ada perlu diperhitungkan. Setiap negara mempunyai regulasi masing – masing. Terdapat perbedaan transparasi dan perbedaan perilaku politikus.
Prof Calypso dari Imperial College Inggris membahas lebih banyak mengenai rationing plan. Tergantung pada situasi di berbagai negara. Perlu independensi negara yang mengembangkan perencanaan pelayanan kesehatan yang masuk ke UHC atau yang tidak. Menentukan Benefit Package dan obat apa yang harus masuk. Untuk itu capacity development penting sekali dalam kegiatan ini. Namun konteks yang ada perlu diperhitungkan. Setiap negara mempunyai regulasi masing – masing. Terdapat perbedaan transparasi dan perbedaan perilaku politikus. Bagi para pembaca yang ingin lebih mendalami mengenai diskusi ini lebih lanjut, silahkan membaca buku yang berjudul menarik ini.
Bagi para pembaca yang ingin lebih mendalami mengenai diskusi ini lebih lanjut, silahkan membaca buku yang berjudul menarik ini.






 Buku ini dapat di-download melalui laman WHO:
Buku ini dapat di-download melalui laman WHO: