Pengantar
Mereka yang berada di pinggiran masih sering terabaikan dalam hal perumusan kebijakan, termasuk dalam program Jaminan Kesehatan Nasional. Berbagai tantangan yang harus dihadapi jika dibandingkan dengan wilayah perkotaan, misal akses pelayanan kesehatan, ketersediaan tenaga medis dan sarana prasarana, serta infrastruktur yang belum memadai dan masih banyak hal lain yang menjadi faktor penghambat tercapainya Universal Health Coverage. Berbagai regulasi telah dirumuskan di level nasional, diperlukan kajian yang mendalam terkait kesiapan berbagai daerah dalam implementasi kebijakan tersebut. Sehingga perlu perhatian lebih dari para policy maker dalam pembuatan kebijakan maupun dalam melakukan revisi kebijakan khususnya memperhatikan mereka yang di pinggiran.
Tujuan
- Mendeskripsikan berbagai masalah yang dihadapi mereka yang dipinggiran pada era JKN
- Membahas revisi kebijakan untuk menyelesaikan masalah di pinggiran agar tepat sasaran
Peserta
- Anggota Community of Practice JKN dan Kesehatan
- Peneliti, praktisi, dan akademisi
Agenda
Diskusi ini akan diselenggarakan pada hari Rabu, 10 Mei 2017; pukul 13:00 – 15.00 WIB; bertempat di Ruang Leadership, Gedung IKM Lama lantai 3 Fakultas Kedokteran, Universitas Gadjah Mada. Bapak/ Ibu/ Sdr yang tidak dapat hadir secara tatap muka dapat tetap mengikuti diskusi webinar melalui link registrasi: https://attendee.gotowebinar.com/register/4571088033512374531
Webinar ID: 980-986-107
Arsip diskusi bersama Community of Practice Pembiayaan Kesehatan dan JKN dapat diakses selengkapnya melalui website http://www.kebijakankesehatanindonesia.net/ dan website http://manajemen-pembiayaankesehatan.net/
Pemateri
- Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D
- P2JK Kemenkes (dalam konfirmasi)
- Rimawati, M. Hum (Dosen Fak. Hukum UGM) (dalam konfirmasi)
Pembahas
- Stefanus Bria Seran, MPH (Bupati Malaka) (dalam konfirmasi)
- Women Research Institute (WRI) (dalam konfirmasi)
Susunan Acara
|
Waktu |
Materi |
Pemateri/Pembahas |
|
13.00-13.10 |
Pembuka |
Moderator |
|
13.10-13.30 |
Sesi 1 : Membahas berbagai masalah yang dihadapi daerah pinggiran di era JKN |
Dr. Dwi Handono, MKes |
|
13.30-13.50 |
Sesi 2 : Membahas kebijakan kesehatan yang membangun dari daerah pinggiran |
P2JK – Kemenkes |
|
13.50-14.10 |
Sesi 3 : Membahas peluang adanya revisi kebijakan yang berpihak dalam mengatasi masalah di daerah pinggiran untuk mendukung penyelenggaraan program JKN |
Rimawati, SH., M. Hum |
|
14.10-14.30 |
Pembahasan |
Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D |
|
14.30-15.00 |
Diskusi/ Tanya Jawab |
Pemateri/ Pembahas |
|
15.00 |
Penutup |
Moderator |
Informasi dan Pendaftaran
Maria Lelyana (Lely)
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan
Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
Telp/Fax. (0274) 549425 (hunting), 081329760006 (HP/WA)
Email: [email protected]
Website:
http://www.kebijakankesehatanindonesia.net/ , http://manajemen-pembiayaankesehatan.net/
Hadir kembali mengenai topik Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pada Rabu (10/5/2017) Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada (PKMK FK UGM) mengadakan seminar (yang juga berlangsung via webinar) dengan mengundang beberapa pemateri dan pembahas yang berkompeten di bidangnya. Topik utama dalam seminar ini mendiskusikan terkait peluang dalam upaya revisi kebijakan JKN yang memperhatikan dan mempertimbangkan kelompok masyarakat di wilayah pinggiran. Dalam seminar ini terdapat 3 (tiga) sesi bahasan, yang pada masing-masing sesi menjelaskan dan mendiskusikan sub topik terkait.
Seminar diawali dengan pengantar dari Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D. Topik seminar ini merupakan persiapan untuk mendukung kegiatan monitoring dan evaluasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Diskusi dalam topik ini dirasa menarik dan dapat menjadi salah satu contoh studi kasus di wilayah pinggiran Indonesia, yang dapat menggambarkan alasan mengapa perlu ada semacam revisi atau perbaikan kebijakan. Hasil diskusi ini juga diharapkan dapat menjadi pelengkap informasi untuk evaluasi kebijakan yang lebih komprehensif dan dapat memperoleh perhatian lebih dari pemerintah, khususnya pemerintah pusat.
Masuk ke dalam sesi pemaparan materi, sesi 1 dimulai dengan membahas tentang berbagai maslalah yang dihadapi daerah pinggiran di era JKN. Pemaparan ini disampaikan oleh Dr. dr. Dwi Handono Sulistyo, MKes. Dalam sesi ini, pembicara menyampaikan studi kasus di Kabupaten Malaka yang merupakan wilayah yang baru berkembang dan berdiri pada 2013. Kabupaten ini berada di ujung timur Indonesia dan lokasinya cukup jauh untuk dijangkau. Sebagai wilayah yang baru berkembang, permasalahan pemenuhan pelayanan kesehatan masih sangat kurang. Ditambah dengan kondisi infrastruktur untuk transportasi juga masih minim. Hal menarik yang dibahas dalam sesi ini adalah peran dan motivasi yang kuat dari Bupati Malaka, yang merupakan seorang dokter, dalam mengupayakan dan mengutamakan kemajuan pelayanan kesehatan di daerahnya. Kelengkapan untuk peningkatan upaya kesehatan yang paripurna dirasa masih lemah karena terbatasnya tenaga kesehatan spesialis di wilayah tersebut. Kondisi ini tentu akan menyulitkan jika harus dilakukan kerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Sebagai salah satu bentuk upaya bantuan akselerasi proses ini, Dr. dr. Dwi Handono Sulistyo, MKes menceritakan pengalamannya saat ini yang membantu akselerasi kesiapan layanan kesehatan di Kabupaten Malaka dengan upaya kerja sama melalui konsep “sisterhood”, utamanya untuk Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Konsep “sisterhood” ini, membawa Kabupaten Kulon Progo untuk menjadi “pendamping/kakak/sister” untuk Kabupaten Malaka yang akan membantu dalam menstabilkan dan meningkatkan kapasitas dan sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Malaka. 1 (satu) Puskesmas di Kabupaten Kulon Progo akan mendampingi 2-3 Puskesmas di Kabupaten Malaka. Begitu pula dengan dinas kesehatannya. Konsep “sisterhood” ini juga sebenarnya diterapkan pada rumah sakit di Kabupaten Malaka. Namun, terdapat kendala dalam peraturan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dikatakan oleh pemateri bahwa akselerasi Kabupaten Malaka, untuk 2017 ini fokus pada upaya akreditasi, kemudian tahun depan mengarah pada status BLUD, hingga pada akhirnya peningkatan kapasitas dinas dan puskesmas tercapai.
Masuk ke sesi 2, melalui webinar, drg. Doni Arianto, MKM dari Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kemenkes membahas tentang kebijakan kesehatan apa saja yang telah dikeluarkan oleh Kemenkes untuk membangun dari daerah pinggiran. Pada dasarnya, pemateri menyampaikan bahwa bukan hal yang mudah untuk memeratakan situasi pelayanan kesehatan di Indonesia karena banyaknya variasi daerah yang pada akhirnya tidak secara serentak seluruh daerah di Indonesia dapat mengalami kesiapan dalam upaya pelayanan kesehatan. Di sisi lain, ada peran dari pemerintah daerah yang sangat penting untuk dapat menentukan kebijakan lokal. Beberapa upaya kebijakan yang telah diupayakan dari berbagai sisi adalah dari sisi penguatan peran pemerintah pusat dan daerah, serta adanya petunjuk untuk perihal apa saja yang perlu disiapkan dalam membangun sistem pelayanan kesehatan di daerah. Beberapa hal yang disebutkan antara lain adalah sistem rujukan, akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan, pengadaan obat dan alat kesehatan, pendanaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK), penguatan sharing pelayanan antara fasilitas kesehatan milik pemerintah dan swasta, serta upaya pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan untuk daerah. Pemerintah pusat, dalam hal ini Kemenkes pun saat ini semakin giat dalam mengajak kerjasama kementerian sektor lain untuk dapat melakukan pembangunan daerah guna mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan yang lebih optimal. Tidak ketinggalan, masalah insentif/ kompensasi pun menjadi isu yang masih terus diupayakan di Kemenkes, akan tetapi masih belum menemukan formula dan kerangka teknis yang tepat. Pemateri menyampaikan bahwa kemungkinan masih perlu ada best practice terlebih dahulu terkait kompensasi yang dapat membuka peluang gambaran konsep kompensasi seperti apa yang cocok diterapkan untuk tenaga kesehatan di daerah.
Selanjutnya di sesi 3, membahas peluang adanya revisi kebijakan yang berpihak dalam mengatasi masalah di daerah pinggiran untuk mendukung penyelenggaraan program JKN. Materi ini disampaikan oleh Rimawati, SH., M. Hum yang merupakan dosen dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Rimawati menyatakan bahwa dalam penyusunan peraturan tertentu, implementasi peraturan menjadi sebuah konsekuensi yang mengikuti. Idealnya, jika sudah diatur dalam peraturan maka harus dijalankan, jika tidak dapat terlaksana sebenarnya bisa ada sanksi tersendiri terkait hal tersebut. Namun, kembali lagi apakah konsep sanksi ini masuk ke dalam peraturan yang disusun. Kemudian terkait dengan masalah kompensasi, dalam hal ini untuk tenaga kesehatan, perlu dimulai dengan adanya konsep, definisi, dan aturan pelaksanaan yang disusun. Hal ini menunjukkan bahwa perlu ada kejelasan dalam peraturannya agar implementasi di daerah tidak “ambigu”. Jika sebuah peraturan/undang-undang ini tidak implementatif, maka dapat dikatakan bahwa ada bias dalam peraturan tersebut.
Konsep kebijakan perlu dituliskan dengan jelas dan dipastikan untuk dapat diimplementasikan dengan baik di daerah. Hal ini juga berlaku untuk mengembangkan peraturan tentang pelayanan kesehatan. Upaya kebijakan yang implementatif tentunya termasuk dalam kemudahan dan kemungkinan dapat diterapkan diseluruh wilayah Indonesia termasuk wilayah pinggiran. Dengan demikian, meskipun ada ketidakseragaman waktu implementasi, namun diharapkan kebijakan ini dapat diterima dengan baik di setiap daerah dan tidak menyebabkan ketimpangan antara satu daerah dengan daerah yang lain.
Reporter : Aulia Novelira, SKM, M.Kes





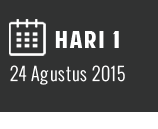
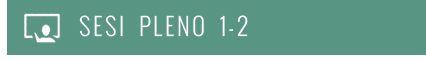
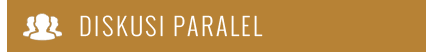
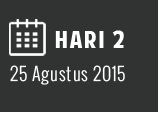


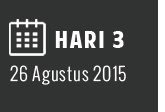











 Forum Nasional (Fornas) Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) XII pada hari ketiga (19/10/2022) mengangkat topik “Peran Analis Kebijakan dan Keterampilan yang Dibutuhkan: Penggunaan Data Sekunder Kesehatan dan Teknik Advokasi”. Acara yang dipandu oleh Mashita Inayah, S.Gz selaku master of ceremony (MC) ini dimulai dengan pembukaan dari Prof. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D., sebagai Ketua JKKI. Laksono membuka acara dengan menekankan pentingnya basis bukti atau evidence dan keterampilan advokasi untuk mendukung proses penyusunan kebijakan. Sesi pembukaan diakhiri dengan pertanyaan,”Apakah diperlukan pemisahan profesi/peran sebagai advokator kebijakan dan analis kebijakan?”
Forum Nasional (Fornas) Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) XII pada hari ketiga (19/10/2022) mengangkat topik “Peran Analis Kebijakan dan Keterampilan yang Dibutuhkan: Penggunaan Data Sekunder Kesehatan dan Teknik Advokasi”. Acara yang dipandu oleh Mashita Inayah, S.Gz selaku master of ceremony (MC) ini dimulai dengan pembukaan dari Prof. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D., sebagai Ketua JKKI. Laksono membuka acara dengan menekankan pentingnya basis bukti atau evidence dan keterampilan advokasi untuk mendukung proses penyusunan kebijakan. Sesi pembukaan diakhiri dengan pertanyaan,”Apakah diperlukan pemisahan profesi/peran sebagai advokator kebijakan dan analis kebijakan?” Acara dilanjutkan dengan paparan dari tiga narasumber. Sesi ini dimoderasi oleh Shita Listyadewi, MM, MPA selaku Kepala Divisi Kesehatan Masyarakat PKMK. Narasumber pertama untuk sesi ini adalah Dr. dra. Dumilah Ayuningtyas, MARS, dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia. Dumilah membawakan materi yang bertajuk “Interpretasi Data Kualitatif dan Kuantitatif untuk Analis Kebijakan”. Dumilah berargumen sebuah kebijakan membutuhkan basis bukti berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Lebih jauh lagi, evidence-based policy membutuhkan kompetensi teknis untuk mengintegrasikan pengalaman, pertimbangan, dan ekspertis dengan data yang tersedia untuk memastikan penyusunan kebijakan dilakukan secara objektif dan bukan sekadar berbasis opini.
Acara dilanjutkan dengan paparan dari tiga narasumber. Sesi ini dimoderasi oleh Shita Listyadewi, MM, MPA selaku Kepala Divisi Kesehatan Masyarakat PKMK. Narasumber pertama untuk sesi ini adalah Dr. dra. Dumilah Ayuningtyas, MARS, dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Indonesia. Dumilah membawakan materi yang bertajuk “Interpretasi Data Kualitatif dan Kuantitatif untuk Analis Kebijakan”. Dumilah berargumen sebuah kebijakan membutuhkan basis bukti berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Lebih jauh lagi, evidence-based policy membutuhkan kompetensi teknis untuk mengintegrasikan pengalaman, pertimbangan, dan ekspertis dengan data yang tersedia untuk memastikan penyusunan kebijakan dilakukan secara objektif dan bukan sekadar berbasis opini. Narasumber kedua adalah dr. Likke Prawidya Putri, MPH, Ph.D (cand), Dosen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK), Universitas Gadjah Mada (UGM). Likke memberikan pemaparan yang berjudul “Metode Realist Evaluation untuk Analis Kebijakan”. Likke menyampaikan bahwa realist evaluation (RE) merupakan pendekatan yang berbasis pada realisme, yakni penerimaan akan kenyataan yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya dan merespon temuan-temuan tersebut.
Narasumber kedua adalah dr. Likke Prawidya Putri, MPH, Ph.D (cand), Dosen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan (FK-KMK), Universitas Gadjah Mada (UGM). Likke memberikan pemaparan yang berjudul “Metode Realist Evaluation untuk Analis Kebijakan”. Likke menyampaikan bahwa realist evaluation (RE) merupakan pendekatan yang berbasis pada realisme, yakni penerimaan akan kenyataan yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya dan merespon temuan-temuan tersebut. Narasumber ketiga yaitu Gabriel Lele, M.Si, Dr.Phil, Dosen Manajemen dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL), UGM. Gabriel memberikan pemaparan “Teknik Advokasi Kebijakan untuk Analis Kebijakan”. Senada dengan paparan Dumilah, Gabriel menyampaikan bahwa peran advokator kebijakan tidak bisa dipisahkan dengan peran analis kebijakan. Gabriel mengatakan bahwa analis kebijakan perlu memposisikan dirinya sebagai “policy entrepreneur” supaya hasil-hasil kajian dapat ditindaklanjuti oleh pembuat kebijakan. Titik-titik advokasi dapat bervariasi, misalnya di fase agenda-setting, formulasi alternatif solusi, implementasi, dan evaluasi.
Narasumber ketiga yaitu Gabriel Lele, M.Si, Dr.Phil, Dosen Manajemen dan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL), UGM. Gabriel memberikan pemaparan “Teknik Advokasi Kebijakan untuk Analis Kebijakan”. Senada dengan paparan Dumilah, Gabriel menyampaikan bahwa peran advokator kebijakan tidak bisa dipisahkan dengan peran analis kebijakan. Gabriel mengatakan bahwa analis kebijakan perlu memposisikan dirinya sebagai “policy entrepreneur” supaya hasil-hasil kajian dapat ditindaklanjuti oleh pembuat kebijakan. Titik-titik advokasi dapat bervariasi, misalnya di fase agenda-setting, formulasi alternatif solusi, implementasi, dan evaluasi. Setelah sesi pemaparan dan diskusi, acara dilanjutkan dengan presentasi policy brief yang dipandu oleh Tri Muhartini, MPA. Presentasi pertama dibawakan oleh Mandira Ajeng Rachmayanthy dengan topik “Integrasi Pelayanan Kesehatan Mental Berbasis Telehealth”. Penggunaan fasilitas Telehealth diharapkan dapat menjembatani masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan mental. Telehealth yang berkembang pesat dapat menjangkau wilayah secara luas sehingga menjadi rekomendasi layanan kesehatan dengan mempertimbangkan aspek tata kelola, keuangan, pelayanan dan potensi bahayanya. Oleh karena itu diperlukan regulasi terkait sistem pelayanan kesehatan mental melalui Telehealth yang terintegrasi dengan sistem pemerintah pusat.
Setelah sesi pemaparan dan diskusi, acara dilanjutkan dengan presentasi policy brief yang dipandu oleh Tri Muhartini, MPA. Presentasi pertama dibawakan oleh Mandira Ajeng Rachmayanthy dengan topik “Integrasi Pelayanan Kesehatan Mental Berbasis Telehealth”. Penggunaan fasilitas Telehealth diharapkan dapat menjembatani masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan mental. Telehealth yang berkembang pesat dapat menjangkau wilayah secara luas sehingga menjadi rekomendasi layanan kesehatan dengan mempertimbangkan aspek tata kelola, keuangan, pelayanan dan potensi bahayanya. Oleh karena itu diperlukan regulasi terkait sistem pelayanan kesehatan mental melalui Telehealth yang terintegrasi dengan sistem pemerintah pusat.