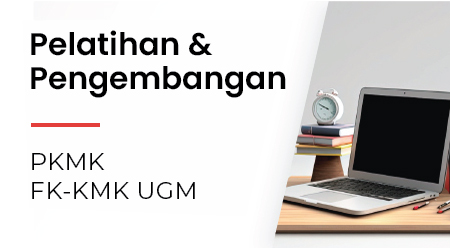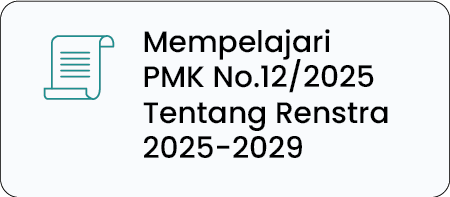Kebijakan pendanaan Kesehatan menjadi salah satu topik pembahasan dalam sesi paralel Forum Nasional (Fornas) XV Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (JKKI) yang diselenggarakan di Yogyakarta pada Selasa (28/10/2025). Dalam sesi ini membahas mengenai aspek pendanaan dalam transformasi sistem kesehatan, khususnya penguatan sistem JKN di Indonesia.
Tren Pembiayaan JKN Pasca Pandemi COVID-19
 Muhamad Faozi Kurniawan, SE, Ak., MPH memaparkan Tren Pembiayaan Kesehatan dan JKN Pasca Pandemi COVID-19. Faozi menyampaikan adanya tren peningkatan belanja kesehatan di Indonesia, dengan sumber pendanaan pemerintah lebih dari 50% yang masih lebih rendah jika dibandingkan dengan beberapa negara lain. Dari segi APBN, anggaran kesehatan mengalami peningkatan setiap tahun namun proporsinya tetap dan target prioritas tidak banyak berubah yaitu untuk KIA, stunting, dan cek kesehatan gratis. Di sisi lain, anggaran Kementerian Kesehatan dari Pemerintah Pusat paling banyak digunakan untuk JKN. Di tingkat daerah, pemerintah daerah masih mengandalkan dana-dana dari pusat untuk pembangunan kesehatan. Pasca COVID-19, terdapat peningkatan belanja kesehatan di tingkat daerah yang menggambarkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk sektor kesehatan. Klaim rasio peserta JKN pasca COVID-19 juga mengami tren peningkatan. Dengan kondisi JKN yang terus mengalami pertumbuhan perlu untuk dipikirkan alternatif pendanaan JKN dari sektor asuransi swasta dan masyarakat, sehingga dana APBN tidak hanya untuk iuran PBI dan JKN.
Muhamad Faozi Kurniawan, SE, Ak., MPH memaparkan Tren Pembiayaan Kesehatan dan JKN Pasca Pandemi COVID-19. Faozi menyampaikan adanya tren peningkatan belanja kesehatan di Indonesia, dengan sumber pendanaan pemerintah lebih dari 50% yang masih lebih rendah jika dibandingkan dengan beberapa negara lain. Dari segi APBN, anggaran kesehatan mengalami peningkatan setiap tahun namun proporsinya tetap dan target prioritas tidak banyak berubah yaitu untuk KIA, stunting, dan cek kesehatan gratis. Di sisi lain, anggaran Kementerian Kesehatan dari Pemerintah Pusat paling banyak digunakan untuk JKN. Di tingkat daerah, pemerintah daerah masih mengandalkan dana-dana dari pusat untuk pembangunan kesehatan. Pasca COVID-19, terdapat peningkatan belanja kesehatan di tingkat daerah yang menggambarkan adanya komitmen pemerintah daerah untuk sektor kesehatan. Klaim rasio peserta JKN pasca COVID-19 juga mengami tren peningkatan. Dengan kondisi JKN yang terus mengalami pertumbuhan perlu untuk dipikirkan alternatif pendanaan JKN dari sektor asuransi swasta dan masyarakat, sehingga dana APBN tidak hanya untuk iuran PBI dan JKN.
Transformasi Pembiayaan Kesehatan Nasional dalam Implementasi UU Kesehatan 2023
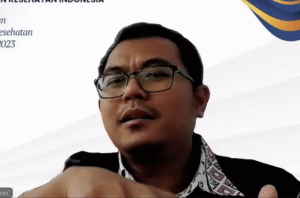 Selanjutnya, Febriansyah Budi Pratama dari Pusat Pembiayaan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI sebagai pembahas menyampaikan implementasi kebijakan pendanaan dalam konteks transformasi sektor kesehatan dan upaya mencapai Universal Health Coverage (UHC) yang dimaknai sebagai kemampuan seluruh masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan. Kemenkes merencanakan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) untuk mensinkronkan dan efisiensi belanja lintas kementerian dan daerah. RIBK ini harapannya berdampak besar pada masyarakat termasuk bagaimana swasta akan berkontribusi. Di sisi lain, terdapat skema belanja pemerintah dan JKN. Tercatat, hampir 60% ke atas pembiayaan peserta dari PBPU dan PBI yang diberikan pemerintah dan pemda. Selain itu, dampak ketidakpatuhan membayar iuran JKN mempengaruhi aset JKN. Maka, diperlukan langkah-langkah kebijakan untuk memperbaiki mutu dan pemerataan akses pelayanan kesehatan, serta peningkatan reveneu dari iuran program JKN. Harapannya dapat mendorong penurunan Out Of Pocket (OOP) dan peningkatan perlindungan finansial masyarakat menuju sistem pembiayaan yang tangguh dan adaptif.
Selanjutnya, Febriansyah Budi Pratama dari Pusat Pembiayaan Kesehatan Kementerian Kesehatan RI sebagai pembahas menyampaikan implementasi kebijakan pendanaan dalam konteks transformasi sektor kesehatan dan upaya mencapai Universal Health Coverage (UHC) yang dimaknai sebagai kemampuan seluruh masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan. Kemenkes merencanakan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) untuk mensinkronkan dan efisiensi belanja lintas kementerian dan daerah. RIBK ini harapannya berdampak besar pada masyarakat termasuk bagaimana swasta akan berkontribusi. Di sisi lain, terdapat skema belanja pemerintah dan JKN. Tercatat, hampir 60% ke atas pembiayaan peserta dari PBPU dan PBI yang diberikan pemerintah dan pemda. Selain itu, dampak ketidakpatuhan membayar iuran JKN mempengaruhi aset JKN. Maka, diperlukan langkah-langkah kebijakan untuk memperbaiki mutu dan pemerataan akses pelayanan kesehatan, serta peningkatan reveneu dari iuran program JKN. Harapannya dapat mendorong penurunan Out Of Pocket (OOP) dan peningkatan perlindungan finansial masyarakat menuju sistem pembiayaan yang tangguh dan adaptif.
materiKajian Dampak Kenaikan Iuran JKN terhadap Peserta dan Sistem Layanan
 Dr. Diah Ayu Puspandari, Apt, M.Kes., MBA., AAK selaku Direktur Pusat Pembiayaan Kesehatan dan Manajemen Asuransi Kesehatan (KPMAK) FK-KMK UGM menyampaikan adanya tantangan serius dalam keberlanjutan pembiayaan JKN yang dipicu oleh kenaikan utilisasi serta inflasi baiya medis yang tinggi. Salah satu isu yang muncul yakni kenaikan premi untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan finansial (sustainability) dan keadilan sosial (equity). Namun, kenaikan iuran dinilai memiliki dampak paling berat pada peserta mandiri (PBPU) yang berpenghasilan tidak rutin, sehingga berisiko memicu tunggakan, dan membuat masyarakat miskin tiga kali lebih mungkin menunda akses layanan Kesehatan. Sedangkan dampak terhadap pelayanan kesehatan terkait dengan likuiditas, kapasitas mutu, serta makro-fiskal dan tata kelola. Dr. Diah menekankan bahwa kenaikan premi perlu diimbangi dengan mekanisme yang fleksibel tanpa menurunkan kepesertaan aktif serta perlu bagi provider untuk meningkatan mutu, sehingga kenaikan premi iuran bukan hanya sekadar untuk menutup defisit klaim. Selain itu, peran aktif dari pemerintah sangat diperlukan untuk mengkomunikasikan manfaat nyata dari kenaikan iuran serta diperlukan earmarking tambahan untuk dana kesehatan untuk mendukung subsidi yang berkelanjutan.
Dr. Diah Ayu Puspandari, Apt, M.Kes., MBA., AAK selaku Direktur Pusat Pembiayaan Kesehatan dan Manajemen Asuransi Kesehatan (KPMAK) FK-KMK UGM menyampaikan adanya tantangan serius dalam keberlanjutan pembiayaan JKN yang dipicu oleh kenaikan utilisasi serta inflasi baiya medis yang tinggi. Salah satu isu yang muncul yakni kenaikan premi untuk menjaga keseimbangan antara keberlanjutan finansial (sustainability) dan keadilan sosial (equity). Namun, kenaikan iuran dinilai memiliki dampak paling berat pada peserta mandiri (PBPU) yang berpenghasilan tidak rutin, sehingga berisiko memicu tunggakan, dan membuat masyarakat miskin tiga kali lebih mungkin menunda akses layanan Kesehatan. Sedangkan dampak terhadap pelayanan kesehatan terkait dengan likuiditas, kapasitas mutu, serta makro-fiskal dan tata kelola. Dr. Diah menekankan bahwa kenaikan premi perlu diimbangi dengan mekanisme yang fleksibel tanpa menurunkan kepesertaan aktif serta perlu bagi provider untuk meningkatan mutu, sehingga kenaikan premi iuran bukan hanya sekadar untuk menutup defisit klaim. Selain itu, peran aktif dari pemerintah sangat diperlukan untuk mengkomunikasikan manfaat nyata dari kenaikan iuran serta diperlukan earmarking tambahan untuk dana kesehatan untuk mendukung subsidi yang berkelanjutan.
Sesi Diskusi
Selanjutnya, muncul pertanyaan mengenai strategi dalam membagun ekosistem pendanaan kesehatan yang berkelanjutan, termasuk optimalisasi dan inovasi sumber pendanaan. Dari kemenkes berfokus pada perbaikan kepatihan JKN dan inovasi pembiayaan yang sudah berjalan, termasuk RIBK sebagai blueprint untuk sinkronisasi pendanaan kesehatan antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, sehingga belanja menjadi efektif, efisien, dan terarah. Earmarking cukai rokok sudah dilakukan sejak 2018 dengan mengalokasikan sebagain pendapatan pajak rokok untuk membayar iuran peserta PBI. Kemenkes akan mendorong perbaikan ketepatsasaran data penerima PBI/PBPU Pemda dan menegakkan kepatuhan bagi peserta yang mampu. Sedangkan Dr. Diah menegaskan pentingnya political willingness bagi Pemerintah untuk mengalokasikan dana kesehatan, karena anggaran pada bidang kesehatan bukan merupakan cost melainkan merupakan investasi.
Peserta juga menyoroti bahwa sumber pembiayaan kesehatan di Indonesia masih terfokus pada APBN, bagaimana potensi health tourism (wisata kesehatan) dapat diintegrasikan dengan sistem pembiayaan nasional? Menanggapi hal tersebut, Faozi menjelaskan bahwa pengembangan health tourism merupakan gagasan yang baik dan relevan untuk daerah seperti Yogyakarta. Menurutnya, pemerintah daerah dapat mengalokasikan sebagian dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk sektor kesehatan, terutama yang berkaitan dengan pengembangan health tourism. Selain itu diperlukan kebijakan yang mampu memayungi inisiatif health tourism hingga ke tingkat paling bawah. Salah satu bentuknya dapat berupa mekanisme penghimpunan dana dari berbagai sumber Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung program-program kesehatan yang belum dapat didanai oleh pemerintah. Ia juga menekankan pentingnya pemetaan kebutuhan di masyarakat agar arah kebijakan lebih tepat sasaran. Sementara itu, Diah menambahkan bahwa Yogyakarta memiliki potensi besar untuk mengembangkan wisata yang sehat dan inklusif. Ia mencontohkan ketersediaan fasilitas publik yang mendukung sanitasi layak, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, serta upaya untuk meminimalkan risiko kecelakaan di kawasan wisata. Selain itu, pengembangan wellness tourism juga diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Sesi ini menegaskan pentingnya transformasi pendanaan kesehatan yang tidak hanya bergantung pada APBN, tetapi juga mendorong inovasi pembiayaan melalui sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Integrasi kebijakan melalui Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK), optimalisasi JKN, serta pengembangan inisiatif seperti health tourism menjadi langkah strategis menuju sistem pembiayaan kesehatan yang berkeadilan, berkelanjutan, dan adaptif. Diharapkan, penguatan komitmen politik (political willingness) pemerintah dalam investasi kesehatan dapat mempercepat tercapainya Universal Health Coverage dan meningkatkan ketahanan sistem kesehatan nasional.
Reporter: Ardhina N (PKMK UGM)
Editor: Latifah Alifiana (PKMK UGM)
Reportase Terkait:
- Topik 1 Kebijakan membangun sistem kesehatan
- Sesi Pleno I Omnibus Law Kesehatan: Antara Simplifikasi Regulasi dan Potensi Masalah Hukum
- Paralel sesi 1 Kebijakan Pelayanan Primer
- Paralel sesi 2 Kebijakan Pendanaan
- Paralel sesi 3 Kebijakan Obat
- Paralel sesi 4 Kebijakan Pelayanan Rujukan
- Paralel sesi 5 Kebijakan Pelayanan Uji Kebijakan Rencana Kesiapsiagaan Krisis Kesehatan
- Paralel sesi 6 Filantropi Kesehatan
- Paralel sesi 5 Kebijakan RIBK
- Sesi Pleno II Mengamankan Investasi Kesehatan: Strategi Pemeliharaan Alkes KJSU di Daerah dengan Akses Terbatas
- Topik 2 Kebijakan Pendidikan Dokter Spesialis dalam UU Kesehatan 2023
- Topik 3 Kebijakan climate resilient dan low carbon health