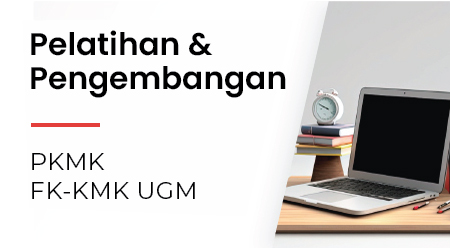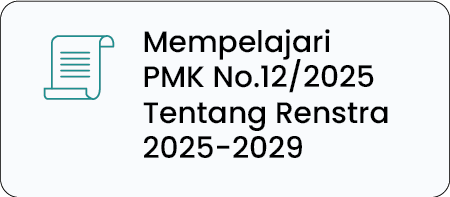Obat esensial merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang efektif dan berkeadilan. Tanpa ketersediaan obat yang memadai, sulit bagi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama untuk memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat. Indonesia, dengan karakteristik geografisnya sebagai negara kepulauan yang luas dan beragam, menghadapi tantangan kompleks dalam hal pengadaan, distribusi, dan pemantauan obat, terutama di wilayah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, transformasi sektor kesehatan menekankan pentingnya kemandirian farmasi nasional serta jaminan ketersediaan obat esensial di seluruh lapisan masyarakat. Sesi ini akan membahas berbagai strategi kebijakan untuk memastikan ketersediaan obat esensial secara berkelanjutan, termasuk sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan tenaga kefarmasian. Penguatan sistem informasi farmasi, digitalisasi rantai pasok, serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di daerah juga menjadi sorotan penting. Melalui kolaborasi lintas sektor, diharapkan Indonesia dapat mewujudkan sistem farmasi nasional yang mandiri dan berorientasi pada pemerataan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Sesi dipandu oleh Monita Destiwi, MA (Researcher Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM) sebagai moderator. Pembicara adalah Reimbuss Blijers Fanda, MPH, Ph.D (Cand) (Konsultan dan Researcher Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM), serta Dr. Dra. Agusdini Banun Saptaningsih, apt., MARS (Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Farmasi Kementerian Kesehatan RI) dan Dr. apt. Niken Nur Widyakusuma, M.Sc. (Dosen, Konsultan, dan Reasearcher Fakultas Farmasi UGM) sebagai pembahas.
Obat esensial merupakan salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang efektif dan berkeadilan. Tanpa ketersediaan obat yang memadai, sulit bagi fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama untuk memberikan layanan yang optimal kepada masyarakat. Indonesia, dengan karakteristik geografisnya sebagai negara kepulauan yang luas dan beragam, menghadapi tantangan kompleks dalam hal pengadaan, distribusi, dan pemantauan obat, terutama di wilayah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Sejalan dengan amanat Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, transformasi sektor kesehatan menekankan pentingnya kemandirian farmasi nasional serta jaminan ketersediaan obat esensial di seluruh lapisan masyarakat. Sesi ini akan membahas berbagai strategi kebijakan untuk memastikan ketersediaan obat esensial secara berkelanjutan, termasuk sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan tenaga kefarmasian. Penguatan sistem informasi farmasi, digitalisasi rantai pasok, serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan di daerah juga menjadi sorotan penting. Melalui kolaborasi lintas sektor, diharapkan Indonesia dapat mewujudkan sistem farmasi nasional yang mandiri dan berorientasi pada pemerataan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Sesi dipandu oleh Monita Destiwi, MA (Researcher Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM) sebagai moderator. Pembicara adalah Reimbuss Blijers Fanda, MPH, Ph.D (Cand) (Konsultan dan Researcher Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK-KMK UGM), serta Dr. Dra. Agusdini Banun Saptaningsih, apt., MARS (Direktur Pengelolaan dan Pelayanan Farmasi Kementerian Kesehatan RI) dan Dr. apt. Niken Nur Widyakusuma, M.Sc. (Dosen, Konsultan, dan Reasearcher Fakultas Farmasi UGM) sebagai pembahas.
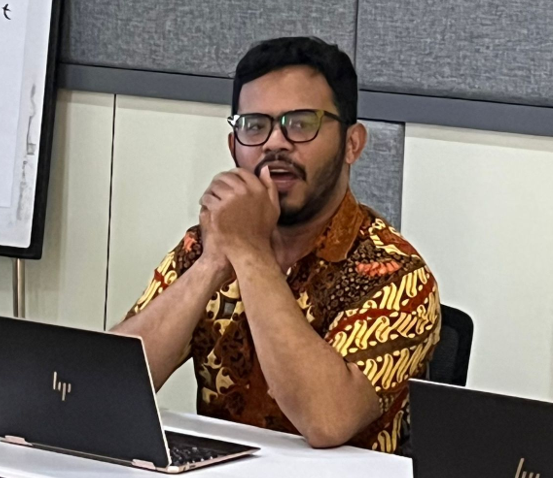 Pemaparan materi pertama berjudul “Pemenuhan Obat Esensial di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dalam Konteks Negara Kepulauan” oleh Reimbuss. Beliau membahas tantangan ketersediaan obat esensial di Indonesia. Secara global, lebih dari 2 miliar orang kesulitan mengakses obat esensial, dengan ketersediaan di sektor publik hanya sekitar 40 persen. Dampaknya mencakup biaya kesehatan katastrofik, mutu layanan rendah, serta paparan obat dengan kualitas yang kurang baik. Analisis nasional menggunakan data Podes, Sismonev JKN, dan Rifaskes 2019 menunjukkan bahwa 17 obat indikator hampir selalu tersedia (93 persen), namun dari 60 obat esensial, hanya sebagian tersedia di puskesmas. Variasi ketersediaan dipengaruhi oleh wilayah, jenis layanan, serta faktor sistemik seperti pengadaan, distribusi, dan kapasitas farmasi daerah. Daerah timur Indonesia paling terdampak karena akses terbatas dan ketergantungan tinggi pada puskesmas. Penelitian yang dilakukan oleh Reimbuss dan tim menemukan bahwa desentralisasi menciptakan kesenjangan antara kebijakan nasional dan praktik lokal. Faktor penyebab utama kekosongan obat mencakup lemahnya koordinasi, kurangnya tenaga farmasi, dan aturan pengadaan yang membingungkan. Rekomendasi kebijakan meliputi transformasi dinas kesehatan daerah, penyesuaian daftar obat esensial berbasis provinsi, peningkatan kompetensi apoteker, sistem pool procurement untuk wilayah timur, dan penguatan manajemen pengetahuan farmasi publik.
Pemaparan materi pertama berjudul “Pemenuhan Obat Esensial di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dalam Konteks Negara Kepulauan” oleh Reimbuss. Beliau membahas tantangan ketersediaan obat esensial di Indonesia. Secara global, lebih dari 2 miliar orang kesulitan mengakses obat esensial, dengan ketersediaan di sektor publik hanya sekitar 40 persen. Dampaknya mencakup biaya kesehatan katastrofik, mutu layanan rendah, serta paparan obat dengan kualitas yang kurang baik. Analisis nasional menggunakan data Podes, Sismonev JKN, dan Rifaskes 2019 menunjukkan bahwa 17 obat indikator hampir selalu tersedia (93 persen), namun dari 60 obat esensial, hanya sebagian tersedia di puskesmas. Variasi ketersediaan dipengaruhi oleh wilayah, jenis layanan, serta faktor sistemik seperti pengadaan, distribusi, dan kapasitas farmasi daerah. Daerah timur Indonesia paling terdampak karena akses terbatas dan ketergantungan tinggi pada puskesmas. Penelitian yang dilakukan oleh Reimbuss dan tim menemukan bahwa desentralisasi menciptakan kesenjangan antara kebijakan nasional dan praktik lokal. Faktor penyebab utama kekosongan obat mencakup lemahnya koordinasi, kurangnya tenaga farmasi, dan aturan pengadaan yang membingungkan. Rekomendasi kebijakan meliputi transformasi dinas kesehatan daerah, penyesuaian daftar obat esensial berbasis provinsi, peningkatan kompetensi apoteker, sistem pool procurement untuk wilayah timur, dan penguatan manajemen pengetahuan farmasi publik.
 Presentasi selanjutnya oleh Agusdini mengenai “Strategi Pemenuhan Ketersediaan Obat Esensial di Pemerintah Pusat” menyoroti langkah strategis pemerintah dalam menjamin ketersediaan obat esensial secara nasional. Berlandaskan RPJMN 2025-2029 dan UU No. 17 Tahun 2023, strategi ini sejalan dengan transformasi sistem kesehatan melalui enam pilar utama, terutama ketahanan farmasi dan alat kesehatan. Kebijakan ini menekankan pentingnya perlindungan masyarakat melalui praktik kefarmasian yang aman, serta penguatan tata kelola rantai pasok dari hulu ke hilir dengan prioritas pada produk dalam negeri. Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab atas ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan dengan sistem informasi logistik terintegrasi berbasis SATUSEHAT Logistik (Digital Inventory Nasional). Perencanaan kebutuhan obat dilakukan menggunakan pendekatan demand dan supply, memanfaatkan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) untuk menjaga keseimbangan permintaan dan penyediaan. Sistem E-Fornas dan e-Monev SatuSehat digunakan sebagai acuan pemilihan dan pemantauan stok obat. Selain itu, indikator ketersediaan obat dalam Renstra Kemenkes 2025–2029 menargetkan 95 persen fasilitas kesehatan memiliki obat esensial sesuai standar, didukung oleh peningkatan mutu pelayanan kefarmasian dan penerapan prinsip penggunaan obat rasional.
Presentasi selanjutnya oleh Agusdini mengenai “Strategi Pemenuhan Ketersediaan Obat Esensial di Pemerintah Pusat” menyoroti langkah strategis pemerintah dalam menjamin ketersediaan obat esensial secara nasional. Berlandaskan RPJMN 2025-2029 dan UU No. 17 Tahun 2023, strategi ini sejalan dengan transformasi sistem kesehatan melalui enam pilar utama, terutama ketahanan farmasi dan alat kesehatan. Kebijakan ini menekankan pentingnya perlindungan masyarakat melalui praktik kefarmasian yang aman, serta penguatan tata kelola rantai pasok dari hulu ke hilir dengan prioritas pada produk dalam negeri. Pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab atas ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan dengan sistem informasi logistik terintegrasi berbasis SATUSEHAT Logistik (Digital Inventory Nasional). Perencanaan kebutuhan obat dilakukan menggunakan pendekatan demand dan supply, memanfaatkan Rencana Kebutuhan Obat (RKO) untuk menjaga keseimbangan permintaan dan penyediaan. Sistem E-Fornas dan e-Monev SatuSehat digunakan sebagai acuan pemilihan dan pemantauan stok obat. Selain itu, indikator ketersediaan obat dalam Renstra Kemenkes 2025–2029 menargetkan 95 persen fasilitas kesehatan memiliki obat esensial sesuai standar, didukung oleh peningkatan mutu pelayanan kefarmasian dan penerapan prinsip penggunaan obat rasional.
 Pemaparan ketiga oleh Niken membahas “Manajemen Distribusi Obat Esensial: Perspektif Keilmuan”. Obat esensial didefinisikan sebagai obat yang paling dibutuhkan masyarakat, serta harus tersedia setiap saat dalam bentuk dan dosis yang tepat. Pemilihannya didasarkan pada prevalensi penyakit, efektivitas, keamanan, dan efisiensi biaya. Hal ini dilakukan untuk menjamin pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas. Ketersediaan obat esensial masih terhambat oleh rantai pasok yang tidak efisien, ketergantungan impor, lemahnya regulasi, serta ketimpangan akses antara wilayah urban dan rural. Siklus manajemen obat mencakup perencanaan, pengadaan, distribusi, dan penggunaan. Proses ini menjadi dasar pemenuhan obat yang efektif dengan dukungan kebijakan, SDM farmasi, pendanaan, dan sistem informasi logistik yang kuat. Niken juga mengatakan bahwa UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 memberikan landasan hukum baru untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan obat esensial, mengatur desentralisasi tata kelola farmasi, serta memperkuat kemandirian industri nasional. Namun, implementasinya menghadapi tantangan berupa transisi regulasi, kapasitas SDM, dan kesiapan digitalisasi sistem logistik obat.
Pemaparan ketiga oleh Niken membahas “Manajemen Distribusi Obat Esensial: Perspektif Keilmuan”. Obat esensial didefinisikan sebagai obat yang paling dibutuhkan masyarakat, serta harus tersedia setiap saat dalam bentuk dan dosis yang tepat. Pemilihannya didasarkan pada prevalensi penyakit, efektivitas, keamanan, dan efisiensi biaya. Hal ini dilakukan untuk menjamin pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas. Ketersediaan obat esensial masih terhambat oleh rantai pasok yang tidak efisien, ketergantungan impor, lemahnya regulasi, serta ketimpangan akses antara wilayah urban dan rural. Siklus manajemen obat mencakup perencanaan, pengadaan, distribusi, dan penggunaan. Proses ini menjadi dasar pemenuhan obat yang efektif dengan dukungan kebijakan, SDM farmasi, pendanaan, dan sistem informasi logistik yang kuat. Niken juga mengatakan bahwa UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023 memberikan landasan hukum baru untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan obat esensial, mengatur desentralisasi tata kelola farmasi, serta memperkuat kemandirian industri nasional. Namun, implementasinya menghadapi tantangan berupa transisi regulasi, kapasitas SDM, dan kesiapan digitalisasi sistem logistik obat.

Sesi diskusi dibuka dengan pengalaman kasus dan pertanyaan oleh peserta yang hadir secara luring maupun daring. Isu utama yang diangkat adalah ketimpangan ketersediaan obat antara wilayah Jawa dan luar Jawa akibat sentralisasi industri farmasi. Peserta menyoroti perlunya pemerataan distribusi, regulasi yang mendukung kolaborasi antar-kementerian, serta percepatan digitalisasi sistem kefarmasian. Selain itu, masalah SDM kefarmasian menjadi perhatian besar. Di beberapa daerah, banyak petugas non-apoteker yang menangani penyusunan RKO yang menyebabkan ketidaksesuaian antara pengadaan dan kebutuhan riil. Fenomena ini berujung pada penumpukan atau kedaluwarsa obat, khususnya obat kesehatan jiwa. Dalam tanggapan, Agusdini menjelaskan bahwa sesuai dengan undang-undang, pengadaan obat kini menjadi tanggung jawab bersama pusat dan daerah, dengan dana DAK yang harus dikelola sesuai kebutuhan lokal. Beliau juga menegaskan bahwa obat esensial ditetapkan berdasarkan Survey Kesehatan Indonesia (SKI) dan konteks daerah. Kemenkes tidak dapat mengintervensi industri, melainkan mengatur keberadaan PBF cabang dan skema harga regional. Penyediaan buffer nasional juga merupakan langkah penting dalam mengatasi kekosongan stok obat di daerah. Dalam kesempatan ini, Agusdini juga menginfokan adanya kemungkinan pengambilalihan pengadaan obat kesehatan jiwa oleh pusat untuk memastikan kesesuaian kebutuhan. Prof. Dr. Chairun Wiedyaningsih, M.Kes, M.App.Sc, Apt. (Guru Besar Fakultas Farmasi UGM) juga turut hadir dalam diskusi dan memaparkan adanya fenomena ketidaksesuaian linimasa penyusunan RKO di daerah dengan jadwal pengumpulan oleh Kemenkes, sehingga memperburuk masalah perencanaan pengadaan obat. Dalam hal ini, Niken menyoroti pentingnya validasi data dan sinkronisasi waktu penyusunan RKO agar kebutuhan daerah tergambar dengan akurat. Reimbuss menekankan bahwa pemerintah diharapkan memperkuat koordinasi antarlevel (puskesmas–kabupaten–provinsi–nasional) dan mendorong kemandirian daerah melalui pemahaman bahwa pengelolaan obat adalah tanggung jawab bersama. Diskusi ditutup dengan penegasan bahwa digitalisasi terintegrasi (SATUSEHAT, SMILE) dan penguatan sistem kesehatan daerah yang adaptif merupakan kunci dalam mewujudkan transformasi ketahanan farmasi nasional.
Sebagai penutup, sesi ini mengglorifikasi pentingnya komitmen bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, dan tenaga kefarmasian dalam menjamin ketersediaan obat esensial yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Tantangan besar seperti kesenjangan distribusi dan keterbatasan SDM harus diatasi melalui penguatan tata kelola, peningkatan kompetensi, serta pemanfaatan sistem informasi yang terpadu. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mewujudkan sistem farmasi nasional yang mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Melalui langkah strategis dan komitmen berkelanjutan, Indonesia diharapkan mampu mencapai ketahanan kefarmasian yang adil dan berkeadilan bagi seluruh rakyat.
Reporter:
dr. Garin Frige Janitra (PKMK UGM)
Reportase Terkait:
- Topik 1 Kebijakan membangun sistem kesehatan
- Sesi Pleno I Omnibus Law Kesehatan: Antara Simplifikasi Regulasi dan Potensi Masalah Hukum
- Paralel sesi 1 Kebijakan Pelayanan Primer
- Paralel sesi 2 Kebijakan Pendanaan
- Paralel sesi 3 Kebijakan Obat
- Paralel sesi 4 Kebijakan Pelayanan Rujukan
- Paralel sesi 5 Kebijakan Pelayanan Uji Kebijakan Rencana Kesiapsiagaan Krisis Kesehatan
- Paralel sesi 6 Filantropi Kesehatan
- Paralel sesi 5 Kebijakan RIBK
- Sesi Pleno II Mengamankan Investasi Kesehatan: Strategi Pemeliharaan Alkes KJSU di Daerah dengan Akses Terbatas
- Topik 2 Kebijakan Pendidikan Dokter Spesialis dalam UU Kesehatan 2023
- Topik 3 Kebijakan climate resilient dan low carbon health