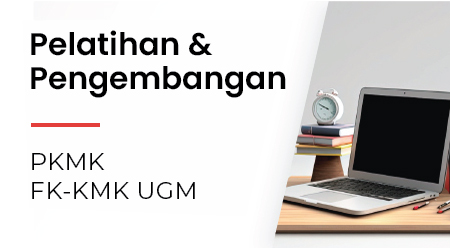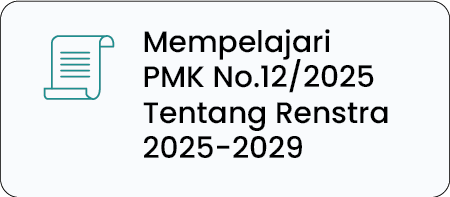Dalam momentum Hari Sumpah Pemuda, sesi ini mengajak peserta untuk merenungkan kembali makna “satu nusa, satu bangsa, satu negara” dalam konteks pembangunan kesehatan. Bukan sekadar slogan, tetapi komitmen untuk memastikan setiap warga negara memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang aman dan bermutu. Alat kesehatan atau yang kerap disingkat Alkes, menjadi simbol dari semangat itu. Alkes bukan sekadar instrumen teknis, melainkan jantung dari sistem layanan rujukan yang menentukan keselamatan pasien dan keberlangsungan pelayanan di seluruh pelosok negeri.
Sesi ini menyoroti bagaimana pemeliharaan, kalibrasi, dan kebijakan pengelolaan alat kesehatan menjadi bagian penting dari transformasi sistem kesehatan nasional. Dari ruang kalibrasi hingga ruang rapat kebijakan, dari kepemimpinan teknis hingga strategi digitalisasi, semua saling terhubung dan menentukan masa depan layanan kesehatan Indonesia. Melalui berbagai perspektif, baik dari pemerintah, rumah sakit, industri, dan akademisi, diskusi ini menggambarkan satu pesan utama, yaitu investasi kesehatan tidak hanya berbicara soal anggaran, tetapi juga tentang menjaga keberfungsian alat kesehatan.
Panel 1 – Alat Kesehatan sebagai Elemen Penting dalam Pilar Transformasi Pelayanan Kesehatan Rujukan
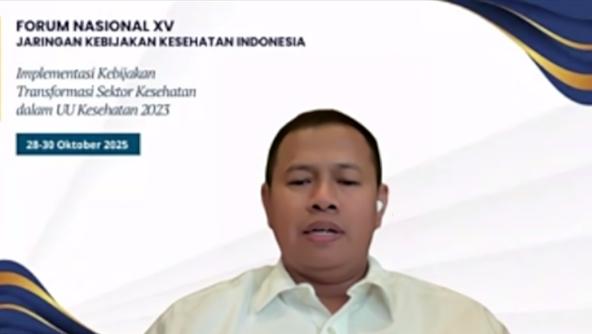 Subadri, ST, M.Si selaku Kepala Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Jakarta mengatakan bahwa alat kesehatan bukan hanya urusan teknologi, melainkan urusan akurasi yang menyelamatkan nyawa. Namun, akurasi tanpa kepemimpinan yang kuat tak akan bermakna. Dalam konteks transformasi sistem kesehatan, kepemimpinan menjadi kunci agar setiap kebijakan benar-benar terlaksana di lapangan.
Subadri, ST, M.Si selaku Kepala Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Jakarta mengatakan bahwa alat kesehatan bukan hanya urusan teknologi, melainkan urusan akurasi yang menyelamatkan nyawa. Namun, akurasi tanpa kepemimpinan yang kuat tak akan bermakna. Dalam konteks transformasi sistem kesehatan, kepemimpinan menjadi kunci agar setiap kebijakan benar-benar terlaksana di lapangan.
Subadri menjelaskan bahwa tantangan terbesar bukan hanya pada ketersediaan alat, tetapi pada bagaimana alat tersebut dipelihara dan dimanfaatkan secara optimal. Banyak daerah masih menghadapi keterbatasan dalam pemeliharaan rutin, padahal inilah aspek yang menjamin umur pakai alat tetap sesuai standar. Kemenkes, melalui jaringan Unit Pelaksana Teknis (UPT), terus berupaya memperluas akses kalibrasi dan pemeliharaan hingga ke wilayah-wilayah terpencil.
Subadri menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, baik dengan pemerintah daerah maupun pihak swasta. Melalui Permenkes 54, rumah sakit daerah kini dapat berfungsi sebagai unit pemeliharaan. Dengan dukungan kebijakan dan kolaborasi yang tepat, daerah-daerah dengan akses terbatas pun dapat memastikan alat kesehatan berfungsi aman dan efektif.
Panel 2 – Leadership Execution: Kebijakan KJSU dan KRIS sebagai Enabling Factors
 Dr. dr. Andreasta Meliala, MKes, DPH, MAS selaku Ketua PKMK FK-KMK UGM menyoroti bahwa transformasi alat kesehatan hanya bisa berjalan jika ada sinergi antara sistem pembiayaan dan kepemimpinan yang visioner.
Dr. dr. Andreasta Meliala, MKes, DPH, MAS selaku Ketua PKMK FK-KMK UGM menyoroti bahwa transformasi alat kesehatan hanya bisa berjalan jika ada sinergi antara sistem pembiayaan dan kepemimpinan yang visioner.
Menurut Andreasta, Indonesia kini memasuki era machine medicine, di mana kualitas layanan sangat ditentukan oleh sejauh mana SDM mampu mengoptimalkan alat yang tersedia. Tantangan utama bukan lagi ketersediaan alat, melainkan bagaimana alat tersebut dapat dioperasikan dan dirawat di daerah dengan sumber daya terbatas, terutama di wilayah 3T.
Andreasta menegaskan bahwa tanpa kepemimpinan yang memahami siklus hidup alat kesehatan, dari pengadaan hingga pemeliharaan, investasi akan sia-sia. Seorang pemimpin kesehatan harus melihat alat sebagai aset strategis, bukan sekadar pelengkap operasional. Kepemimpinan yang kuat menjadi penentu keberlanjutan layanan, efisiensi anggaran, dan keselamatan pasien.
Panel 3 – Model Pembiayaan Pemeliharaan Alkes pada BLU/BLUD
 Oktelin Kaswadie, MARS, FISQua selaku Direktur RSUPP Betun Malaka NTT membawa perspektif dari wilayah perbatasan yang menghadapi keterbatasan sumber daya. Dengan anggaran terbatas, rumah sakitnya berupaya memaksimalkan setiap bantuan alat kesehatan dari pusat, termasuk CT scan dan mammografi. Namun, Oktelin menyoroti pentingnya sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah. Pengadaan alat tidak akan bermakna tanpa kesiapan infrastruktur dan SDM pendukung, seperti radiografer dan fisikawan medis.
Oktelin Kaswadie, MARS, FISQua selaku Direktur RSUPP Betun Malaka NTT membawa perspektif dari wilayah perbatasan yang menghadapi keterbatasan sumber daya. Dengan anggaran terbatas, rumah sakitnya berupaya memaksimalkan setiap bantuan alat kesehatan dari pusat, termasuk CT scan dan mammografi. Namun, Oktelin menyoroti pentingnya sinkronisasi antara kebijakan pusat dan daerah. Pengadaan alat tidak akan bermakna tanpa kesiapan infrastruktur dan SDM pendukung, seperti radiografer dan fisikawan medis.
Oktelin berbagi pengalaman bahwa pemeliharaan dan kalibrasi masih menjadi tantangan besar di daerah terpencil. Biaya kalibrasi tinggi karena keterbatasan fasilitas lokal, sementara kehadiran BPAFK belum merata. Oktelin mendorong agar laboratorium kesehatan daerah dapat mengambil peran dalam kalibrasi alat sederhana, untuk menekan biaya dan mempercepat layanan.
Menurutnya, dukungan kepemimpinan daerah sangat krusial. Di wilayahnya, komitmen bupati terhadap kesehatan menjadi faktor penentu keberhasilan pengelolaan alat. Dengan sinergi kebijakan, pembiayaan yang fleksibel, dan dukungan kepemimpinan yang konsisten, rumah sakit di daerah tertinggal pun bisa menjaga keberfungsian alat secara berkelanjutan.
Panel 4 – Industri Alkes dan Transfer Teknologi
 Erwin Hermanto selaku Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI) menyoroti kondisi industri alat kesehatan nasional yang masih tertinggal dalam riset dan pengembangan. Menurutnya, sebagian besar produsen masih berada pada tahap perakitan (assembling), belum menyentuh riset mendalam dan inovasi mandiri. Karena itu, transfer teknologi menjadi kunci untuk memperkuat daya saing industri dalam negeri. Berbagai bentuk kerja sama, mulai dari riset bersama, investasi asing langsung, hingga franchising, perlu diarahkan agar sesuai kebutuhan pasar dan tujuan jangka panjang. Erwin menekankan pentingnya konsistensi regulasi TKDN untuk menjamin pasar bagi produk lokal dan memastikan keberlanjutan kolaborasi jangka panjang.
Erwin Hermanto selaku Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Alat Kesehatan Indonesia (ASPAKI) menyoroti kondisi industri alat kesehatan nasional yang masih tertinggal dalam riset dan pengembangan. Menurutnya, sebagian besar produsen masih berada pada tahap perakitan (assembling), belum menyentuh riset mendalam dan inovasi mandiri. Karena itu, transfer teknologi menjadi kunci untuk memperkuat daya saing industri dalam negeri. Berbagai bentuk kerja sama, mulai dari riset bersama, investasi asing langsung, hingga franchising, perlu diarahkan agar sesuai kebutuhan pasar dan tujuan jangka panjang. Erwin menekankan pentingnya konsistensi regulasi TKDN untuk menjamin pasar bagi produk lokal dan memastikan keberlanjutan kolaborasi jangka panjang.
 Dari perspektif perusahaan global, Nugroho Madukusumo selaku Technical Support Manager APAC Philips menegaskan bahwa SDM merupakan pilar utama dalam pemanfaatan alat kesehatan. Menurutnya, kemampuan teknis tenaga Indonesia sudah memadai, hanya perlu diberdayakan melalui kebijakan dan prosedur yang berorientasi pada pencegahan melalui pemeliharaan alat, bukan perbaikan. Nugroho menekankan peran teknologi digital dan IoT yang memungkinkan prediksi kerusakan lebih dini serta pemeliharaan jarak jauh, terutama untuk daerah terpencil. Nugroho mengingatkan bahwa investasi terbaik bukan pada alat berteknologi tinggi, melainkan pada infrastruktur pendukung yang menjamin alat dapat berfungsi optimal di semua wilayah.
Dari perspektif perusahaan global, Nugroho Madukusumo selaku Technical Support Manager APAC Philips menegaskan bahwa SDM merupakan pilar utama dalam pemanfaatan alat kesehatan. Menurutnya, kemampuan teknis tenaga Indonesia sudah memadai, hanya perlu diberdayakan melalui kebijakan dan prosedur yang berorientasi pada pencegahan melalui pemeliharaan alat, bukan perbaikan. Nugroho menekankan peran teknologi digital dan IoT yang memungkinkan prediksi kerusakan lebih dini serta pemeliharaan jarak jauh, terutama untuk daerah terpencil. Nugroho mengingatkan bahwa investasi terbaik bukan pada alat berteknologi tinggi, melainkan pada infrastruktur pendukung yang menjamin alat dapat berfungsi optimal di semua wilayah.
Panel 5 – Digitalisasi dan Internet of Things (IoT) dalam Pemeliharaan Alkes
 Dr. Ir. Hendrana Tjahjadi, ST., MSi selaku Ketua Kolegium Elektromedis, Konsil Kesehatan Indonesia menyoroti bahwa membeli alat kesehatan jauh lebih mudah daripada memeliharanya. Menurutnya, tantangan terbesar bukan pada pengadaan, tetapi pada bagaimana memastikan alat berfungsi optimal sepanjang umur pakainya. Banyak rumah sakit belum menghitung return of investment dari setiap alat, sehingga fase pemeliharaan sering terabaikan dan digantikan dengan perbaikan reaktif.
Dr. Ir. Hendrana Tjahjadi, ST., MSi selaku Ketua Kolegium Elektromedis, Konsil Kesehatan Indonesia menyoroti bahwa membeli alat kesehatan jauh lebih mudah daripada memeliharanya. Menurutnya, tantangan terbesar bukan pada pengadaan, tetapi pada bagaimana memastikan alat berfungsi optimal sepanjang umur pakainya. Banyak rumah sakit belum menghitung return of investment dari setiap alat, sehingga fase pemeliharaan sering terabaikan dan digantikan dengan perbaikan reaktif.
Hendrana menekankan pentingnya mengubah paradigma dari repair menjadi maintenance. Pemeliharaan harus menjadi indikator kinerja utama, bukan sekadar tanggapan terhadap kerusakan. Dengan dukungan digitalisasi dan IoT, kondisi alat dapat dipantau secara real-time, bahkan diprediksi sebelum terjadi kerusakan.
Hendrana mencontohkan penggunaan sensor dan teknologi RFID untuk melacak pergerakan alat serta memastikan kalibrasi tepat waktu. Hendrana menegaskan, pemanfaatan teknologi digital bukan hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga mengurangi kerugian akibat downtime dan memperpanjang usia pakai alat kesehatan.
Panel 6 – Best Practice RSUD dr. Iskak Tulungagung
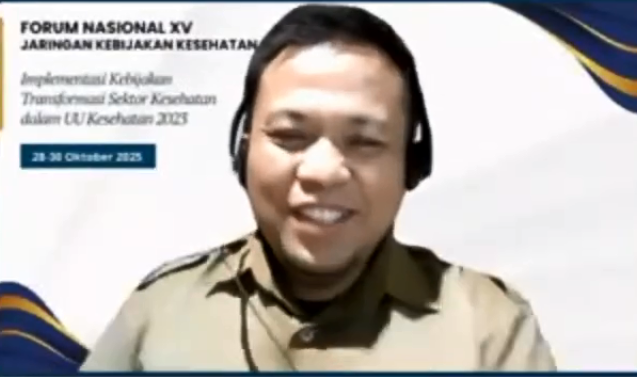 Kabib Abdullah, Amd. TEM. SKM. M.Kes selaku Kepala Sarana Prasarana RSUD dr. Iskak Tulungagung memaparkan pengalaman RSUD dr. Iskak Tulungagung yang berhasil mengembangkan sistem pemeliharaan alat berbasis total productive maintenance. Pendekatan ini berfokus pada peningkatan efisiensi dan penurunan downtime alat melalui pelibatan aktif tim rumah sakit.
Kabib Abdullah, Amd. TEM. SKM. M.Kes selaku Kepala Sarana Prasarana RSUD dr. Iskak Tulungagung memaparkan pengalaman RSUD dr. Iskak Tulungagung yang berhasil mengembangkan sistem pemeliharaan alat berbasis total productive maintenance. Pendekatan ini berfokus pada peningkatan efisiensi dan penurunan downtime alat melalui pelibatan aktif tim rumah sakit.
Kabib menjelaskan bahwa keberhasilan tidak datang dari investasi besar, tetapi dari perubahan mindset. Setiap alat dianggap sebagai aset yang harus dijaga agar tetap bernilai. Tim di RSUD dr. Iskak melatih staf untuk melakukan daily maintenance sederhana, menerapkan prinsip Kaizen, dan membangun budaya autonomous maintenance agar pemeliharaan menjadi bagian dari rutinitas kerja.
Hasilnya, terjadi penurunan kerusakan signifikan dan penghematan biaya hingga ratusan juta rupiah per tahun. Menurut Kabib, kunci keberhasilan terletak pada kepemimpinan yang mendorong inovasi dan memberikan ruang bagi tim untuk belajar serta beradaptasi.
Sesi Diskusi
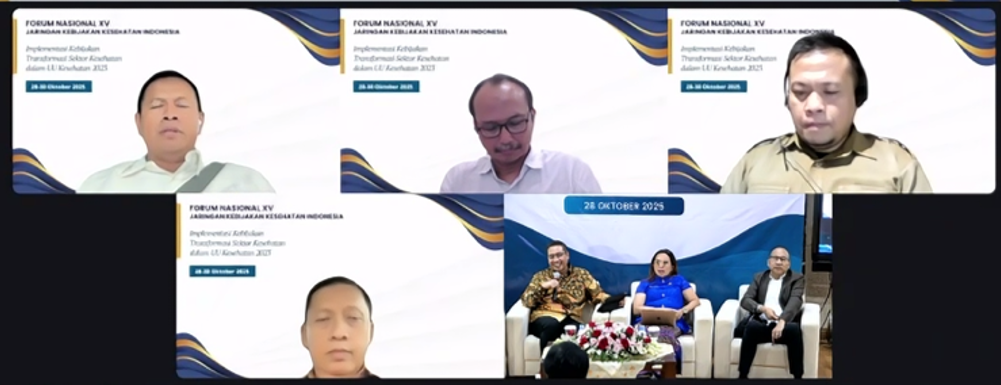
Diskusi dibuka dengan pembahasan mengenai industri alat kesehatan nasional. Moderator menyoroti fakta bahwa nilai agregat industri alat kesehatan di Indonesia telah mencapai lebih dari Rp50 triliun, namun 90% bahan bakunya masih impor, dan sebagian besar produsen masih berada pada tahap semi knock-down. Menjawab hal ini, Erwin dari ASPAKI menjelaskan bahwa asosiasi terus mendorong business matching antara produsen lokal dengan mitra internasional, termasuk lembaga riset luar negeri. Langkah ini dilakukan untuk membuka peluang ekspor dan memperkuat proses manufaktur dalam negeri. Erwin menekankan bahwa keberlanjutan industri membutuhkan konsistensi regulasi TKDN agar produsen lokal tidak berhenti pada tahap perakitan, tetapi mampu melakukan inovasi dan pengembangan teknologi sendiri.
Andreasta menambahkan bahwa percepatan transfer teknologi perlu menjadi prioritas nasional, terutama untuk alat kesehatan berteknologi tinggi. Erwin menegaskan pentingnya peran pemerintah dalam mendefinisikan ulang konsep transfer teknologi yang sesungguhnya, tidak hanya sekadar membuka pabrik asing di Indonesia, tetapi memastikan ada kolaborasi riset dan pengembangan bersama. Menurutnya, investasi yang sinkron dan berpihak akan menjadi fondasi bagi kemandirian industri alat kesehatan Indonesia dalam satu dekade ke depan.
Diskusi menghangat ketika peserta membahas tantangan pemeliharaan alat di rumah sakit dengan sumber daya terbatas. Putu menanyakan kemungkinan pembentukan pusat pemeliharaan regional untuk mengatasi kekurangan SDM elektromedis. Kabib menjawab bahwa pendekatan daily maintenance dapat menjadi solusi awal, karena kedekatan antara pengguna dan alat mampu mencegah sebagian besar masalah.
Moderator menyoroti temuan bahwa hingga 30% alat kesehatan di fasilitas pelayanan masih tidak berfungsi optimal, sementara kalibrasi dan pemeliharaan sering dianggap beban. Subadri menekankan bahwa desentralisasi layanan kalibrasi melalui UPT daerah akan memangkas biaya dan memperluas akses. Hendrana menambahkan bahwa biaya terbesar sering kali berasal dari akomodasi, bukan operasional kalibrasi itu sendiri, karena itu Labkesda perlu diperkuat untuk melayani daerah sekitar. Nugroho menekankan perlunya uji keterimaan rutin agar masa berlaku kalibrasi bisa lebih panjang dan efisien. Oktelin mengangkat isu standar biaya perbaikan yang bervariasi antar rumah sakit. Nugroho menjawab bahwa e-Katalog versi baru akan mengatur penyeragaman harga layanan pemeliharaan. Andreasta menutup sesi diskusi dengan menyoroti pentingnya koordinasi lintas kementerian, karena keberfungsian alat bergantung pada infrastruktur seperti listrik dan utilitas dasar. Menurut Andreasta, leadership adalah fondasi untuk mengubah kesadaran menjadi kebijakan.
Penutup
Dari seluruh diskusi, satu pesan besar mengemuka: investasi kesehatan tidak berhenti pada pengadaan alat, tetapi pada kemampuan mengelolanya. Keberhasilan transformasi kesehatan bergantung pada kepemimpinan visioner, model pembiayaan berkelanjutan, serta dukungan industri dan teknologi yang adaptif. Pemeliharaan yang terencana, kalibrasi yang tepat, dan digitalisasi yang cerdas akan memastikan setiap alat bekerja sebagaimana mestinya, baik di kota besar maupun di daerah terpencil. Bila alat kesehatan dikelola dengan cermat, maka kesehatan masyarakat pun akan lebih terjaga.
Penutupan Hari Pertama FORNAS XV JKKI
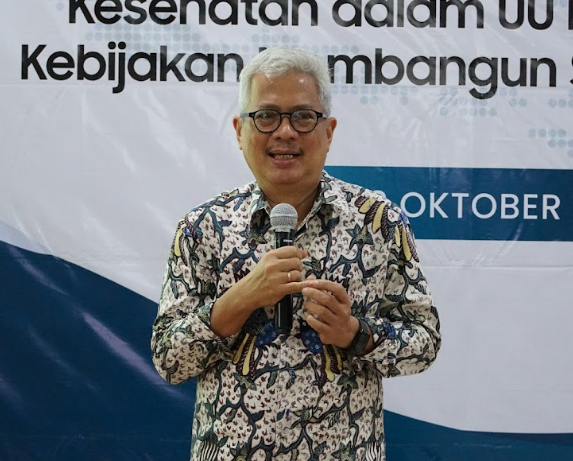 Hari pertama Forum Nasional Kebijakan Kesehatan Indonesia (FORNAS) 2025 ditutup dengan pesan reflektif dari Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, Ph.D., yang menekankan pentingnya memperkuat sistem kesehatan melalui riset kebijakan yang berkelanjutan. Laksono menggambarkan diskusi hari ini sebagai “talkshow yang rumit namun sangat bermakna,” karena memperlihatkan betapa rapuhnya sistem kesehatan ketika satu komponen saja seperti alat kesehatan tidak berfungsi.
Hari pertama Forum Nasional Kebijakan Kesehatan Indonesia (FORNAS) 2025 ditutup dengan pesan reflektif dari Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, Ph.D., yang menekankan pentingnya memperkuat sistem kesehatan melalui riset kebijakan yang berkelanjutan. Laksono menggambarkan diskusi hari ini sebagai “talkshow yang rumit namun sangat bermakna,” karena memperlihatkan betapa rapuhnya sistem kesehatan ketika satu komponen saja seperti alat kesehatan tidak berfungsi.
Laksono menegaskan bahwa setiap sesi paralel hari ini membuka ruang bagi peneliti dan mahasiswa untuk menggali lebih dalam isu-isu strategis, mulai dari prosedur pengadaan alat, tata kelola, hingga pembiayaan dan kesiapan infrastruktur seperti kelistrikan. Banyak topik di antaranya dapat menjadi gudang inspirasi riset kebijakan yang aplikatif dan berdampak langsung.
Laksono berharap, pada triwulan awal tahun 2026 dapat muncul berbagai proposal riset yang menyoroti pelaksanaan kebijakan dan tantangannya di lapangan. Penelitian kebijakan, ujarnya, tidak harus mahal, yang penting relevan dan menjawab persoalan nyata. FORNAS 2026 diharapkan menjadi ajang untuk mendiseminasikan hasil-hasil riset tersebut, sebagai bukti bahwa kolaborasi riset dan kebijakan dapat memperkuat fondasi transformasi sistem kesehatan Indonesia.
Reporter:
Dhea Keyle Fortunandha, MHPM (Divisi Public Health, PKMK UGM)
Reportase Terkait:
- Topik 1 Kebijakan membangun sistem kesehatan
- Sesi Pleno I Omnibus Law Kesehatan: Antara Simplifikasi Regulasi dan Potensi Masalah Hukum
- Paralel sesi 1 Kebijakan Pelayanan Primer
- Paralel sesi 2 Kebijakan Pendanaan
- Paralel sesi 3 Kebijakan Obat
- Paralel sesi 4 Kebijakan Pelayanan Rujukan
- Paralel sesi 5 Kebijakan Pelayanan Uji Kebijakan Rencana Kesiapsiagaan Krisis Kesehatan
- Paralel sesi 6 Filantropi Kesehatan
- Paralel sesi 5 Kebijakan RIBK
- Sesi Pleno II Mengamankan Investasi Kesehatan: Strategi Pemeliharaan Alkes KJSU di Daerah dengan Akses Terbatas
- Topik 2 Kebijakan Pendidikan Dokter Spesialis dalam UU Kesehatan 2023
- Topik 3 Kebijakan climate resilient dan low carbon health