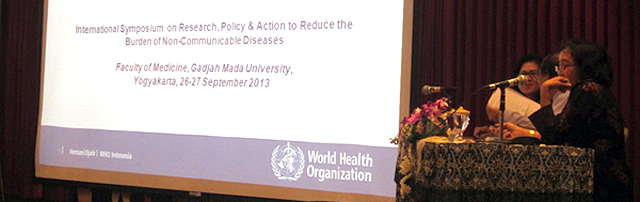Forum Tingkat Tinggi Pembelajaran Antar Negara
untuk Perluasan Cakupan Sektor Informal
Menuju Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Pembukaan Forum Tingkat Tinggi Pembelajaran Antar Negara untuk Perluasan Cakupan Sektor Informal Menuju Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dilakukan pada Senin (30/9/2013) di Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta. Acara dibuka secara seremonial dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya kemudian dilanjutkan tari Gambyong yang dibawakan oleh mahasiswa dari Unit Kesenian Jogja Gaya Surakarta (UGM).
Kemudian, Ketua Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan (P2JK) menyampaikan sambutan, forum ini untuk menemukan rencana aksi dan cakupan pilot project untuk sektor informal. Indonesia. Dalam hal ini, jumlah sektor informal I Indonesia lebih besar, hal serupa terjadi juga di Thailand dan Filipina. Acara ini dihadiri oleh pembuat kebijakan dari Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementrian Kesejahteraan Rakyat, Kementrian Keuangan, Kementrian Kesehatan, Bappenas. DPR, peneliti akademisi dan wakil sektor informal. Panitia juga mengundang narasumber dari negara lain seperti Filipina, India, Thailand, AS, Inggris, dan lain-lain. GIZ, WHO, Bank Dunia, WHO merupakan lembaga donor yang mendukung terselenggaranya acara ini.
Wamenkes Prof. Ali Ghufron menyampaikan dalam definisinya definisi istilah sektor informal yang terkait dengan jaminan kesehatan (tantangan). Apakah pemerintah membayar atau UU yang mengatur siapa yang disubsidi apakah hanya orang miskin? Sehingga, hasil forum untuk diperhatikan pemerintah daerah dan pusat. Saat ini atau 93 hari menuju BPJS (integrated one single scheme), regulasi mana yang telah selesai, yang siap diimplementasikan. Kemungkinan Indonesia akan menjadi single payment terbesar di dunia. Dorongan dari semua pihak akan menjamin berjalannya BPJS, namun pelaksanaanya masih mengalami kesulitan di sektor informal.
Diskusi Panel : Isu-Isu Penting Apa Saja Terkait Apa Saja Sektor Informal Indonesia?

Diskusi panel yang pertama ini disampaikan oleh Dr. Lukita Dinarsyah Tuwo, MA (Wamen Perencanaan Pembangunan Nasional), Prof. Ali Ghufron Mukti (Wamen Kesehatan), Prof. dr. Bambang Purwoko, Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Iskandar Maulana, wakil dari Pembinaan Hubungan Industrial, Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sesi ini dimoderatori oleh Tantri Murdopo, Anchor Metro Tv.
Kasali Situmorang dalam bukunya pernah menyampaikan bahwa perlu dicari jalan terbaik untuk Indonesia (Jaminan Sosial). indonesia-jalan yang terbaik untuk Indonesia. Sejauh ini, definisi sektor informal merujuk pada mereka yang bekerja namun tidak mendapat hubungan kerja yang jelas dan tidak mendapat jaminan. Dr. Nafsiah Mboi, Menkes RI menyampaikan 72% pekerja formal sudah ter-cover jaminan sosial dan 28% merupakan pekerja informal. Dalam hal ini, kemampuan membayar, kemauan atau kesediaan untuk membayar masih menjadi dua hal yang penting untuk didiskusikan.
 Dr. Lukita Dinarsyah Tuwo, MA, Wamen Perencanaan Pembangunan Nasional menyampaikan SJSN tidak bisa secara massal, namun harus bertahap. Dalam hal ini, pelaksanaanya memerlukan sistem SDM yang terencana (transformasi), transfer dari Jamsostek ke BPJS kesehatan, integrasi Jamkesmas ke Jamkesda, perluasan ingin mencakup UHC dari Jaminan Sosial.
Dr. Lukita Dinarsyah Tuwo, MA, Wamen Perencanaan Pembangunan Nasional menyampaikan SJSN tidak bisa secara massal, namun harus bertahap. Dalam hal ini, pelaksanaanya memerlukan sistem SDM yang terencana (transformasi), transfer dari Jamsostek ke BPJS kesehatan, integrasi Jamkesmas ke Jamkesda, perluasan ingin mencakup UHC dari Jaminan Sosial.
Tujuan utamanya: mampu menjamin kesehatan masyarakatnya dan supaya menjadi negara yang maju-cerdas dan sehat. Hingga saat ini masih sekitar 85% pekerja informal masih menerima upah dalam bentuk tunai. Kemudian, masih terjadi gap pelayanan di Puskesmas, kesenjangan jumlah dokter-bidan-nakes di daerah. Tujuan utama yang ingin diraih Jamkesmas yaitu membantu kesehatan yang tidak mampu.
Pilihan strategi pelaksanaan BPJS, diantaranya contributory (namun database harus baik), non contributory (Korsel-Filipina) jika di Indonesia dilakukan makin banyak yang akan masuk ke informality, kombinasi keduanya (Vietnam-Cina) ada beberapa sektor yang didukung pemerintah di Cina untuk sektor pertanian.
Hal lain yang ingin diraih ialah perluasan kepesertaan. Survei Bappenas-48% masyarakat tidak tahu tentang Jaminan Kesehatan dan banyak yang tak tahu fungsi Jamkes. Maka, diperlukan beberapa langkah yang harus diambil, pertama, sosialisasi edukasi salah satunya terkait manfaat yang diperoleh dari Jamkes mutlak diperlukan. Iuran itu untuk membayar dan bermanfaat. Masih ada perbedaan bagaimana membayarnya (tiap bulan atau seperti apa?). selain itu, perlu dilakukan lebih jauh sosialisasi untuk mengurangi beban-hidup sehat bersih yang harus digalakkan stakeholders. Kondisi keuangan negara-pemerintah meng-cover penduduk yang tidak mampu sekitar 86,4 juta atau 36% penduduk terbawah. Jamkesda meng-cover yang tidak masuk di Jamkesmas. Kedua, manfaatkan lembaga sosial masyarakat-dasar hukum dan tata kelola karena jaminan memerlukan kepercayaan. Mungkin masyarakat tidak mau membayar karena kurang percaya, apa yang akan mendapatkan layanan tersebut. Maka, dibutuhkan koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ketiga, uji coba alternatif strategi dan evaluasi. Mana yang cocok dengan situasi Indonesia.
 Prof. Ali Ghufron Mukti-Wamenkes RI menyampaikan Resolusi PBB No 67 Tahun 2012 untuk mewujudkan UHC. Indonesia sudah mencoba aktif berpartisipatsi dalam WHO dan Bank Dunia tingkat Asia. Sejak diberlakukannya Jamkesmas, jaminan dan pemanfaatnya meningkat tajam. Tahun 2012 sekitar 76,4 juta orang dan tahun 2013 sekitar 86,6 juta.
Prof. Ali Ghufron Mukti-Wamenkes RI menyampaikan Resolusi PBB No 67 Tahun 2012 untuk mewujudkan UHC. Indonesia sudah mencoba aktif berpartisipatsi dalam WHO dan Bank Dunia tingkat Asia. Sejak diberlakukannya Jamkesmas, jaminan dan pemanfaatnya meningkat tajam. Tahun 2012 sekitar 76,4 juta orang dan tahun 2013 sekitar 86,6 juta.
Isu-isu penting : pertama tentang definisi-stuktur atau mandiri terkait pajak dan lain-lain. Kedua, siapa yang bertanggung jawab membayar premi? Bagaimana sektor informal Filipina masuk dalam skema. 5% dari APBN idealnya untuk jaminan. Amanat UU Kesehatan-perlu dibuat keputusan strategis untuk sektor informal. Jika ada pertanyaan, sesuai tidak dengan yang diharapkan? Ada sekitar 19,9 Trilyun untuk peserta jamkesmas (86.4 juta). Hal lain yang perlu diperhatikan yaitu kesehatan ibu dan anak-Jamkesmas dan Jamkesda masyarakat harus'membayar biaya kesehatan. Klaim untuk jaminan ini masih sulit dan dana yang dari Pusat terpotong di tingkat daerah.
Prof. dr. Bambang Purwoko, Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Rumusan kebijakan Pasal 6 UU No 20 Tahun 2004 SJSN. Informal sejak Orba-dulu menjadi andalan saat krisis-devaluasi rupiah atas dolar. Ada unsur ketidakpastian beroperasi tidak pasti penghasilannya. Mau tidak mau ada keputusan politik dari pemerintah. Secara ekonomi, 70% sudah tidak seimbang. UKM jika terdaftar maka GDP 8000 Trilyun akan lebih banyak lagi. Masalah kepegawaian sejak Orba masih belum ditata hingga hari ini. Harus ada transformasi dari informal ke formal.
Saat beroperasi pajak masuk ke negara. Jika lebih dari enam bulan tidak beroperasi, maka akan terdaftar dalam PBI. Pertama, political will. Kedua, transformasi mengubah pekerja informal ke formal 3,4-18,75% tergantung APBN-dana yang berkelanjutan karena ada penuaan performance product. 2030 kemungkinan masyarakat membayar BPJS Kesehatan. 2050 sudah ada reserved fund atau dana cadangan.
Masalah: pekerja Upah Minimum Provinsi-upah masih bermasalah. Jaminan sosial merupakan variabel tergantung dari pekerja, kualitas dari pajak. Perlindungan jangka panjang harus difasilitasi. Masyarakat yang ter-PHK langsung free fall menjadi informal.
Iskandar Maulana, wakil dari Pembinaan Hubungan Industrial, Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Sektor informal butuh ketegasan dari pemerintah. Modal kecil, ketrampilan terbatas, rentan resiko sosial, merupakan tiga kelemahan sektor informal. Sulitnya dari informal ke formal, pendidikan rendah-53 juta orang masih berpendidikan SD (informal). Kesempatan terbuka dalam dan luar negri. Pencari kerja dapat kerja yang tepat. Serikat Buruh belum masuk ke jaminan sosial. Sektor informal upah minimum bagi tenaga kerja 0-12 bulan bagi sektor yang terkecil-mikro dan UKM. Upah minimum salah kaprah, harusnya di atas upah minimum.
Penanya yaitu Oda Muchtar (Institut Jaminan Sosial Indonesia) menyampaikan 86 juta peserta JKN dibayar PBI. Menurut data dari Kementrian UKM, 52 juta UKM diduga informal sektor. Bagaimana supaya informal masuk ke Jaminan Sosial. Perpres 46 tahun 2013 pajak untuk UKM 1% dari aset sekitar 5-14 juta minimum setahun. Iuran JKN 500 ribu untuk saving plan. Insentif untuk UKM-membayar pajak. Jadi ada pemasukan dulu baru dialokasikan untuk insentif.
Prof. Ali Ghufron: Bagaimana pajak bisa dikumpulkan? Ekslporasi sumber pembiayaan? 270 M per tahun dari rokok. 270 T dari rokok jika pajaknya dinaikkan bisa mengcover Jaminan Sosial. Sosialisasi tugas pemerintah, media massa dan masyarakat. Khususnya TV terberdaya untuk sosialisasi.
Dr. Lukita, sampai 2019 untuk pencapaian BPJS. Data yang dibutuhkan harus jelas lalu marketing harus independen. Untuk hal-hal tertentu misalnya pensiun ada kewajiban iur. Informal komitmen dari pemerintah. BPJS Ketenagakerjaan saving plan untuk sektor informal.
Bambang-UU SJSN asas keadilan dan gotong royong. Gotong royong : getting benefit, ini salah kaprah, yang benar membayar iur karena ada manfaat yang diperoleh masyarakat.
Prof. Ali Ghufron-roadmap leaflet seminar poster untuk sosialisasi. Sudah dilakukan intensif. Join dengan DJSN dan pemda untuk sosialisasi BPJS. Dengar sudah, kewajiban dan hak belum diketahui secara umum.
Dr. Lukita, Jamkesda-kontribusi sektor informal. Contributory-amanat UU. Untuk kondisi Indonesia saat ini: model kombinasi yang tepat. Ali Ghufron sektor informal bisa dicover pemerintah. Model pembiayaan-bagaimana ke depannya? Mana yang lebih tepat.
Program SJSN ada 5, yang untuk sektor informal tercakup kesehatan-kematian prematur, jaminan hari tua (saving plan).
Isu poin: pertama, sosialisasi-banyak yang belum mau membayar iuran, bagaimana dengan daerah lain yang belum terjangkau. Kedua, bagaimana sistem pembayarannya? Foemulasi terbaik untuk masyarakat Indonesia hak dan kewajibannya.
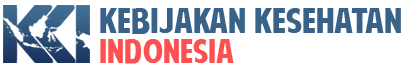



 Dr. Lukita Dinarsyah Tuwo, MA, Wamen Perencanaan Pembangunan Nasional menyampaikan SJSN tidak bisa secara massal, namun harus bertahap. Dalam hal ini, pelaksanaanya memerlukan sistem SDM yang terencana (transformasi), transfer dari Jamsostek ke BPJS kesehatan, integrasi Jamkesmas ke Jamkesda, perluasan ingin mencakup UHC dari Jaminan Sosial.
Dr. Lukita Dinarsyah Tuwo, MA, Wamen Perencanaan Pembangunan Nasional menyampaikan SJSN tidak bisa secara massal, namun harus bertahap. Dalam hal ini, pelaksanaanya memerlukan sistem SDM yang terencana (transformasi), transfer dari Jamsostek ke BPJS kesehatan, integrasi Jamkesmas ke Jamkesda, perluasan ingin mencakup UHC dari Jaminan Sosial. Prof. Ali Ghufron Mukti-Wamenkes RI menyampaikan Resolusi PBB No 67 Tahun 2012 untuk mewujudkan UHC. Indonesia sudah mencoba aktif berpartisipatsi dalam WHO dan Bank Dunia tingkat Asia. Sejak diberlakukannya Jamkesmas, jaminan dan pemanfaatnya meningkat tajam. Tahun 2012 sekitar 76,4 juta orang dan tahun 2013 sekitar 86,6 juta.
Prof. Ali Ghufron Mukti-Wamenkes RI menyampaikan Resolusi PBB No 67 Tahun 2012 untuk mewujudkan UHC. Indonesia sudah mencoba aktif berpartisipatsi dalam WHO dan Bank Dunia tingkat Asia. Sejak diberlakukannya Jamkesmas, jaminan dan pemanfaatnya meningkat tajam. Tahun 2012 sekitar 76,4 juta orang dan tahun 2013 sekitar 86,6 juta.