Reportase Pleno IV

Diskusi panel ke-4 ini membahas dua hal yaitu memposisikan puskesmas sebagai sentral dalam fasilitas kesehatan tingkat pertama dan majerial puskesmas yang harus berjalan. Selain itu, diskusi ini juga mengajak untuk jangan ada pembiaran terhadap peran puskesmas. Diskusi ini difasilitatori oleh Dr.dr Deni Sunjaya DESS dari Universitas Padjajaran dengan pembahas Prof.Dr. dr. Akmal Taher, Sp. U; dr. Adang Bahtiar, MPH, D.Sc (Ketua IAKMI Pusat) dan H. Andra Sjafril, SKM, M. Kes (Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau).
Diskusi diawali dengan presentasi dari Prof. Dr. dr. Hj. Rizanda Machmud, M. Kes dari Universitas Andalas mengenai penguatan fasilitas kesehatan tingkat pertama dan penguatan dinas kesehatan kabupaten/ kota dalam Pelayanan UKP dan UKM. Dalam paparannya, Rizanda menekankan tentang tugas puskemas yang harus dilakukan terkait dengan Permenkes No.75 tahun 2014. Puskesmas yang diharapkan berperan sebagai sentral akan memiliki kesulitan untuk menjalankan Permenkes No.75 tahun 2014 karena akan ada permasalahan di pelaporan dan pencatatannya. Untuk mengatasi hal ini memang sudah ada aplikasi PCare tetapi aplikasi ini tidak bisa mendistribusikan semua keperluan di Puskesmas. Presentasi kedua disampaikan oleh DR. dr. Mubasysyr Hasanbasri, MA dari Universitas Gadjah Mada mengenai apakah puskesmas sebagai lembaga pemerintah mampu menjalankan fungsi sebagai FKTP yang baik. Presentasi ini menyoroti tentang organisasi yang ada di puskesmas, khususnya manajerialnya. Manajerial ini perlu dilakukan untuk keperluan pengelolaan karena kerja di puskesmas tidak dapat dijalankan seorang diri. Meskipun demikian, sistem manajerial ini tidak akan berjalan dengan baik jika tidak didukung oleh Dinas Kesehatan.
Pembahasan mengenai kedua topik ini menjelaskan tentang kurangnya integrasi di puskesmas sehingga permasalahan di puskesmas sudah ada sebelum era JKN. Permasalahan ini masih ada hingga saat ini. Selain itu,menurut Prof. dr. Akmal Taher, Sp puskesmas memang enggan untuk mengatur manajerialnya sendiri karena pihak puskesmas tidak mau ribut di level bawah sehingga lebih baik level atas saja yang mengatur. Ide yang muncul disini adalah memilih tokoh di manajerial yang komprehensif sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik. Pihak yang diharapkan untuk melakukan manajerial ini berasal dari lulusan dari Fakultas Kesehatan Masyarakat dan bukan lagi dokter. Kendalanya adalah lulusan FKM tidak percaya diri menjalankan peran ini.
Untuk keikutsertaan pihak Dinas Kesehatan terhadap peran puskesmas dibahas oleh H. Andra Ajafril, SKM, M. Kes yang menjelaskan bahwa di Dinas Kesehatan Riau sudah diutamakan akreditasi dan manajemen puskesmas. Sayangnya, menurut Prof. Dr. dr. Hj. Rizanda Machmud, M.Kes hal tersebut belum terjadi di Padang. Umpan balik belum terjadi dari dinas kesehatan ke puskesmas. Sehingga bisa dikatakan bahwa keadaan puskesmas masih sulit di generalisasikan akibat dari otonomi daerah.
Materi Presentasi
|
Penguatan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan penguatan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam Pelayanan UKP dan UKM: Prof. DR. dr. Hj. Rizanda Machmud, M.Sc., Ph.D |
materi |
| Apakah Puskesmas sebagai lembaga pemerintah mampu menjalankan fungsi sebagai FKTP dengan baik?
DR. dr. Mubasysyr Hasanbasri, MA. Universitas Gadjah Mada |
materi |
|
Video Sesi Diskusi |
|
Reportase Pleno V

“Strategi Pemanfaatan Kenaikan Anggaran Kesehatan 5 % untuk Pencapaian Target UHC dan SDGs”
Pembicara dalam diskusi sesi pleno V yaitu Dr.drg. Theresia Ronny Andayani, MPH dan Prof. Syahfuddin Karimi. Sementara pembahasnya ialah dr. Adang Bahtiar, MPH, D.Sc, Sumiyati, Ak. M.FM, Dr. Gatot Soetono, MPH dan Dr. Artati Suryani, M.Kes. Pada diskusi pleno sesi V ini dibahas isu yang sedang hangat diperbincangkan saat ini terkait dengan rencana pemerintah menaikkan anggaran kesehatan sebesar 5% pada APBN tahun 2016. Pada saat ini, pengeluaran kesehatan publik untuk belanja kesehatan masih rendah. Oleh karena itu, pemerintah berencana menaikkan anggaran sektor kesehatan sesuai dengan tuntutan undang-undang yaitu sebesar 5%. Pemerintah juga bertekad meningkatkan alokasi anggaran kesehatan bagi daerah menjadi 22 Trilyun, naik 7 kali lipat dibandingkan tahun 2014 sebesar 3 Trilyun.
Pertanyaan selanjutnya adalah dengan kenaikan sektor anggaran ini, bagaimana strategi Bappenas? Dalam paparannya drg. Theresia Ronny Andayani, MPH yang diwakili oleh staf menyampaikan pentingnya upaya meningkatkan kegiatan promotif dan preventif, menyediakan tenaga kesehatan, obat dan peralatan kesehatan yang memadai, mengembangkan penelitian dan pengembangan guna mendukung dalam pengambilan kebijakan berbasis bukti, serta peningkatan sistem informasi kesehatan. Selain itu, salah satu strategi yang tidak kalah pentingnya pelaksanaan sistem kontrak dan public private partnership untuk meningkatkan kemampuan penyerapan anggaran.
Profesor Syahfuddin, Ekonom Universitas Andalas menjelaskan bahwa ada tantangan yang luar biasa besar dengan kenaikan anggaran sektor kesehatan sebesar 5 % ini yaitu bagaimana penyerapan anggaran bisa maksimal. Sebagai contoh Kementerian Pendidikan yang mengalami kesulitan dalam penyerapan anggaran kesehatan 5%. Syahfuddin mengusulkan strategi yang harus dilakukan adalah asuransi bagi semua masyarakat, keterbukaan informasi tentang kualitas dan biaya pelayanan kesehatan serta melakukan perencanaan yang baik dengan melibatkan pengguna layanan kesehatan.
Terkait dengan strategi kenaikan anggaran sektor kesehatan, dr. Adang Bachtiar mengusulkan perlu adanya mobilisasi sumber daya manusia, utilisasi data epidemi untuk health intervention serta perbaikan tata kelola anggaran, efisiensi, dan akuntabilitas. Sementara itu, Sumiyati dari Kementerian keuangan menekankan pentingnya strategi perencanaan yang baik yang yang meliputi: review peraturan dan prosedur yang ada, penyediaan SDM yang proporsional antara medis dan pendukungnya, sistem remunerasi yang baik, monitoring dan evaluasi yang kuat,serta sistem yang baik dan komitmen. dr Artati juga setuju dan sependapat dengan apa yang disampaikan dengan Sumiyati bahwa strategi yang paling penting adalah perencanaan yang tepat dengan melibatkan pengguna layanan kesehatan.
Materi presentasi
| Dr. drg. Theresia Ronny Andayani, MPH, Deputi Kesehatan dan Gizi Bappenas RI *) |
materi |
| Prof. Syahfuddin Karimi, Direktur Pascasarjana Universitas Andalas |
materi |
Reporter: Oktomi Wijaya
Reportase Pleno VI

Fraud berpotensi menurunkan mutu pelayanan kesehatan di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan oleh dr. Hanevi Djasri, MARS, Hanevi adalah salah satu konsultan Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK) FK UGM. Konsultan yang sehari-hari berkutat dengan mutu ini menjadi moderator pada acara Forum Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (FKKI) ke-6 di hotel Bumi Minang, Padang 25 Agustus 2015.
Forum ini menampilkan berbagai pembicara dan pembahas dari tingkat regulator, akademisi, pemberi pelayanan kesehatan dan regulator di tingkat wilayah. Paparan isu pertama tentang cukupkah Permenkes No. 36 Tahun 2015 mencegah fraud pada JKN oleh Prof. Dr. dr. Budi Sampurno SpPF. Ada tiga faktor yang menyebabkan fraud yakni motivasi, rasionalisasi, dan kesempatan. Permenkes yanng digagas oleh akademisi FK UGM ini telah mengandung unsur untuk menghilangkan penyebab fraud, mulai dari etika, remunerasi, bekerja menggunakan panduan klinis. Peraturan ini juga masih perlu didukung dengan peraturan lain di tingkat daerah.
KPK juga tidak tinggal diam terhadap ancaman fraud di layanan kesehatan. Dalam prsentasinya, Niken Ariati mengungkapkan bahwa KPK mempunyai fungsi pencegahan dan kewenangan di pasal 14. Kebjakan baru JKN berdampak masif. Pelaksanaan JKN ini ibarat kapal yang belum jadi tapi dipaksakan untuk berlayar, dibuktikan dengan keterlambatan Perpres 32 sehingga para pembaca bisa membayangkan hiruk pikuk penerapan JKN. Permenkes 36 dirasa telat keluar, yang seharusnya Permenkes ini keluar tahun 2014. Masalah fraud ini tentunya bisa diatasi dari akarnya, yakni dengan memasukkan kurikulum cara koding yang tepat dan benar pada fakultas kedokteran sehingga semua dokter mengetahui cara melakukan koding yang tepat.
Faktanya, fraud ini sudah lama terjadi. Sebelum JKN, fraud sudah mengancam sistem INA DRG. Dalam JKN ini, timbul konflik ideologi untuk merasionalkan pendapatan. dr. Donald Pardede, M.Kes mengungkapkan bahwa “Ketika masa transisi ini diperlukan pemahaman yang cukup, regulasi penting untuk memberikan definisi operasinal sehingga stakeholder bisa meng-alert fraud”. Selain itu, yang paling penting adalah menumbuhkan budaya anti fraud. Upaya ini dapat dilakukan pelatihan dan disemenasi untuk pencegahan fraud.
dr. Arida Oetami, M.Kes, dan Dr. dr. C. H. Soejono, SpPd, K-Ger, MEpid, FACP, FINASIM sebagai pembahas menekankan bahwa perlunya sosialisai Permenkes No 36 Tahun 2015. Namun walaupun Permenkes ini belum tersosialisasi dengan baik, penyedia layanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat Primer (FKTP) dan di Fasilitas Kesehatan tingkat Rujukan lanjutan (FKRTL) tetap terus mendukung upaya pencegahan fraud dengan terus berinovasi mencegah fraud dengan cara mengambangkan klinik fraud, membuat sistem rujukan, membuat sarana pelaporan fraud, pelatihan dan edukasi tentang bahaya fraud, sosialisasi tentang deteksi, pencegahan dan penindakan fraud. Mari bahu membahu mebangun sistem pencegahan fraud di Indonesia. JKN Indonesia lebih baik dari Obama Care.
Materi presentasi
| Prof. Dr. dr. Budi Sampurno SpPF, Universitas Indonesia Peraturan Menteri Kesehatan untuk mencegah Fraud: Apakah sudah cukup kuat? |
materi video |
| Direktorat litbang KPK – Niken Arianti Usaha pencegahan yang sedang dilakukan KPK |
materi video |
oleh Eva Tirtabayu Hasri, S.kep, MPH
Keynote Speech dari DFAT
Pemerintah Australia merasa terhormat karena bisa memberikan dukungan dalam konferensi seperti ini. Tentu pertemuan ini sangat penting, mengingat akan digelar UN Summit pada September 2015. Ini momentum yang penting sekali, mudah-mudahansemua negara akan meratifikasi sustainable development goals (SDG’s). SDG’s memiliki tujuan dan target yang ambisius, ada 17 goal dan 107 target. Ada 5 P yang mendasari lahirnya SDG’s ini, antara lain people, planet, prosperity, peace, dan partnership.
People atau orang menjadi prioritas pertama, banyak yang khawatir saat Millenium Development Goals (MDG’s) usai maka kesehatan tidak menjadi prioritas lagi. Sebelumnya, tiga target dari MDG’s berfokus pada kesehatan. Meski nanti dalam SDG hanya ada satu tujuan untuk kesehatan, namun seyogyanya hal ini sudah disusun secara komprehensif, karena menyangkut kesehatan, nutrisi dan well being (kemakmuran) seseorang.
Tentu saja akan banyak tantangan karena ada target baru yang diperkenalkan. Beruntung, salah satu target SDG ialah mencapai Universal Health Coverage (UHC). Poin yang menarik yaitu UHC bukan hanya perlindungan finansial. Pastinya model yang diusung WHO yaitu UHC mengarah ke layanan yang diberikan dan perlindungan sosial. Seharusnya ada 5 dimensi dalam UHC, dua yang menjadi tambahan ialah kualitas layanan kesehatan yang diberikan dan cakupan/pemerataan layanan kesehatan. Ini merupakan tantangan besar untuk Indonesia dan negara ini sudah mengambil langkah penting di area terkait.
Dua langkah penting yang dimaksud ialah skreditasi puskesmas dan penetapan standar pelayanan minimum. Sayangnya, kita sering memikirkan sektor publik, namun banyak masyarakat yang memilih ke klinik swasta. Oleh karena itu, kita masih memiliki PR untuk mutu dari penyedia layanan swasta. Hal yang harus digarisbawahi ialah di dalam layanan kesehatan masyarakat, pencegahan lebih baik dari pengobatan. Hal ini senada dengan yang disampaikan Jusuf Kalla, “Saya tantang Anda semua untuk tidak menambah RS, tempat tidur dan faskes lainnya, pikirkan bagaimana caranya orang keluar dari RS”. Pernyataan tersebut disampaikan wakil presiden saat Mukernas IAKMI beberapa tahun lalu di Kupang, NTT.
Saat ini menjadi kesempatan emas karena anggaran di bidang kesehatan akan ditingkatkan. Salah satu kunci besar untuk mampu memberikan layanan kesehatan yang baik karena ada kepemimpinan yang baik di politis dan birokrasi di tingkat kabupaten dan provinsi. Misalnya Frans Lebu Raya (Gubernur NTT) yang memiliki kepemimpinan politik yang kuat sehingga seluruh bupati mendukung Frans. Frans berhasil karena Bappeda, BPMD dan banyak lintas sektor pemerintah yang mengusung satu tujuan.
Di akhir keynote speech-nya, John sangat optimis, bibit kepemimpinan seperti itu maka Indonesia akan berlayar maju menuju tujuan yang ingin dicapai (wid).
Keynote Speech
Perencanaan UHC dalam Pembangunan Nasional untuk Mewujudkan Masyarakat Sehat Paripurna
Dra. Nina Sardjunani, MA
Keynote Speech Menteri Kesehatan RI
Penguatan Sistem Kesehatan Untuk Mewujudkan Indonesia Sehat
 Forum JKKI telah memasuki hari kedua, yang special dihari ini yaitu keynote speech menteri Kesehatan RI Prof. Dr. dr. Nila Djuwita F. Moeloek, Sp.M (K) hadir ditengah-tengah kami. Beliau memaparkan materi mengenai Penguatan Sistem Kesehatan Untuk Mewujudkan Indonesia Sehat.
Forum JKKI telah memasuki hari kedua, yang special dihari ini yaitu keynote speech menteri Kesehatan RI Prof. Dr. dr. Nila Djuwita F. Moeloek, Sp.M (K) hadir ditengah-tengah kami. Beliau memaparkan materi mengenai Penguatan Sistem Kesehatan Untuk Mewujudkan Indonesia Sehat.
Era Jaminan Kesehatan (JKN) yang sudah berlangsung selama 1,5 tahun, merupakan batu loncatan yang cukup besar. Sekitar 189 juta jiwa tertolong dalam hal kesehatan dalam era JKN ini. Banyak kendala yang dialami selama keberlangsungan perogram JKN. Ibu Nila memaparkan apapun program yang sudah berjalan kita selayaknya belajar menganalisa dan menutupi kekurangan, dan apabila ada kelebihan dari program tersebut, bisa dijadikan kebanggaan.
Biaya klaim yang dilakukan selama era JKN sebagian besar pada Rawan Inap . Penyakit jantung menduduki urutan pertama dengan klaim sebesar 3,5 Triliun. Kemudian disusul oleh Persalinan dengan klaim sebesar 2,3 Triliun. Selain rawat inap, klaim juga dilakukan pada rawat jalan. Penyakit gagal ginjal memiliki nilai klaim paling besar yaitu 1,7 Triliun, karena sebagian besar pasien melakukan Hemodialisa (HD) yang memerlukan dana cukup besar.
Perbedaan kasus rawat inap dan rawat jalan antara Penerima bantuan Iuran (PBI) dan non PBI, lebih banyak pada non PBI. Hal ini menjadi pertanyaan, apakah yang PBI ini belum mendapatkan informasi yang lengkap terkait layanan kesehatan yang mereka terima?. Dalam era JKN, dana yang ada masih mencukupi untuk pembiayaan kesehatan, tetapi belum dimanfaatkan dengan baik. Azas yang diberlakukan dalam JKN adalah azas gotong royong, dimana yang sakit dibantu oleh yang sehat dan yang tidak mampu dibantu oleh yang mampu. Hal ini mennjadi evaluasi untuk kita bersama.
Selanjutnya dibahas mengenai program MDGs yang telah berjalan cukup baik, Indonesia memiliki target optimal pencapaian MDGs di tahun 2015. Salah satu bidang yang sangat diutamakan Indonesia ialah kesehatan terutama masalah gizi dan kesehatan ibu-anak. Fokus pemerintah untuk memenuhi target MDGs dalam bidang ini ialah dengan menekan angka kematian ibu dan anak (AKI). Data dari Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2012 angka kematian ibu sebesar 359 per 100.000 kelahiran. Berbagai macam cara dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengurangi atau menekan angka kematian ibu. Seperti contoh yang dilakukan oleh Ibu Tri Rismaharini (Walikota Surabaya) dan Dinas Kesehatan Surabaya membuat program “Ramah Posyandu”. Dengan program tersebut berhasil menurunkan angka kematian ibu yang signifikan.
MDGs 4 dan 5 tidak hanya sebatas menekan angka kematian ibu dan anak. Tetapi bagaimana menciptakan generasi penerus yang bisa mensukseskan pembangunan kesehatan di Indonesia. Salah satu ancaman serius terhadap tujuan pembangunan kesehatan kita, khususnya kualitas generasi mendatang adalah stunting. Terlihat bahwa secara nasional rata-rata angka kejadian stunting pada balita kita adalah 37.2%. Dengan asumsi jika seorang ibu memiliki anak 5 maka 2 diantaranya akan stunting atau gangguan kognitif yang mengakibatkan IQ nya tidak akan mencapai standar. Menurut standar WHO, persentase ini termasuk kategori berat, dan untuk kita perlu memberikan perhatian yang lebih serius dalam upaya menurunkan angka kejadian stunting di negara kita. Untuk mengatasinya maka dimulai dengan perbaikan kesehatan dan mengubah mindset sejak usia remaja. Dengan berbagai program yang diberikan harapannya bisa mengurangi kejadian stunting di Indonesia.
Program Nawa cita yang dibuat oleh Presiden Republik Indonesia berprioritas pada pembangunan dimulai dari daerah perifer ke sentral. Begitupula pada sektor kesehatan, dengan program Nusantara Sehat yang berfokus untuk penguatan pelayanan kesehatan primer melalui pengiriman tenaga kesehatan ke daerah pinggiran dan daerah terpencil di Indonesia. Dimulai dari layanan Posyandu, Posbindu, Poskestren hingga Puskesmas. Hal ini tentunya berdampak pada peningkatan mutu pelayanan kesehtan ditingkat primer.
Untuk mewujudkan Indonesia sehat, Kementerian Kesehatan tidak bisa berjalan sendiri. Dalam hal ini tentunya kementerian kesehatan melakukan kerjasama dengan beberapa kementerian agar program-program yang ada bisa berjalan dengan baik. Dengan adanya kerjasama lintas kementrian diharapkan pembangunan kesehatan di Indonesia bisa lebih baik lagi.
materi presentasi video Part 1 part 2 part 3 part 4
Reporter : Elisa Sulistyaningrum
Untung Suseno Sutarjo menyampaikan sejumlah hal menarik melalui Forum Kebijakan Kesehatan Indonesia Keenam pada Selasa (25/8/2015). Tantangan pembangunan kesehatan ke depan yaitu pencapaian MDG’S atau SDG’s dan implementasi JKN dengan meningkatkan pelayanan. MDG’s akan menjadi SDG’s, dan secara nasional sudah disusun strategi salah satunya melalui Indonesia Sehat yang diusung Jokowi (Nawacita). Situasi lain yang cukup penting ialah kepesertaan PBI yang akan meningkat dari 88,2 juta ke 92,4 juta untuk PBI (untuk bayi dan yang membutuhkan) pada tahun 2016. Selain itu, akan dilakukan penyesuaian anggaran Kemkes yang jumlahnya hanya 64,8 Trilyun, 25 Trilyun akan dialokasikan untuk JKN.
Sesi tanya jawab dalam sesi ini memunculkan beberapa pertanyaan. Edward dari Papua menanyakan untuk Mei 2016 akan ada peningkatan dana 5% untuk Dana Alokasi Khusus (DAK). Hal yang ditakutkan ialah pola pikir yang berkembang di daerah dimana UHC sulit dicapai di daerah seperti Papua. Salah satunya, untuk JKN tidak ada biaya pendamping untuk staf Dinkes, sementara kartu Papua Sehat misalnya disertai dengan biaya sosialisasi dan biaya pendampingan.
Ariawati dari Dinkes Lampung menanyakan DAK non teknis terdiri dari DAK BOK dan akreditasi Puskesmas. Semua DAK Non teknis akan masuk ke Biro Keuangan, apakah tidak menambah panjangnya birokrasi?
Pertanyaan lain yang muncul ialah, apakah mungkin program UKM di Puskesmas dikontrakkan ke pihak ketiga?
Untung mencoba memaparkan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang baru (2016) berbeda dengan yang tahun sebelumnya. DAK model baru yang diturunkan ke Provinsi dibagi sesuai kriteria (juknis berjalan). Provinsi harus melihat kabupaten mana yang siap menerima DAK. Dana Alokasi Khusus (DAK) 2016 bisa diperoleh melalui proposal dari staf nakes yang akan melaksanakan kegiatan di daerah. Setelah DAK suatu daerah disetujui, maka akan ada penilai profesional yang menyeleksi daerah mana yang memungkinkan untuk menerima DAK. Jika tidak terserap, akan diberikan ke daerah lain.Khusus BPKP akan dikirim ke Papua untuk menilai kesiapan Papua dalam penerimaan DAK.
Untung menutup sesi dengan menjawab pertanyaan terkait kontrak. Dari DAK apa saja program yang bisa dikontrakkan? Namun, jika banyak program yang dikontrakkan, Dinkes jadi apa? Jika program dilakukan Puskesmas, maka Dinkes sebagai pengawas. Sementara provinsi mengawasi pelaksanaan program tersebut, misal daerah mana yang gunakan pajak rokok untuk membangun ruang merokok, tegas Untung.
FKKI Keenam resmi ditutup pada Selasa (25/8/2015) dengan pengumuman dari ketua panitia yaitu Prof. Rizanda Machmud bahwa FKKI berikutnya (2016) akan digelar di Makassar (wid).



 Dr. Deni menyampaikan selamat datang kepada semua peserta Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (Fornas JKKI) V, yang mana Forum JKKI yang kelima ini kebetulan bertepatan dengan ulang tahun Universitas Padjajaran yang ke 57.Hari ketiga Forum Nasional JKKI V akan diisi dengan pelatihan penyusunan policy brief pada tanggal 26 September 2014 di Gedung RSP FK Unpad. Tema FJKKI V ini adalah Monitoring pelaksanaan kebijakan jaminan kesehatan Nasional di Tahun 2014 : Kendala, Manfaat dan Harapan dengan kelompok-kelompok kerja yang terdiri dari (1) Kebijakan Pembiayaan Kesehatan, (2) Kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak (3) Kebijakan HIV/AIDS (4) Kebijakan Gizi, (5) Kebijakan Kesehatan Jiwa Masyarakat (6) Kebijakan Pendidikan SDM Kesehatan (7) Kebijakan Palayanan Kesehatan.
Dr. Deni menyampaikan selamat datang kepada semua peserta Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (Fornas JKKI) V, yang mana Forum JKKI yang kelima ini kebetulan bertepatan dengan ulang tahun Universitas Padjajaran yang ke 57.Hari ketiga Forum Nasional JKKI V akan diisi dengan pelatihan penyusunan policy brief pada tanggal 26 September 2014 di Gedung RSP FK Unpad. Tema FJKKI V ini adalah Monitoring pelaksanaan kebijakan jaminan kesehatan Nasional di Tahun 2014 : Kendala, Manfaat dan Harapan dengan kelompok-kelompok kerja yang terdiri dari (1) Kebijakan Pembiayaan Kesehatan, (2) Kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak (3) Kebijakan HIV/AIDS (4) Kebijakan Gizi, (5) Kebijakan Kesehatan Jiwa Masyarakat (6) Kebijakan Pendidikan SDM Kesehatan (7) Kebijakan Palayanan Kesehatan. Prof. Laksono menyampaikan monitoring JKN ini merupakan satu program besar yang memerlukan peneliti dan para praktisi, para peneliti harus menjadi pihak yang independen. Contohnya PU itu semua program pengembangan selalu mempunyai dana monitoring yang dikerjakan pihak Independen sekitar 5%-7%, tapi dis ektor kesehatan tidak ada dana monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pihak Independen. Ini juga yang akan disampaikan ke tim Jokowi nanti, kita berharap di semua sektor kesehatan termasuk JKN ini ada 1%-2% anggaran untuk monitoring dan evaluasi oleh pihak Independen. Dengan cara ini, sektor kesehatan menjadi lebih akurat dalam membuat program-programnya. Kemudian, ada sub tema mengenai KIA, yang mana angka kematian Ibu masih tinggi sekali, yang merupakan juga salah satu pengalaman kami di NTT karena tidak adanya monitoring dan evaluasi program di KIA oleh lembaga Independen.
Prof. Laksono menyampaikan monitoring JKN ini merupakan satu program besar yang memerlukan peneliti dan para praktisi, para peneliti harus menjadi pihak yang independen. Contohnya PU itu semua program pengembangan selalu mempunyai dana monitoring yang dikerjakan pihak Independen sekitar 5%-7%, tapi dis ektor kesehatan tidak ada dana monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh pihak Independen. Ini juga yang akan disampaikan ke tim Jokowi nanti, kita berharap di semua sektor kesehatan termasuk JKN ini ada 1%-2% anggaran untuk monitoring dan evaluasi oleh pihak Independen. Dengan cara ini, sektor kesehatan menjadi lebih akurat dalam membuat program-programnya. Kemudian, ada sub tema mengenai KIA, yang mana angka kematian Ibu masih tinggi sekali, yang merupakan juga salah satu pengalaman kami di NTT karena tidak adanya monitoring dan evaluasi program di KIA oleh lembaga Independen. Sambutan ketiga adalah dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran oleh Prof. dr. med Tri Hanggono Ahmad, dr. Dekan FK Unpad menyambut para peserta FJKKI V dengan kata “Sampurasun” yang dibalas serempak oleh peserta dengan “Rampes”, karena pada hari Rabu merupakan rabu nyunda di Jawa Barat untuk terus mempertahankan dan mengembangkan budaya Sunda ini. Prof Hanggono menyampaikan permohonan maaf atas absennya Rektor Unpad. Prof Hanggono menyampaikan upaya keras akan dilakukan karena pertemuan ini memiliki nilai yang strategik, tahun 2014 adalah tahun yang luar biasa utuk kita semua. Temanya pun ikut mendukung dalam mencapai MDGs. Jangan sampai membuat kebijakan yang tidak ada kesinambungannya dengan kebijakan lain. Mudah-mudahan apa yang dibangun dan dihasilkan dari pembicaraan hari ini mengenai implementasi JKN akan membahas mengenai tujuan pembangunan global. Harapannya adalah bagaimana berupaya bersama-sama menghasilkan produk kebijakan dalam forum ini. Selamat menikmati kota Bandung.
Sambutan ketiga adalah dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran oleh Prof. dr. med Tri Hanggono Ahmad, dr. Dekan FK Unpad menyambut para peserta FJKKI V dengan kata “Sampurasun” yang dibalas serempak oleh peserta dengan “Rampes”, karena pada hari Rabu merupakan rabu nyunda di Jawa Barat untuk terus mempertahankan dan mengembangkan budaya Sunda ini. Prof Hanggono menyampaikan permohonan maaf atas absennya Rektor Unpad. Prof Hanggono menyampaikan upaya keras akan dilakukan karena pertemuan ini memiliki nilai yang strategik, tahun 2014 adalah tahun yang luar biasa utuk kita semua. Temanya pun ikut mendukung dalam mencapai MDGs. Jangan sampai membuat kebijakan yang tidak ada kesinambungannya dengan kebijakan lain. Mudah-mudahan apa yang dibangun dan dihasilkan dari pembicaraan hari ini mengenai implementasi JKN akan membahas mengenai tujuan pembangunan global. Harapannya adalah bagaimana berupaya bersama-sama menghasilkan produk kebijakan dalam forum ini. Selamat menikmati kota Bandung. Pembahas dalam sesi ini adalah Dr. Anung Sugihantono, dr.,M.Kes yang menjabat sebagai Dirjen Bina Gizi dan KIA Kementerian Kesehatan RI. dr.Anung memaparkan mengenai kompleksitas masalah menuju periode akhir MDGs pada tahun 2015 mendatang. Pencapaian keberhasilan Indonesia dianggapnya masih jauh dari harapan berdasarkan isu-isu MDGs. Isu yang paling disoroti adalah isu kemiskinan yang jumlahnya masih sangat menghawatirkan. Masalah tersebut dapat diatasi dengan perbaikan sistem kesehatan yang lebih optimal, lanjutnya. Namun saat ini, pola kebijakan kesehatan akan ditentukan oleh pemimpin yang baru, sebab Indonesia sudah mengalami peralihan kekuasaan.
Pembahas dalam sesi ini adalah Dr. Anung Sugihantono, dr.,M.Kes yang menjabat sebagai Dirjen Bina Gizi dan KIA Kementerian Kesehatan RI. dr.Anung memaparkan mengenai kompleksitas masalah menuju periode akhir MDGs pada tahun 2015 mendatang. Pencapaian keberhasilan Indonesia dianggapnya masih jauh dari harapan berdasarkan isu-isu MDGs. Isu yang paling disoroti adalah isu kemiskinan yang jumlahnya masih sangat menghawatirkan. Masalah tersebut dapat diatasi dengan perbaikan sistem kesehatan yang lebih optimal, lanjutnya. Namun saat ini, pola kebijakan kesehatan akan ditentukan oleh pemimpin yang baru, sebab Indonesia sudah mengalami peralihan kekuasaan.

 Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),di bawah naungan BPJS,telah berjalan hampirsembilan bulan. Masih banyak ditemui kekurangan dalam pelaksanaan program ini.Butuh pemikiran dan terobosan untuk memperbaiki program agar lebih sesuai harapan.Isu ini ditangkap penyelenggara Forum Nasional V Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (Fornas V JKKI) 2014. Diskusi berbagai usulan untuk menciptakan program JKN yang lebih baik difasilitasi dalam sesi pleno 3 Fornas V JKKI 2014 ini.
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),di bawah naungan BPJS,telah berjalan hampirsembilan bulan. Masih banyak ditemui kekurangan dalam pelaksanaan program ini.Butuh pemikiran dan terobosan untuk memperbaiki program agar lebih sesuai harapan.Isu ini ditangkap penyelenggara Forum Nasional V Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia (Fornas V JKKI) 2014. Diskusi berbagai usulan untuk menciptakan program JKN yang lebih baik difasilitasi dalam sesi pleno 3 Fornas V JKKI 2014 ini. John Lengenbrunner (juga senang dipanggil sebagai pak Joko) sebagai pembicara pertama membahas mengenai hubungan antara MDG dengan UHC. Lengenbrunner yang juga memiliki pengalaman bekerja di Word Bank tersebut mengatakan bahwa sebenarnya sulit untuk menghubungkan hal tersebut.
John Lengenbrunner (juga senang dipanggil sebagai pak Joko) sebagai pembicara pertama membahas mengenai hubungan antara MDG dengan UHC. Lengenbrunner yang juga memiliki pengalaman bekerja di Word Bank tersebut mengatakan bahwa sebenarnya sulit untuk menghubungkan hal tersebut. Berbeda dengan pembicara pertama, Ascobat Gani sebagai pembicara kedua menekankan tentang kebiasaan pengambil keputusan di Indonesia yang sering mengikuti trend/mode kebijakan internasional tanpa memperhatikan konsep dasar kebijakan baru dan keberlangsungan antar kebijakan serta alokasi sumber daya untuk meneruskan kebijakan lama. Presentasi Gani lebih menekankan kritiknya tetang JKN yang tidak memperhatian aspek kesehatan masyarakat.
Berbeda dengan pembicara pertama, Ascobat Gani sebagai pembicara kedua menekankan tentang kebiasaan pengambil keputusan di Indonesia yang sering mengikuti trend/mode kebijakan internasional tanpa memperhatikan konsep dasar kebijakan baru dan keberlangsungan antar kebijakan serta alokasi sumber daya untuk meneruskan kebijakan lama. Presentasi Gani lebih menekankan kritiknya tetang JKN yang tidak memperhatian aspek kesehatan masyarakat. Sesi pleno 5 pada Kamis (25/9/2014) dibuka dengan pemaparan Prof. Dr. Nanan Sekarwana, dr., Sp. A (K)., MARS., mengenai permasalahan implementasi JKN di Jawa Barat. “Sistem yang baru berjalan perlu perbaikan dimana-mana karena distribusi beban yang tidak merata” ucap dr Nanan mengawali sesi ini. JKN yang baru saja berjalan selama hampirsembilan bulan memang masih sarat dengan masalah masalah yang perlu terus diatasi. Pelayanan JKN yang merata merupakan harapan besar dari berbagai pihak. Tidak hanya peserta, hal tersebut juga menjadi harapan besar dari provider kesehatan maupun penyelenggara (BPJS). Namun, apakah implementasi JKN sudah memenuhi harapan itu? Tentu saja belum. Ada beberapa masalah implementasi JKN di Jawa Barat yang diungkapkan oleh Guru besar FK UNPAD ini, antara lain: permasalahan sistem rujukan, kurang optimalnya implementasi clinical pathway, perbedaan keinginan antara BPJS dengan dokter, kurangnya pemahaman terhadap buku panduan layanan BPJS, banyaknya kepesertaan mendadak, dan keterlambatan klaim. Permasalahan tersebut jika tidak diatasi dapat berdampak besar pada kendali mutu dan kendali biaya.
Sesi pleno 5 pada Kamis (25/9/2014) dibuka dengan pemaparan Prof. Dr. Nanan Sekarwana, dr., Sp. A (K)., MARS., mengenai permasalahan implementasi JKN di Jawa Barat. “Sistem yang baru berjalan perlu perbaikan dimana-mana karena distribusi beban yang tidak merata” ucap dr Nanan mengawali sesi ini. JKN yang baru saja berjalan selama hampirsembilan bulan memang masih sarat dengan masalah masalah yang perlu terus diatasi. Pelayanan JKN yang merata merupakan harapan besar dari berbagai pihak. Tidak hanya peserta, hal tersebut juga menjadi harapan besar dari provider kesehatan maupun penyelenggara (BPJS). Namun, apakah implementasi JKN sudah memenuhi harapan itu? Tentu saja belum. Ada beberapa masalah implementasi JKN di Jawa Barat yang diungkapkan oleh Guru besar FK UNPAD ini, antara lain: permasalahan sistem rujukan, kurang optimalnya implementasi clinical pathway, perbedaan keinginan antara BPJS dengan dokter, kurangnya pemahaman terhadap buku panduan layanan BPJS, banyaknya kepesertaan mendadak, dan keterlambatan klaim. Permasalahan tersebut jika tidak diatasi dapat berdampak besar pada kendali mutu dan kendali biaya.
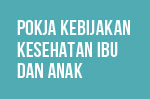
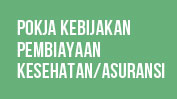
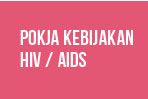
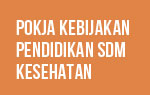
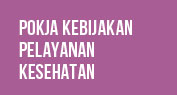

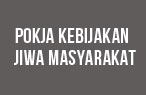

 PENDAFTARAN DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN:
PENDAFTARAN DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN:
 Mutu kesehatan dalam era JKN menjadi isu hangat yang selalu diperbincangkan oleh peneliti. Tiga peneliti daru UNHAS dan dua peneliti dari UGM menyajikan hasil penelitian tentang mutu kesehatan pada Forum kebijakan kesehatan Indonesia yang ke-6 yang diselenggarakan di hotel Bumi Minang. Kelima peneliti berhasil memancing peneliti dari berbagai universitas lain di Indonesia untuk berdiskusi agar dicapai rekomendasi-rekomendasi mauoun saran untuk perbaikan penelitian lebih lanjut.
Mutu kesehatan dalam era JKN menjadi isu hangat yang selalu diperbincangkan oleh peneliti. Tiga peneliti daru UNHAS dan dua peneliti dari UGM menyajikan hasil penelitian tentang mutu kesehatan pada Forum kebijakan kesehatan Indonesia yang ke-6 yang diselenggarakan di hotel Bumi Minang. Kelima peneliti berhasil memancing peneliti dari berbagai universitas lain di Indonesia untuk berdiskusi agar dicapai rekomendasi-rekomendasi mauoun saran untuk perbaikan penelitian lebih lanjut. Tahun 2015 ini, untuk pertama kalinya Pokja Penanggulangan Bencana membuka kajian dalam forum Kebijakan Kesehatan Indonesia. Pada kelas paralel Pokja Penanggulangan Bencana ini membahas tentang kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia. Pada sesi ini menghadirkan 3 pembicara yaitu dari Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, UNFPA dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat.
Tahun 2015 ini, untuk pertama kalinya Pokja Penanggulangan Bencana membuka kajian dalam forum Kebijakan Kesehatan Indonesia. Pada kelas paralel Pokja Penanggulangan Bencana ini membahas tentang kebijakan penanggulangan bencana di Indonesia. Pada sesi ini menghadirkan 3 pembicara yaitu dari Pusat Penanggulangan Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, UNFPA dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat. Sesi I dari Pokja HIV dan AIDS kali ini membahas tentang ‘Integrasi Penanggulangan HIV dan AIDS ke dalam Sistem Kesehatan untuk Mendukung Pencapaian UHC 2019’. Sesi ini dipimpin oleh dr. Juliandi Harahap sebagai moderator dan tiga materi terkait tema diatas akan dibawakan oleh tim peneliti dari PKMK UGM yaitu M. Suharni, Ign.Hersumpana dan Chrysant Lily. Sesi I ini dihadiri sekitar 47 peserta dengan latar belakang yang cukup bervariasi mulai dari perwakilan LSM local, pemangku kepentingan dan juga dari akademisi.
Sesi I dari Pokja HIV dan AIDS kali ini membahas tentang ‘Integrasi Penanggulangan HIV dan AIDS ke dalam Sistem Kesehatan untuk Mendukung Pencapaian UHC 2019’. Sesi ini dipimpin oleh dr. Juliandi Harahap sebagai moderator dan tiga materi terkait tema diatas akan dibawakan oleh tim peneliti dari PKMK UGM yaitu M. Suharni, Ign.Hersumpana dan Chrysant Lily. Sesi I ini dihadiri sekitar 47 peserta dengan latar belakang yang cukup bervariasi mulai dari perwakilan LSM local, pemangku kepentingan dan juga dari akademisi.

 Selain terdapat pokja Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pada Forum Kebijakan Kesehatan Nasional (FKKI) VI tahun 2015 kali ini terdapat kelompok kerja yang berfokus pada pembiayaan kesehatan.Diskusi paralel pokja yang diselenggarakan sore di hari kedua ini (25 Agustus 2015) diisi oleh dua pemateri yang masing-masing memiliki topik spesifik.
Selain terdapat pokja Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pada Forum Kebijakan Kesehatan Nasional (FKKI) VI tahun 2015 kali ini terdapat kelompok kerja yang berfokus pada pembiayaan kesehatan.Diskusi paralel pokja yang diselenggarakan sore di hari kedua ini (25 Agustus 2015) diisi oleh dua pemateri yang masing-masing memiliki topik spesifik. Pada sesi diskusi, Bapak Deni dari Dinas Kesehatan Lima Puluh Kota menyatakan bahwa kurang optimalnya pembiayaan untuk kegiatan kesehatan gigi kemungkinan karena program ini dinilai kurang prioritas diantara program promosi dan pelayanan kesehatan dasar yang lainnya. Prof. Laksono juga menegaskan bahwa kesehatan gigi memang sangat erat kaitannya dengan perilaku kesehatan masing-masing individu. Peran advokasi, terutama PDGI sanngat penting dalam menyuarakan pentingnya dukungan pembiayaan pada program kesehatan gigi berbasis masyarakat. Sependapat dengan pendapat beliau, ibu Erna juga menambahkan bahwa adanya Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia dapat menjadi wadah kelompok kerja untuk advokasi, baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional.
Pada sesi diskusi, Bapak Deni dari Dinas Kesehatan Lima Puluh Kota menyatakan bahwa kurang optimalnya pembiayaan untuk kegiatan kesehatan gigi kemungkinan karena program ini dinilai kurang prioritas diantara program promosi dan pelayanan kesehatan dasar yang lainnya. Prof. Laksono juga menegaskan bahwa kesehatan gigi memang sangat erat kaitannya dengan perilaku kesehatan masing-masing individu. Peran advokasi, terutama PDGI sanngat penting dalam menyuarakan pentingnya dukungan pembiayaan pada program kesehatan gigi berbasis masyarakat. Sependapat dengan pendapat beliau, ibu Erna juga menambahkan bahwa adanya Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia dapat menjadi wadah kelompok kerja untuk advokasi, baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional.
 Keterlibatan yang pertama Pokja Penanggulangan Bencana dalam Forum Kebijakan Kesehatan Indonesia, dimanfaatkan oleh Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK UGM sebagai penyelenggara untuk menginisiasi terbentuknya forum perguruan tinggi kesehatan untuk penanggulangan bencana di Indonesia. Untuk itu, hari kedua ini khusus membahas mengenai kurikulum bencana kesehatan di FK dan FKM. FK diwakili oleh FK UGM dan FKM diwakili oleh FKM Universitas Andalas.
Keterlibatan yang pertama Pokja Penanggulangan Bencana dalam Forum Kebijakan Kesehatan Indonesia, dimanfaatkan oleh Divisi Manajemen Bencana Kesehatan PKMK FK UGM sebagai penyelenggara untuk menginisiasi terbentuknya forum perguruan tinggi kesehatan untuk penanggulangan bencana di Indonesia. Untuk itu, hari kedua ini khusus membahas mengenai kurikulum bencana kesehatan di FK dan FKM. FK diwakili oleh FK UGM dan FKM diwakili oleh FKM Universitas Andalas. Pembicara pertama memulai penelitiannya ketika melihat adanya fenomena ODHA yang belum mau memulai terapi ARV meski jumlah CD4 sudah memenuhi syarat. Penelitian yang dilakukan di RS.Labuang Baji kota Makassar memberikan hasil bahwa keputusan untuk tidak memulai terapi lebih disebabkan oleh rasa takut akan efek samping. Sebagai kota besar di bagian timur di Indonesia, Makassar juga menanggung risiko akan besarnya peluang peredaran narkotika. Sudirman Nasir melakukan sebuat studi etnografi pada pecandu narkotika suntik di slum area kota ini. Dengan melihat aspek social capital dari kelompok ini, ditemukan bahwa unemploymentmenjadi sebuah konteks sosial bagi sebagian besar pengguna narkotika yang menjadikan mereka berhubungan dengan kegiatan yang ilegal. Selain itu unsur masculinity atau konsep rewa pada suku bugis makassar juga menjadi faktor anak laki-laki untuk membutikan kelaki‐lakiannya dengan cara yang berisiko. Laju inisiasi dari ‘penggunaan’ menuju ‘ketergantungan’ menjadi lebih cepat di kalangan pengguna narkotika laki-laki.
Pembicara pertama memulai penelitiannya ketika melihat adanya fenomena ODHA yang belum mau memulai terapi ARV meski jumlah CD4 sudah memenuhi syarat. Penelitian yang dilakukan di RS.Labuang Baji kota Makassar memberikan hasil bahwa keputusan untuk tidak memulai terapi lebih disebabkan oleh rasa takut akan efek samping. Sebagai kota besar di bagian timur di Indonesia, Makassar juga menanggung risiko akan besarnya peluang peredaran narkotika. Sudirman Nasir melakukan sebuat studi etnografi pada pecandu narkotika suntik di slum area kota ini. Dengan melihat aspek social capital dari kelompok ini, ditemukan bahwa unemploymentmenjadi sebuah konteks sosial bagi sebagian besar pengguna narkotika yang menjadikan mereka berhubungan dengan kegiatan yang ilegal. Selain itu unsur masculinity atau konsep rewa pada suku bugis makassar juga menjadi faktor anak laki-laki untuk membutikan kelaki‐lakiannya dengan cara yang berisiko. Laju inisiasi dari ‘penggunaan’ menuju ‘ketergantungan’ menjadi lebih cepat di kalangan pengguna narkotika laki-laki.

 Indonesia kebanjiran hasil penelitian. Hasil penelitian dibuat sebagai syarat untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi, menaikkan pangkat, maupun syarat lainnya. Puluhan ribu hasil penelitian yang dihasilkan setiap tahun, dicetak dan dipajang di perpustakaan bahkan dipublikasikan secara online.
Indonesia kebanjiran hasil penelitian. Hasil penelitian dibuat sebagai syarat untuk memenuhi syarat menyelesaikan studi, menaikkan pangkat, maupun syarat lainnya. Puluhan ribu hasil penelitian yang dihasilkan setiap tahun, dicetak dan dipajang di perpustakaan bahkan dipublikasikan secara online.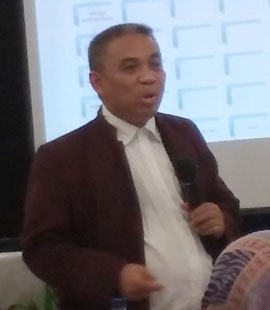 Faktanya saat ini, telah banyak regulasi yang mengatur semua program yang harus diawasi. Pegawasan atau controling merupakan komponen penting dalam implementasi. Controling digunakan untuk mencari penyimpangan dan mengatasi penyimpangan. Dr. dr. Mubasyir Hasanbasri, MA sebagai narasumber workshop ini, mengungkapkan bahwa program tidak efektif karena penyimpangan tidak pernah terdeteksi, program pengawasan yang efektif adalah yang terjun langsung melihat kenyataan.
Faktanya saat ini, telah banyak regulasi yang mengatur semua program yang harus diawasi. Pegawasan atau controling merupakan komponen penting dalam implementasi. Controling digunakan untuk mencari penyimpangan dan mengatasi penyimpangan. Dr. dr. Mubasyir Hasanbasri, MA sebagai narasumber workshop ini, mengungkapkan bahwa program tidak efektif karena penyimpangan tidak pernah terdeteksi, program pengawasan yang efektif adalah yang terjun langsung melihat kenyataan.
 Konsep contracting out atau disebut dengan PPP (Public Private Partnership) sebenarnya sudah dipakai selama ini dalam membangun kerjasama baik antara pemerintah dan swasta. Bentuk kemitraan dalam berbagai bentuk baik dana, tenaga dan waktu.
Konsep contracting out atau disebut dengan PPP (Public Private Partnership) sebenarnya sudah dipakai selama ini dalam membangun kerjasama baik antara pemerintah dan swasta. Bentuk kemitraan dalam berbagai bentuk baik dana, tenaga dan waktu.
 Salah satu sesi paralel dalam Fornas V JKKI yaitu mengenai kebijakan pembiayaan yang dimoderatori oleh Bapak Prawira. Sesi pertama kebijakan pembiayaan diawali dengan bahasan mengenai studi hambatan dalam pendanaan kesehatan di Puskesmas. Pada bahasan ini, M. Faozi Kurniawan (PKMK FK UGM) menjelaskan berbagai hambatan dalam fund-channelling beserta solusi alternatif yang kerap dilakukan Puskesmas. dr. Azhar Jaya, SKM, MARS selaku pembahas juga menegaskan bahwa kapasitas fiskal daerah perlu diperhatikan. Menurut beliau, kapasitas fiskal lebih cocok untuk mekanisme DAK. Ketersediaan SDM administrasi juga sangat diperlukan dalam penyesuaian kaidah keuangan di Puskesmas.
Salah satu sesi paralel dalam Fornas V JKKI yaitu mengenai kebijakan pembiayaan yang dimoderatori oleh Bapak Prawira. Sesi pertama kebijakan pembiayaan diawali dengan bahasan mengenai studi hambatan dalam pendanaan kesehatan di Puskesmas. Pada bahasan ini, M. Faozi Kurniawan (PKMK FK UGM) menjelaskan berbagai hambatan dalam fund-channelling beserta solusi alternatif yang kerap dilakukan Puskesmas. dr. Azhar Jaya, SKM, MARS selaku pembahas juga menegaskan bahwa kapasitas fiskal daerah perlu diperhatikan. Menurut beliau, kapasitas fiskal lebih cocok untuk mekanisme DAK. Ketersediaan SDM administrasi juga sangat diperlukan dalam penyesuaian kaidah keuangan di Puskesmas. Sesi Pertama Kebijakan Ibu dan Anak dalam Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia ini dimoderatori adalah Prof. Dr. dr. Alimin Mahidin, MPH. Paparan pertama dalam Sesi ini disampaikan oleh Dr Stefanus Bria Seran, MD, MPH, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur yang menyajikan hasil kegiatan Sister Hospital di Propinsi NTT. Program Sister Hospital merupakan bagian dari Kebijakan Revolusi KIA yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Propinsi NTT, dalam rangka percepatan penurunan angka kematian Ibu, Bayi dan Balita. Revolusi KIA, pada intinya memaksa para ibu hamil untuk melahirkan di fasilitas kesehatan, terutama di Puskesmas dan Rumah Sakit. Program Sister Hospital ini menitikberatkan kepada penyediaan pelayanan rujukan untuk komplikasi medis spesialistik. Sampai saat ini program ini mampu menurunkan angka kematian ibu di NTT secara signifikan, tetapi belum berdampak kepada angka kematian bayi dan balita.
Sesi Pertama Kebijakan Ibu dan Anak dalam Forum Nasional Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia ini dimoderatori adalah Prof. Dr. dr. Alimin Mahidin, MPH. Paparan pertama dalam Sesi ini disampaikan oleh Dr Stefanus Bria Seran, MD, MPH, Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Nusa Tenggara Timur yang menyajikan hasil kegiatan Sister Hospital di Propinsi NTT. Program Sister Hospital merupakan bagian dari Kebijakan Revolusi KIA yang dicanangkan oleh Pemerintah Daerah Propinsi NTT, dalam rangka percepatan penurunan angka kematian Ibu, Bayi dan Balita. Revolusi KIA, pada intinya memaksa para ibu hamil untuk melahirkan di fasilitas kesehatan, terutama di Puskesmas dan Rumah Sakit. Program Sister Hospital ini menitikberatkan kepada penyediaan pelayanan rujukan untuk komplikasi medis spesialistik. Sampai saat ini program ini mampu menurunkan angka kematian ibu di NTT secara signifikan, tetapi belum berdampak kepada angka kematian bayi dan balita. Sesi Paralel dua dimulai dengan presentasi dari Bapak Ir. Agustinus Bagio, M. MT (Bappeda Provinsi Papua). Beliau menyampaikan paparan berjudul Perencanaan Berbasis Bukti untuk Sektor KIA di Provinsi Papua. Pemaparan ini menjadi starting point untuk penyampaian materi selanjutnya. Pemaparan selanjutnya merupakan bentuk pembelajaran dari inisiatif perencanaan dan penganggran untuk sektor KIA. Materi tersebut antara lain District Team Problem Solving (DTPS) Nasional (Lukas C. Hermawan, M.Kes) dan Kota Kupang (Agustinus Hake), Integrated Microplanning untuk KIA di Provinsi Papua (dr. Agnes Ang), ASIA (Analisa Situasi Ibu dan Anak) (Hikmah, ST, Msi) dan ditutup dengan Dr. Arum Atmawikarta, MPH yang menyampaikan Millenium Acceleration Framework (MAF) UNDP.
Sesi Paralel dua dimulai dengan presentasi dari Bapak Ir. Agustinus Bagio, M. MT (Bappeda Provinsi Papua). Beliau menyampaikan paparan berjudul Perencanaan Berbasis Bukti untuk Sektor KIA di Provinsi Papua. Pemaparan ini menjadi starting point untuk penyampaian materi selanjutnya. Pemaparan selanjutnya merupakan bentuk pembelajaran dari inisiatif perencanaan dan penganggran untuk sektor KIA. Materi tersebut antara lain District Team Problem Solving (DTPS) Nasional (Lukas C. Hermawan, M.Kes) dan Kota Kupang (Agustinus Hake), Integrated Microplanning untuk KIA di Provinsi Papua (dr. Agnes Ang), ASIA (Analisa Situasi Ibu dan Anak) (Hikmah, ST, Msi) dan ditutup dengan Dr. Arum Atmawikarta, MPH yang menyampaikan Millenium Acceleration Framework (MAF) UNDP. ASIA menjadi salah satu bentuk pencapaian upaya perbaikan perencanaan. Tidak serta merta menyelesaikan masalah tetapi adanya ASIA dapat menajamkan kebijakan program implementasi yang lebih tepat sasaran. Hal ini sangat membantu Pemerintah Daerah dalam menentukan program kerja untuk penanganan masalah kesehatan. Setiap materi pemaparan pada sesi ini sangat menarik. Bahkan hingga di akhir sesi diskusi justru makin seru dengan respon dari para pembahas. Salah satu Pembahas yaitu dr. Azhar Jaya, SKM, MARS menyampaikan pendapatnya terkait Pekerjaan Rumah (PR) Penurunan AKI dan AKB seharusnya bukan menjadi tanggung jawab Kemenkes.
ASIA menjadi salah satu bentuk pencapaian upaya perbaikan perencanaan. Tidak serta merta menyelesaikan masalah tetapi adanya ASIA dapat menajamkan kebijakan program implementasi yang lebih tepat sasaran. Hal ini sangat membantu Pemerintah Daerah dalam menentukan program kerja untuk penanganan masalah kesehatan. Setiap materi pemaparan pada sesi ini sangat menarik. Bahkan hingga di akhir sesi diskusi justru makin seru dengan respon dari para pembahas. Salah satu Pembahas yaitu dr. Azhar Jaya, SKM, MARS menyampaikan pendapatnya terkait Pekerjaan Rumah (PR) Penurunan AKI dan AKB seharusnya bukan menjadi tanggung jawab Kemenkes. Launching hasil kajian kebijakan AIDS ini mengambil bagian klaster paralel diskusi oleh Pokja Kebijakan AIDS pada forum nasional jaringan peneliti kebijakan dan Kesehatan Indonesia ke-5 pada 24 September 2014. Hasil Kajian Kebijakan AIDS di Indonesia oleh PKMK FK UGM merupakan upaya untuk memetakan upaya penanggulangan AIDS selama 25 tahun terakhir. Penelitian ini mengambil 5 Kabupaten/kota sebagai fokus area yakni Sumatera Utara, Surabaya, Bali, Makasar dan Papua. Muhammad Suharni. MA mempresentasikan hasil kajian dengan pembahas oleh Prof. Dr. Irwanto (Atmajaya), Dr. Irwan Julianto (Wartawan Senior Kompas), dan dr. Nadia Tarmizi, M.Epid dari Subdit Kemenkes.
Launching hasil kajian kebijakan AIDS ini mengambil bagian klaster paralel diskusi oleh Pokja Kebijakan AIDS pada forum nasional jaringan peneliti kebijakan dan Kesehatan Indonesia ke-5 pada 24 September 2014. Hasil Kajian Kebijakan AIDS di Indonesia oleh PKMK FK UGM merupakan upaya untuk memetakan upaya penanggulangan AIDS selama 25 tahun terakhir. Penelitian ini mengambil 5 Kabupaten/kota sebagai fokus area yakni Sumatera Utara, Surabaya, Bali, Makasar dan Papua. Muhammad Suharni. MA mempresentasikan hasil kajian dengan pembahas oleh Prof. Dr. Irwanto (Atmajaya), Dr. Irwan Julianto (Wartawan Senior Kompas), dan dr. Nadia Tarmizi, M.Epid dari Subdit Kemenkes.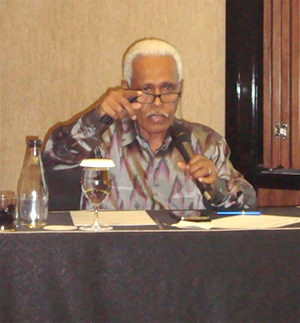 “Masalah stunting dan underweight di Indonesia cenderung naik di tahun 2013. Di saat Vietnam dan Thailand sudah melewati masalah tersebut, Indonesia masih belum bisa mengatasinya. Permasalahan terkait kematian neonatal, jumlah bayi meninggal juga cenderung meningkat. Belum lagi penyakit-penyakit tidak menular yang juga ikut meningkat” ujar Prof Abdul Razak Thaha.
“Masalah stunting dan underweight di Indonesia cenderung naik di tahun 2013. Di saat Vietnam dan Thailand sudah melewati masalah tersebut, Indonesia masih belum bisa mengatasinya. Permasalahan terkait kematian neonatal, jumlah bayi meninggal juga cenderung meningkat. Belum lagi penyakit-penyakit tidak menular yang juga ikut meningkat” ujar Prof Abdul Razak Thaha. Perhatian terhadap gizi pada 1000 hari pertama kehidupan juga mendapat dukungan dari Ir. Doddy izwardy, M.A, yang membawakan tentang Tantangan Kebijakan Gizi di Indonesia pada Era JKN. Mewujudkan generasi bebas masalah gizi, apalagi sejak 1000 hari pertama tentu bukan pekerjaan ahli gizi saja. Namun, perlu ada dukungan lintas profesi. Partisipasi perguruan tinggi dan sektor lain akan membantu intervensi sensitif untuk melengkapi intervensi spesifik yang sudah dilakukan.
Perhatian terhadap gizi pada 1000 hari pertama kehidupan juga mendapat dukungan dari Ir. Doddy izwardy, M.A, yang membawakan tentang Tantangan Kebijakan Gizi di Indonesia pada Era JKN. Mewujudkan generasi bebas masalah gizi, apalagi sejak 1000 hari pertama tentu bukan pekerjaan ahli gizi saja. Namun, perlu ada dukungan lintas profesi. Partisipasi perguruan tinggi dan sektor lain akan membantu intervensi sensitif untuk melengkapi intervensi spesifik yang sudah dilakukan. Sesi terakhir pada panel kebijakan gizi ini dibawakan oleh Dr. Dewi MDH, drg., Msi, membahas Analisis Kebijakan Gizi di Indonesia pada Era JKN. Tidak hanya memaparkan masalah gizi di tingkat masyarakat, namun juga memaparkan masalah gizi di RS. Masalah malnutrisi pada pasien rupanya berdampak pada peningkatan keparahan penyakit.
Sesi terakhir pada panel kebijakan gizi ini dibawakan oleh Dr. Dewi MDH, drg., Msi, membahas Analisis Kebijakan Gizi di Indonesia pada Era JKN. Tidak hanya memaparkan masalah gizi di tingkat masyarakat, namun juga memaparkan masalah gizi di RS. Masalah malnutrisi pada pasien rupanya berdampak pada peningkatan keparahan penyakit. Forum Nasional V Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia yang diselenggarakan di Trans Luxury Hotel Bandung untuk sesi paralel 1 Kebijakan Kesehatan Jiwa Masyarakat diawali dengan presentasi free paper oleh Sekar Ayu Paramita tentang survey kapasitas SDM yankeswa di setting non-spesialis di Provinsi Jawa Barat. Hanya 1.600 Puskesmas di Indonesia yang dapat menangani gangguan mental. Hal ini berhubungan dengan tingkat kapabilitas tenaga kesehatannya. Untuk itu dilakukan suatu penelitian di 11 kabupaten di Jawa Barat. Metodologinya yakni deskriptif dengan menyebarkan 1.008 kuesioner ke dokter dan perawat di Puskesmas. Hasilnya diketahui bahwa 77% responden merasa sudah mendapatkan pengetahuan tentang penanganan gangguan jiwa, namun hanya 30% yang kompeten menangani gangguan jiwa. Selain itu, penatalaksanaan pengobatan gangguan jiwa sudah banyak, namun persediaan obat masih sangat kurang. Dokter spesialis jiwa pun di rumah sakit masih sangat kurang. Sementara dokter primer yang ada masih kurang pengetahuannya tentang penanganan gangguan jiwa dan sistem rujukan untuk penanganan gangguan jiwa pun masih buruk.
Forum Nasional V Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia yang diselenggarakan di Trans Luxury Hotel Bandung untuk sesi paralel 1 Kebijakan Kesehatan Jiwa Masyarakat diawali dengan presentasi free paper oleh Sekar Ayu Paramita tentang survey kapasitas SDM yankeswa di setting non-spesialis di Provinsi Jawa Barat. Hanya 1.600 Puskesmas di Indonesia yang dapat menangani gangguan mental. Hal ini berhubungan dengan tingkat kapabilitas tenaga kesehatannya. Untuk itu dilakukan suatu penelitian di 11 kabupaten di Jawa Barat. Metodologinya yakni deskriptif dengan menyebarkan 1.008 kuesioner ke dokter dan perawat di Puskesmas. Hasilnya diketahui bahwa 77% responden merasa sudah mendapatkan pengetahuan tentang penanganan gangguan jiwa, namun hanya 30% yang kompeten menangani gangguan jiwa. Selain itu, penatalaksanaan pengobatan gangguan jiwa sudah banyak, namun persediaan obat masih sangat kurang. Dokter spesialis jiwa pun di rumah sakit masih sangat kurang. Sementara dokter primer yang ada masih kurang pengetahuannya tentang penanganan gangguan jiwa dan sistem rujukan untuk penanganan gangguan jiwa pun masih buruk. Pemaparan pokja KIA pada sesi ini memfokuskan pada program penurunan AKI, AKB dan AKABA. Beberapa langkah telah diilakukan, salah satunya melalui kerja sama dengan perusahaan. Hal ini seperti yang dipaparkan oleh Dwi Endah, MPH. Menurut Dwi kerjasama dengan CSR dengan pengadaan program mobil sehat sebagai suatu implementasi untuk menurunkan AKI, AKB dan persalinan nakes di daerah dengan akses sulit. Dengan adanya program ini cakupan persalinan nakes mencapai 100%. Selain dengan program mobil sehat penurunan AKI dan AKB dapat dilakukan dengan cara prediksi kematian neonatal dengan data rekam medik yang dipaparkan oleh Herlin Priscila Pay. Herlin memaparkan dengan rekam data medik dapat memprediksikan bagaimana resiko kematian ibu dan anak oada waktu persalinan.
Pemaparan pokja KIA pada sesi ini memfokuskan pada program penurunan AKI, AKB dan AKABA. Beberapa langkah telah diilakukan, salah satunya melalui kerja sama dengan perusahaan. Hal ini seperti yang dipaparkan oleh Dwi Endah, MPH. Menurut Dwi kerjasama dengan CSR dengan pengadaan program mobil sehat sebagai suatu implementasi untuk menurunkan AKI, AKB dan persalinan nakes di daerah dengan akses sulit. Dengan adanya program ini cakupan persalinan nakes mencapai 100%. Selain dengan program mobil sehat penurunan AKI dan AKB dapat dilakukan dengan cara prediksi kematian neonatal dengan data rekam medik yang dipaparkan oleh Herlin Priscila Pay. Herlin memaparkan dengan rekam data medik dapat memprediksikan bagaimana resiko kematian ibu dan anak oada waktu persalinan. Hari kedua Fornas V JKKI memiliki 3 pleno besar yang kemudian diikuti oleh sesi-sesi paralel di setiap kelompok kerja. Pokja pembiayaan kesehatan mengawalinya melalui sesi paralel 3 kebijakan pembiayaan yang dimoderatori oleh Dr. Felix Kasim, dr., M.Kes. Presentasi pertama menjelaskan tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan SJKN oleh BPJS di provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014. Menurut Rini Anggraeni, peningkatan peserta mandiri lebih dari 100% dan diikuti adanya kolaborasi antara fasilitas kesehatan primer milik pemerintah dan swasta. Faskes tingkat lanjut justru sudah mencukupi tetapi tidak disertai dengan ketersediaan obat yang memadai. Upaya yang Rini usulkan antara lain : menambah faskes tingkat pertama, redistribusi peserta terdaftar, dan mengurangi workload rumah sakit. Dukungan dari asosiasi faskes memegang peranan penting dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan JKN.
Hari kedua Fornas V JKKI memiliki 3 pleno besar yang kemudian diikuti oleh sesi-sesi paralel di setiap kelompok kerja. Pokja pembiayaan kesehatan mengawalinya melalui sesi paralel 3 kebijakan pembiayaan yang dimoderatori oleh Dr. Felix Kasim, dr., M.Kes. Presentasi pertama menjelaskan tentang monitoring dan evaluasi pelaksanaan SJKN oleh BPJS di provinsi Sulawesi Selatan tahun 2014. Menurut Rini Anggraeni, peningkatan peserta mandiri lebih dari 100% dan diikuti adanya kolaborasi antara fasilitas kesehatan primer milik pemerintah dan swasta. Faskes tingkat lanjut justru sudah mencukupi tetapi tidak disertai dengan ketersediaan obat yang memadai. Upaya yang Rini usulkan antara lain : menambah faskes tingkat pertama, redistribusi peserta terdaftar, dan mengurangi workload rumah sakit. Dukungan dari asosiasi faskes memegang peranan penting dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan JKN. Pada hari kedua Forum Nasional V Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia 2014 diselenggarakan sesi paralel dari Pokja Kebijakan HIV/AIDS, dengan tema Strategi dan Aksi Nasional Penanggulangan AIDS 2015-2019. Dr. Suriadi Gunawan, MPH mewakili Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) menyampaikan materi dengan judul “Strategi dan Rencana Aksi Nasional dalam Rangka Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia”. Para pembahas materi tersebut, terdiri dari Setia Perdana dari GWL-Ina, Aldo Napitupulu dari OPSI, Dr. Trijoko Yudopuspito MSc.PH dari Subdit AIDS Kemenkes dan Hersumpana, MA dari PKMK FK UGM.
Pada hari kedua Forum Nasional V Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia 2014 diselenggarakan sesi paralel dari Pokja Kebijakan HIV/AIDS, dengan tema Strategi dan Aksi Nasional Penanggulangan AIDS 2015-2019. Dr. Suriadi Gunawan, MPH mewakili Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN) menyampaikan materi dengan judul “Strategi dan Rencana Aksi Nasional dalam Rangka Pelaksanaan Pencegahan dan Penanggulangan HIV dan AIDS di Indonesia”. Para pembahas materi tersebut, terdiri dari Setia Perdana dari GWL-Ina, Aldo Napitupulu dari OPSI, Dr. Trijoko Yudopuspito MSc.PH dari Subdit AIDS Kemenkes dan Hersumpana, MA dari PKMK FK UGM. Pada hari kedua ini, sesi paralel pokja gizi lebih banyak menyoroti tentang gizi pada anak, meskipun ada juga topik lain yang cukup menarik seperti penggunaan teknologi untuk mengukur asupan gizi. Sesi pertama membahas mengenai pengambilan keputusan dalam pengaturan pemberian makan saat anak diare. Sesuai dengan standar pemberian makanan pada anak diare tetap dilakukan bahkan dengan frekuensi tambah dengan memberi nasi dan asupan makanan bergizi lainnya. Namun faktanya malah bertolak belakang dimana para ibu kurang berusaha untuk memberi makanan saat anak diare karena anak sulit untuk makan sehingga hanya diberi ASI dan snack sehingga asupan gizi menjadi berkurang.
Pada hari kedua ini, sesi paralel pokja gizi lebih banyak menyoroti tentang gizi pada anak, meskipun ada juga topik lain yang cukup menarik seperti penggunaan teknologi untuk mengukur asupan gizi. Sesi pertama membahas mengenai pengambilan keputusan dalam pengaturan pemberian makan saat anak diare. Sesuai dengan standar pemberian makanan pada anak diare tetap dilakukan bahkan dengan frekuensi tambah dengan memberi nasi dan asupan makanan bergizi lainnya. Namun faktanya malah bertolak belakang dimana para ibu kurang berusaha untuk memberi makanan saat anak diare karena anak sulit untuk makan sehingga hanya diberi ASI dan snack sehingga asupan gizi menjadi berkurang. Lain halnya dengan dr. Nova, dr. Eka Viora SpKJ menyorot hubungankesehatn jiwa dengan penyakit. Gangguan jiwa sumbangan terbesar beban penyakit. Ada warning dari WHO bahwa depresi adalah krisis global. Sehingga perlu perhatian terhadap kesehatan jiwa agar depresi tidak mempengaruhi sistem kesehatan. dalam MDG’s 4 dan 5 tahun 2009-2015 kurang diperhatikan kesehatan jiwa karena secara langsung tidak berpengaruh terhadap penurunan angka kematian ibu dan bayi. Sementara di lain tempat, hasil penelitian di Cina, India menunjukkan adanya hubunga kesehatan jiwa dengan angkan kematian ibu dan bayi.
Lain halnya dengan dr. Nova, dr. Eka Viora SpKJ menyorot hubungankesehatn jiwa dengan penyakit. Gangguan jiwa sumbangan terbesar beban penyakit. Ada warning dari WHO bahwa depresi adalah krisis global. Sehingga perlu perhatian terhadap kesehatan jiwa agar depresi tidak mempengaruhi sistem kesehatan. dalam MDG’s 4 dan 5 tahun 2009-2015 kurang diperhatikan kesehatan jiwa karena secara langsung tidak berpengaruh terhadap penurunan angka kematian ibu dan bayi. Sementara di lain tempat, hasil penelitian di Cina, India menunjukkan adanya hubunga kesehatan jiwa dengan angkan kematian ibu dan bayi. Ir. Hadadi dari ASDA III memberikan fakta spesifik tentang masalah kesehatan Jiwa di Indonesia khususnya di bandung. Pemerintah kota telah bekerja sama dengan perguruan tinggi UNPAD untuk meningkatkan layanan kesehatn Jiwa. Berbagai kegiatan untuk pengembangan kesehatan jiwa seperti Revitasiasi SDM. Jumlah SDM kesehatan jiwa diharapkan ada mulai layanan primer sehingga usaha promotif dan preventif bisa dilakukan.
Ir. Hadadi dari ASDA III memberikan fakta spesifik tentang masalah kesehatan Jiwa di Indonesia khususnya di bandung. Pemerintah kota telah bekerja sama dengan perguruan tinggi UNPAD untuk meningkatkan layanan kesehatn Jiwa. Berbagai kegiatan untuk pengembangan kesehatan jiwa seperti Revitasiasi SDM. Jumlah SDM kesehatan jiwa diharapkan ada mulai layanan primer sehingga usaha promotif dan preventif bisa dilakukan. Paralel Kebijakan Pendidikan SDM Kesehatan dipimpin oleh moderator Sari Puspa Dewi, dr., MPHE. Membuka sesi ini, moderator menekankan bahwa pokja SDM Kesehatan adalah pokja yang baru terbentuk sehingga diharapkan akan dapat memberikan kontribusi terhadap tenaga kesehatan sehingga tidak akan terjadi “pelayanan kesehatan jelek karena tenaga kesehatan jelek”.
Paralel Kebijakan Pendidikan SDM Kesehatan dipimpin oleh moderator Sari Puspa Dewi, dr., MPHE. Membuka sesi ini, moderator menekankan bahwa pokja SDM Kesehatan adalah pokja yang baru terbentuk sehingga diharapkan akan dapat memberikan kontribusi terhadap tenaga kesehatan sehingga tidak akan terjadi “pelayanan kesehatan jelek karena tenaga kesehatan jelek”.