21 Juli 2025
Quality and Demand in Mixed Primary Health Care Systems: Evidence from the Soweto Primary Care Study
Comparing the Quality and Efficiency of Primary Care Providers in Soweto. A Standardised Patient Audit
 Blaauw menyatakan studi ini menggambarkan penyedia layanan milik pemerintah maupun swasta. Studi ini mengambil studi untuk beberapa penyedia layanan kesehatan. Studi menemukan bahwa kualitas teknis penyedia layanan rendah di semua penyedia layanan di tingkat publik dan swasta yang hanya 40% kasus ditangani sesuai pedoman berbasis bukti. Dokter umum swasta sedikit lebih unggul (45.2% penanganan benar) dibandingkan klinik publik (38.1%) dan MLW swasta (37.4%).
Blaauw menyatakan studi ini menggambarkan penyedia layanan milik pemerintah maupun swasta. Studi ini mengambil studi untuk beberapa penyedia layanan kesehatan. Studi menemukan bahwa kualitas teknis penyedia layanan rendah di semua penyedia layanan di tingkat publik dan swasta yang hanya 40% kasus ditangani sesuai pedoman berbasis bukti. Dokter umum swasta sedikit lebih unggul (45.2% penanganan benar) dibandingkan klinik publik (38.1%) dan MLW swasta (37.4%).
Manajemen kasus PPD relatif baik, tetapi pengujian dahak untuk TB sangat kurang. Patient-centredness lebih baik di penyedia swasta, sementara klinik publik kurang dalam aspek ini. Namun, penyedia swasta (khususnya GP) menunjukkan inefisiensi signifikan. Penyedia layanan swasta meresepkan lebih banyak obat (+1.441) dari penyedia layanan publik, terutama yang tidak perlu. Untuk biaya total obat lebih tinggi (R30.442) dari pada penyedia layanan publik, termasuk obat tidak tepat (R13.136). Pada penggunaan obat generik lebih rendah (-6.6%) dari penyedia layanan publik dan klinik MLW swasta juga meresepkan lebih banyak obat, tetapi biaya obat tidak tepat lebih rendah (R-4.967).
Terdapat know-do gap serius dalam kualitas teknis di semua sektor PHC. Penyedia swasta, meski lebih patient-centred, cenderung boros dan kurang efisien. Peningkatan kualitas teknis, efisiensi, dan patient-centredness di semua penyedia PHC—melalui model kontrak NHI yang mendorong nilai (value)—penting untuk kesetaraan hasil kesehatan di Afrika Selatan.
Examining Patient Choice and the Role of Quality Information in Healthcare Markets in South Africa
 Stacee mengatakan bahwa reformasi kesehatan berbasis penyedia swasta—seperti skema Asuransi Kesehatan Nasional (JKN) di Afrika Selatan—mengasumsikan kompetisi pasar akan meningkatkan kualitas dan efisiensi. Namun demikian hal in tergantung pada respons permintaan terhadap kualitas di pasar layanan kesehatan kompleks. Hal ini terjadi karena kualitas pelayanan masih sulit untuk dinilai. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi: (1) faktor penentu pilihan penyedia layanan kesehatan (kualitas dengan kedekatan/jenis penyedia), dan (2) dampak informasi kualitas terhadap pilihan pasien.
Stacee mengatakan bahwa reformasi kesehatan berbasis penyedia swasta—seperti skema Asuransi Kesehatan Nasional (JKN) di Afrika Selatan—mengasumsikan kompetisi pasar akan meningkatkan kualitas dan efisiensi. Namun demikian hal in tergantung pada respons permintaan terhadap kualitas di pasar layanan kesehatan kompleks. Hal ini terjadi karena kualitas pelayanan masih sulit untuk dinilai. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi: (1) faktor penentu pilihan penyedia layanan kesehatan (kualitas dengan kedekatan/jenis penyedia), dan (2) dampak informasi kualitas terhadap pilihan pasien.
Studi menggunakan pendekatan eksperimen lapangan yang melibatkan kurang lebih 850 rumah tangga di Soweto dengan akses gratis kepada jaringan kecil penyedia publik/swasta selama 3 bulan. Model pilihan yang dipilih dianalisis berdasarkan karakteristik penyedia layanan yaitu jarak, kualitas (persepsi), tipe (dokter/swasta), dan kategori (perawat/dokter). Pada fase kedua (2 bulan tambahan) studi, separuh klaster secara acak menerima informasi tentang 2 penyedia berkualitas terbaik.
Hasil studi utama menunjukkan bahwa: Pertama, jarak mengalahkan kualitas dan kedekatan geografis menjadi faktor dominan dengan elastisitas jarak: 0.11 km. Penyedia swasta dianggap lebih berkualitas (persepsi) yaitu 93% rumah tangga (area kontrol) memilih klinik publik terdekat meski kualitasnya dinilai rendah. Kedua, Informasi yang kualitas tidak mengubah perilaku. Pada kelompok ini yang menerima informasi tentang penyedia terbaik tetap memilih penyedia terdekat (bukan yang berkualitas lebih tinggi). Respons permintaan terhadap kualitas tidak elastis. Ketiga, hasil ini menunjukkan bahwa overuse bernilai rendah yang berarti bahwa akses gratis dapat meningkatkan kunjungan kesehatan sebesar 53%, namun hal ini didominasi oleh low-value visits dengan rasio 3:1 berbanding dengan high-value visit, terutama di penyedia swasta.
Hal ini menunjukkan bahwa temuan mempertanyakan asumsi efisiensi pasar di sektor kesehatan dalam reformasi JKN Afrika Selatan. Ketidakefektifan informasi kualitas dan dominasi faktor jarak mengindikasikan bahwa perlunya intervensi pasokan (supply-side), seperti penempatan strategis penyedia dan insentif berbasis kualitas. Hal ini untuk mendorong efisiensi alokatif pada peneydia layanan baik ditingkat publik maupun swasta.
Free Access, Indirect Barriers and Healthcare Efficiency: Experimental Evidence from Soweto
 Mylene Lagarde menyatakan bahwa studi ini mengevaluasi dampak akses ke penyedia layanan kesehatan primer (PHC) swasta di Soweto terhadap pola pemanfaatan layanan kesehatan, dengan fokus pada peran jarak geografis. Metode yang diapaki adalah randomized controlled trial (RCT) terhadap 1.400 rumah tangga berpenghasilan rendah (memiliki anak di bawah 6 tahun tanpa asuransi swasta), dan membandingkan tiga kelompok yaitu kelompok kontrol (akses publik standar), kelompok dengan akses ke penyedia swasta terdekat (rata-rata 1.79 km), dan kelompok dengan akses ke penyedia swasta lebih jauh (rata-rata 6.69 km). Dalam studi dijelaskan bahawa kartu kesehatan memberikan akses gratis ke penyedia swasta selama tiga bulan. Gejala penyakit dan kunjungan dicatat dalam pictorial diary, kemudian dianalisis menggunakan pedoman WHO (c-IMCI) untuk mengidentifikasi kunjungan tepat, tidak perlu, atau tidak bermanfaat.
Mylene Lagarde menyatakan bahwa studi ini mengevaluasi dampak akses ke penyedia layanan kesehatan primer (PHC) swasta di Soweto terhadap pola pemanfaatan layanan kesehatan, dengan fokus pada peran jarak geografis. Metode yang diapaki adalah randomized controlled trial (RCT) terhadap 1.400 rumah tangga berpenghasilan rendah (memiliki anak di bawah 6 tahun tanpa asuransi swasta), dan membandingkan tiga kelompok yaitu kelompok kontrol (akses publik standar), kelompok dengan akses ke penyedia swasta terdekat (rata-rata 1.79 km), dan kelompok dengan akses ke penyedia swasta lebih jauh (rata-rata 6.69 km). Dalam studi dijelaskan bahawa kartu kesehatan memberikan akses gratis ke penyedia swasta selama tiga bulan. Gejala penyakit dan kunjungan dicatat dalam pictorial diary, kemudian dianalisis menggunakan pedoman WHO (c-IMCI) untuk mengidentifikasi kunjungan tepat, tidak perlu, atau tidak bermanfaat.
Hasil studi ini menunjukkan bahwa pertama, terjadi penginkatan utilisasi. Hal ini terjadi karena akses gratis ke penyedia swasta meningkatkan kunjungan kesehatan sebesar 53%, terutama di kelompok penyedia terdekat dengan persentase (+38 poin) untuk kelompok jauh sebesar (+17 poin). Kedua, pada hasil lainnya menunjukkan bahwa ada efisiensi namun tidak optimal. Hal ini digambarkan dengan adanya kunjungan tepat meningkat 2 kali, namun ini diimbangi oleh peningkatan tajam pada kunjungan yang tidak perlu dengan rasio 3:1. Pada kunjungan tidak bermanfaat (underuse) tetap tinggi (tidak ada perubahan signifikan). Ketiga, ada pengaruh jarak, dimana jarak mengurangi kedua jenis kunjungan dengan elastisitas yaitu 0.13 untuk nilai yang rendah dan 0.09 untuk *nilai yang tinggi. Keempat, terkait dengan biaya, pada pengeluaran biaya farmasi menagalami penuruan, namun biaya transportasi tetap naik, khususnya pada kelompok yang jauh dari jaringa penyedia layanan.
Reportase
M Faozi Kurniawan (PKMK UGM)
22 Juli 2025
Understanding Mental Health Prevalence, Service Use and Economic Consequences
Beban gangguan kesehatan mental, terutama kecemasan dan depresi, meningkat di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (LMIC), namun prevalensi dan konsekuensinya masih kurang dipahami. Sesi ini berfokus pada Indonesia, menyoroti tantangan kesehatan masyarakat yang berkembang dari gangguan kesehatan mental dan memberikan bukti untuk menginformasikan kebijakan, penyusunan rencana pelayanan kesehatan, dan intervensi yang dibutuhkan.
Orang dengan penyakit mental di Indonesia ditengarai menghadapi hambatan yang signifikan untuk mengakses perawatan, termasuk stigma, isolasi sosial, keterbatasan ketersediaan penyedia layanan kesehatan, dan rendahnya kesadaran kesehatan mental. Bukti saat ini tentang prevalensi kesehatan mental dan pemanfaatan perawatan kesehatan terutama bergantung pada data survei dan surveilans, dengan penggunaan data berbasis register yang terbatas. Oleh karena itu, berbagai penelitian tambahan dengan sumber data yang berbeda diperlukan untuk merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran.
 Laura Anselmi (University of Manchester) melakukan penelitian yang menganalisis data dari sampel Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS), yang mewakili 1% individu yang diasuransikan (data tahun 2015-2020) , untuk menilai prevalensi penyakit mental, karakteristik pasien, dan pemanfaatan perawatan kesehatan. Temuan ini dibandingkan dengan data dari RISKESDAS untuk mengidentifikasi kesenjangan dari kondisi kesehatan mental yang dilaporkan sendiri dan didiagnosis.
Laura Anselmi (University of Manchester) melakukan penelitian yang menganalisis data dari sampel Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS), yang mewakili 1% individu yang diasuransikan (data tahun 2015-2020) , untuk menilai prevalensi penyakit mental, karakteristik pasien, dan pemanfaatan perawatan kesehatan. Temuan ini dibandingkan dengan data dari RISKESDAS untuk mengidentifikasi kesenjangan dari kondisi kesehatan mental yang dilaporkan sendiri dan didiagnosis.
Dengan menggunakan data sampel BPJS (2015–2020), prevalensi penyakit jiwa dilacak berdasarkan usia, jenis kelamin, dan provinsi, dengan statistik deskriptif tentang pemanfaatan kesehatan. Regresi logistik digunakan untuk menilai hubungan antara diagnosis penyakit mental dan karakteristik individu seperti jenis kelamin, usia, status perkawinan, segmentasi asuransi, dan provinsi. Temuan prevalensi dan penggunaan layanan dibandingkan dengan data RISKESDAS untuk mengevaluasi kesenjangan antara penyakit mental yang dilaporkan sendiri (self-reported) dengan penyakit mental yang didiagnosis.
Analisis regional menunjukkan bahwa kemungkinan untuk didiagnosis bervariasi antar Provinsi, mengindikasikan adanya perbedaan akses ke pelayanan yang menyediakan diagnosis. Prevalensi depresi yang dilaporkan sendiri pada RISKESDAS (6,1%) jauh lebih tinggi daripada tingkat yang didiagnosis pada data BPJS (0,04%). Namun, kesenjangannya berkurang untuk kasus depresi yang diobati (0,55% vs 0,05%).
Temuan ini menyoroti perlunya mengatasi kesenjangan regional dan demografis dalam diagnosis dan perawatan kesehatan mental di Indonesia. Kontras yang mencolok antara depresi yang dilaporkan sendiri dan didiagnosis menggarisbawahi pentingnya memperluas akses ke layanan kesehatan mental dan meningkatkan kapasitas diagnostik. Pembuat kebijakan harus memprioritaskan wilayah dan kelompok dengan kebutuhan tinggi yang belum terpenuhi, yaitu pekerja non-penerima upah (sektor informal), laki-laki (yang secara umum terbukti memiliki prevalensi lebih tinggi) khususnya di usia lebih dari 50 tahun. Selain itu, kebijakan berpendekatan system diperlukan di provinsi-provinsi tertentu yang memiliki kecenderungan kurangnya penyakit mental terdiagnosis untuk memastikan perawatan kesehatan mental yang setara.
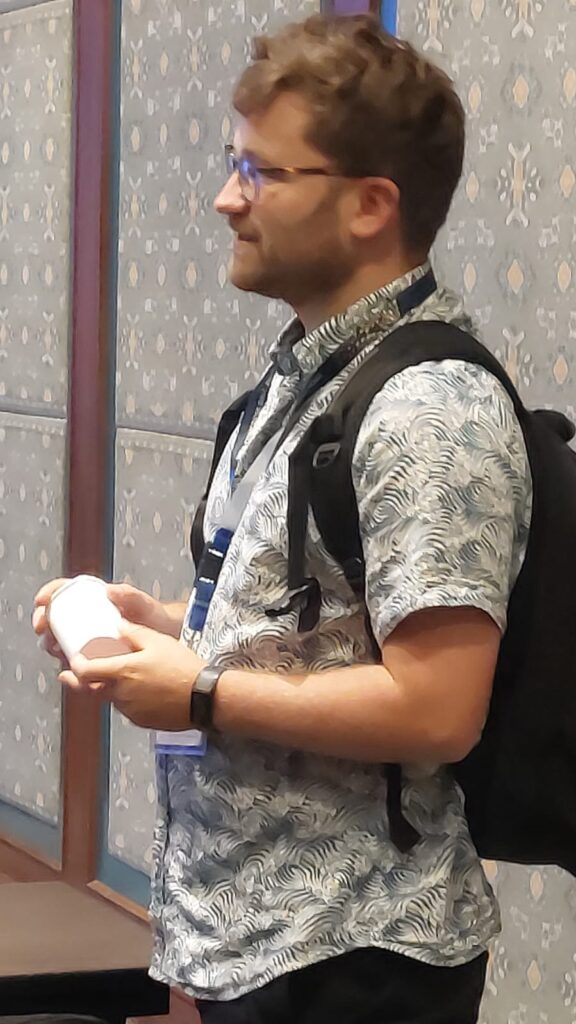 Kesehatan mental memiliki dampak ekonomi negative terhadap seseorang karena memengaruhi kemampuannya untuk bekerja. Jon Gibson (Universitas Manchester) melakukan pendalaman dengan melakukan segregasi data lebih jauh untuk melihat dampak dari Kesehatan mental terhadap produktivitas. Penelitiannya menunjukkan bahwa kesehatan mental secara signifikan memengaruhi produktivitas. Depresi dan kecemasan meningkatkan kemungkinan ketidakhadiran dan presenteeisme, meskipun efeknya bervariasi menurut jenis pekerjaan. Namun, dampaknya (ketidakhadiran) sedikit lebih kecil di sektor formal, dibandingkan dengan kategori pekerjaan lainnya.
Kesehatan mental memiliki dampak ekonomi negative terhadap seseorang karena memengaruhi kemampuannya untuk bekerja. Jon Gibson (Universitas Manchester) melakukan pendalaman dengan melakukan segregasi data lebih jauh untuk melihat dampak dari Kesehatan mental terhadap produktivitas. Penelitiannya menunjukkan bahwa kesehatan mental secara signifikan memengaruhi produktivitas. Depresi dan kecemasan meningkatkan kemungkinan ketidakhadiran dan presenteeisme, meskipun efeknya bervariasi menurut jenis pekerjaan. Namun, dampaknya (ketidakhadiran) sedikit lebih kecil di sektor formal, dibandingkan dengan kategori pekerjaan lainnya.
Dengan kata lain, pekerja di sektor formal lebih terlindungi dari Kesehatan mental yang buruk dalam hal dampak produktivitas, kemungkinan besar karena adanya kebijakan dan sistem pendukung di tempat kerja yang terstruktur. Temuan ini menekankan pentingnya intervensi kesehatan mental di tempat kerja, dan perlunya perhatian lebih untuk mengupayakan tersedianya system dukungan serupa untuk pekerja sektor informal dan pengangguran, untuk mengatasi kehilangan produktivitas yang terkait dengan ketidakhadiran dan presenteeisme. Hal ini penting dilakukan untuk melindungi mereka yang khususnya bekerja sebagai kepala keluarga untuk menjamin kelangsungan hidup keluarga.
 Asri Maharani (University of Manchester) mengeksplorasi aspek lain dari kesehatan mental. Studinya menyelidiki perilaku pencarian, pemanfaatan, dan pengeluaran out-of-pocket (OOP) untuk perawatan kesehatan mental (mental health disorder/MHD) di kelompok usia dewasa di Indonesia dengan melakukan survei terhadap 19.236 orang dewasa berusia 18+ tahun pada bulan Juli dan Oktober 2023.
Asri Maharani (University of Manchester) mengeksplorasi aspek lain dari kesehatan mental. Studinya menyelidiki perilaku pencarian, pemanfaatan, dan pengeluaran out-of-pocket (OOP) untuk perawatan kesehatan mental (mental health disorder/MHD) di kelompok usia dewasa di Indonesia dengan melakukan survei terhadap 19.236 orang dewasa berusia 18+ tahun pada bulan Juli dan Oktober 2023.
Hasilnya menunjukkan bahwa sekitar 2.119 (11%) responden mencari perawatan kesehatan mental, dengan 615 orang menerima perawatan rawat jalan dan 39 orang menerima perawatan rawat inap. Rata-rata biaya OOP adalah Rp140.359 untuk pelayanan rawat jalan dan Rp1.372.000 untuk pelayanan rawat inap.
Hanya 36% pengguna rawat jalan dan 56% pengguna rawat inap yang menggunakan asuransi kesehatan, dengan asuransi kesehatan sosial (JKN) menjadi asuransi yang paling umum digunakan. Kemungkinan MHD diidentifikasi pada 849 (4,42%) responden dengan depresi, 2.339 (12,17%) dengan kecemasan, dan 602 (3,13%) dengan keduanya. Perilaku pencarian bantuan lebih sering dilakukan oleh mereka yang memiliki kemungkinan MHD (19%) dibandingkan dengan yang tidak memiliki (10%), dan biaya OOP untuk perawatan Kepemilikan asuransi (khususnya JKN), usia yang lebih tua, jenis kelamin perempuan, dan berada di kuintil terkaya, juga dikaitkan dengan peluang yang lebih tinggi untuk mencari bantuan.
Hal ini mengindikasikan bahwa gangguan kesehatan mental meningkatkan pemanfaatan perawatan kesehatan dan biaya OOP, namun tetap ada ketidaksetaraan. Orang yang lebih kaya dan mereka yang memiliki asuransi lebih mungkin mengakses perawatan kesehatan mental. Kebijakan untuk memperluas cakupan asuransi Kesehatan akan meningkatkan akses ke perawatan yang terjangkau, dan mengatasi kesenjangan. Namun ini harus diimbangi dengan peningkatan investasi dalam intervensi pencegahan, promosi, dan pengobatan.
Manajemen dan pemulihan yang efektif untuk individu dengan gangguan kesehatan mental bergantung pada perawatan kesehatan mental yang tepat. Di Indonesia, layanan kesehatan mental disediakan melalui pengaturan perawatan psikiatri dan non-psikiatri. Di Indonesia telah tersedia Pedoman Klasifikasi Diagnosis Gangguan Mental Indonesia III (berdasarkan ICD-10) yang memberikan kriteria diagnostik standar, namun sejauh mana pengaturan non-psikiatri mematuhi standar ini dan memberikan perawatan masih belum jelas.
 Sri Idaiani (University of Manchester) mencoba mengeksplorasi distribusi diagnosis kesehatan mental di tingkat layanan klinis (RS D, C, B, A dan RS khusus jiwa) dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pola dan jalur pengobatan (care pathway) di Indonesia. Sri menganalisis 4.335 kunjungan rawat jalan dengan diagnosis kode ICD-10 F yang tercatat dalam database Badan Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS-K) dari tahun 2019–2020. Data tersebut dikaitkan dengan informasi dari Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) 2019 tentang ketersediaan psikiater, psikolog klinis, dan rumah sakit jiwa.
Sri Idaiani (University of Manchester) mencoba mengeksplorasi distribusi diagnosis kesehatan mental di tingkat layanan klinis (RS D, C, B, A dan RS khusus jiwa) dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pola dan jalur pengobatan (care pathway) di Indonesia. Sri menganalisis 4.335 kunjungan rawat jalan dengan diagnosis kode ICD-10 F yang tercatat dalam database Badan Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS-K) dari tahun 2019–2020. Data tersebut dikaitkan dengan informasi dari Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) 2019 tentang ketersediaan psikiater, psikolog klinis, dan rumah sakit jiwa.
Sri menemukan sebagian besar pasien dengan gangguan kesehatan mental di Indonesia dirawat di RS khusus jiwa. Namun, diagnosis spesifik, seperti gangguan perkembangan psikologis, gangguan perilaku onset masa kanak-kanak, dan gangguan mental organik, ternyata lebih sering dikelola dalam pengaturan non-psikiatri (RS D,C,B,A) daripada di RS khusus jiwa. Perawatan juga lebih banyak dilakukan di RS A. Temuan ini mengungkapkan kesenjangan dalam sistem perawatan kesehatan mental Indonesia, terutama untuk kasus-kasus kompleks yang membutuhkan perawatan khusus. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan untuk memperkuat sistem rujukan dan meningkatkan akses ke spesialis kesehatan mental, yang akan menjadi sangat penting untuk meminimalkan kesenjangan ini.
Sesi ini menunjukkan bahwa di Indonesia masih terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi kesehatan mental yang didiagnosis dan dengan kondisi yang dilaporkan sendiri (self-reported), dan hal ini menggarisbawahi keterbatasan akses untuk dapat menyediakan layanan diagnosis kesehatan mental. Sesi ini juga membahas penggunaan klinik non-psikiatri untuk perawatan kesehatan mental, yang mencerminkan hambatan terhadap layanan khusus (klinik psikiatri) dan kebutuhan untuk memperkuat sistem perawatan. Konsekuensi ekonomi dari gangguan kesehatan mental dieksplorasi melalui dampaknya terhadap produktivitas di tempat kerja, dengan ketidakhadiran dan perilaku presenteeisme.
Studi ini berkontribusi dalam memahami kesehatan mental di Indonesia, menawarkan wawasan yang dapat menginformasikan pembuat kebijakan dan penyedia layanan kesehatan dalam mengatasi tantangan kesehatan mental dan meningkatkan outcome-nya dengan cara mendisain kebijakan yang setara dan inklusif untuk mendukung kesehatan mental. Hal lain yang juga penting dieksplorasi lebih lanjut adalah mengenai kualitas layanan dan juga kontinuitas layanan, serta pengayaan informasi melalui studi-studi kualitatif.
Reporter:
Shita Dewi (PKMK FKKMK UGM)


 Blaauw menyatakan studi ini menggambarkan penyedia layanan milik pemerintah maupun swasta. Studi ini mengambil studi untuk beberapa penyedia layanan kesehatan. Studi menemukan bahwa kualitas teknis penyedia layanan rendah di semua penyedia layanan di tingkat publik dan swasta yang hanya 40% kasus ditangani sesuai pedoman berbasis bukti. Dokter umum swasta sedikit lebih unggul (45.2% penanganan benar) dibandingkan klinik publik (38.1%) dan MLW swasta (37.4%).
Blaauw menyatakan studi ini menggambarkan penyedia layanan milik pemerintah maupun swasta. Studi ini mengambil studi untuk beberapa penyedia layanan kesehatan. Studi menemukan bahwa kualitas teknis penyedia layanan rendah di semua penyedia layanan di tingkat publik dan swasta yang hanya 40% kasus ditangani sesuai pedoman berbasis bukti. Dokter umum swasta sedikit lebih unggul (45.2% penanganan benar) dibandingkan klinik publik (38.1%) dan MLW swasta (37.4%). Stacee mengatakan bahwa reformasi kesehatan berbasis penyedia swasta—seperti skema Asuransi Kesehatan Nasional (JKN) di Afrika Selatan—mengasumsikan kompetisi pasar akan meningkatkan kualitas dan efisiensi. Namun demikian hal in tergantung pada respons permintaan terhadap kualitas di pasar layanan kesehatan kompleks. Hal ini terjadi karena kualitas pelayanan masih sulit untuk dinilai. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi: (1) faktor penentu pilihan penyedia layanan kesehatan (kualitas dengan kedekatan/jenis penyedia), dan (2) dampak informasi kualitas terhadap pilihan pasien.
Stacee mengatakan bahwa reformasi kesehatan berbasis penyedia swasta—seperti skema Asuransi Kesehatan Nasional (JKN) di Afrika Selatan—mengasumsikan kompetisi pasar akan meningkatkan kualitas dan efisiensi. Namun demikian hal in tergantung pada respons permintaan terhadap kualitas di pasar layanan kesehatan kompleks. Hal ini terjadi karena kualitas pelayanan masih sulit untuk dinilai. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi: (1) faktor penentu pilihan penyedia layanan kesehatan (kualitas dengan kedekatan/jenis penyedia), dan (2) dampak informasi kualitas terhadap pilihan pasien.  Mylene Lagarde menyatakan bahwa studi ini mengevaluasi dampak akses ke penyedia layanan kesehatan primer (PHC) swasta di Soweto terhadap pola pemanfaatan layanan kesehatan, dengan fokus pada peran jarak geografis. Metode yang diapaki adalah randomized controlled trial (RCT) terhadap 1.400 rumah tangga berpenghasilan rendah (memiliki anak di bawah 6 tahun tanpa asuransi swasta), dan membandingkan tiga kelompok yaitu kelompok kontrol (akses publik standar), kelompok dengan akses ke penyedia swasta terdekat (rata-rata 1.79 km), dan kelompok dengan akses ke penyedia swasta lebih jauh (rata-rata 6.69 km). Dalam studi dijelaskan bahawa kartu kesehatan memberikan akses gratis ke penyedia swasta selama tiga bulan. Gejala penyakit dan kunjungan dicatat dalam pictorial diary, kemudian dianalisis menggunakan pedoman WHO (c-IMCI) untuk mengidentifikasi kunjungan tepat, tidak perlu, atau tidak bermanfaat.
Mylene Lagarde menyatakan bahwa studi ini mengevaluasi dampak akses ke penyedia layanan kesehatan primer (PHC) swasta di Soweto terhadap pola pemanfaatan layanan kesehatan, dengan fokus pada peran jarak geografis. Metode yang diapaki adalah randomized controlled trial (RCT) terhadap 1.400 rumah tangga berpenghasilan rendah (memiliki anak di bawah 6 tahun tanpa asuransi swasta), dan membandingkan tiga kelompok yaitu kelompok kontrol (akses publik standar), kelompok dengan akses ke penyedia swasta terdekat (rata-rata 1.79 km), dan kelompok dengan akses ke penyedia swasta lebih jauh (rata-rata 6.69 km). Dalam studi dijelaskan bahawa kartu kesehatan memberikan akses gratis ke penyedia swasta selama tiga bulan. Gejala penyakit dan kunjungan dicatat dalam pictorial diary, kemudian dianalisis menggunakan pedoman WHO (c-IMCI) untuk mengidentifikasi kunjungan tepat, tidak perlu, atau tidak bermanfaat.  Laura Anselmi (University of Manchester) melakukan penelitian yang menganalisis data dari sampel Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS), yang mewakili 1% individu yang diasuransikan (data tahun 2015-2020) , untuk menilai prevalensi penyakit mental, karakteristik pasien, dan pemanfaatan perawatan kesehatan. Temuan ini dibandingkan dengan data dari RISKESDAS untuk mengidentifikasi kesenjangan dari kondisi kesehatan mental yang dilaporkan sendiri dan didiagnosis.
Laura Anselmi (University of Manchester) melakukan penelitian yang menganalisis data dari sampel Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS), yang mewakili 1% individu yang diasuransikan (data tahun 2015-2020) , untuk menilai prevalensi penyakit mental, karakteristik pasien, dan pemanfaatan perawatan kesehatan. Temuan ini dibandingkan dengan data dari RISKESDAS untuk mengidentifikasi kesenjangan dari kondisi kesehatan mental yang dilaporkan sendiri dan didiagnosis.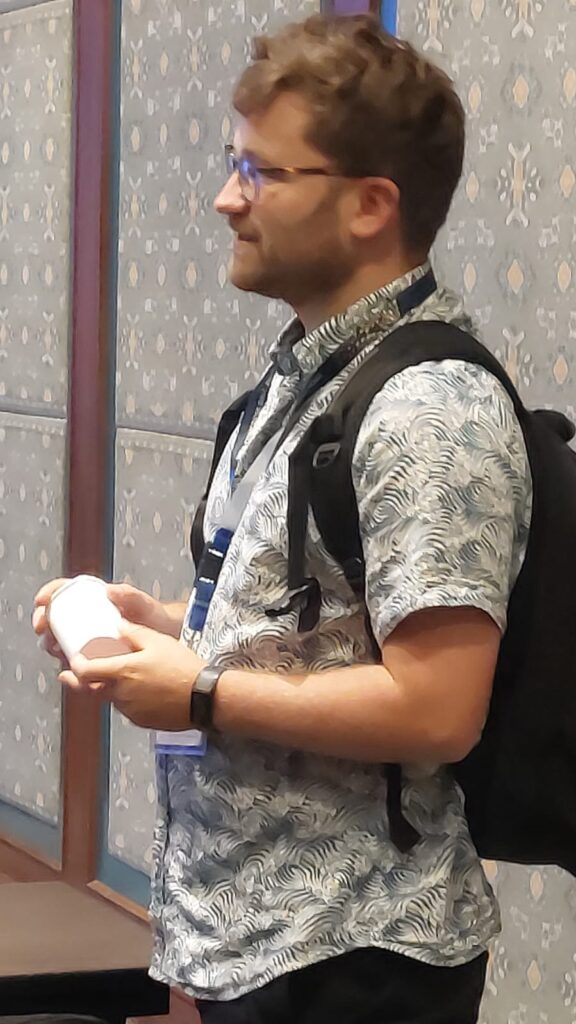 Kesehatan mental memiliki dampak ekonomi negative terhadap seseorang karena memengaruhi kemampuannya untuk bekerja. Jon Gibson (Universitas Manchester) melakukan pendalaman dengan melakukan segregasi data lebih jauh untuk melihat dampak dari Kesehatan mental terhadap produktivitas. Penelitiannya menunjukkan bahwa kesehatan mental secara signifikan memengaruhi produktivitas. Depresi dan kecemasan meningkatkan kemungkinan ketidakhadiran dan presenteeisme, meskipun efeknya bervariasi menurut jenis pekerjaan. Namun, dampaknya (ketidakhadiran) sedikit lebih kecil di sektor formal, dibandingkan dengan kategori pekerjaan lainnya.
Kesehatan mental memiliki dampak ekonomi negative terhadap seseorang karena memengaruhi kemampuannya untuk bekerja. Jon Gibson (Universitas Manchester) melakukan pendalaman dengan melakukan segregasi data lebih jauh untuk melihat dampak dari Kesehatan mental terhadap produktivitas. Penelitiannya menunjukkan bahwa kesehatan mental secara signifikan memengaruhi produktivitas. Depresi dan kecemasan meningkatkan kemungkinan ketidakhadiran dan presenteeisme, meskipun efeknya bervariasi menurut jenis pekerjaan. Namun, dampaknya (ketidakhadiran) sedikit lebih kecil di sektor formal, dibandingkan dengan kategori pekerjaan lainnya. Asri Maharani (University of Manchester) mengeksplorasi aspek lain dari kesehatan mental. Studinya menyelidiki perilaku pencarian, pemanfaatan, dan pengeluaran out-of-pocket (OOP) untuk perawatan kesehatan mental (mental health disorder/MHD) di kelompok usia dewasa di Indonesia dengan melakukan survei terhadap 19.236 orang dewasa berusia 18+ tahun pada bulan Juli dan Oktober 2023.
Asri Maharani (University of Manchester) mengeksplorasi aspek lain dari kesehatan mental. Studinya menyelidiki perilaku pencarian, pemanfaatan, dan pengeluaran out-of-pocket (OOP) untuk perawatan kesehatan mental (mental health disorder/MHD) di kelompok usia dewasa di Indonesia dengan melakukan survei terhadap 19.236 orang dewasa berusia 18+ tahun pada bulan Juli dan Oktober 2023. Sri Idaiani (University of Manchester) mencoba mengeksplorasi distribusi diagnosis kesehatan mental di tingkat layanan klinis (RS D, C, B, A dan RS khusus jiwa) dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pola dan jalur pengobatan (care pathway) di Indonesia. Sri menganalisis 4.335 kunjungan rawat jalan dengan diagnosis kode ICD-10 F yang tercatat dalam database Badan Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS-K) dari tahun 2019–2020. Data tersebut dikaitkan dengan informasi dari Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) 2019 tentang ketersediaan psikiater, psikolog klinis, dan rumah sakit jiwa.
Sri Idaiani (University of Manchester) mencoba mengeksplorasi distribusi diagnosis kesehatan mental di tingkat layanan klinis (RS D, C, B, A dan RS khusus jiwa) dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pola dan jalur pengobatan (care pathway) di Indonesia. Sri menganalisis 4.335 kunjungan rawat jalan dengan diagnosis kode ICD-10 F yang tercatat dalam database Badan Jaminan Kesehatan Nasional (BPJS-K) dari tahun 2019–2020. Data tersebut dikaitkan dengan informasi dari Riset Fasilitas Kesehatan (Rifaskes) 2019 tentang ketersediaan psikiater, psikolog klinis, dan rumah sakit jiwa.