- Topik Reportase
- Pilih Field
- Equitable and Sustainable Workforce Policies
- Innovations in the Payment and Delivery of Primary Care
- Demand & utilization of health services
- Economic evaluation of health and related care interventions
- Evaluation of policy, programs and health system performance
- Health beyond the health system
- Health care financing & expenditures
- Health, its valuation, distribution and economic consequences
- Supply and regulation of health services and products
21 Juli 2025
Innovations in the Payment and Delivery of Primary Care
Effects of Integrating Primary Care and Specialist Physician Practices Handout(s) available
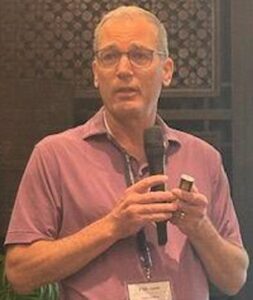 Laurence Baker menyatakan dalam pembukannya bahwa studi ini mengeksplorasi dampak integrasi vertikal antara praktik dokter umum (primary care) dan spesialis terhadap efisiensi sistem kesehatan di AS. Studi ini menggunakan data klaim dari data Medicare tahun 2006–2020 dari 181.075 peserta yang dilibatkan, penelitian ini memanfaatkan desain movers yaitu membandingkan perubahan pola penggunaan layanan dan biaya pada peserta yang berpindah wilayah residensi (Hospital Referral Region) sekaligus bertransisi antara praktik pelayanan dasar (primary care/PC) tunggal dan multidisiplin. Peneliti menggunakan metode Difference-in-Differences (DiD) dan event study untuk mengisolasi efek integrasi, dengan mengontrol karakteristik peserta (misal: usia, komorbiditas) dan tren temporal.
Laurence Baker menyatakan dalam pembukannya bahwa studi ini mengeksplorasi dampak integrasi vertikal antara praktik dokter umum (primary care) dan spesialis terhadap efisiensi sistem kesehatan di AS. Studi ini menggunakan data klaim dari data Medicare tahun 2006–2020 dari 181.075 peserta yang dilibatkan, penelitian ini memanfaatkan desain movers yaitu membandingkan perubahan pola penggunaan layanan dan biaya pada peserta yang berpindah wilayah residensi (Hospital Referral Region) sekaligus bertransisi antara praktik pelayanan dasar (primary care/PC) tunggal dan multidisiplin. Peneliti menggunakan metode Difference-in-Differences (DiD) dan event study untuk mengisolasi efek integrasi, dengan mengontrol karakteristik peserta (misal: usia, komorbiditas) dan tren temporal.
Hasil studi ini menunjukkan bahwa praktik multidisiplin (PC+spesialis) terkait dengan pengurangan biaya kesehatan tahunan sebesar 7,2% (±1,8%) dan penurunan pemanfaatan sumber daya secara signifikan dalam utilisasi layanan intensif. Peserta yang bertransisi ke praktik PC-tunggal menunjukkan peningkatan 11,3% pada rawat inap dan 9,6% penggunaan layanan pasca-akut (post-acute care). Namun sebaliknya, pada praktik multidisiplin menghasilkan 14,2% lebih sedikit kunjungan total dan peningkatan 6,5 poin persentase pada indikator pencegahan (Prevention Quality Indicators). Temuan ini konsisten dengan hipotesis yaitu integrasi mengurangi biaya transaksi dan perselisihan antar-spesialis karena adanya rujukan pasien.
Hasil ini juga bahwa menguatkan proposisi bahwa integrasi vertikal antara PC-spesialis berpotensi meningkatkan nilai (value) layanan kesehatan melalui efisiensi alokatif dan teknis. Namun, Baker menyatakan bahwa studi ini mengidentifikasi tantangan endogenisitas yaitu pemilihan praktik setelah perpindahan lokasi praktik, mungkin dipengaruhi faktor non-observabel (misal: preferensi peserta). Baker juga menyatakan bahwa akan ada implikasi kebijakan untuk mengadakan insentif dengan model praktik terintegrasi dalam sistem value-based care. Meskipun membutuhkan pendalaman lebih lanjut mengenai dampak pada pasar dan variasi efektivitas menurut ukuran praktik.
Private Equity Investments in Primary Care and Changes to Medicare Spending and Utilization
 Yashaswini Singh menjelaskan bahwa efek akuisisi praktik layanan primer (PC) oleh private equity (PE) terhadap pola utilisasi dan belanja Medicare di AS.Data klaim Medicare Part B tahun 2016–2022 digunakan dan peneliti juga melakukan identifikasi kepemilikan PE melalui PitchBook serta sumber data sekunder lainnya. Penelitian ini menganalisis kurang lebih 2.304 praktik PC yang diakuisisi PE. Desain studi yang digunakan adalan Difference-in-Differences (DiD) diterapkan dengan membandingkan praktik yang diakuisisi PE terhadap kelompok kontrol yang dipadankan (propensity score matching) berdasarkan volume layanan, lokasi, dan karakteristik pasien pra-akuisisi. Model regresi dengan fixed effects dokter dan kuartal digunakan untuk mengisolasi dampak akuisisi.
Yashaswini Singh menjelaskan bahwa efek akuisisi praktik layanan primer (PC) oleh private equity (PE) terhadap pola utilisasi dan belanja Medicare di AS.Data klaim Medicare Part B tahun 2016–2022 digunakan dan peneliti juga melakukan identifikasi kepemilikan PE melalui PitchBook serta sumber data sekunder lainnya. Penelitian ini menganalisis kurang lebih 2.304 praktik PC yang diakuisisi PE. Desain studi yang digunakan adalan Difference-in-Differences (DiD) diterapkan dengan membandingkan praktik yang diakuisisi PE terhadap kelompok kontrol yang dipadankan (propensity score matching) berdasarkan volume layanan, lokasi, dan karakteristik pasien pra-akuisisi. Model regresi dengan fixed effects dokter dan kuartal digunakan untuk mengisolasi dampak akuisisi.
Hasil studi ini menunjukkan bahwa akuisisi PE meningkatkan belanja Medicare per dokter sebesar 20% (±3,1%), didorong oleh peningkatan utilisasi layanan diagnostik (laboratorium: +24%) dan preventif (skrining: +18%). Setiap dokter menangani 17% lebih banyak pasien unik, namun diikuti fragmentasi perawatan—ditandai kenaikan 5% jumlah dokter umum berbeda dan 8% jumlah spesialis berbeda yang dikunjungi pasien. Meski utilisasi meningkat, tidak ada perbaikan outcome klinis: probabilitas kunjungan IGD (*ED visits*) dan rawat inap (*inpatient admissions*) tetap statis. Peningkatan beban biaya pasien (*out-of-pocket spending*) mencapai 15%.
Studi ini juga menjelaskan bahwa bahwa model bisnis PE yaitu yang berorientasi pada skalabilitas dan efisiensi operasional, berpotensi memicu supply-induced demand tanpa manfaat klinis jangka pendek. Pada akhirnya studi ini menujukkan bahwa terjadi fragmentasi perawatan yang merefleksikan bahwa risiko destabilisasi jejaring perawatan primer terjadi akibat pergantian dokter (physician turnover) dan insentif finansial yang tidak selaras atau tidak terintegrasi dengan baik.
Integrating Virtual Primary Care: Evidence and Learnings from Lower-Middle Income Countries
 Divya Srivastava menjelaskan bahwa studi ini menganalisis integrasi layanan kesehatan primer virtual (VPC) di lima negara berpenghasilan menengah-bawah (termasuk Indonesia) selama pandemi COVID-19. Studi ini menggunakan Delphi consensus exerciset dengan pakar kebijakan kesehatan. Beberapa hal teridentifikasi bahwa pertumbuhan VPC yang dipicu pandemi terjadi secara spontan di sektor swasta tanpa kerangka regulasi memadai. Tantangan utama mencakup: (1) absennya standar akreditasi penyedia, (2) kerentanan privasi data pasien, dan (3) kesenjangan digital yang memperparah ketidaksetaraan akses—di Indonesia, 72% pengguna VPC berasal dari kuintil pendapatan tertinggi.
Divya Srivastava menjelaskan bahwa studi ini menganalisis integrasi layanan kesehatan primer virtual (VPC) di lima negara berpenghasilan menengah-bawah (termasuk Indonesia) selama pandemi COVID-19. Studi ini menggunakan Delphi consensus exerciset dengan pakar kebijakan kesehatan. Beberapa hal teridentifikasi bahwa pertumbuhan VPC yang dipicu pandemi terjadi secara spontan di sektor swasta tanpa kerangka regulasi memadai. Tantangan utama mencakup: (1) absennya standar akreditasi penyedia, (2) kerentanan privasi data pasien, dan (3) kesenjangan digital yang memperparah ketidaksetaraan akses—di Indonesia, 72% pengguna VPC berasal dari kuintil pendapatan tertinggi.
Penelitian ini mengembangkan Standardized Integration Framework berbasis enam pilar yaitu pembiayaan, regulasi, interoperabilitas data, tata kelola privasi, keterlibatan tenaga kesehatan, dan pemerataan akses. Hasil penerapannya menunjukkan bahwa Fragmentasi Regulasi**: 80% negara sampel tidak memiliki payung hukum spesifik untuk kontrak VPC dalam sistem jaminan kesehatan nasional. Fasilitas kesehatan mengalami disparitas infrastruktur, 35% fasilitas kesehatan tingkat primer yang memiliki sistem informasi elektronik yang mendukung interoperabilitas VPC. Namun, risiko kesenjangan terjadi pada subsidi telemedisin terbatas yang mengakibatkan cakupan penduduk pedesaan hanya <15%.
Studi ini menggarisbawahi urgensi koordinasi sektor publik-swasta dalam pengembangan VPC. Rekomendasi kebijakan prioritas meliputi: (1) penyusunan pedoman akreditasi penyedia berbasis bukti, (2) integrasi VPC ke dalam paket manfaat jaminan kesehatan nasional dengan skema pembayaran berorientasi hasil (outcome-based), dan (3) investasi infrastruktur digital di daerah terpencil berbasis public-private partnership. Studi menekankan bahwa keberlanjutan VPC memerlukan pendekatan holistik yang mengatasi determinan sosial kesehatan—khususnya literasi digital dan keterjangkauan.
Unlocking Fiscal Autonomy: The Economic Impact of the BLUD Model on Strengthening Primary Health Care in Decentralized Indonesia
 Rooswanti Soeharno menjelaskan studi evaluasi terhadap piloting program dari UNICEF. Studi ini menjelaskan bahwa ada dampak model Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai respons terhadap tantangan desentralisasi kesehatan Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan mixed-methods, dengan menganalisis data kinerja 55 Puskesmas BLUD di Lombok Barat dan Lombok Timur tahun 2021–2023. Analisis datanya yaitu dengan membandingkan indikator pra-pasca intervensi UNICEF dan setelah terjadi intervensi. Intervensi mencakup yaitu (1) penguatan kapasitas tata kelola keuangan fiskal otonom, (2) pelatihan manajemen berbasis kinerja, dan (3) integrasi sistem informasi kesehatan (Satusehat). Kerangka evaluasi mengadopsi instrumen WHO-UNICEF PHCPI yang dimodifikasi.
Rooswanti Soeharno menjelaskan studi evaluasi terhadap piloting program dari UNICEF. Studi ini menjelaskan bahwa ada dampak model Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada Puskesmas di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai respons terhadap tantangan desentralisasi kesehatan Indonesia. Studi ini menggunakan pendekatan mixed-methods, dengan menganalisis data kinerja 55 Puskesmas BLUD di Lombok Barat dan Lombok Timur tahun 2021–2023. Analisis datanya yaitu dengan membandingkan indikator pra-pasca intervensi UNICEF dan setelah terjadi intervensi. Intervensi mencakup yaitu (1) penguatan kapasitas tata kelola keuangan fiskal otonom, (2) pelatihan manajemen berbasis kinerja, dan (3) integrasi sistem informasi kesehatan (Satusehat). Kerangka evaluasi mengadopsi instrumen WHO-UNICEF PHCPI yang dimodifikasi.
Hasil implementasi BLUD meningkatkan kapasitas fiskal dan kinerja layanan primer secara signifikan yaitu pertama terkait aspek keuangan. Puskemas yang mendapatkan alokasi APBD kesehatan mengalami peningkatan 8,1% di Lombok Barat dan 138% di Lombok Timur. Puskesmas juga mendapatkan pendapatan BLUD rata-rata Rp3 miliar/tahun. Kedua, kapasitas layanan, menunjukkan skor tata kelola yang mengalami kenaikan sebesar 35,1% dari 2,39 menjadi 3,23 poin. Hal ini menunjukkan bahwa rekrutmen 42 tenaga dokter kontrak untuk memenuhi rasio BPJS (1:5.000 penduduk) dapat memberikan dampak pelayanan dan kenaikan pemanfaatan puskesmas. Ketiga, untuk outcome kesehatan menunjukkan kepuasan pengguna layanan yang melonjak 25,1%, cakupan pengobatan TB juga meningkat 48,7%, dan life expectancy juga mengalami kenaikan sebesar 4,5 tahun.
Sebagai penutup, penelitian ini mungkin efektif, namun studi mengidentifikasi kendala sistematis yaitu adanya fragmentasi dalam sistem informasi kesehatan, regulasi pendukung terbatas, dan disparitas kapasitas SDM antarwilayah seperti Papua hanya 25% Puskesmas memenuhi standar tenaga kesehatan. Untuk itu dalam skala nasional dengan model BLUD perlu mengembangkan dashboard kinerja daerah yang terintegrasi, dan perlunya pelatihan digital untuk pemerataan kapasitas manajerial.
Accounting for Morbidity in Capitation Payments: A Person-Based Model for Primary Medical Care in England
 Laura Anselmi dalam studinya, peneliti mengembangkan model pembayaran kapitas berbasis morbiditas untuk layanan medis primer di Inggris. Hal ini bertujuan untuk menanggapi kelemahan formula Carr-Hill yang berlaku yang hanya mempertimbangkan usia, gender, dan deprivasi area. Data yang digunakan adalah data pseudonymised 12,6 juta pasien dari Clinical Practice Research Datalink Aurum (CPRD Aurum). Studi ini menganalisis beban kerja riil praktik umum melalui biaya konsultasi (dokter, perawat, asisten) dan frekuensi kunjungan tahun 2018–2019. Pendekatan dengan model regresi multivariat digunakan untuk menghitung workload weights dengan memasukkan tiga lapis variabel. Tiga lapis ini yaitu karakteristik demografis (usia, etnisitas, deprivasi indeks Index of Multiple Deprivation/IMD), dan diagnosa morbiditas (20 kondisi kronis Quality and Outcomes Framework/QOF, 152 kode ICD-10 rawat inap, 209 kondisi Caliber), serta practice fixed-effects untuk mengontrol variasi praktik.
Laura Anselmi dalam studinya, peneliti mengembangkan model pembayaran kapitas berbasis morbiditas untuk layanan medis primer di Inggris. Hal ini bertujuan untuk menanggapi kelemahan formula Carr-Hill yang berlaku yang hanya mempertimbangkan usia, gender, dan deprivasi area. Data yang digunakan adalah data pseudonymised 12,6 juta pasien dari Clinical Practice Research Datalink Aurum (CPRD Aurum). Studi ini menganalisis beban kerja riil praktik umum melalui biaya konsultasi (dokter, perawat, asisten) dan frekuensi kunjungan tahun 2018–2019. Pendekatan dengan model regresi multivariat digunakan untuk menghitung workload weights dengan memasukkan tiga lapis variabel. Tiga lapis ini yaitu karakteristik demografis (usia, etnisitas, deprivasi indeks Index of Multiple Deprivation/IMD), dan diagnosa morbiditas (20 kondisi kronis Quality and Outcomes Framework/QOF, 152 kode ICD-10 rawat inap, 209 kondisi Caliber), serta practice fixed-effects untuk mengontrol variasi praktik.
Hasil studi ini menjelaskan bahwa morbiditas sebesar 50% merupakan disparitas beban kerja terkait usia dan deprivasi. Pasien lanjut usia (>65 tahun) pada area yang sangat termarjinalkan (kuintil IMD 1) membutuhkan biaya 40% lebih tinggi (£154 vs £110 rerata nasional).
Implementasi model ini mengoreksi ketimpangan sistemik yaitu alokasi kapitas baru yang meningkatkan pembiayaan ke praktik pada area deprivasi tinggi sebesar £607,5 juta/tahun (+10,24%) dengan menyetarakan biaya per pasien miskin (£90,94) dengan masyarakat mampu (£80,84). Pendekatan ini mengakui beban kompleks passien komorbid dan deprivasi struktural terutama relevan untuk populasi aging society. Keterbatasan mencakup potensi unmet needs yang belum terekam dalam data diagnosis.
Reporter
M Faozi Kurniawan (PKMK UGM)
Pharmaceutical R&D and Pharmaceutical Shortages
Sesi ini dimoderatori oleh Yoko Ibuka dari Keio University, Jepang.
Presenter yang pertama adalah Ana Correa Ossa dari University College London, Inggris Raya. Krisis kekurangan obat di Inggris, Eropa, dan Amerika Serikat mencapai tingkat tertinggi dalam sejarah pada 2023, hal tersebut menyebabkan rumah sakit harus menggelar rapat darurat mingguan untuk mengatasi pasokan yang tidak stabil. Studi ini meneliti faktor-faktor penyebab kelangkaan obat, dan menemukan bahwa obat dengan harga rendah memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk mengalami kekurangan pasokan. Temuan kualitatif dari lokakarya bersama pemangku kepentingan di Eropa menunjukkan bahwa kelangkaan juga dipicu oleh sistem pengadaan yang terlalu fokus pada harga murah, kurangnya produsen alternatif, serta keterbatasan regulasi dalam mengganti atau berbagi stok. Untuk mengatasi hal ini, para ahli merekomendasikan reformasi dalam sistem pengadaan, perluasan kapasitas produksi lokal, dan pengembangan sistem data real-time untuk melacak ketersediaan obat secara transparan. Kebijakan baru seperti Critical Medicines Act di Uni Eropa menunjukkan kemajuan, namun pelaksanaannya masih menghadapi banyak tantangan.
Presentasi kedua adalah Yoko Ibuka dari Faculty of Economics, Keio University Jepang terkait The Impact of Drug Shortages on Patients’ Financial Costs: Evidence from Japan. Jepang menghadapi krisis kekurangan obat generik akibat penangguhan produksi oleh pemerintah setelah ditemukan pelanggaran oleh produsen, yang berdampak langsung pada pasien dengan penyakit kronis. Karena obat generik lebih terjangkau dibandingkan obat bermerek, kelangkaan ini memaksa pasien beralih ke obat yang lebih mahal, meningkatkan beban biaya pengobatan. Studi ini menemukan bahwa penangguhan produksi menyebabkan lebih dari 10% resep untuk hipertensi, dislipidemia, dan obat psikotropika dihentikan, serta meningkatkan pengeluaran pribadi pasien hingga hampir 10% pada beberapa kelompok. Penurunan penggunaan obat generik sebesar 1–3 poin persentase menunjukkan bahwa lonjakan biaya sebagian besar disebabkan oleh peralihan ke obat bermerek. Temuan ini menegaskan bahwa dampak finansial dari kelangkaan obat harus menjadi perhatian utama dalam kebijakan kesehatan dan sistem asuransi publik.
Presenter ketiga adalah Mr. Puwadol Chawengkul dari Health Intervention and Technology Assessment Program Foundation (HITAP), Thailand dengan judul Bridging Gaps in Medical Innovation: from Development to Market Access and Reimbursement in Thailand. Sejak diluncurkan pada 2015, Daftar Inovasi Thailand bertujuan mendorong pengembangan produk lokal, terutama di bidang medis, melalui insentif pengadaan publik. Namun, meskipun banyak produk medis terdaftar, adopsi di sistem kesehatan masih rendah karena tidak semua inovasi berhasil menembus pasar atau masuk dalam skema pembiayaan publik. Studi ini menganalisis 393 produk medis dan menemukan bahwa produk alat kesehatan lokal justru menunjukkan tingkat inovasi yang lebih tinggi dibanding obat-obatan, tetapi lebih jarang mendapat dukungan asuransi pemerintah. Kurangnya kolaborasi, pembiayaan awal, dan dukungan produksi skala besar menjadi hambatan utama, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Oleh karena itu, dibutuhkan reformasi ekosistem inovasi kesehatan agar proses dari pengembangan hingga adopsi inovasi dapat berjalan selaras dan berkelanjutan.
Masih membahas negara yang sama, Chee Ern Har, Saw Swee Hock School of Public Health, National University of Singapore and National University Health System, Singapura, memaparkan tulisannya dengan judul Identification of Factors Associated With High-Value Health Innovations in Thailand. Inovasi kesehatan sangat penting untuk menjawab tantangan biaya dan permintaan layanan kesehatan yang terus meningkat, namun banyak inovasi sulit masuk pasar. Studi ini menganalisis 383 produk medis dalam Daftar Inovasi Thailand dan menemukan bahwa kesuksesan inovasi lebih dipengaruhi oleh kesesuaian dengan prioritas sistem kesehatan serta ketersediaan aset pelengkap seperti uji klinis dan akses ke skema pembiayaan publik. Transfer teknologi terbukti mendukung keberhasilan masuk ke dalam skema asuransi, sedangkan pendanaan eksternal dan kolaborasi riset justru menunjukkan hubungan negatif. Produk yang telah menjalani uji klinis dan mendapat pembiayaan publik memiliki peluang pasar lebih besar. Oleh karena itu, reformasi kebijakan diperlukan untuk memperkuat kemitraan translasi, mempercepat proses pembiayaan, dan mendorong dukungan bagi teknologi medis yang sedang berkembang.
Reporter:
Relmbuss Fanda (PKMK UGM)
