Reportase Sesi 3: Isu Prioritas

Sesi ini menghadirkan empat pembicara dan satu pembahas. Di awal paparannya, Ign. Praptorahadjo menyampaikan gambaran secara umum situasi penaggulangan AIDS di tahun 2015 yang mengalami cenderungan penurunan dalam gerakannya . Praptorahardjo merupakan pembicara pertama untuk sesi ini. Beberapa agenda yang mendukung pada arah kebijakan tidak cukup mendapatkan respon. Situasi ini tidak terlepas dari berkurang dan berakhirnya bantuan pendanaan yang berkontribusi dalam upaya merespon kebijakan penanggulangan AIDS, seperti Global Fund, USAID, dan DFAT. Implikasi dari situasi ini adalah semakin berkurangnya sumber-sumber pendanaan yang dapat diakses oleh sektor komunitas yang selama ini kegiatannya lebih banyak di-support oleh Mitra Pembangunan Indonesia (MPI). Salah satu upaya yang sudah dilakukan untuk menyikapi situasi pembiayaan di sektor komunitas adalah dengan memberikan rekomendasi bagi Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas dalam mengembangkan kebijakan bagi pendanaan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS).
Sementara itu, refleksi dari tiga agenda utama dalam kebijakan penanggulangan AIDS yang dilakukan melalui penelitian kebijakan, advokasi dan jaringan menunjukkan bahwa (1) Penanggulangan AIDS masih merupakan kegiatan yang bersifat sentralistik dan vertikal yang berfokus pada kebijakan nasional, sementara kebijakan daerah seringkali merupakan replikasi dari kebijakan di level nasional. (2) Sumberdaya dalam isu penanggulangan AIDS masih terbatas. Sektor komunitas lebih banyak melakukan peran pragmatis daripada peran strategis. Sama halnya dengan penelitian kebijakan AIDS cenderung dilakukan oleh peneliti saja, dan belum terintegrasi dengan isu pada kebijakan kesehatan yang lain. (3) Kebutuhan dari jaringan dalam website kebijakan AIDS belum dapat ditangkap secara jelas. Pengelolaan pengetahuan untuk kebijakan belum mendapatkan respon dan partisipasi yang positif dari hasil-hasil kerja jaringan yang dimungkinkan karena variasi dari kepentingan dan kebutuhan yang berbeda. Sebagai bagian dari penutup paparan, pemateri pada sesi ini menyampaikan agenda dan tantangan pada tahun 2016. Isu yang dikedepankan adalah masalah pembiayaan yang terkait dengan kebijakan pemerintah serta, perubahan skema pendanaan penanggulangan AIDS.
Pembicara kedua ialah konsultan senior PKMK FK UGM, yaitu dr. Sitti Noor Zaenab, M. Kes. Pelayanan KIA masih merupakan isu prioritas di Indonesia apalagi dengan melihat Hasil SDKI 2012, hal ini merupakan Isu lama yang tetap menjadi prioritas. Kedepan isu sudah akan berkembang yakni yang dulunya adalah Isu MDG's ke depan kita akan berfokus ke SDG'S dengan sederet target yang lebih ambisius, isu anggaran yang akan naik sebanyak 5% pada tahun depan, isu Jampersal kembali dengan bentuk yang baru, isu keberadaan rumah tunggu, isu APBD sudah diakomodir adanya konsultan (kalau dulu tidak ada) sehingga dimungkinkan adanya monev bersama. Ada juga isu Jamkesda yang akan hilang karena apabila masuk ke konsep jaminan kesehatan nasional (JKN) menjadi tidak luwes.
PKMK FK UGM pada tahun 2015 telah melakukan berbagai kegiatan terkait dengan masalah pelayanan KIA, terutama tentang ketersediaan dokter spesialis melalui kegiatan sister hospital dengan penguatan rumah sakit PONEK yang di mulai sejak tahun 2010 di Nusa Tenggara Timur (NTT) dan berkembang saaat ini di Balikpapan, Pengembangan manual rujukan maternal dan neonatal yang dimulai sejak 2011 di NTT dan saat ini juga telah meluas dan dikembangkan juga Manual Rujukan KIA ke Kabupaten Mimika, Replikasi Manual Rujukan KIA ke DKI Jakarta sekaligus memperluas ruang lingkup hingga mencakup semua jenis rujukan dari Puskesmas dan Perbaikan mekanisme AMP di tiga Kabupaten NTT termasuk menyusun pedoman 10 langkah AMP.
Ditekankan pula bahwa kerangka konsep dalam manual rujukan bukan hanya rujukan emergensi namun juga elektif dan dalam penyusunannya PKMK sudah mengembangkan langkah penyusunan dan penerapan manual rujukan AMP dengan tidak lupa memasukkan komponen Pemda, karena sangat disadari bahwa masalah kesehatan tidak hanya harus diselesaikan oleh tenaga kesehatan saja sehingga sangat dibutuhkan peran pemerintah daerah. Dengan adanya peran ini sampai dengan tahun 2015 beberapa Kabupaten sudah berada pada tahap sudah menyusun manual rujukan yakni NTT, DIY, Jayapura dan Balikpapan. Ada pula yang saat ini pada tahap sedang menyusun yakni Kota Bontang Kaltim, Kabupaten Kutai Kartanegara Kaltim serta ada juga yang masih dalam tahap sosialisasi yakni Provinsi NTB. Provinsi Maluku dan Kab Mimika.
Hasil yang ada saat ini adalah bahwa angka kematian di tiga wilayah yang menjadi wilayah intervensi KIA oleh tim PKMK mengalami penurunan yakni DIY, NTT dan Balikpapan, terutama di DIY bahwa sekitar 50% target penurunan kematian sudah berhasil ditekan. Ini bukan merupakan suatu kebetulan saja karena sejak lima tahun terakhir upaya intervensi rutin dilakukan agar jumlah kematian dapat menurun. Output yang dihasilkan oleh Tim KIA PKMK FK UGM dalam menekan kematian ibu dan anak sudah cukup menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Prof Laksono Trisnantoro selaku pembahas dalam diskusi isu prioritas bahwa apakah kita sebagai konsultan KIA berguna? Apa bukti-buktinya (apa yang sudah terjadi selama proses pendampingan serta bagaimana dengan kematian?).
Pemaparan ketiga terkait social determinant of health (SDH) adalah setting kondisi sosial yang membuat orang tidak berdaya untuk menjadi sehat. Kebijakan upstream policy perlu dieksekusi dengan baik di bagian hilir. Modul kursus SDH dapat diperoleh dari web Intrect, serta sumber sumber lain yang relevan. Salah satu implementasi SDH di bangku kuliah pada 2015 di lingkungan UGM ialah kursus blended learning. Kursus blended learning tentang Social determinants of health tahap pertama telah dilaksanakan pada bulan Juli – Desember 2015. Peserta dari Indonesia (14), Vietnam (2), Thailand (1) Bangladesh (1) dan Timor Leste (2) mendiskusikan topik- topik social determinant of health dalam masalah-masalah kesehatan pada konteks lokal; kebiasaan minum beer di Vietnam dan Thailand, rendahnya penggunaan layanan maternal oleh ethnis minoritas Raglai di Vietnam, Dengue Fever di daerah kumuh di Dhaka, Domestic Violence dan Malnutrisi pada Balita di Timor Leste, bisnis periklanan terhadap obesitas di daerah perkotaan, pendidikan seks yang rendah di pesantren, bagaimana peran kyai sebagai model perilaku hidup bersih di pesantren, peningkatan demand dan supply maternal care, kegagalan maternal emergency care system , bullying di sekolah, underage Smokers , dan sulitnya akses pengobatan oleh penyandang tuna grahita di Yogyakarta.
Kebutuhan yang penting dan mendesak adalah menyediakan mentor atau supervisor yang tepat dan benar –benar mau terlibat untuk mengembangkan paper yang utuh dari abstrak- abstrak tersebut sebelum Postgraduate Forum 2016. Kendala yang dihadapi adalah koneksi internet yang tidak lancar dan penggunaan website yang belum maksimal. Goal kursus SDH di tahun 2016 adalah mengintregasikan SDH dengan kuliah S2 MPH, pelatihan SDH untuk aktor birokrasi dan dosen dosen muda (Ahok case learning), membuat web yang lebih menarik dan interaktif, akomodasi dan fasilitasi untuk publikasi manuskrip SDH, Travel Fellowship untuk seminar internasional dan kursus SDH spesifik untuk dosen IKM dan FKM serta menciptakan network yang baik antara peserta dan fasilitator serta institusi lain yang terlibat.
Sebagai pembicara terakhir, dr. Luthfan Lazuardi, MPH memaparkan sejumlah hal terkait electronic health (e-health). Ada berbagai definisi yang berbeda mengenai e-health, namun ada beberapa kata kunci yang sama yaitu Information and Communication Technology (ICT) yang digunakan untuk bidang kesehatan, apapun aktivitasnya. Kata kunci yang sering digunakan di literatur terdahulu adalah sistem informasi kesehatan. Namun sejak tahun 2005, WHO kemudian menggunakan kata e-health untuk merujuk pada sistem informasi dan komunikasi di kesehatan. Posisi e-health sebenarnya ada di semua komponen sistem kesehatan. Sehingga harapannya dengan difasilitasi oleh e-health, sistem kesehatan dapat berjalan lebih efektif dan fungsional. Berbagai aktivitas yang sudah dilakukan misalnya untuk memfasilitasi pelayanan kesehatan di puskesmas. Sudah ada 200 lebih puskesmas yang menggunakan sistem yang kita kembangkan. Di level nasional, mungkin sudah ada sekitar seribu lebih puskesmas yang telah difasilitasi oleh e-health.
Salah satu manfaat e-health adalah data dapat lebih mudah dipahami dengan visualisasi yang lebih menarik, pelaporan juga akan lebih mudah dikerjakan. Awal tahun 2007, PKMK mengembangkan dashboard KIA, yang mana menjadi salah satu tonggak sejarah dimana kemudian banyak inovasi visualiasi data kesehatan dikembangkan. Benefit lain yang sebenarnya sangat potensial namun belum banyak dimanfaatkan adalah data yang sudah terkumpul tidak dianalisis lebih lanjut selain untuk pelaporan. Ibaratnya kaya data tapi miskin informasi.
Di level global, paradigma pemanfaatan ICT terus berubah. Pada tahun 80-an tren di negara maju berfokus pada administrasi dan manajemen, misalnya pengembangan billing system untuk rumah sakit. Namun, ketika itu dirasa sudah mapan, pemanfaatan mulai mengarah untuk petugas kesehatan, seperti pembuatan clinical information system, laboratorium information system, sistem untuk nerumerasi dan penghitungan jasa medik. Isu di masa depan akan lebih mengarah ke patient-safety. Isu yang berkembang sekarang pelayanan kesehatan akan mengarah ke personalised medicine, pervasive & ubiquitus health, wearable devices, well-being, dan UHC. Namun, mungkin ini belum kita alami untuk konteks di Indonesia, setidaknya kita masih berfokus ke manajemen.
Pembahasan disampaikan oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD menegaskan apa kita (konsultan) berguna untuk klien dan masyarakat atau hanya proyek saja? Rekan-rekan PKMK harus berguna untuk masyarakat luas. Hal yang terpenting ialah konsultan PKMK bukan merupakan kelompok konsultan pedagang ilmu.
Dr. dr. Mubasysyr Hasanbasri menyatakan pendapatnya berpikir adalah proses lateral thinking, sehingga sebagai konsultan, kita harus bisa membangun kapasitas lingkungan atau klien. Pasar kita sangat banyak, kita bisa membangun sistem konsultasi yang melahirkan manajer yang efektif. Jangan sampai terjebak dengan membantu orang dalam kepemimpinan yang tidak efektif. Kita harus membangun kapaitas oorang tersebut. Kapasitas manajemen dalam organisasi, Sehingga, uutlook menurut saya ialah apa yang bisa dikerjakan berbeda di tahun depan dan mencari opsi yang berbeda.
Diskusi
Atik Tri Ratnawati menanyakan poin pertama untuk kelompok pencegahan HIV/AIDS, apakah bisa dibentuk gerakan social baru di wilayah 3T angka HIV AIDSnya luar biasa, dari ketidaktahuan, migrasi, banyak pendatang di perbatasan. Jika kebijakan di nasional dan daerah tidak berdaya, jika ada gerakan baru Pusat akan tergerak untuk berubah. Kebijakan bisa di provinsi/kabupaten. Poin kedua untuk SDH perlu disebarluaskan ke mahasiswa S1, S2 dan S3. Banyak masalah kesehatan yang tidak bekerja dengan baik karena hambatan budaya.mengapa orang tidak mampu berdaya karena kesehatan?
Ign. Praptorahardjo menegaskan bahwa gerakan pencegahan penularan HIV/AIDS ini berbeda dengan gerakan lain, fokus kita pada populasi kunci, akhirnya melupakan masyarakat umum. Dulu, masyarakat umum dianggap tidak penting. Saat ini HIV sudah menular ke ibu-ibu yang dianggap beresiko rendah. Usulan ibu Atik sangat relevan untuk kembali ke dasar. Maka, kembali ke daerah menjadi sangat strategis karena lokalitas. Sayangnya, template nasional digunakan di daerah, hal ini kurang sesuai dengan situasi daerah lokal.
Retna Siwi Padmawati sepakat dengan pendapat Atik. Sekitar 50 universitas FKM dan IKM hanya 1-2 yang memberikan SDH ke dalam kurikulum pembelajarannya. Seharusnya SDH ini masuk juga ke fakultas ilmu sosial dan humaniora. Mulai tahun depan SDH akan dikenalkan ke bangku kuliah. Di Kemkes, SDH siapa yang menangani? Dulunya ada, sekarang dipindah ke Promkes.
• Tim reporter:
Swasti Sempulur; Andriani Yulianti, MPH; Yuli Mawarti, MPH; Mohamad Ali Rosadi; Widarti, SIP
{jcomments on}
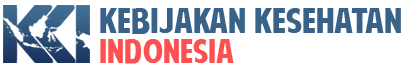







 Bagian 1: Berbagai kebijakan kesehatan yang menarik di tahun 2015
Bagian 1: Berbagai kebijakan kesehatan yang menarik di tahun 2015 Bagian 2:
Bagian 2: