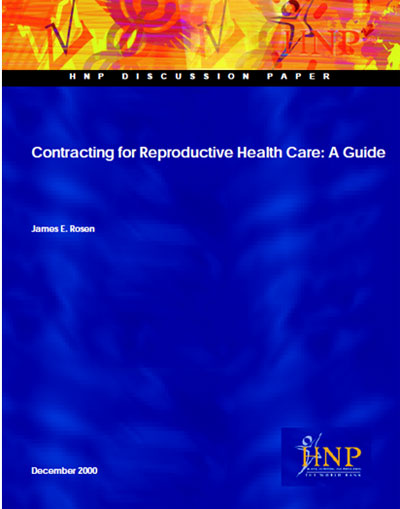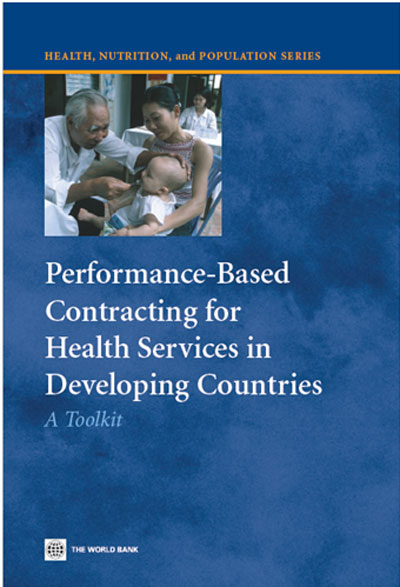{tab Pemicu Diskusi|red}
Pada hari Senin (15 Juni 2015) Prof. Laksono Trisnantoro menyampaikan pendapat dalam rapat yang diselenggarakan oleh Biro Perencanaan Kemenkes di Bandung. Paper ini membahas opsi sistem kontrak untuk menghadapi rencana kenaikan anggaran sektor kesehatan menjadi 5%. Hal yang ditekankan dalam paper ini jika tanpa ada opsi kontrak dikawatirkan masalah penyerapan Kemenkes akan kembali memburuk dan mutu pelaksanaan program menjadi tidak terjamin. Di samping itu, ada kemungkinan dana kenaikan akan lebih banyak terpakai untuk tindakan kuratif JKN yang seharusnya dapat dibayar oleh masyarakat mampu. Silakan simak paparannya pada link berikut
{tab Ringkasan Diskusi|orange}
Ringkasan Diskusi Tahap I tersebut adalah sebagai berikut:
- Gagasan Prof Laksono untuk menerapkan kontrak di sektor kesehatan, secara umum dapat diterima oleh semua pihak baik dari kalangan akademisi, konsultan, NGO, maupun pengambil kebijakan di dinas kesehatan. Argumentasinya mulai dari aspek teoritis, evidence-based, analisis kemampuan absorbsi anggaran, potensi yang dimiliki NGO, dan lain-lain.
- Kendala yang masih ditemui antara lain
- peraturan kebijakan yang belum mendukung sistem kontrak diterapkan untuk program kesehatan (saat ini, sistem kontrak baru diterapkan untuk “belanja modal”);
- NGO terutama NGO keagamaan memiliki potensi sebagai calon mitra tetapi belum dioptimalkan potensinya baik melalui pendataan, pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan atau kesempatan untuk menjadi provider.
- Peluang penerapan sistem kontrak ini terbuka luas karena sudah diakomodir dalam Pasal 11 RPP tentang SPM.
{tab Proses Diskusi|blue}
GambitPak Laksono dan kawan-kawan, Terima kasih untuk kesempatan memberikan komentar di milis ini. Paparan tentang contracting di website KKI bagi saya yang bekerja bersama LSM merupakan sesuatu yang selama ini menjadi ‘mimpi’ dari LSM agar bisa mengakses pendanaan dari pemerintah. Memang LSM bisa memperoleh dana dari pemerintah melalui mekanisme bantuan sosial untuk melaksanakan event-event tertentu tetapi tidak untuk program. Pengalaman penanggulangan AIDS di Indonesia sebenarnya memperlihatkan bahwa pemerintah tidak bisa melakukan semua pelayanan yang diperlukan, apalagi untuk promosi dan pencegahan (bdk DFID, 2004; Barnett et al, 2001; USAID, 2014). Barangkali ini menjadi kasus yang spesifik karena target dari penanggulangan AIDS adalah marginalized populations yang tidak bisa mengakses layanan regular (karena stigma atas perilakunya) sehingga perlu pihak lain (LSM) untuk mendekatkan layanan itu ke populasi. Hingga saat ini, hasil kerja LSM secara langsung berkontribusi terhadap cakupan program promosi dan pencegahan HIV secara nasional, yang saat ini bisa mendekati 60%. Akibatnya cakupan puskesmas dalam memberikan layanan infeksi menular seksual dan Tes HIV meningkat tajam dan rumah sakit bisa meningkatkan cakupan pengobatan ARV. Kontribusi besar LSM tersebut diafirmasi di tingkat lapangan oleh penelitian yang sedang dilakukan oleh tim AIDS PKMK tentang peran sektor komunitas dalam penanggulangan AIDS di 11 provinsi. Sayangnya pendanaan Kementerian Kesehatan yang berasal dari APBN selama ini hampir semuanya digunakan untuk membeli obat (lihat SRAN AIDS 2015-2019). Sementara untuk program promosi dan pencegahan ‘dibebankan’ kepada lembaga donor tradisional untuk AIDS (DFAT, Global Fund, USAID). Perkiraan dari KPAN bahwa pasca 2017 akan terjadi kekurangan dana untuk penanggulangan HIV karena berkurangnya dukungan dana dari negara donor (meski sudah diasumsikan kenaikan 20% pendanaan pemerintah daerah setiap tahun). Akibatnya adalah kegiatan promosi dan pencegahan terancam tidak akan ada alokasi karena dana yang tersedia akan habis untuk membeli obat (bahkan diperkirakan kurang). Jika anggaran Kementerian Kesehatan akan meningkat 5%, apakah ada imbas positifnya terhadap kegiatan promosi dan pencegahan AIDS? Apakah dana tersebut bisa dimanfaatkan sebagai pengganti dana dari donor yang selama ini mendanai LSM? Jika ini terjadi, maka permasalahannya adalah bagaimana LSM bisa menggunakan dana promosi dan pencegahan yang tersedia di kementerian kesehatan tersebut? Dalam kerangka seperti ini maka menjadi sangat relevan untuk membicarakan tentang isu contracting ini dalam isu HIV. Berbagai tools untuk mendukung pelaksanaan contracting pelayanan (misalnya untuk penghitungan unit cost untuk setiap jenis intervensi atau menentukan, standar kualitas lembaga, mekanisme M&E) sudah dikembangkan dan diterapkan di sebagian besar LSM yang menerima bantuan hibah dari lembaga donor sehingga LSM pada dasarnya cukup siap jika sistem kontrak ini bisa dilakukan lebih cepat (lihat tools yang dikembangkan oleh SUM 2 USAID, HCPI – DFAT, Kerangka CSS – GF). Selain ranah pelayanan, sebenarnya contracting dalam penanggulangan AIDS ini bisa didorong pada kontrak monev dan informasi strategis secara independen atau technical assistance program yang selama ini lebih banyak diperankan oleh lembaga donor dari pada oleh kemenkes. Oleh karena isu contracting ini sudah dilempar, maka tentunya kita bisa mulai ‘berisik’ melalui CoP – CoP yang menjadi jaringan tim AIDS PKMK di beberapa provinsi. Mungkin itu komentar awal saya tentang ide contracting. Maaf saya hanya berfokus pada isu penanggulangan AIDS karena ini yang menjadi ‘ladang’ saya. |
Dwi HandonoUntuk saya pribadi, inisiatif contracting out bukan hal baru. Pada tahun 2007, saya sudah ditugaskan Pak Laksono untuk memfasilitasi inisiatif tersebut di Kab. Berau, Kalimantan Timur. Saat itu, inisiatif tersebut gagal. Penyebabnya antara lain karena tidak adanya provider lokal yang memenuhi kualifikasi. Kegagalan tersebut tidak membuat ide tersebut mati, tetapi terus dikembangkan seperti dilakukan di NTT dengan Program Sister Hospital pada pertengahan 2010 hingga berakhir pertengahan 2015 ini. Berhasil tidaknya gagasan ini, menurut saya, tergantung 2 faktor. Pertama, bagaimana meyakinkan para pengambil keputusan di level pusat. Kedua, bagaimana secara teknis mengeksekusi gagasan tersebut. Dari sisi teknis, hambatannya adalah karena belum siapnya sektor kesehatan untuk menerapkan inisiatif tersebut. Untuk lelang dan kontrak pengadaan barang dan jasa, memang sudah biasa dilakukan, tetapi untuk kontrak program kesehatan apalagi dalam jangka panjang, belum biasa dilakukan. Terlepas dari itu semua, WHO sendiri sudah merekomendasikan pendekatan kontrak ini sejak tahun 2003. Itu berarti sudah 12 tahun yang lalu! Di sejumlah negara di Afrika seperti Chad, Mali, Burkina Faso, Senegal, Burundi, Madagaskar, dan Maroko telah memiliki kebijakan nasional tentang contracting (WHO News, 2006), di Indonesia kebijakan nasional semacam itu belum dikembangkan. |
Hilmi SRTerimakasih Prof.Laksono dan rekan2 sekalian atas kesempatan berdiskusi ini. Sebagai pelaku di NGO, seperti yang disampaikan pak Gambit di komentar sebelumnya, wacana ini sangat menarik bagi saya, karena sinergi dengan pemerintah merupakan sesuatu yang dinanti oleh sebagian besar NGO. Alasan utamanya bukan karena NGO bisa mengakses dana pemerintah dan mendapatkan sumber pendanaan baru, namun lebih kepada adanya pembagian tugas yang lebih jelas, karena NGO dan pemerintah berada pada sisi yang sama, dengan tujuan agar pelayanan publik esensial mampu menjangkau seluas mungkin kalangan masyarakat. Meskipun, hal lain yang perlu diantisipasi, pola ini bisa menjadikan NGO kehilangan objektivitas dan daya kritisnya, karena menggunakan sumber dana pemerintah dalam menjalankan program. Seperti yang telah disampaikan pak Gambit dan pak Dwi Handono, sudah ada cukup banyak evidence yang memberikan landasan adanya sinergi yang lebih baik antara pemerintah dan sektor non pemerintah. Pada negara yang pemerintahnya mampu merangkul sektor non pemerintah, baik sosial maupun swasta, terbukti memiliki outcome sistem kesehatan yang lebih baik. Contoh terdekat adalah di Nepal dan Srilanka, yang dengan sumber daya terbatas namun mampu menurunkan AKI secara signifikan, karena selain menjadikan isu kesehatan prioritas sebagai isu cross cutting, pemerintahnya juga melibatkan banyak unsur diluar pemerintahan untuk bekerja bersama-sama. Pada konteks Indonesia, dalam pandangan saya, CSR adalah salah satu contoh praktik Contracting Out yang sudah banyak dilakukan. Dalam hal ini, perusahaan seringkali mengontrak NGO atau universitas untuk menjalankan berbagai program CSR, termasuk bidang kesehatan. Bahkan, proses terebut seringkali sudah dimulai dari tahap perancangan/desain program, berikut indikator keberhasilannya. Pada kondisi tersebut, NGO dan pihak perusahaan menyepakati bersama apa yang menjadi indikator kinerja kunci/Key Performance Indicator dari program yang akan dilaksanakan. Namun, pada skema kontrak CSR ini, tidak bisa dipungkiri bahwa banyak NGO yang menyusun anggaran cukup tinggi, karena memasukkan komponen “management fee” yang dibutuhkan untuk kesinambungan dan perkembangan organisasi. Meskipun terjadi negosiasi pada batas harga yang “reasonable” dalam pandangan perusahaan pemberi CSR, tidak jarang pada akhirnya perusahaan sebetulnya membayar harga yang “over price” untuk suatu layanan, baik yang bersifat ukp/kuratif maupun ukm/promotif-preventif. Dan hal seperti ini tentu tidak boleh terjadi dalam situasi anggaran yang digunakan adalah milik pemerintah. Oleh karena itu, sebagai tanggapan awal wacana contracting out ini, selain dari yang sudah disampaikan dalam makalah Prof.Laksono dkk, saran saya adalah:
Selain hal-hal yang saya sampaikan pada komentar sebelumnya, poin penting lain yang saya simpulkan dari penelitian yang pernah saya lakukan, adalah perlunya pendataan NGO yang massif dan pembinaan NGO yang lebih terstruktur oleh pemerintah. Sistem pencatatan organisasi sosial di era orde baru tampak jauh lebih baik dibandingkan saat ini, yang membuat pemerintah seringkali tidak bisa berbuat apa-apa karena minimnya informasi yang teregistrasi tentang sumber daya dan kapasitas organisasi sosial. Di satu sisi, aktivitas pendataan ini tidak dipandang prioritas oleh pemerintah, karena dianggap sebagai pekerjaan dan beban tambahan. Padahal, aktivitas pendataan ini ibarat pekerjaan mengasah gergaji bagi penebang pohon, yang pada saat ini mungkin dianggap tidak bermanfaat dalam mempercepat tujuan menebang pohon, tapi begitu selesai dikerjakan, si penebang pohon bisa melakukan pekerjaannya jauh lebih cepat karena gergajinya jauh lebih tajam. |
Chrysant LilyIde yang sangat bagus untuk contracting out bagi bagian dari layanan kesehatan yang porsinya bisa dilakukan oleh CSO sesuai expertise mereka. Dalam dokumennya WHO berjudul Strategic Alliances: Civil Society’s Role in Health (2001), sudah dijabarkan bidang-bidang layanan kesehatan yang memerlukan kontribusi CSO. Ini termasuk melakukan penjangkauan ke populasi yang memiliki barrier tinggi dalam mengakses layanan kesehatan karena alasan marjinalisasi ataupun stigma, mendistribusikan alat kesehatan seperti jaring nyamuk, kondom, alat suntik steril untuk pengurangan dampak buruk bagi penasun dsb, serta melakukan peran dua arah yaitu di satu sisi menerjemahkan berbagai kebutuhan komunitas kepada sektor kesehatan dan sebaliknya menjadi agen untuk promosi kesehatan lewat berbagai kegiatan pendidikan masyarakat (Alliance et al, 2007; Asthana and Oostvogels, 1996; Cornman et al., 2005; Global Fund, 2014). Karena model contracting out ini masih belum umum dalam sektor kesehatan, kedua pihak (CSO maupun sektor kesehatan) sama-sama butuh belajar, melakukan penyesuaian dan mengelola resiko. Contohnya, CSO harus bisa mengatasi resiko berkurangnya independensi dan tetap memainkan ‘watchdog role’ terhadap pemerintah walaupun pemerintah menjadi salah satu sumber pendanaan lembaganya. Di sisi lain, sektor kesehatan sendiri harus memiliki kemauan untuk menghadapi resiko ketidaknyamanan mengelola hubungan kerja dengan pihak yang mungkin mengambil posisi kritis terhadap kebijakan-kebijakannya. Ada banyak lagi contoh resiko-resiko lainnya yang sama-sama dihadapi dan perlu dikelola oleh kedua belah pihak, tetapi seperti yang disimpulkan WHO (2001) ‘the benefits of collaboration for both the State and CSOs outweigh the risks of possible tensions in CSO-state interactions’. Semoga ada jalan untuk segera merealisasikan sinergi antara pemerintah dan CSO lewat mekanisme contracting out ini. |
Laksono TrisnantoroTerimakasih atas tanggapan-tanggapannya. Saat ini memang sudah terjadi sistem kontrak terutama di Program AIDS, dan beberapa eksperimen oleh tim PKMK FKUGM. Hal ini dapat dipahami karena untuk AIDS, tidak mungkin seorang PNS melakukan penyuluhan ataupun pendekatan ke komunitas-komunitas tertentu. Oleh karena itu donor banyak yang memberikan kontrak untuk LSM |
Dwi HandonoSelamat pagi Bapak/Ibu Pemerhati Diskusi Kontrak di Sektor Kesehatan, saya Dwi Handono Sulistyo selaku moderator dalam Diskusi ini, mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Bapak/Ibu baik secara aktif maupun pasif. Saya mengundang Bapak/Ibu yang belum memberikan opininya, agar dapat berkontribusi optimal di Forum Diskusi ini, terutama dari para pengambil kebijakan di Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi, dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Mengapa demikian? Karena opini yang ada sejauh ini baru dari satu pihak yaitu dari kalangan NGO dan akademisi yang mendukung gagasan tersebut. Tentu diskusi akan sangat menarik jika muncul tanggapan dari pihak dan opini yang berbeda. Terlepas dari itu, topik diskusi juga kita tambah sesuai masukan Prof. Laksono yaitu bagaimana mengantisipasi berkurangnya dana asing untuk kegiatan AIDS misalnya. Apakah APBN atau APBD bisa menggantikannya? |
Dwi HandonoSelamat pagi Bapak/Ibu Pemerhati Diskusi Kontrak di Sektor Kesehatan, berikut saya sampaikan Rangkuman hasil diskusi Minggu I:
Demikian terima kasih |
Hilmi SRProf.laksono, pak Dwi Handono, dan rekan2 sekalian. Sehubungan dengan contracting out ini, saya berpikir bisa digabungkan dengan fenomena social entrepreneurship yang saat ini sedang marak. Di website ini dulu pernah mengunggah jurnal ttg dampak social enterprise terhadap health outcome. Namun, kerangka yang digunakan dalam jurnal tersebut berbeda dengan apa yang saya pahami, meskipun memang terdapat banyak versi dari social enterpreneur. Saya sendiri sudah mencoba “corat-coret” untuk menggambarkan skema social entrepreneur yang saya pahami, yang menurut saya cukup relevan dengan isu yang sedang dibahas di bagian ini. Mohon review prof.laksono, pak dwi, dan rekan2 lain, apakah skema seperti yang saya gambarkan memungkinkan. Skema tersebut dapat dilihat di link http://1drv.ms/1TcTFff Disclaimer: Skema ini hasil pemikiran konseptual, bukan hasil riset. |
HudaSaya saat ini live ini di sebuah Kabupaten Perbatasan di Propinsi Baru, Kalimantan Utara. Sangat tertarik dengan gagasan contracting out dengan harapan bila skema ini benar dapat dijalankan bisa membantu percepatan peningkatan derajat kesehatan dan penguatan mutu layanan kesehatan, khususnya bagi warga di perbatasan yang selama ini masih kalah dibanding wilayah non perbatasan. Secara konsep contracting out saya fikir sangat bagus. Namun tantangan nyatanya adalah bagaimana mengoperasionalkan di level teknis yang sebenarnya pada banyak hal, tidak melulu terkait dengan isu kesehatan. Namun lebih pada managemen, administrasi, kelembagaan, dan adanya peraturan pemerintah atau semacamnya yang bisa dijadikan rujukan bagi institusi yang berminat terlibat dan pemerintah daerah. Saya melihat, gagasan contracting out, perlu segera dibawa ke beberapa stakeholder penentu lainnya, bukan hanya kemenkes. Tapi juga ke Bapenas, Kemenkeu, dan beberapa kementrian lainnya seperti Kemendagri, Kemendes, dan Kemenaker. Dan tentunya juga, komisi IX DPR RI. Upaya ini tetap harus diperbincangkan dengan “pusat” karena dengan begitu pemerintah prop/kab, memiliki payung untuk menjalankannya. Otonomi daerah saat ini, harus diakui masih seolah-olah, banyak kepala daerah (Bupati/walikota/Gubernur) takut mengambil terobosan karena kebijakannya berpotensi dikriminalisasi atas nama tiadanya pijakan peraturan. Senyampang proses tersebut dilakukan, saya lihat perguruan tinggi atau lembaga yang berada di bawah perguruan tinggi, perlu lebih agresive menawarkan hal ini ke pemerintah daerah namun dengan kesadaran bahwa kenaikan 5% anggaran itu masih ada di saku pemerintah pusat. Yang ini berarti bahwa saat menawarkan ke daerah tidak hanya membawa skema program kesehatan saja, tapi juga plus dengan skema untuk mendapatkan pendanaan tersebut. Berat memang. Tapi beginilah fakta/sitausi “bisnis” di lapangan. Sebagai gambaran, di kabupaten saya live in sekarang, karena kabupaten baru dan di propinsi baru, pecahan Kaltim, yang PAD-nya lebih kecil dibanding saat bergabung dengan Kaltim. Anggaran program pembangunan menjadi PR yang berat. Karenanya, pemerintah kabupaten, sangat berharap mendapatkan dana langsung dari pusat melalui DAU, DAK dan atau skema lainnya yang ada. Nah, untuk mendapatkan dana ini, persaingannya bukan main. Dan karenanya, muncullah “makelar anggaran” yang sangat rentan namun faktanya “dibutuhkan”. Skema yang digunakan, biasanya pemkab akan meminta pada pihak ke-3, untuk “memetik” dana pusat dengan perjanjian, segala konsekwensi biaya “pemetikan” itu ditanggung oleh pihak ke-3, dan bila dana tersebut gol, maka pihak ke-3 itu yang akan ditunjuk oleh pemkab untuk menjalankan proyeknya. Ini situasi saat ini. Nah, apakah kampus, lembaga di bawah kampus atau LSM siap melakukan hal semacam ini? Ini cerita abu-abunya. Sejauh yang saya tahu, di kabupaten Malinau sini, saat ini Pemkab mengontrak dokter-dokter umum dan spesialis dengan kontrak perseorangan. Menurut informasi dari Bupati, untuk 1 dokter umum, disediakan gaji Rp 30 Juta dan Spesilais Rp 40-60 Juta, dengan syarat tidak membuka praktik umum dan hanya focus memberikan layanan di RSUD. di RSUD sekarang ada 60 dokter. Dengan biaya yang lumayan itu, ternyata tidak semua dokter memberikan layanan yang cakap dan memuaskan. Bahkan beberapa alkes canggih yang didatangkan juga tak semuanya mampu digunakan dengan maksimal oleh para tenaga medis. Saya bayangkan akan berbeda kejadiannya, bila contracting out bisa dijalankan, apalagi dengan lembaga yang pelaksana yang kredibel. Karenanya menurut hemat saya perguruan tinggi yang punya peluang untuk melakukan ini, sehingga tidak hanya untuk layanan tapi juga memberikan tehnical assistance program kebijakan kesehatannya. Untuk LSM, saya lihat masih jauh. Kecuali professional LSM yang bekerja bersama dengan perguruan tinggi. Atau mungkinkah, perusahaan-perushaan Alkes yang akan melihat peluang ini dengan mengembangkan divisi programnya? Terima kasih, |
Ahyani RaksanagaraSelamat siang para peserta diskusi. Terima kasih untuk gagasan yang sangat baik. Demikian sebagai masukan semoga bermanfaat |
Krishnajayasaya termasuk orang yang sangat setuju dengan di pihak ketigakan kegiatan pelayanan kesehatan, saya coba kirim catatan kecil dari RPP
Sebagai Negara Kesatuan, maka penanggungjawab akhir pelaksanaan urusan pemerintahan adalah Presiden (Menteri Kesehatan dalam bidang Kesehatan) sehingga kewajiban Kementerian Kesehatan sebagai bagian dari pembinaan teknis berupa kegiatan fasilitasi (Pasal 16 UU No.23 tahun 2014) pelaksanaan pembangunan kesehatan di daerah, melalui DAK. Dengan demikian, sambil menunggu PP tentang Pelaksanaan SPM, saya mendukung PKMK terus menggali kemungkinannya dipihak ketigakannya pelayanan kesehatan di daerah dengan dukungan sumber daya dari pusat. |
SeikkaYth. Bapak/Ibu sekalian, Kalau kita lihat peraturan penganggaran baik di APBN maupun di APBD, maka hanya “belanja modal” yang bisa dikontrakkan ke pihak ke-3, sedangkan untuk untuk “program kegiatan” tidak bisa dikontrakkan ke pihak ke-3.
|
SeikkaIjinkan saya menyampaikan pendapat untuk kedua kalinya. Kalau untuk meningkatkan penyerapan anggaran sektor kesehatan, maka perlu melibatkan masyarakat, NGO, kelompok profesi bidang kesehatan, dan swasta, dengan mendorong mereka harus terorganisir dalam badan hukum sehingga mereka bisa ikut tender/dikontrak. demikian
|
Harmein HarunProf. Laksono, Pak Dwi Handono. Saya sangat setuju dengan konsep ini mengingat alokasi pembiayaan operasional Puskesmas pada umumnya dilakukan berdasarkan alokasi orang hari; sementara tidak semua Puskesmas memiliki jumlah personil yang cukup. Pada tahun 1992 pernah dibahas konsep “Transforming in Primary Health Care” dengan pola contracting out ini, tetapi disebut sebagai suatu konsep yang terlalu radikal pada saat itu. Perlu bahasan secara teknis dan persyaratan lainnya untuk contracting out ini. Berikut saya sampaikan beberapa link untuk download berbagai pedoman/standard dan persyaratan yang digunakan oleh UK NHS sebagai berikut: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/406204/Guidance.pdf Dalam website tersebut terdapat lagi berbagai link untuk hal yang lebih teknis. Wassalam, Harmein Harun
|
Harmein HarunProf. Laksono dan Pak Dwi Handono Ijinkan saya menambahkan informasi tentang hasil Laporan Sensus Infrastruktur yang dipublikasikan tahun 2014 yang menyebutkan bahwa : Apakah wilayah 383 kecamatan ini tidak berhak mendapatkan biaya operasional Puskesmas karena tidak memiliki Puskesmas? Apakah Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mampu melakukan kegiatan outreach untuk primary care? Wassalam,
|
{/tabs}


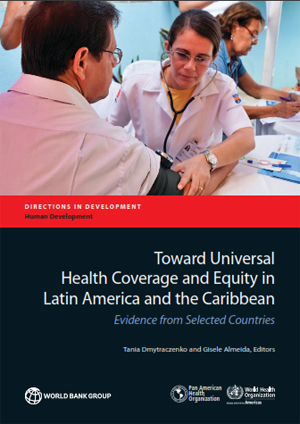
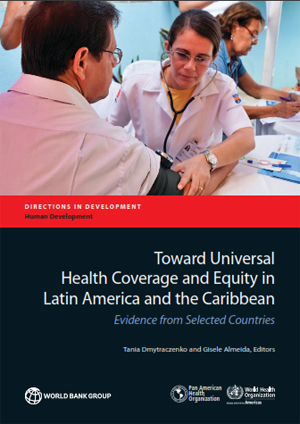 Selama tiga dekade terakhir, banyak negara Amerika Latin dan Karibia (LAC) telah mengakui bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan mengambil langkah strategis atas pengakuan itu. Negara-negara tersebut telah mengubah Undang-Undang untuk menjamin hak kesehatan warganya. Sebagian besar telah meratifikasi konvensi internasional dengan menetapkan dengan mengimplementasikan secara terus-menerus dan adil bahwa hak kesehatan merupakan kewajiban negara.
Selama tiga dekade terakhir, banyak negara Amerika Latin dan Karibia (LAC) telah mengakui bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan mengambil langkah strategis atas pengakuan itu. Negara-negara tersebut telah mengubah Undang-Undang untuk menjamin hak kesehatan warganya. Sebagian besar telah meratifikasi konvensi internasional dengan menetapkan dengan mengimplementasikan secara terus-menerus dan adil bahwa hak kesehatan merupakan kewajiban negara.