Parallel 1
Bagaimana mengatasi Defisit BPJS: Jangka pendek dan Jangka Panjang

Sesi diskusi paralel pertama membahas tentang bagaimana isu dan cara mengatasi defisit BPJS pada periode jangka pendek dan jangka panjang. Sesi ini merupakan agenda forum nasional ketujuh kebijakan kesehatan Indonesia yang diadakan di Universitas Gadjah Mada. Agenda hari pertama fornas ini menghadirkan pembicara pakar yang berhubungan dengan aspek kompleksitas JKN dari kacamata permasalahan defisit pada BPJS. Pembahas sesi ini terdiri dari dr. Kalsum Komaryani, MPPM (Kepala Pusat Pebiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kemenkes RI), Dr. Taufik Hidayat, MM, AKK (Ketua Umum Perkumpulan Ahli Manajemen Jaminan dan Asuransi Kesehatan Indonesia), Andayani Budii Lestari, SE. MM, AKK (Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan) dan Dr. DRs, Zulendri, M.Kes (FKM USU). Acara ini dimoderasi oleh Budi Eko Siswoyo, SKM, MPH yang merupakan peneliti dan konsultan tentang pembiayaan kesehatan dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM. Selain itu, acara tahunan ini dihadiri oleh praktisi kebijakan kesehatan, dosen, BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan Indonesia dan mahasiswa.
Keseimbangan antara revenue collection dan expenditure merupakan variabel utama dalam kesinambungan pembiayaan JKN untuk menghindari mismatch. Hingga saat ini, cakupan kepesertaan JKN pada tahun keempat berjalannya sistem JKN oleh BPJS yakni 70%. Namun, apakah ini merupakan aspek positif dalam menurunkan efek negatif dari defisit atau mismatch ? Di sisi lain, beberapa data dan riset menyebutkan bahwa terdapat peningkatan utilitas penggunaan fasilitas kesehatan mulai dari jenjang FKTP hingga FKTL. Di aspek pemanfaatan layanan, penyakit-penyakit katastropik yang bersifat jangka panjang merupakan permasalahan yang tentunya akan mengakibatkan defisit sistem JKN pada BPJS. Dari sisi kepesertaan, proporsi PBI memiliki kuantitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan non PBI. Namun, dalam pemanfaatan layanan, non PBI memiliki proporsi yang lebih tinggi dibandingkan pada anggota PBI sehingga ini akan mengakibatkan inequality pada penerima layanan khususnya pada kelompok PBI.
Berdasarkan pemaparan dr. Kalsum Komaryani, MPPM, isu defisit pada BPJS merupakan topik yang paling esensial saat ini. Pada utamanya, kondisi dana jaminan sosial berada pada neraca yang tidak sehat. Hal ini ditandai dengan adanya defisit pada BPJS dan penyertaan modal negara pada BPJS hingga diproyeksikan sebesar Rp. 12, 7 T pada 2019. Selain itu, telah dilakukan telaah dalam analisis defisit yang terjadi pada BPJS. Berdasarkan hal tersebut, revisi regulasi mulai dari Peraturan Presiden merupakan langkah yang sedang didalami. Kondisi defisit atau mismatch pada BPJS pada umumnya disebabkan oleh tidak efektifnya paket untuk PBI dan non PBI, ledakan utilisasi kasus katastropik dalam layanan JKN oleh non PBI khususnya PBPU. Patut disadari bahwa premi JKN saat ini masih under price. Mismatch akan tetap terjadi apabila pembayaran premi dibayarkan 100% oleh masyarakat Indonesia. Untuk itu, unifikasi dan regulasi berbagai regulasi sangat perlu direalasasikan dalam perbaikan neraca keuangan BPJS. Menurut Dr. Drs. Zulfendri, M. Kes, topik defisit pada BPJS merupakan isu yang harus segera diselesaikan dalam waktu dekat untuk optimalitas layanan keberlanjutan yang berkualitas pada program BPJS. Edukasi dan peningkatan kesadaran pada pengguna layanan JKN adalah salah satu aspek utama untuk efektifitas perbaikan neraca anggaran BPJS.
Perlu ada regulasi dan tindakan spesifik dalam menangani permasalahan mismatch di BPJS. Menurut Andayani Budi Lestari, SE, MM, AAK., tren peningkatan utilisasi pada era BPJS memiliki efek negatif dalam peningkatan beban pembiayaan pada BPJS Kesehatan. Pada dasarnya, UHC dan peningkatan kepatuhan peserta dalam keberlanjutan pembayaran premi merupakan pilihan dalam mengurangi aspek mismatch pada pembiayaan di BPJS Kesehatan. Selain itu, dr. Taufik Hidayat, MM, AAK. menyatakan bahwa prinsip sosial dan gotong royong harus selalu digaungkan pada era JKN saat ini. Perlu disosialisasikan ke pengguna layanan bahwa premi yang dibayarkan akan membantu masyarakat dalam menjaga kualitas kesehatan masyarakat lainnya.
Diskusi panel ini menekankan bahwa saat ini keadaan mismatch atau keadaan defisit pada BPJS merupakan alarm pada sistem jaminan kesehatan nasional di Indonesia. Untuk itu, perlu ada langkah yang jelas dan spesifik terhadap permasalahan mismatch atau defisit yang tentunya secara tidak langsung akan mempengaruhi terhadap mutu dan layanan pada sistem JKN. Selain itu, regulasi yang jelas tentang pelayanan, unifikasi pembiayaan pada fasilitas kesehatan, peningkatan kepesertaan yang bersifat adil dan edukasi untuk meningkatkan resistensi peserta dalam pembayaran premi merupakan beberapa aspek krusial yang diharapkan dapat menjadi pilihan jawaban dalam kondisi neraca pembiayaan defisit pada BPJS Kesehatan.
Reporter: Nopryan Ekadinata
Parallel 2
Konsep Dan Riset Implementasi Terhadap Penyelangaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional

Pada Parallel Session 2 ini terdiri dari 4 orang pembahas, diawali dengan topik Implementation Research. Pembahas pertama adalah Dr. Yodi Mahendradhata, M.Sc, Ph.D. Saat ini merupakan Wakil Dekan Bidang Penelitian dan Pengembangan Fakultas Kedokteran UGM.
MATERI
Riset implementasi dalam dunia kesehatan merupakan riset yang baru berkembang selama sepuluh tahun terakhir. Dalam dunia riset implementasi dikenal dengan berbagai macam mazhab atau aliran dimana mazhab tersebut mempunyai sifat yang sedikit berbeda-beda sehingga apabila kita tidak dapat memahami mazhab tersebut dengan baik maka akan mengakibatkan kebingungan, adapun 2 mazhab yang berbenturan adalah riset implementasi yang mucul dari dunia political science atau lebih dikenal dengan Policy Implementation Riset dengan riset implementasi yang muncul dari literatur dunia kedokteran Evidence Base Medicine. Kedua riset implementasi ini mempunyai persamaan namun lebih memiliki banyak perbedaan sehingga mengakibatkan banyaknya benturan, apabila dianalogikan Implementation Scientists dari planet Mars sedangkan policy implementation researchers dari planet Venus dimana mereka berbicara dalam bahasa yang berbeda sehingga tidak sedikit membuat banyak orang bingung terutama bagi yang baru mempelajarinya.
Pada topik selanjutnya yaitu Manfaat dan Tantangan Riset Implementasi Bagi Kebijakan: Perspektif Pemangku Kepentingan. Pembahasnya adalah drg. Doni Arianto, MKM.
Salah satu kendala di era sebelum JKN dimana puskesmas didesain dengan hanya melakukan pelayanan sehingga setelah era JKN puskesmas merasa kesulitan dalam memberikan inovasi atau memberikan hal-hal yang sifatnya berbeda untuk mengembangkan puskesmas itu sendiri. Saat ini puskesmas bingung dalam mengelola anggarannya sendiri karena masih saja berkutat dengan sistem administrasi tentang bagaimana membuat pertanggungjawaban untuk penggunaan anggaran yang diberikan pemerintah untuk puskesmas.
MATERI
Regulasi merupakan hal yang penting pada era JKN saat ini. Diawal pembuatan regulasi tentang pemanfaatan dana puskesmas, dimana regulasi ini bersifat mengambang, tujuannya tidak lain yaitu memberi kebebasan puskesmas untuk melakukan hal yang mereka inginkan dengan kata lain dapat mengelola anggaran yang ada sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan puskesmas, namun realita yang terjadi dilapangan tenaga di puskesmas tidak mau melakukan kegiatan itu, karena merasa bahwa kalau kebijakan tersebut mengambang maka pihak puskesmas tidak mempunyai kepastian regulasi dalam membelanjakan anggarannya, namun dilain pihak regulasi itu memberikan dampak yang positif bagi beberapa puskesmas dengan memanfaatkan secara bijak anggaran guna pengembangan dan keberlangsungan dalam memberikan pelayanan yang bermutu. Dengan adanya hasil riset implementasi diharapkan dapat digunakan sebagai standar atau acuan dalam pembuatan regulasi yang baik bagi puskesmas.
Pada topik selanjutnya yaitu Proses Pembelajaran untuk Menguatkan Penyelenggaraan JKN. Pembahas adalah Edhie Santosa Rahmat, MD, MSc. Saat ini merupakan Penasehat untuk Penguatan Sistem KesehatanUSAID Indonesia.
MATERI
Kebijakan dibuat untuk memperbaiki sistem kesehatan tetapi selalu ada tantangan dalam pengimplementasiannya termasuk dalam pengimplementasian sistem JKN. Manfaat dari Riset implementasi terhadap suatu kebijakan yaitu menilai bagaimana tantangan serta realita yang ada di lapangan terkait suatu kebijakan sehinga diharapkan dapat menjawab apakah dilaksanakan sesuai rencana, Faktor apa yang mengganggu di tengah jalan, apakahdampak yang diinginkan tercapai, Adakah akibat sampingan yang terjadi? Bagaimana memperbaiki? serta Bisakah cara itu diperkuat/disebarkan?.
Realita dilapangan dalam Implementation Research banyak menemukan tantangan sehingga untuk harapan semua pihak serta para pembuat kebijakan bekerja sama dengan peneliti untuk melakukan riset implementasi yang nantinya akan memperoleh proses pembelajaran berupa riset sebagai bagian proses pengambilan kebijakan, belajar dan berkolaborasi memecahkan masalah, serta berusaha untuk tidak terikat oleh sumber daya agar semuanya berjalan baik.
Pada akhir sesi yaitu Kontribusi Keilmuan dan Kebijakan: Pembelajaran dari Implementasi Kebijakan Kapitasi di 5 Kabupaten/Kota di Indonesia. Dengan pembahas adalah dr. Likke Prawidya Putri, MPH. Saat ini merupakan peneliti PKMK FK UGM.
MATERI
Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penerapan sistem JKN saat ini memberikan dampak pada pelayanan primer, dimana dampak yang paling besar terjadi pada 2 sektor yaitu yang pertama adalah berupa sistem pembayaran dimana sebelum era JKN menggunakan metode Fee for service yaitu pembayaran sesuai dengan pelayanan yang diberikan, sedangkan setelah era JKN metode yang digunakan adalah Kapitasi yaitu berdasarkan jumlah dokter, dokter gigi, rasio nakes dan populasi, untuk sektor kedua yang mengalami perubahan yaitu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) sebagai Gatekeeper dimana sebelum era JKN fungsi gatekeeping belum ada ketentuan mutlak jenis diagnosis penyakit sedangkan setelah era JKN fungsi gatekeeping sudah dengan 144 diagnosis penyakit yang wajib ditangani di pelayanan primer.
Dalam penelitian tentang riset pengimplementasian ini diperoleh manfaat yaitu bagaimana suatu peraturan itu dapat disebarkan dengan baik sesuai dengan kondisi daerah masing-masing, manfaat selanjutnya apabila dilihat dari kacamata peneliti yaitu dapat memetakan atau mengelompokan permasalahan-permasalahan yang ada, apakah masuk dalam kelompok eksternal atau internal, dan juga kelompok individu atau proses.
Oleh: Ikhsan Amir

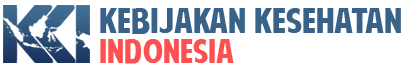



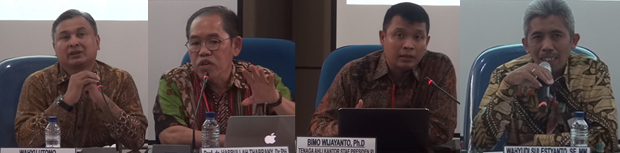




 Sesi yang membahas Evaluasi Kebijakan dan dan Equity dipandu oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD menghadirkan Staf Ahli Bidang Pembiayaan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesi dr. Donald Pardede, MPPM yang menggantikan Menteri Kesehatan yang pada kesempatan ini berhalangan hadir karena ada kegiatan di Istana Mendeka.
Sesi yang membahas Evaluasi Kebijakan dan dan Equity dipandu oleh Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., PhD menghadirkan Staf Ahli Bidang Pembiayaan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesi dr. Donald Pardede, MPPM yang menggantikan Menteri Kesehatan yang pada kesempatan ini berhalangan hadir karena ada kegiatan di Istana Mendeka.

