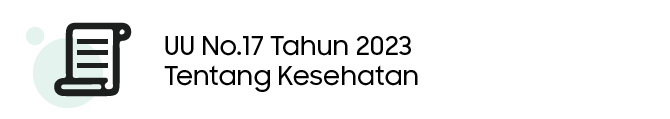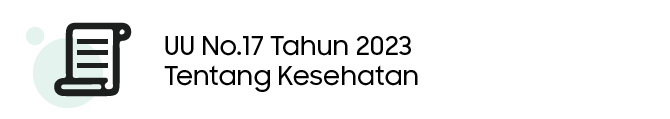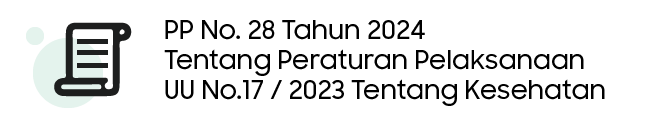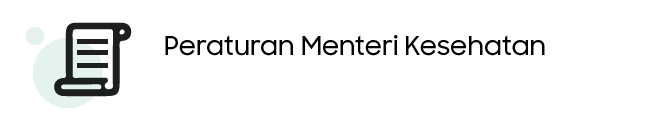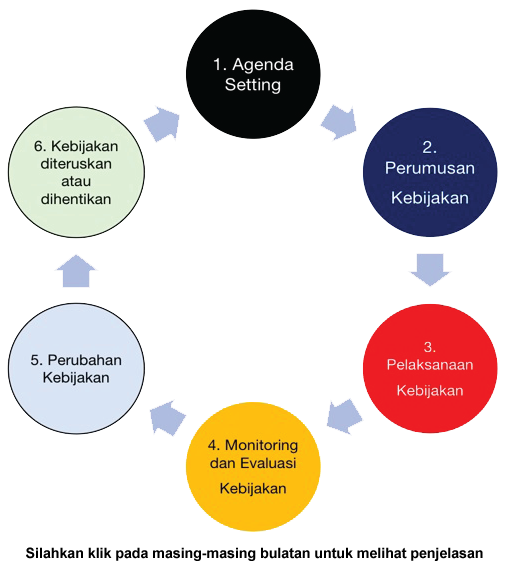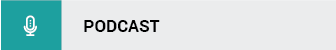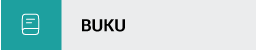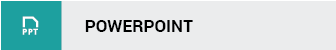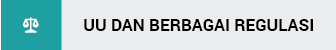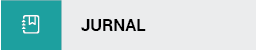Selasa, 19 November 2024
Research that should matter at Primary Health Care level: linking demand and supply in Asia Pacific
Hari kedua HSR2024 diisi dengan kegiatan seminar, diskusi panel, dan peningkatan kapasitas. Hari ini juga menandai pembukaan resmi kegiatan HSR2024 di Nagasaki yang diisi dengan sesi pleno. Reportase ini mendokumentasikan berbagai kegiatan yang merupakan bagian dari rangkaian hari kedua HSR2024.
Salah satu kegiatan di hari kedua adalah sesi satellite bertajuk “Advancing learning systems for health in the Asia-Pacific Region through health policy and systems research”. Sesi ini berisi pemaparan dan diskusi kelompok. Sesi ini menghadirkan empat pemapar dari beragam institusi.
Pembukaan
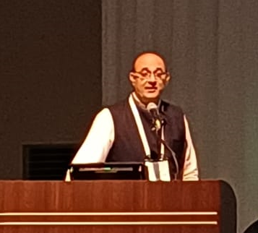 Sesi ini dibuka oleh Dr Nima Asgari, direktur Asia Pacific Observatory (APO). Dalam pemaparannya, Asgari memperkenalkan APO sebagai suatu kemitraan yang mendukung evidence-informed health system policy di tingkat kawasan maupun nasional. Lebih jauh lagi, Asgari menjelaskan lima klaster tematik APO, yakni (1) Primary Health Care (PHC) untuk mendukung pencapaian Universal Health Coverage (UHC); (2) ketahanan sistem kesehatan; (3) kesehatan digital (memanfaatkan teknologi dan data untuk meningkatkan hasil kesehatan); (4) Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK), yang dirancang untuk kebutuhan kini dan nanti; serta (5) ketimpangan dalam kesehatan (aspek gender dan inklusi sosial dan aspek hard-to-reach). Untuk memperkuat kolaborasi, APO mendorong keterlibatan organik berbagai pihak melalui penyelenggaraan acara dan prakarsa, termasuk pembentukan local chapters yang melibatkan peneliti, organisasi kebijakan kesehatan, lembaga penelitian, pekerja kesehatan, pembuat kebijakan lokal, dan pemerintah.
Sesi ini dibuka oleh Dr Nima Asgari, direktur Asia Pacific Observatory (APO). Dalam pemaparannya, Asgari memperkenalkan APO sebagai suatu kemitraan yang mendukung evidence-informed health system policy di tingkat kawasan maupun nasional. Lebih jauh lagi, Asgari menjelaskan lima klaster tematik APO, yakni (1) Primary Health Care (PHC) untuk mendukung pencapaian Universal Health Coverage (UHC); (2) ketahanan sistem kesehatan; (3) kesehatan digital (memanfaatkan teknologi dan data untuk meningkatkan hasil kesehatan); (4) Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK), yang dirancang untuk kebutuhan kini dan nanti; serta (5) ketimpangan dalam kesehatan (aspek gender dan inklusi sosial dan aspek hard-to-reach). Untuk memperkuat kolaborasi, APO mendorong keterlibatan organik berbagai pihak melalui penyelenggaraan acara dan prakarsa, termasuk pembentukan local chapters yang melibatkan peneliti, organisasi kebijakan kesehatan, lembaga penelitian, pekerja kesehatan, pembuat kebijakan lokal, dan pemerintah.
Pembicara pertama
 Pembicara pertama pada sesi ini adalah Manoj Jhalani, direktur Health Systems Development, WHO SEARO. Jhalani membuka paparannya dengan menggambarkan pelajaran penting dari pandemi COVID-19, yakni bahwa investasi awal dalam fondasi PHC untuk kesiapsiagaan dan respons adalah hal yang penting. Pandemi juga menegaskan pentingnya efisiensi PHC dalam mencapai UHC, keterlibatan komunitas, serta kolaborasi multisektoral. Komitmen politik terhadap PHC sebagai dasar UHC telah mendapat momentum, dimulai dari deklarasi Menteri Kesehatan Asia Tenggara pada bulan September 2021, yang menyebut pandemi sebagai pendorong transformasi sistem kesehatan berbasis PHC. Deklarasi ini diperkuat dalam pertemuan UNGA 2023, KTT G20, hingga Delhi Declaration pada Oktober 2023 yang menegaskan PHC sebagai elemen kunci UHC. Berbagai negara di kawasan Asia Tenggara juga telah memprioritaskan PHC dan menerbitkan kebijakan pendukung. Selain itu, Forum PHC, seperti yang baru-baru ini digelar di Jakarta, memfasilitasi pertukaran praktik baik antarnegara, memperkuat budaya sistem kesehatan yang terus belajar dan berinovasi sesuai konteks lokal.
Pembicara pertama pada sesi ini adalah Manoj Jhalani, direktur Health Systems Development, WHO SEARO. Jhalani membuka paparannya dengan menggambarkan pelajaran penting dari pandemi COVID-19, yakni bahwa investasi awal dalam fondasi PHC untuk kesiapsiagaan dan respons adalah hal yang penting. Pandemi juga menegaskan pentingnya efisiensi PHC dalam mencapai UHC, keterlibatan komunitas, serta kolaborasi multisektoral. Komitmen politik terhadap PHC sebagai dasar UHC telah mendapat momentum, dimulai dari deklarasi Menteri Kesehatan Asia Tenggara pada bulan September 2021, yang menyebut pandemi sebagai pendorong transformasi sistem kesehatan berbasis PHC. Deklarasi ini diperkuat dalam pertemuan UNGA 2023, KTT G20, hingga Delhi Declaration pada Oktober 2023 yang menegaskan PHC sebagai elemen kunci UHC. Berbagai negara di kawasan Asia Tenggara juga telah memprioritaskan PHC dan menerbitkan kebijakan pendukung. Selain itu, Forum PHC, seperti yang baru-baru ini digelar di Jakarta, memfasilitasi pertukaran praktik baik antarnegara, memperkuat budaya sistem kesehatan yang terus belajar dan berinovasi sesuai konteks lokal.
Pembicara kedua
 Sesi dilanjutkan dengan pemaparan dari Lluis Vinyals Torres, direktur Health Systems and Services WHO WPRO. Torres mengawali paparannya dengan menekankan kebutuhan terhadap PHC. Model pelayanan kesehatan yang ada saat ini tidak mampu menangani volume perawatan yang timbul terkait dengan tingginya beban penyakit tidak menular (PTM) dan ageing population. Isu perawatan jangka panjang, yang membutuhkan tenaga kerja dan model layanan yang memadai, juga perlu menjadi perhatian utama dalam konteks populasi yang menua. Torres juga mengatakan bahwa dengan ekonomi Asia Tenggara yang tumbuh pesat dan masyarakat yang semakin sadar akan kesehatan, PHC harus lebih responsif dan mampu membangun hubungan saling percaya yang berkelanjutan antara pasien dengan penyedia layanan kesehatan. Perubahan-perubahan ini menuntut pendekatan baru dalam mengorganisasi PHC untuk memastikan kebutuhan kesehatan terpenuhi secara efektif.
Sesi dilanjutkan dengan pemaparan dari Lluis Vinyals Torres, direktur Health Systems and Services WHO WPRO. Torres mengawali paparannya dengan menekankan kebutuhan terhadap PHC. Model pelayanan kesehatan yang ada saat ini tidak mampu menangani volume perawatan yang timbul terkait dengan tingginya beban penyakit tidak menular (PTM) dan ageing population. Isu perawatan jangka panjang, yang membutuhkan tenaga kerja dan model layanan yang memadai, juga perlu menjadi perhatian utama dalam konteks populasi yang menua. Torres juga mengatakan bahwa dengan ekonomi Asia Tenggara yang tumbuh pesat dan masyarakat yang semakin sadar akan kesehatan, PHC harus lebih responsif dan mampu membangun hubungan saling percaya yang berkelanjutan antara pasien dengan penyedia layanan kesehatan. Perubahan-perubahan ini menuntut pendekatan baru dalam mengorganisasi PHC untuk memastikan kebutuhan kesehatan terpenuhi secara efektif.
Torres memberikan contoh area tematik produksi pengetahuan yang relevan dengan tujuan di atas. Dalam konteks SDMK, selain terkait dengan ketersediaan dan maldistribusi, hal yang tidak kalah penting untuk dikaji adalah ketiadaan data dasar SDMK. Terkait dengan sistem informasi, fragmentasi sistem dan tingginya beban pengisian data menjadi isu. Torres menekankan bahwa pertukaran pengetahuan perlu terjadi antarnegara maupun antar unit dalam negara (misalnya provinsi). Dalam hal supply chain, isu mendasar yang diamati oleh Torres adalah bahwa kesehatan seringkali diatur oleh mekanisme pasar yang mempengaruhi ketersediaan item-item yang, kendati esensial, dianggap tidak mendatangkan keuntungan komersial. Torres menutup pemaparannya dengan memberikan pesan kunci bahwa pengetahuan yang diproduksi perlu diterjemahkan dan dikomunikasikan pada pembuat kebijakan, sehingga peran perantara kebijakan sangat dibutuhkan.
Pembicara ketiga
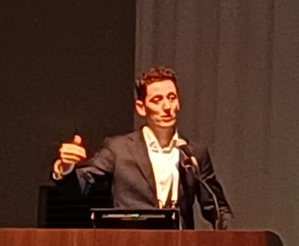 Pembicara terakhir dalam sesi ini adalah Dr Jasper Tromp dari National University of Singapore School of Public Health. Tromp memaparkan hasil kajiannya tentang lanskap penelitian PHC di Asia Tenggara (SEAR) dan Pasifik Barat (WPR) dan potensi menutup kesenjangan antara produksi pengetahuan dengan implementasi. Studi ini menggunakan metode systematic mapping artikel ilmiah yang dipublikasi dalam 10 tahun terakhir dalam bahasa Inggris atau Cina, diikuti dengan presentasi hasil awal dan workshop untuk mendiskusikan hasil tersebut.
Pembicara terakhir dalam sesi ini adalah Dr Jasper Tromp dari National University of Singapore School of Public Health. Tromp memaparkan hasil kajiannya tentang lanskap penelitian PHC di Asia Tenggara (SEAR) dan Pasifik Barat (WPR) dan potensi menutup kesenjangan antara produksi pengetahuan dengan implementasi. Studi ini menggunakan metode systematic mapping artikel ilmiah yang dipublikasi dalam 10 tahun terakhir dalam bahasa Inggris atau Cina, diikuti dengan presentasi hasil awal dan workshop untuk mendiskusikan hasil tersebut.
Studi ini menemukan bahwa publikasi penelitian PHC di SEAR dan WPR meningkat sejak tahun 2014 dan mencapai puncaknya pada kisaran tahun 2020. Jika didisagregasi per negara, penelitian sebagian besar berasal dari Australia, China, dan India, diikuti oleh Malaysia, Selandia Baru, Singapura, dan Jepang. Beberapa negara, seperti Maladewa dan negara-negara Pasifik memiliki jumlah publikasi yang sangat rendah atau bahkan tidak ada sama sekali. Fokus penelitian di negara berpenghasilan tinggi (HIC) cenderung pada PTM, sementara negara berpenghasilan menengah dan rendah (LMIC) lebih banyak meneliti kesehatan ibu dan anak (MCH). Studi ini juga menemukan bahwa sebagian besar penelitian memiliki fokus penyampaian layanan, namun belum banyak yang berfokus pada sistem informasi kesehatan, kepemimpinan dan tata kelola, serta pembiayaan kesehatan. Pendanaan penelitian PHC di negara HIC didominasi oleh sumber domestik, sementara di LMIC dan negara-negara kepulauan Pasifik (PIC), proporsi pendanaan domestik jauh lebih rendah. Outcome penelitian sebagian besar berfokus pada kualitas dan efektivitas layanan., sementara outcome terkait keselamatan, akses atau cakupan layanan, serta responsivitas layanan belum banyak tersentuh.
Studi ini mengidentifikasi beberapa faktor yang menjadi tantangan dalam produksi penelitian PHC yang berkualitas. Pertama, penelitian sering kali tidak menjadi prioritas pembuat kebijakan dan lebih didorong oleh mitra pembangunan eksternal. Oleh karena itu, prioritas nasional untuk penelitian PHC perlu ditetapkan. Kedua, SDMK, terutama di fasilitas kesehatan, sering kekurangan waktu dan sumber daya untuk melakukan penelitian. Mengaitkan penelitian PHC dengan jenjang karier dianggap dapat menjadi solusi alternatif. Ketiga, pembatasan regulasi dan struktur penelitian, termasuk akses terbatas ke Institutional Review Boards (IRB), juga menjadi tantangan. Terakhir, terdapat kesenjangan signifikan antara peneliti dan orang-orang yang bekerja di lapangan, sehingga pertanyaan penelitian sering tidak relevan atau tepat waktu. Untuk mengatasi ini, diperlukan penguatan hubungan antara pemerintah, akademisi, klinisi, dan konsumen melalui community of practice dan kolaborasi penelitian. Selain itu, studi juga memberikan rekomendasi pendanaan domestik yang selaras dengan prioritas nasional untuk mendukung produksi penelitian PHC yang berkualitas.
Ketiga sesi ini kemudian diakhiri dengan sesi tanya-jawab dan diskusi berkelompok. Pada sesi tanya jawab, muncul pembahasan tentang diskoneksi antara peneliti dengan orang-orang yang bekerja di lapangan, tekanan politis untuk mengatasi permasalahan di lapangan, dan pentingnya pendekatan interdisiplin. Dalam kegiatan diskusi kelompok, timbul bahasan-bahasan tentang hal-hal yang mendukun kolaborasi dan penyelarasan riset PHC di tingkat nasional berdasarkan pengalaman berbagai negara. Konsep konsorsium PHC yang ada di Indonesia mendapatkan perhatian dari para peserta. Sesi ditutup dengan perenungan terkait kebijakan berbagi data riset PHC dan peninjauan kembali peran dan posisi seorang perantara kebijakan.
Planetary Health
Sesi pleno hari ini dibuka oleh Adnan Hyder (profesor dalam bidang kesehatan global di Milken Institute School of Public Health, The George Washington University), Steph Topp (profesor dalam bidang kesehatan global dan pembangunan di James Cook University Australia) dan Keizo Takemi (Menteri Kesehatan Jepang). Sambutan kegiatan ini memunculkan isu-isu untuk direnungkan, seperti misinformasi dan tekanan politik sebagai tantangan utama sains. Resiliensi menjadi kunci untuk melindungi integritas dan kredibilitas sains. Di samping tantangan bagi perkembangan sains, sistem kesehatan sebagai entitas yang kompleks dan politis perlu dipahami dan dioptimasi dengan upaya kolektif guna meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

Sesi Pleno
Sesi pleno dibuka dengan pemaparan dari tiga pembicara dan dilanjutkan dengan diskusi panel. Pembicara dalam sesi ini terdiri atas Helen Clark (mantan Perdana Menteri Selandia Baru), Shweta Narayan (campaign lead, Global Climate and Health Alliance), dan Susannah Mayhew (London School of Hygiene & Tropical Medicine co-chair technical working group resiliensi iklim dan sistem kesehatan berkelanjutan).
 Sebagai pembicara pertama, Clark mengatakan bahwa perubahan iklim sebagai ancaman serius kesehatan global telah diakui oleh WHO dan didokumentasikan dalam berbagai laporan. Selain itu, ancaman pandemi telah membuat jutaan orang menjadi rentan secara ekonomi. Kegagalan kebijakan, ketimpangan, dan ketidakadilan dalam menghadapi perubahan iklim harus menjadi perhatian utama. Kajian sistem kesehatan perlu meliputi peran pemerintah dan siapa yang seharusnya mengambil keputusan untuk menjaga keberlanjutan kesehatan iklim, termasuk mengeksplorasi upaya untuk mengurangi jejak karbon. Clark menutup pemaparannya dengan menekankan kolaborasi lintas sektor dan perlunya peran komunitas health policy and systems research (HPSR) harus mengambil peran aktif dalam membawa perubahan, memperbaiki komunikasi kesehatan dan sains kepada publik, serta melawan narasi anti-kesehatan dan anti-sains.
Sebagai pembicara pertama, Clark mengatakan bahwa perubahan iklim sebagai ancaman serius kesehatan global telah diakui oleh WHO dan didokumentasikan dalam berbagai laporan. Selain itu, ancaman pandemi telah membuat jutaan orang menjadi rentan secara ekonomi. Kegagalan kebijakan, ketimpangan, dan ketidakadilan dalam menghadapi perubahan iklim harus menjadi perhatian utama. Kajian sistem kesehatan perlu meliputi peran pemerintah dan siapa yang seharusnya mengambil keputusan untuk menjaga keberlanjutan kesehatan iklim, termasuk mengeksplorasi upaya untuk mengurangi jejak karbon. Clark menutup pemaparannya dengan menekankan kolaborasi lintas sektor dan perlunya peran komunitas health policy and systems research (HPSR) harus mengambil peran aktif dalam membawa perubahan, memperbaiki komunikasi kesehatan dan sains kepada publik, serta melawan narasi anti-kesehatan dan anti-sains.
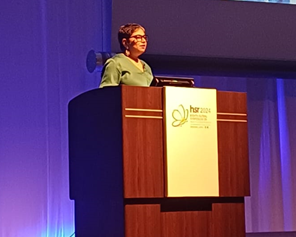 Selanjutnya, Narayan memantik dengan penekanan bahwa dunia saat ini menghadapi triple planetary crisis yang terdiri atas perubahan iklim, polusi (udara, air, dan tanah), serta hilangnya keanekaragaman hayati. Krisis iklim sudah terjadi sejak sekarang. Salah satu aspek yang dianggap paling merugikan adalah polusi udara akibat penggunaan bahan bakar fosil, dengan perkiraan biaya hingga 6% dari pendapatan domestik bruto (PDB) global. Narayan juga menyayangkan bahwa negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, yang memiliki kontribusi paling kecil dalam menyebabkan masalah ini, justru menjadi paling rentan terhadap dampaknya.
Selanjutnya, Narayan memantik dengan penekanan bahwa dunia saat ini menghadapi triple planetary crisis yang terdiri atas perubahan iklim, polusi (udara, air, dan tanah), serta hilangnya keanekaragaman hayati. Krisis iklim sudah terjadi sejak sekarang. Salah satu aspek yang dianggap paling merugikan adalah polusi udara akibat penggunaan bahan bakar fosil, dengan perkiraan biaya hingga 6% dari pendapatan domestik bruto (PDB) global. Narayan juga menyayangkan bahwa negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah, yang memiliki kontribusi paling kecil dalam menyebabkan masalah ini, justru menjadi paling rentan terhadap dampaknya.
 Melanjutkan pemaparan Narayan, Mayhew menjelaskan bahwa upaya mitigasi krisis iklim belum banyak berfokus pada sistem kesehatan. Mayhew juga menggunakan contoh Pandemi COVID-19 untuk membandingkan responsivitas pemerintahan di berbagai belahan dunia. COVID-19 ditanggapi dengan sangat cepat, namun banyak pemerintahan lambat menanggapi isu perubahan iklim. Selain itu, penurunan emisi yang terjadi di masa pandemi akibat restriksi mobilisasi sulit untuk dipertahankan tanpa perubahan paradigma ekonomi yang saat ini masih sangat bergantung pada teknologi berbasis fosil. Untuk mengatasi ini dan mencapai keadilan ekologi, Global Green New Deal diluncurkan. Mayhew menutup paparannya dengan menekankan bahwa sistem kesehatan yang tangguh, berkelanjutan, dan adil memerlukan langkah-langkah seperti memperluas visi dan kemitraan, berkontribusi pada tata kelola lintas sektor, penelitian yang lebih inklusif, pembiayaan inovatif ex ante, komitmen donor, model kepemimpinan baru, serta platform baru untuk produksi bukti (evidence) maupun memfasilitasi tindakan.
Melanjutkan pemaparan Narayan, Mayhew menjelaskan bahwa upaya mitigasi krisis iklim belum banyak berfokus pada sistem kesehatan. Mayhew juga menggunakan contoh Pandemi COVID-19 untuk membandingkan responsivitas pemerintahan di berbagai belahan dunia. COVID-19 ditanggapi dengan sangat cepat, namun banyak pemerintahan lambat menanggapi isu perubahan iklim. Selain itu, penurunan emisi yang terjadi di masa pandemi akibat restriksi mobilisasi sulit untuk dipertahankan tanpa perubahan paradigma ekonomi yang saat ini masih sangat bergantung pada teknologi berbasis fosil. Untuk mengatasi ini dan mencapai keadilan ekologi, Global Green New Deal diluncurkan. Mayhew menutup paparannya dengan menekankan bahwa sistem kesehatan yang tangguh, berkelanjutan, dan adil memerlukan langkah-langkah seperti memperluas visi dan kemitraan, berkontribusi pada tata kelola lintas sektor, penelitian yang lebih inklusif, pembiayaan inovatif ex ante, komitmen donor, model kepemimpinan baru, serta platform baru untuk produksi bukti (evidence) maupun memfasilitasi tindakan.
Acara dilanjutkan dengan sesi diskusi yang dimoderatori oleh Renzo Guinto, associate professor SingHealth Duke-NUS Global Health Institute. Sesi diskusi ini memunculkan gagasan tentang peran komunikasi kesehatan dalam isu iklim. Komunitas kesehatan telah terlibat dalam negosiasi iklim, seperti di Paris Agreement, untuk memastikan isu kesehatan menjadi perhatian dalam tata kelola iklim global. Berbagai bukti sejarah, seperti upaya yang dilakukan oleh John Snow untuk menemukan penyebab kolera di Inggris, menunjukkan bahwa komunitas kesehatan memiliki peran strategis dalam memperjuangkan kebijakan berbasis bukti yang berorientasi pada kesehatan masyarakat. Selain itu, pandemi COVID-19 menunjukkan bahwa kesehatan bisa menjadi topik advokasi yang kuat dalam mendesak aksi cepat berdasarkan bukti di lapangan. Sistem kesehatan dan komunitas penelitian juga perlu direorganisasi untuk mempercepat pengambilan keputusan dan aksi yang lebih responsif terhadap ancaman perubahan iklim.
Sesi pleno dan pembukaan HSR2024 diakhiri dengan pemberian penghargaan kepada insan-insan yang dianggap berprestasi serta berdedikasi dalam bidang HPSR serta penampilan kesenian dari kelompok mahasiswa Nagasaki University.
Reporter:
Mentari Widiastuti (Divisi PH, PKMK FK-KMK UGM)
Link Terkait
- Pra Konferens
- Reportase hari Kedua
- Reportase hari Ketiga
- Reportase hari Keempat
- Reportase Hari Kelima

 Pembicara kedua, yakni Saminarsih, menggarisbawahi peran pelayanan kesehatan primer atau primary health care (PHC) sebagai tulang punggung sistem kesehatan Indonesia. CISDI sebagai sebuah think tank telah mendorong agenda ini selama lebih dari satu dekade dan pada akhirnya diakui oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Pada tahun 2012, CISDI meluncurkan program Pencerah Nusantara untuk menguji perubahan proses bisnis PHC di daerah pedesaan. Prinsip dari program ini kini telah diperluas dan diterapkan hingga ke puskesmas pembantu.
Pembicara kedua, yakni Saminarsih, menggarisbawahi peran pelayanan kesehatan primer atau primary health care (PHC) sebagai tulang punggung sistem kesehatan Indonesia. CISDI sebagai sebuah think tank telah mendorong agenda ini selama lebih dari satu dekade dan pada akhirnya diakui oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Pada tahun 2012, CISDI meluncurkan program Pencerah Nusantara untuk menguji perubahan proses bisnis PHC di daerah pedesaan. Prinsip dari program ini kini telah diperluas dan diterapkan hingga ke puskesmas pembantu.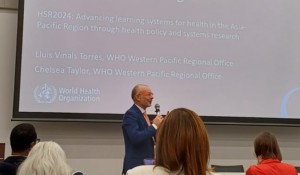 Selanjutnya, Torres membuka paparannya dengan menjelaskan masalah terkait kurangnya kebijakan efektif untuk mengatasi kesulitan finansial akibat layanan kesehatan dan belum optimalnya penyediaan layanan kesehatan dalam konteks penuaan penduduk dan peningkatan prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM). Model pelayanan kesehatan klasik yang bersifat wait and see dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan isu kesehatan saat ini. Selain itu, salah satu tantangan utama dalam mencapai Cakupan Kesehatan Semesta (UHC) adalah keterbatasan SDMK. Memperbaiki masalah SDMK diperkirakan memerlukan waktu setidaknya 10 tahun, sementara banyak negara masih belum memiliki sumber daya dan sistem informasi yang memadai untuk mendukung inisiatif tersebut. SDMK selama ini banyak diatur oleh mekanisme pasar yang menentukan distribusi dan remunerasi SDMK. Meskipun berbagai negara telah menunjukkan praktik-praktik baik, skalanya belum cukup besar. Torres menutup pemaparannya dengan mengajak audiens untuk terus belajar satu sama lain dan terus melakukan penelitian untuk memperbaiki sistem kesehatan secara menyeluruh.
Selanjutnya, Torres membuka paparannya dengan menjelaskan masalah terkait kurangnya kebijakan efektif untuk mengatasi kesulitan finansial akibat layanan kesehatan dan belum optimalnya penyediaan layanan kesehatan dalam konteks penuaan penduduk dan peningkatan prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM). Model pelayanan kesehatan klasik yang bersifat wait and see dianggap tidak lagi relevan dengan perkembangan isu kesehatan saat ini. Selain itu, salah satu tantangan utama dalam mencapai Cakupan Kesehatan Semesta (UHC) adalah keterbatasan SDMK. Memperbaiki masalah SDMK diperkirakan memerlukan waktu setidaknya 10 tahun, sementara banyak negara masih belum memiliki sumber daya dan sistem informasi yang memadai untuk mendukung inisiatif tersebut. SDMK selama ini banyak diatur oleh mekanisme pasar yang menentukan distribusi dan remunerasi SDMK. Meskipun berbagai negara telah menunjukkan praktik-praktik baik, skalanya belum cukup besar. Torres menutup pemaparannya dengan mengajak audiens untuk terus belajar satu sama lain dan terus melakukan penelitian untuk memperbaiki sistem kesehatan secara menyeluruh. Mengawali diskusi panel, Joarder mengatakan bahwa kawasan Asia-Pasifik memiliki populasi yang sangat besar dan kaya akan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan, namun hal ini belum berlangsung optimal. Salah satu masalah utama adalah jeda waktu yang panjang antara proses produksi dan transfer pengetahuan kepada pembuat kebijakan, sehingga menghambat penerapan kebijakan berbasis bukti secara efektif. Melanjutkan pernyataan Joarder, Abimbola mengatakan bahwa learning health systems sejatinya tidak hanya terjadi di tingkat nasional, namun juga unit-unit kecil seperti fasiltias kesehatan. Platform untuk pembelajaran di unit-unit ini harus dioptimalkan agar pengetahuan yang ada di dalam sistem dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Panelis selanjutnya, yakni Reyes, membagikan pengalaman di Filipina, di mana UHC berbasis bukti telah didukung oleh kebijakan nasional. Selain itu, terdapat hibah khusus untuk penelitian promosi kesehatan. Reyes juga menggarisbawahi pentingnya produksi bukti yang dekat dengan episentrum masalah dan menanyakan pertanyaan yang tepat kepada pihak yang tepat. Selain itu, learning health systems harus dikelola oleh pihak yang memiliki kapasitas untuk melakukannya secara berkelanjutan. Saat ini, untuk promosi kesehatan di Filipina, lembaga-lembaga universitas telah mengambil peran dalam mewujudkan hal ini dan membangun kapasitas untuk mendukung implementasi kebijakan yang berbasis bukti.
Mengawali diskusi panel, Joarder mengatakan bahwa kawasan Asia-Pasifik memiliki populasi yang sangat besar dan kaya akan pengetahuan yang dapat dimanfaatkan, namun hal ini belum berlangsung optimal. Salah satu masalah utama adalah jeda waktu yang panjang antara proses produksi dan transfer pengetahuan kepada pembuat kebijakan, sehingga menghambat penerapan kebijakan berbasis bukti secara efektif. Melanjutkan pernyataan Joarder, Abimbola mengatakan bahwa learning health systems sejatinya tidak hanya terjadi di tingkat nasional, namun juga unit-unit kecil seperti fasiltias kesehatan. Platform untuk pembelajaran di unit-unit ini harus dioptimalkan agar pengetahuan yang ada di dalam sistem dapat dimanfaatkan dengan maksimal. Panelis selanjutnya, yakni Reyes, membagikan pengalaman di Filipina, di mana UHC berbasis bukti telah didukung oleh kebijakan nasional. Selain itu, terdapat hibah khusus untuk penelitian promosi kesehatan. Reyes juga menggarisbawahi pentingnya produksi bukti yang dekat dengan episentrum masalah dan menanyakan pertanyaan yang tepat kepada pihak yang tepat. Selain itu, learning health systems harus dikelola oleh pihak yang memiliki kapasitas untuk melakukannya secara berkelanjutan. Saat ini, untuk promosi kesehatan di Filipina, lembaga-lembaga universitas telah mengambil peran dalam mewujudkan hal ini dan membangun kapasitas untuk mendukung implementasi kebijakan yang berbasis bukti. Topik pertama yang dibahas pada sesi ini adalah tentang investasi untuk HPSR. Nagpal mengatakan bahwa kompleksitas sistem kesehatan yang berkembang dan transformasi pembiayaan kesehatan memerlukan asesmen yang tepat tentang area investasi dan kapasitas untuk mengoperasionalkan investasi. Selanjutnya, Takizawa mengatakan bahwa riset sistem kesehatan terkadang dianggap tidak cukup tangible jika dibandingkan dengan riset-riset biomedis. Namun demikian, JICA mulai bergerak untuk mengeksplorasi investasi di bidang HPSR, dengan catatan sumber daya dan konteks lokal harus dipahami dengan baik. Saxena menimpali dengan menjelaskan bahwa USAID Asia Bureau melakukan analisis lanskap untuk menentukan area yang menerima alokasi dana dan masalah utama yang membutuhkan bantuan USAID. Hasil analisis lanskap yang dilakukan USAID juga menunjukkan adanya kesenjangan dalam hal evidence to policy yang mensinyalir pentingnya memperkuat inisiatif tersebut. Selanjutnya, Kagubare menekankan bahwa pendanaan penelitian harus bersifat katalitik dengan fokus pada kebutuhan negara dan solusi lokal. Namun demikian, perlu diakui bahwa saat ini belum ada indikator pengukuran kinerja sistem kesehatan yang baku, di samping anggaran dan iklim politik yang seringkali menjadi hambatan penguatan sistem kesehatan. Saminarsih kemudian menambahkan bahwa waktu adalah hal yang dibutuhkan untuk sebuah intervensi sistem kesehatan mulai menampakkan hasilnya.
Topik pertama yang dibahas pada sesi ini adalah tentang investasi untuk HPSR. Nagpal mengatakan bahwa kompleksitas sistem kesehatan yang berkembang dan transformasi pembiayaan kesehatan memerlukan asesmen yang tepat tentang area investasi dan kapasitas untuk mengoperasionalkan investasi. Selanjutnya, Takizawa mengatakan bahwa riset sistem kesehatan terkadang dianggap tidak cukup tangible jika dibandingkan dengan riset-riset biomedis. Namun demikian, JICA mulai bergerak untuk mengeksplorasi investasi di bidang HPSR, dengan catatan sumber daya dan konteks lokal harus dipahami dengan baik. Saxena menimpali dengan menjelaskan bahwa USAID Asia Bureau melakukan analisis lanskap untuk menentukan area yang menerima alokasi dana dan masalah utama yang membutuhkan bantuan USAID. Hasil analisis lanskap yang dilakukan USAID juga menunjukkan adanya kesenjangan dalam hal evidence to policy yang mensinyalir pentingnya memperkuat inisiatif tersebut. Selanjutnya, Kagubare menekankan bahwa pendanaan penelitian harus bersifat katalitik dengan fokus pada kebutuhan negara dan solusi lokal. Namun demikian, perlu diakui bahwa saat ini belum ada indikator pengukuran kinerja sistem kesehatan yang baku, di samping anggaran dan iklim politik yang seringkali menjadi hambatan penguatan sistem kesehatan. Saminarsih kemudian menambahkan bahwa waktu adalah hal yang dibutuhkan untuk sebuah intervensi sistem kesehatan mulai menampakkan hasilnya. Barber memulai dengan menyatakan bahwa tantangan HPSR termasuk tantangan kerja sama global health security (GHS) dan tantangan dari luar sektor kesehatan. Grepin menambahkan bahwa learning sejatinya terjadi pada konteks dan tingkatan yang berbeda, namun HPSR seringkali berfokus pada konteks nasional atau kawasan. Tang menimpali bahwa peneliti dan pembuat kebijakan masih sangat terpisah dan belum berinteraksi dengan optimal. Salah satu pengamatan Tang adalah kurangnya kelompok peneliti yang bertujuan untuk mengadvokasi isu tertentu.
Barber memulai dengan menyatakan bahwa tantangan HPSR termasuk tantangan kerja sama global health security (GHS) dan tantangan dari luar sektor kesehatan. Grepin menambahkan bahwa learning sejatinya terjadi pada konteks dan tingkatan yang berbeda, namun HPSR seringkali berfokus pada konteks nasional atau kawasan. Tang menimpali bahwa peneliti dan pembuat kebijakan masih sangat terpisah dan belum berinteraksi dengan optimal. Salah satu pengamatan Tang adalah kurangnya kelompok peneliti yang bertujuan untuk mengadvokasi isu tertentu. Diskusi #21 Masa Depan Pelayanan Kesehatan Ibu
Diskusi #21 Masa Depan Pelayanan Kesehatan Ibu Diskusi #19 Pengembangan Perawatan Palliative berlandaskan UU kesehatan 2023 : Rancangan Pendidikan, Pelayanan dan Penelitian
Diskusi #19 Pengembangan Perawatan Palliative berlandaskan UU kesehatan 2023 : Rancangan Pendidikan, Pelayanan dan Penelitian Diskusi #15 Dampak Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Pelayanan THT
Diskusi #15 Dampak Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Pelayanan THT Diskusi #14 Topik Potensi Pengembangan Intervensi Gizi Di Indonesia
Diskusi #14 Topik Potensi Pengembangan Intervensi Gizi Di Indonesia



 Diskusi #20 Era Baru Sistem Kesehatan: Kasus Pelayanan Penyakit Tidak Menular (Jantung)
Diskusi #20 Era Baru Sistem Kesehatan: Kasus Pelayanan Penyakit Tidak Menular (Jantung) Diskusi #17 Pengaruh UU No.17 Th 2023 terhadap Persoalan One Health
Diskusi #17 Pengaruh UU No.17 Th 2023 terhadap Persoalan One Health




 Diskusi #1 Kebijakan Pendidikan terkait dengan Kolegium dan Konsil Kedokteran dan berbagai isu lainnya
Diskusi #1 Kebijakan Pendidikan terkait dengan Kolegium dan Konsil Kedokteran dan berbagai isu lainnya